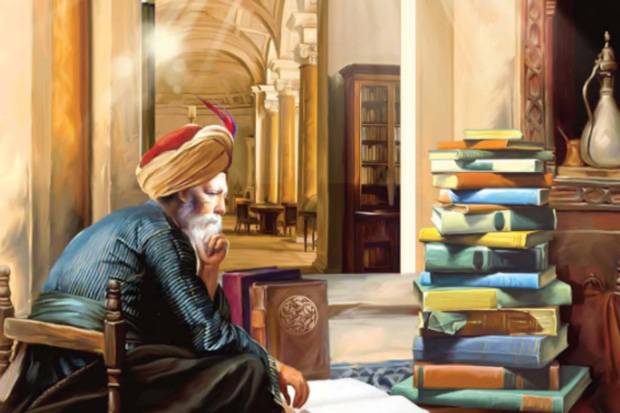Abdul Karim al-Jili (w. 1424 M) adalah sufi besar asal Baghdad yang memiliki pengaruh cukup luas di Nusantara (lebih-lebih lagi di Aceh), terutama dalam bentangan waktu antara abad ke-17 hingga awal akhir abad ke-19. Pengaruh penting sosok ini terletak pada ajarannya yang amat penting tentang “manusia sempurna” (al-Insan al-Kamil). Catatan: ajaran ini sama sekali beda secara mendasar dengan ide Übermensch-nya Nietzsche.
Gagasan ini mendapat sambutan yang lumayan antusias di kalangan para keluarga kerajaan di kawasan nusantara. Dalam tarekat Syattariyah, misalnya, dikenal ajaran mengenai hirarki wujud hingga tujuh tingkat, dan karena itu disebut ajaran martabat tujuh. Wujud ketujuh disebut “insan kamil”. Tarekat Syattariyah, kita tahu, amat populer di kalangan keluarga raja-raja Islam nusantara: Banten, Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Konon, bahkan Pangeran Diponegoro amat menggemari dan mendalami ajaran ini.
Di Indonesia, ajaran tentang martabat tujuh dan insan kamil ini dipopulerkan oleh para ulama seperti Abdurrauf Singkel (w. 1693) dari Aceh, Muhammad Nafis (w. 1812) dari Banjar, dan Abdul Muhyi (w. 1730). Amat disayangkan bahwa pengaruh ajaran ini, belakangan, meredup di tengah-tengah masyarakat muslim, kecuali di kalangan terbatas yang berminat pada ajaran-ajaran Ibn Arabi. Teori martabat tujuh ini memang berasal dari ajaran pokok Ibn Arabi mengenai “wahdatul wujud” (“manunggaling kahanan”).
Kembali kepada Abdul Karim al-Jili. Dalam kitabnya yang amat masyhur, “al-Insan al-Kamil fi Ma’rifat al-Awa’ili w al-Awakhir”, ia mencoba mengungkapkan sari-pati dari seluruh pengalaman rohaninya. Al-Jili sadar, tidak semua orang bisa menerima ilmu yang ia tulis dalam kitab itu. Pengalaman-pengalaman rohani yang lahir dari “perjumpaan” seorang salik dengan Tuhan memang kerap “misterius”. Mengungkapkannya kadang tidak bisa dengan bahasa yang terus-terang. Harus melalui bahasa “sanepa”, isyarat.
Karena itu, dalam pembukaan kitab ini, al-Jili menegaskan sebuah kaidah rohani yang, menurut saya, amat penting. Ia mengatakan: “fi min al-ma’ani ma la-yufhamu illa lughzan aw isyaratan” (فمن المعانى ما لا يفهم إلا لغزا أو إشارة). Artinya: ada sejumlah hal yang tidak bisa dikemukakan dan dipahami kecuali melalui teka-teki (sanepa?) dan isyarat.
Dan persis di sinilah masalah muncul. Tak semua orang paham bahasa isyarat. Kadang, isyaratpun belum tentu tepat mengungkapkan maksud hati seseorang. Ada isyarat yang gahal Contoh sederhana: ada pengendara motor yang menghidupkan lampu riting (dari bahasa Belanda “richting,” arah) kanan, eh, ternyata dia belok kiri. Atau sebaliknya.
Karena rumitnya bahasa isyarat ini, al-Jili kemudian mengemukakan “kaidah rohani” kedua: Jika engkau, entah karena keterbatasan pengetahuanmu atau yang lain, tidak memahami bahasa isyarat dan teka-teka spiritual yang ditulis oleh para sufi, engkau jangan buru-buru menyanggah, mengkritik, dan menolaknya. Diamlah sebentar, dan renungkan.
Dengan tegas, al-Jili mengemukakan bahwa semua yang tulis dalam kitabnya itu, taak satupun yang melenceng dari, dan bertengan dengan Al-Qur’an dan sunnah. “Jika ada kata-kataku yang seolah-olah berlawanan dengan Al-Qur’an dan sunnah,” katanya, “itu hanyalah pada permukaan “mafhum”-nya saja; jika diselidiki lebih dalam, “murad” atau makna rahasia yang ada di balik “mafhum” itu, sejatinya tidak bertentangan.”
Saya kira, kaidah ini bisa kita berlakukan dalam konteks yang lebih luas lagi. Kaidah al-Jili ini tentu saja, pertama-tama, berlaku untuk ajaran-ajaran sufi yang tampak “kontroversial” pada lapisan permukaan. Ia menganjurkan, jika seseorang berhadapan dengan hal semacam ini, sebaiknya ia diam, merenung. Ia tidak boleh buru-buru “kebakaran jenggot,” lalu menolaknya, bahkan menyesatkannya. Jika ini yang terjadi, ia justru akan terhalang dari kesempatan untuk memperoleh hikmah yang tersembunyi di balik ajaran-ajaran para sufi itu.
Jika diperluas konteksnya, ajaran al-Jili ini juga mengajarkan kita bersikap hati-hati saat berjumpa dengan sebuah gagasan. Ide yang di permukaan tampak “aneh” dan “sesat,” boleh jadi, jika ditelaah lebih dalam, mengandung hikmah yang amat kaya.
Seorang salik dan sufi bukanlah manusia yang “gumunan,” gampang kagetan, atau reaksioner. Ia akan memandang segala sesuatu dengan permenungan. Ia tidak grusa-grusu.
Sekian.