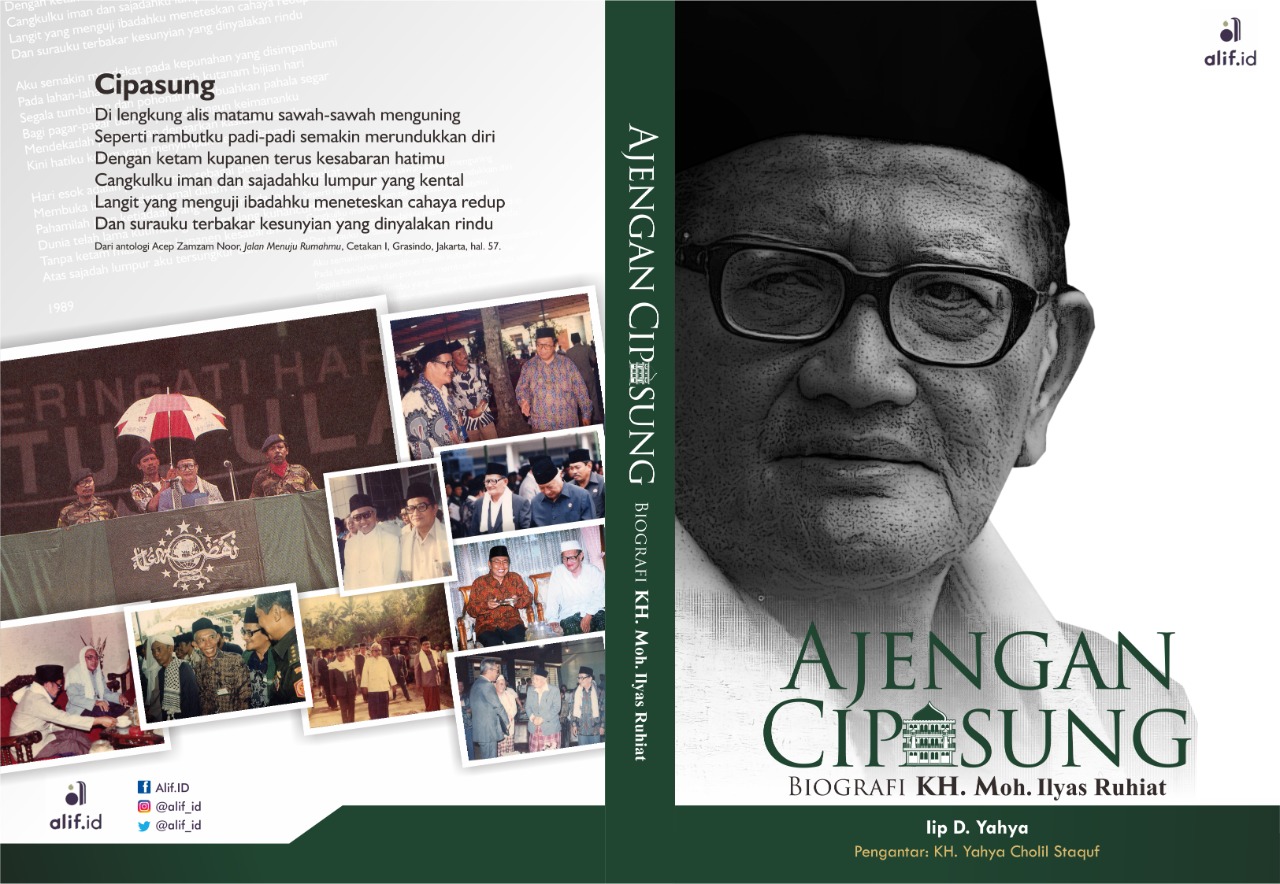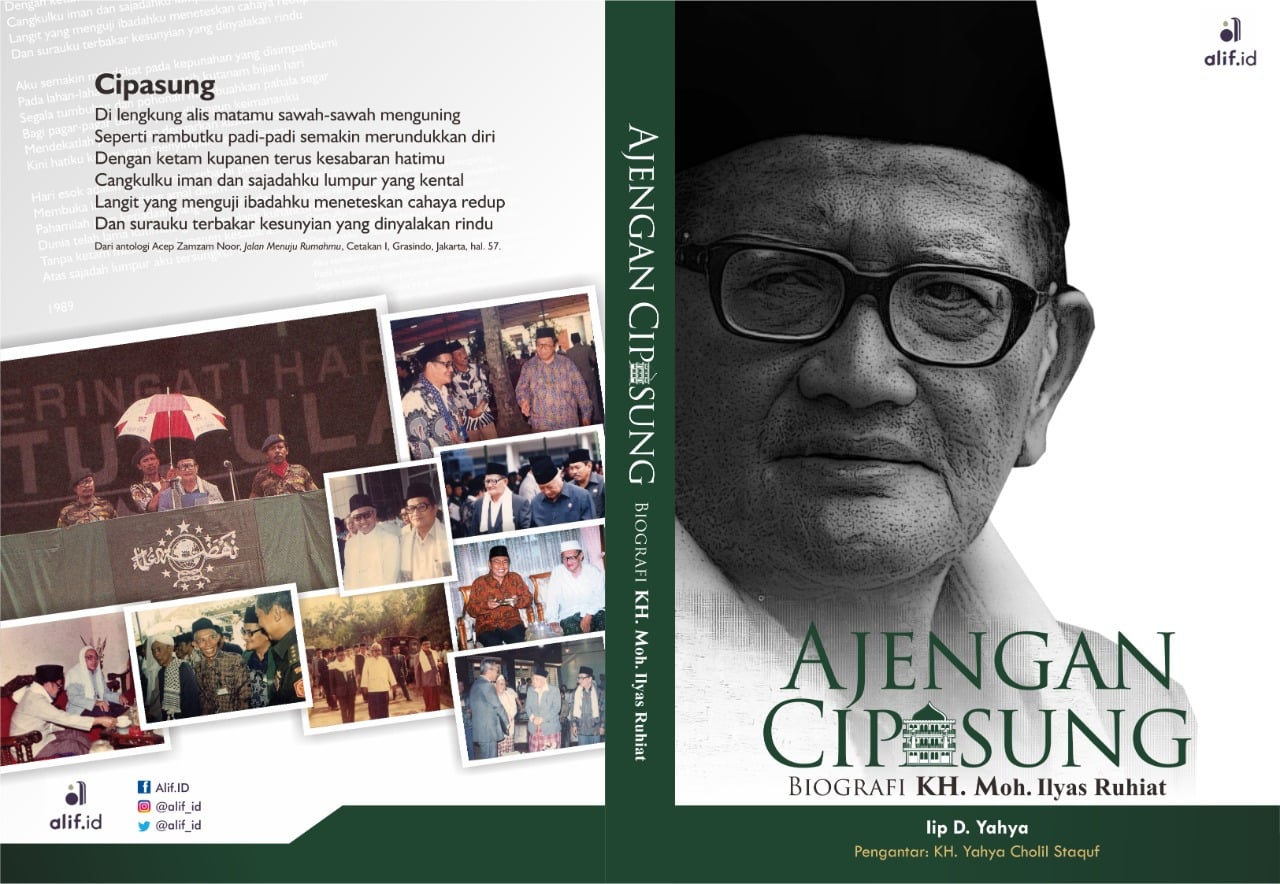Jika kita bertanya, di antara seluruh nama-nama ulama besar yang ada dalam sejarah, siapakah di antara mereka yang paling besar pengaruhnya dalam keberagamaan masyarakat Indonesia? Mungkin akan ada beragam jawaban. Namun Montgomery Watt memiliki pendapat tersendiri. Dalam dua bukunya Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali (1963) dan The Faith and Practice of al-Ghazali (1967), dia berkata, orang kedua setelah Nabi Muhammad yang paling memberi pengaruh dalam keberislaman adalah Imam al-Ghazali.
Di Indonesia, jejak pemikiran beliau begitu terasa. Dari strata sosial paling rendah sampai tingkat atas, dari ceramah-ceramah di langgar-langgar desa, pengajian-pengajian di pesantren, hingga di bangku perkuliahan, nama beliau selalu relevan. Dari konsepsi hikmah Sunan Bonang, antara rivalitas tasawuf Hamzah Fansuri dan Nuruddin al-Raniri, hingga konsep kepemimpinan yang dipegang teguh hampir seluruh ormas Islam di Indonesia.
Kita memiliki kedekatan terhadap al-Ghazali. Secara fikih, kita sama-sama menganut mazhab Syafi’i. Dalam hal keyakinan kita banyak menggunakan paham Asy’ariyah. Dua hal ini, jika bukan keseluruhan, membentuk pemahaman yang di Indonesia kita sebut sebagai Sunni.
Al-Ghazali bahkan mungkin lebih kita kenal ketimbang Asy’ari sendiri. Jika Asy’ari adalah sosok yang memberikan patokan, maka al-Ghazali adalah seseorang yang menggunakan patokan-patokan tersebut di dalam karya-karyanya dengan sangat baik dan bisa diterima secara luas. Tidak salah jika Masdar F Mas’udi suatu kali menulis dalam jurnal Pesantren (1986), “NU dan Teologi al-Asy’ari”, bahwa karena al-Ghazali teologi Asy’ariyah dapat menyebar luas di berbagai wilayah Islam, termasuk Indonesia.
Corak sufisme yang sangat terasa dalam karya-karya al-Ghazali, bisa jadi adalah salah satu yang membuatnya begitu diminati di Indonesia, yang secara historis dekat dengan pengamalan sufisme. Sehingga, dalam banyak hal, al-Ghazali lebih banyak kita temukan sebagai seorang sufi ketimbang bidang-bidang lain yang juga ditulisnya. Dalam bidang filsafat, karyanya Tahafut al-Falasifah justru datang lebih belakang, seiring persentuhan kampus-kampus Islam terhadap filsafat.
Gus Dur suatu kali menjabarkan silsilah keilmuan pesantren-pesantren di nusantara dalam sebuah tulisan yang diterbitkan jurnal Pesantren edisi 1, 1984, “Asal-Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren.” Menurutnya, keilmuan Islam berkembang dalam dua periode. Periode pertama dimulai ketika orang-orang Arab dan Non-Arab yang telah beragama Islam datang dan mengajarkan agama Islam ke daerah-daerah ini hingga sekitar abad ke-16.
Pada periode ini, Islam yang masuk dan diajarkan sangat bernuansa tasawuf dalam bentuk yang sudah dikembangkan di Persia dan kemudian di anak benua India. Fikih memang dipelajari, begitu pula tauhid, ilmu alat, juga hadis, tafsir dan semacamnya. Namun orientasinya adalah tasawuf, sehingga semua ajaran dalam fakultas keilmuan tersebut tetap memberikan nuansa mistik.
Periode kedua dimulai ketika banyak orang-orang di Nusantara yang telah memeluk Islam mulai melakukan perjalanan haji ke Arab, terutama Makkah dan Madinah; beberapa di antara mereka justru tinggal dan menetap di sana untuk memperdalam keilmuan. Setelahnya mereka kembali ke daerah masing-masing dan mengajarkan keilmuan yang mereka dapatkan. Periode ini dimulai sekitar abad ke-17 hingga beberapa tahun belakangan, dan mulai meredup semenjak aktivitas pembelajaran Islam juga bergeser dari masjid-masjid ke kampus dan pesantren.
Orang-orang yang telah belajar ke Makkah dan Madinah inilah yang setelah kepulangannya kebanyakan mendirikan pesantren, institusi yang menjadi begitu penting dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Mereka memindahkan system dan metode-metode pengajaran di Jazirah Arab ke Indonesia, namun tetap mempertahankan pengajaran pada periode pertama, terutama bidang tasawuf.
Bagi Gus Dur, kitab Bidayah al-Hidayah karangan Imam al-Ghazali, menjadi salah satu kitab rujukan utama, atau bisa jadi merupakan cerminan bagaimana kedua periode itu berjalan. Menurutnya, kitab ini, dan kitab semacamnya, mampu menggabungkan fikih dengan amal-amal akhlak yang merupakan bahan pelajaran utama. Kitab ini paling menonjol selama berabad-abad, bahkan sampai abad ini di pesantren-pesantren.
Bukan hanya Bidayah. Sejarawan Snouck Hurgronje dalam Mekka in the Latter Part of the 19th Century (hal, 160), mengatakan, kitab induk al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, telah ada seiring napas keberagamaan di Indonesia. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah, memungkinkannya dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, bukan terbatas kepada orang-orang pesantren. Bagi orang yang paham bahasa Arab, baik karena pernah menetap di Jazirah Arab ataukah belajar di pesantren, mereka akan merujuk langsung kepada kitab yang berbahasa Arab. Sedangkan orang-orang yang hanya bisa bahasa Indonesia, bisa mengakses terjemahannya. Bagi orang yang tidak bisa membaca, mereka masih bisa mendengarkan ceramah para guru dan kiai yang hampir kesemuanya bersumber dari kitab tersebut.
Dalam pandangan banyak sarjana muslim di Indonesia, kehidupan pribadi al-Ghazali adalah salah satu karakter seorang penuntut ilmu tanpa kenal lelah. Ia mencakup hampir seluruh aspek keilmuan, meluruskan hampir seluruh pemahaman golongan-golongan yang keliru. Periode kehidupan al-Ghazali yang berujung pada pembenaran bahwa hanya jalan sufisme yang mampu membuat seseroang sampai kepada Tuhannya, tetapi juga tetap bertumpu kepada syariah yang ketat. Selain itu, al-Ghazali juga mampu menjelaskan berbagai perihal gaib dan peristiwa-peristiwa sufisme baik dengan logika dan doktrin tekstual. (RM)