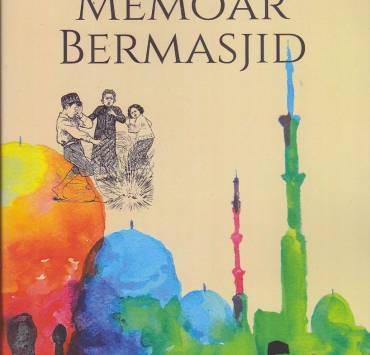Sahabat adalah siapapun mereka yang bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman, baik ikut ambil bagian dalam jejer pandita maupun tidak. Kedudukan Sahabat terlampau agung dibandingkan generasi setelahnya. Rasul mengatakan bahwa para sahabatnya seperti nabi-nabi Bani Israil.
Keberadaan sahabat menjadi pelita dan bintang sebagai petunjuk oleh generasi selanjutnya. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, kapan, di mana dan untuk apa dan siapa wahyu turun, oleh karenanya mereka orang-orang terdekat yang mampu memahami apa yang dikandung tiap nash yang turun.
Mereka begitu harmonis dan syahdu. Saling asih dan asuh satu sama lain. Asyik masyuk menjadi oksigen yang menghidupi mereka. Juga betapa Rasul mencitai mereka. Begitu asihnya Rasul pada para sahabatnya sampai kelaparan ashhâbussufah (santri serambi masjid Rasul) menjadi tanda bahwa Rasul sedang tidak menelan barang sebiji gandum pun. Kenapa?
Sebab kalau ada yang bisa dimakan di ndalem maka orang pertama yang memakannya adalah para santri di serambi masjid beliau itu. Kalau mereka sampai kelaparan bertanda Rasul lebih dari itu!
Keharmonisan para sahabat mulai surup saat Rasul mangkat kersaneng gusti. Disusul pecahnya fitnah kubra yang mengepung rumah khalifah Utsman ibnu Affan hingga berakhir terbunuhnya menantu Nabi tersebut, sampai terbunuhnya Ali ibnu Abi Thalib, menantu Nabi yang juga khalifah setelah Utsman.
Pasca fitnah kubra meletus, antar sahabat tidak lagi harmonis. Ada gep tebal yang terus dipertebal, mulai dari idiologi sampai politik!
Dulu di zaman para sahabat tidak ada taradhdhi (ucapan radhiyaallhu ‘anh) satu sama lain, sebab kedudukan mereka sama. Kedudukan shuhbah yang sekian tingkat di atas puncak para wali. Setinggi apapun kedudukan wali, paribasan sundul langit pun tidak akan mampu sejajar dengan level sahabat.
Hingga fitnah kian besar dan dirawat dengan berbagai kepentingan, ulama merasa perlu mengucapkan taradhdhi pada para sahabat kala menyebut nama mereka. Saat melangitkan selawat dan salam, yang tadinya hanya hanya terbatas pada Rasulullah dan keluarganya, kini selawat juga dialamatkan atas para sahabat yang bening itu. Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammad wa ‘ala alihi washahbi ajma’in.
Di Mesir, paruh awal abad kedua hijriyah masyarakatnya tidak suka sampai taraf mencaci Sayidina Utsman ibnu Affan hingga lahirlah Imam Laits ibnu Saad (W. 175 H), tokoh puncak keilmuan Mesir di zamannya, mujtahid pemilik mazhab fikih yang kata Imam Syafi’i lebih fakih daripada Imam Malik dan juga guru dari para guru Imam Bukhari sehingga riwayatnya tidak sedikit di dalam kitab paling sahih setelah Alquran tersebut; lalu Imam Laits ibnu Saad menceritakan keutamaan-keutamaan Sayidina Utsman hingga mereka bungkam dan berbalik menghormati.
Di Homs, salah satu kota Syiria, masyarakatnya tidak suka sampai taraf mencaci Sayidina Ali ibnu Abi Thalib hingga datanglah Ismail ibnu Iyasy lalu ia menceriterakan keutamaan-keutamaan ayah Hasan dan Husen itu hingga mereka bungkam dan berbalik menghormati.
Di Kufah lebih parah, di zaman Imam Abu Hanifah (W. 150 H) tidak sedikit orang-orang yang membenci dan mencaci menantu Rasulullah, Utsman ibnu Affan, yang memperistri dua putri Rasulullah hingga dijuluki dzunnuroin (pemilik dua permata), seseorang yang malaikat saja malu padanya. Salah seorang di antaranya hingga menganggapnya bukan orang muslim. Ia (sebut saja Polan) meyakini bahwa Utsman orang Yahudi. Keyakinan yang dipegang teguh sejak lama.
Tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan padanya bahwa Utsman bukan Yahudi.
Datanglah Imam Abu Hanifah, puncak keilmuan madrasah ahlu ra’yi Baghdad yang kecerdasannya melebihi akalnya. Dia datang ke rumah Polan dengan maksud melamar putrinya untuk orang lain.
“Saya datang untuk melamar putri Anda, untuk laki-laki yang mulia, hafal kitab Allah, jutawan nan dermawan.”
“O, Tuan, meski tidak sebegitu sempurna pun saya mau.”
“Hanya saja ada satu masalah.”
“Apa itu?”
“Dia Yahudi!”
Tiba-tiba muka Pola berubah. Ia merasa dipermainkan sama Imam Abu Hanifah.
“Subhanallah! Kamu memerintahkan aku menikahkan putriku dengan seorang Yahudi?!”
“Kenapa tidak mau, Rasulullah saja menikahkan dua putrinya dengan Yahudi!” Maksudnya Utsman ibnu Affan.
Ia pun tersadar bahwa tidak mungkin menuduh Rasulullah seceroboh itu menikahkan kedua putrinya dengan Yahudi. Ia pun kemudian bertaubat dari apa yang ia yakini sebelumnya.
Sahabat, betapa pun agung nan luhur kedudukan mereka, mereka tetaplah manusia. Ada kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan baik kecil maupun besar.
Mereka, kata guru kami sebagaimana saya dengar saat bersimpuh di bawah kaki Syekh Abdullah Izzuddin, adalah kambing yang dikorbankan (kabsyul fida’) untuk umat Islam guna sebagai praktik terapan hukum yang dibawa oleh syariat.
Mereka paham apa yang mereka lakukan, hanya saja, seolah, kesadaran mereka diangkat sejenak untuk melakukan hal yang keliru dalam kaca mata syariat. Sampai Imam Nawawi (676 H) berkata:
“Jika tiada perang antara Ali dan Muawiyah, niscaya kita tidak akan tahu apa hukumnya bughat (pemberontak),”
Kemelut perang saudara antara Ali dan Muawiyah dampaknya masih terasa sampai sekarang. Dari pecah perang tersebut umat Islam menjadi terkelompok dalam beberapa ruang. Kendati demikian ditemukan banyak ulama yang enggan membicarakannya, mengambil jalan aman hingga muncul kaedah “wama jaro bainas shohabati naskutu”, “apa yang terjadi di antara sahabat kami enggan membicarakannya”, mereka mauquf atau abstain dalam bersikap yang terjadi antar sahabat, terlebih mengomentari personalnya!