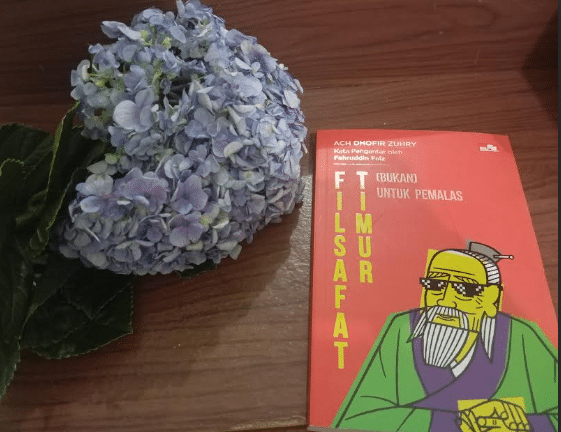Kekerasan seksual bukan hanya pernah terjadi di pesantren—ia masih terjadi, berulang, dan menunggu dipahami. Namun, alih-alih disebut sebagai krisis struktural, kasus-kasus ini sering kali dianggap sebagai anomali: satu-dua “oknum”, satu-dua “penyimpangan”, lalu dilupakan.
Buku Menjaga Marwah Pesantren mencoba keluar dari jebakan itu. Ditulis oleh tim peneliti PPIM UIN Jakarta yang terjun langsung ke lapangan, buku ini menyajikan catatan reflektif yang jujur, gamblang, dan sangat menyentuh, tentang bagaimana kekerasan seksual di pesantren terjadi dalam selimut relasi kuasa, ruang tertutup, tafsir diam-diam, dan penghormatan yang keliru.
Kekerasan yang Nyata, Tapi Tidak Diakui
Kekerasan seksual bukan sekadar potensi, tapi realitas di banyak lembaga pendidikan berbasis agama. Ada pengasuh pesantren yang mencabuli santri perempuan bertahun-tahun dengan dalih “air dzuriyat suci” (hlm. 4). Ada ustaz yang menyalahgunakan pengaruh spiritualnya untuk mendekati anak laki-laki. Ada pula santri yang mengaku dilecehkan, tapi kemudian dipaksa diam atas nama “marwah” lembaga.
Namun, ironisnya, semakin kuat marwah yang diklaim, semakin kental pula budaya diam yang mengendap. Dalam banyak kasus, korban justru tak dianggap sebagai penyintas, tetapi sebagai “pengganggu ketenangan lembaga”.
Mengapa hanya sesekali terdengar? Buku ini memberi jawabannya: karena ada kombinasi antara rasa takut, rasa hormat, dan jebakan simbol.
Pesantren dianggap lembaga suci, tempat pendidikan ruhani. Maka ketika kasus kekerasan muncul, banyak pihak yang merasa lebih penting untuk “menjaga nama baik” daripada mendengarkan korban. Bahkan ada narasi religius yang membungkus tindakan diam itu sebagai “ikhtiar menjaga izzah ulama”.
Jika satu kasus berhasil masuk ke media, kasus itu langsung meledak. Sayangnya, ledakan itu lebih sering menghasilkan stigma umum (“pesantren tidak aman”), alih-alih pembenahan sistemik.
Adakah Agama Mendiamkan?
Ini bagian paling getir. Buku ini tidak menyalahkan Islam, tetapi juga tidak memaafkan tafsir dan praktik agama yang membungkam. Misalnya hadis tentang kehormatan ulama dipakai untuk melindungi pelaku yang bersurban. Bahkan dalam kasus tertentu, relasi spiritual antara santri dan guru digunakan sebagai justifikasi kekuasaan absolut atas tubuh (hlm. 10, 12).
Buku ini dengan jernih menegaskan: agama Islam tidak pernah melegitimasi kekerasan seksual. Yang bermasalah adalah tafsir-tafsir patriarkal dan budaya kekuasaan yang menunggangi simbol agama demi melanggengkan ketimpangan dan ketakutan.
Mengapa Kekerasan Ini Terjadi?
Tidak ada pesantren yang bercita-cita menjadi tempat kekerasan. Tidak ada kiai, tidak ada sistem, yang secara sadar ingin menyakiti. Namun di antara lantunan zikir dan suara pengajian, kekerasan itu tetap terjadi—berulang, sunyi, dan sering kali dianggap angin lewat.
Kekerasan seksual tidak muncul dari niat jahat semata, melainkan dari jaring-jaring diam yang ditenun perlahan oleh banyak faktor: kekuasaan yang tak diawasi, ruang yang tak terbuka, ilmu yang tak dibagi, dan budaya yang terlalu cepat percaya.
Di pesantren, ustaz dan kiai bukan hanya guru. Mereka adalah wakil orang tua, penerus ilmu agama, dan dalam banyak kasus, dihormati lebih dari siapa pun. Hubungan spiritual itu sangat dalam—tapi juga rapuh jika tidak dijaga dengan kesadaran kuasa. Santri diajarkan untuk patuh, untuk tunduk, untuk tidak membantah. Dalam tradisi ini, keberanian untuk berkata “tidak” sering hilang ditelan rasa takut dianggap durhaka.
Faktor kedua: ruang. Banyak pesantren, terutama yang tradisional, dibangun dengan konsep keakraban dan pengawasan moral yang cair. Tapi ruang-ruang itu bisa berubah menjadi lorong gelap ketika satu-dua orang memiliki kunci atas semua pintu. Tak ada CCTV. Tak ada prosedur pelaporan. Tak ada sekat antara kekuasaan dan kedekatan.
Ketiga: literasi tubuh dan seksualitas yang nyaris tak diajarkan. Santri tidak tahu bahwa tubuhnya bisa diberi batas. Tidak diajarkan bahwa disentuh tanpa izin adalah pelanggaran. Banyak korban yang tak hanya bingung, tapi juga ragu apakah dirinya memang benar menjadi korban (hlm. 15).
Di Mana Harapan?
Para penulis menyebut pentingnya membuat pesantren menjadi ruang aman, bukan hanya ruang disiplin. Pendidikan seksualitas berbasis nilai Islam, sistem pelaporan yang berpihak pada korban, pengawasan internal yang sehat—semua itu memungkinkan. Tapi syaratnya satu: pesantren harus berani bercermin, bukan sibuk membenarkan citra.
Menjaga Marwah Pesantren adalah buku yang tidak nyaman, karena membicarakan luka yang terlalu lama disembunyikan. Tapi justru dari ketidaknyamanan itulah kejujuran bisa tumbuh. Buku ini perlu dibaca, tidak untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memastikan siapa yang tidak lagi diam.