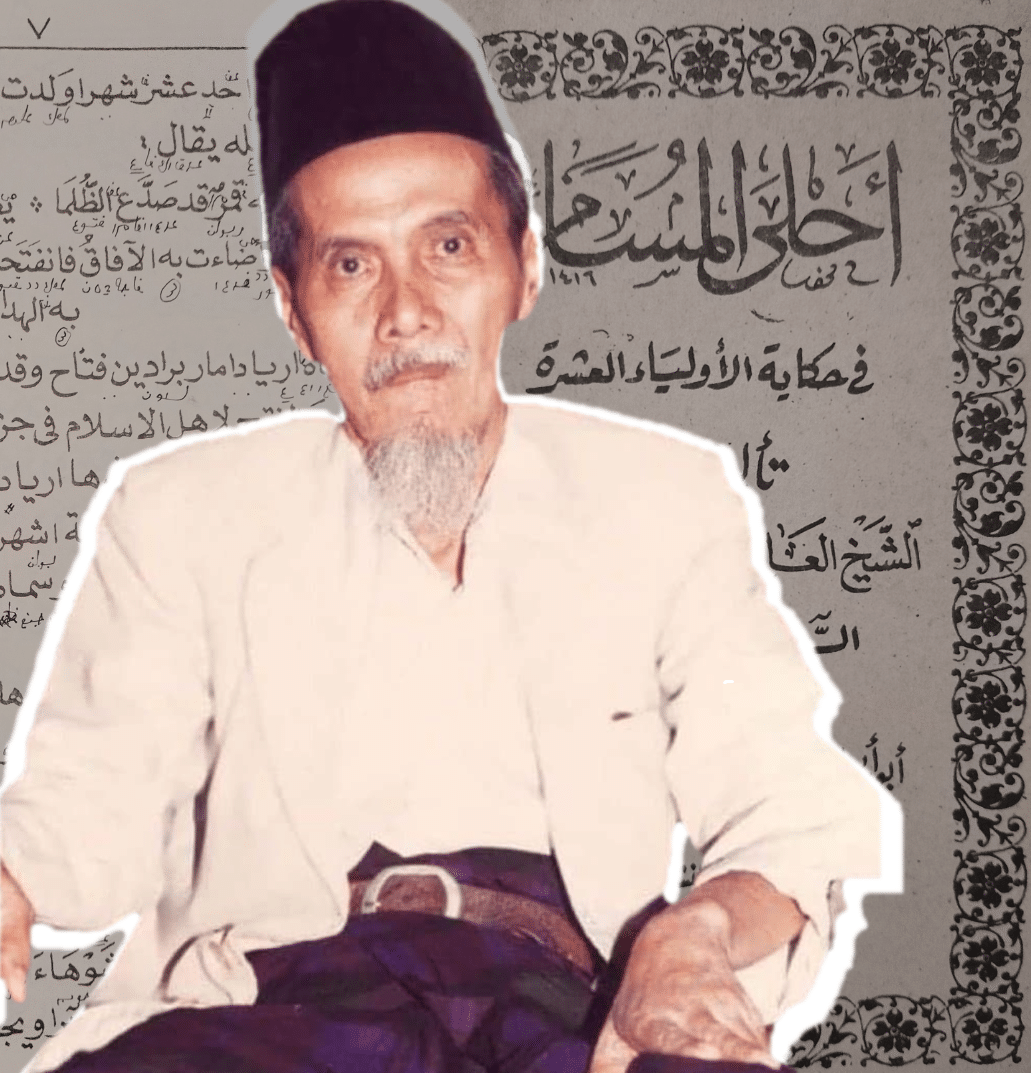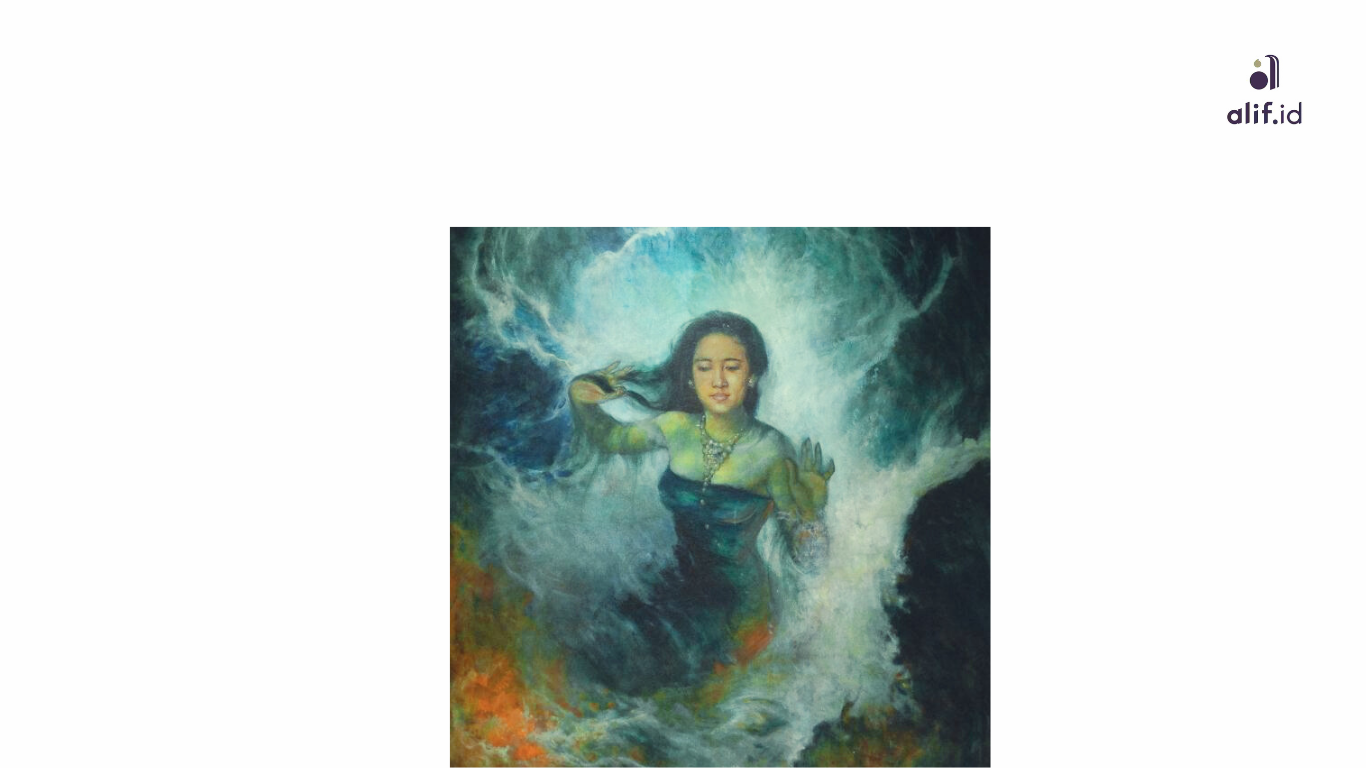“The more I study religions, the more I am convinced that man never worshipped anything but himself.”
Kutipan Richard Burton di atas barangkali cukup relevan untuk film Prancis Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? (2014). Sebuah drama keluarga yang berkisah tentang anak-anak gadis dari pasangan Katolik konservatif yang menikah dengan keturunan imigran dari agama dan ras lain. Film ini menjadi menarik karena dibalut dengan humor satire yang kental sekali.
Saya lebih suka judul aslinya ketimbang versi internasionalnya: Serial Bad Weddings. Judul aslinya (Apa yang Telah Kita Perbuat pada Tuhan yang Maha Baik?) lebih mewakili isi film dan terasa sangat transendental. Sebaliknya, versi bahasa Inggrisnya terkesan mengerdilkan keseluruhan cerita dan pragmatis.
Alkisah, Claude Verneuil dan Marie Verneuil dikaruniai empat anak perempuan jelita. Keluarga Verneuil hidup bahagia, harmonis, dan serba berkecukupan. Hingga kemudian tiba saat anak-anaknya tumbuh dewasa dan siap menikah.
Film ini dibuka dengan pernikahan tiga putri pasangan Verneuil. Anak pertama mereka menikah dengan Rashid, seorang Franco-Algeria beragama Islam. Disusul anak kedua yang menikah dengan David, seorang Yahudi keturunan Israel beragama Yudaisme. Anak ketiga pun tak mau kalah. Ia menikah dengan Chao, seorang Tionghoa yang tak terlalu mempedulikan agama.
Prancis memang negara paling multikultural di Eropa. Premis yang dipasang dalam film ini adalah peluang paling memungkinkan yang bisa terjadi di sebuah keluarga Eropa modern. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga tersebut mau berkompromi dengan gap dan perbedaan baru yang sangat mendadak dan signifikan? Apa yang akan mereka lakukan sebagai seorang Katolik konservatif di satu sisi dan melihat anak-anaknya bahagia di atas bahtera cinta mereka di sisi lain?
Di sinilah letak keseruan film ini. Philippe de Chauveron, sang sutradara dan penulis naskah, telah berhasil menciptakan karakter sentral seperti Claude dan Marie dengan segala ketidaksempurnaannya. Ia menempatkan sepasang mertua yang sangat manusiawi itu di hadapan para menantu imigran mereka yang lugu.
Claude digambarkan cukup sulit mengontrol stigmanya tentang ras dan agama lain. Sedangkan Marie, meski terlihat tenang, ia sebenarnya sedang menyesali betapa “nasib buruk” telah menimpa keluarganya. Tapi muara pikiran mereka sama: mendambakan menantu dari komunitas (kaukasian-Katolik) mereka sendiri.
Terkait stigma, Claude sebenarnya tidak sendiri. Para menantunya tak kalah gila. Mereka bahkan bisa saling melempar ejekan satu sama lain di meja makan. David bisa saja mengejek Rashid dan tradisi sunat dalam Islam yang dipandang barbar karena dilakukan saat seorang anak menginjak remaja. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, sunat dilakukan saat anak masih bayi dengan alasan meminimalisir trauma atas rasa sakit.
Di kesempatan lain, Rashid bisa gantian mengejek Chao karena orang Asia suka “menjilat”, terlalu murah senyum, dan bermuka dua. Atau tiba giliran Chao mengolok David karena orang-orang Yahudi payah berdagang dan berbisnis: sesuatu yang sangat mahir dilakukan orang-orang Tionghoa. Stigma-stigma ini dilempar begitu saja. Chauveron seakan sengaja menyajikan hal-hal yang masih melekat di pikiran masyarakat Eropa tentang ras atau agama tertentu, bukan untuk diamini, melainkan untuk ditertawakan bersama.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? dibangun dari premis yang kokoh, selipan humor yang proporsional di setiap detail adegannya, juga konflik yang dinamis; meski sejujurnya plot film ini masih terlalu normatif.
Ketika dinamika konflik mengalami surut, gerombolan menantu itu bisa juga rukun dan kompak layaknya timnas sepak bola Prancis. Seperti ketika Claude dan Marie mengundang semua putri dan menantunya untuk merayakan Natal bersama di rumahnya. Pada satu momen, David dan Rashid terlihat sedang menggendong anaknya masing-masing sambil memandangi diorama mini kelahiran Yesus. Marie tiba-tiba datang mengenalkan dioramanya pada cucu-cucunya.
“Lihat, ini namanya keledai. Ini lembu. Nah, kalau ini adalah Yesus, sang putra Tuhan,” kata Marie sembari berlalu. Setelah si mertua pergi, David bilang ke anaknya, “Nenekmu terlalu melebihi-lebihkan Yesus. Ia hanya seorang nabi.” Rashid pun menimpali, “Paman David benar. Dia hanya nabi.”
Film ini tambah pecah ketika putri keempat keluarga Verneuil memutuskan untuk menikah. Claude dan Marie tentu saja berharap kalau anak bungsunya mendapatkan seorang Katolik. Ia adalah satu-satunya harapan. Ketika anaknya mengiyakan, mereka bahagia sekali. Tapi apalah kebahagiaan itu. Ia adalah barang fana belaka. Terlebih ketika Claude dan Marie bertemu calon menantunya: Charles, seorang kulit hitam asal Pantai Gading, Afrika.
Melihat line-up karakter di film ini, saya teringat film Prancis lain yang tak kalah membekas: La Haine (1995). Sebuah drama-kriminal tentang perjalanan tiga pemuda imigran: Arab, Yahudi, dan kulit hitam di pinggiran kota (banlieu) Paris. Di konteks yang berbeda, mereka adalah komunitas yang muak dengan diskriminasi dan stigma dari masyarakat.
Pada akhirnya, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ikut menggenapi film-film Prancis yang berbicara tentang keberagaman, multikulturalisme, dan toleransi tanpa mengenal sekat. Chauveron sepertinya ingin menyeret stigma-stigma generalis untuk dihakimi bersama-sama lewat produk budaya yang menghibur.
Bahwa seorang muslim yang enggan memakan babi bukan berarti ekstremis. Bahwa seorang Yahudi yang menyunat bayinya bukan berarti sedang mempraktikkan budaya barbar. Sebab, semua kebudayaan mempunyai alasan. Semua ritual keagamaan juga memiliki dasar.
Sebagaimana kutipan Burton di atas, Claude dan Marie barangkali tak sedang benar-benar menyembah Tuhan. Dengan segala kesinisannya pada perbedaan (agama dan ras lain), barangkali mereka sedang menyembah egonya sendiri. Pesan-pesan implisit tentang toleransi dalam film ini: pentingnya dialog, perlunya mendengar sebelum berkomentar, menghargai keyakinan lain, adalah daya tawar yang kuat untuk diikuti.
Dalam penayangannya, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? mendapat sambutan positif dari para kritikus. Film ini memenangkan satu penghargaan dan masuk dua nominasi dalam festival film yang diikutinya. Meski ada beberapa penolakan pendistribusian seperti di Inggris dan Amerika, film ini telah melanglang buana tayang di Prancis, Jerman, Spanyol, Belgia, Austria, Italia, Kanada, Yunani, Polandia, dan Korea Selatan. Di Indonesia, kita bisa mengakses film ini lewat lembaga kebudayaan Prancis seperti IFI (Institut Français d’Indonésie) yang ada di Bandung, Jakarta, Jogja, dan Surabaya.