
“Kenapa kawan-kawan (muslim) gak mau makan babi, tapi masih mau (menenggak minuman sampai) mabok? Bukankah jika berbicara dosa (menurut Islam), keduanya sama-sama berdosa?” tanya kawan saya beberapa waktu lalu ketika sedang asyik menikmati kerupuk kulit-babi bersama kawan-kawan lain, merencanakan pesta kecil demi sesuatu keberhasilan yang layak dirayakan dengan bir dan wine.
Siang itu, tak setiap dari kami yang “kebetulan” beragama Islam dan bahkan beberapa pernah mengenyam pendidikan di pesantren tapi masih juga (kadang) “minum” itu, agaknya tak memiliki jawaban yang pasti, tegas, jelas, dan berterima. Namun, pertanyaan itu telah mengusik kesadaran dan membikin saya memikirkan babi (dengan berbagai hasil olahan dagingnya) dalam beberapa hari.
Ya, kenapa babi—sebagai binatang maupun sebagai suatu olahan makanan—begitu melekat dalam kepala kami, paling tidak dalam kepala saya, sebagai sesuatu yang teramat haram, sangat haram, paling haram, sehingga tiada lagi yang melebihi keharamannya jika dibandingkan dengan binatang atau makanan/minuman lain yang juga diharamkan dalam agama Islam?
Adakah “citra” haram si babi ini merupakan salah satu keberhasilan guru-guru agama kami, baik di madrasah ataupun di pesantren, dalam menanamkan suatu keyakinan yang tak bisa ditawar-tawar lagi? Sementara soal minuman yang memabukkan, kami masih saja bernegosiasi?
Seorang kawan lain menimpali pertanyaan itu dengan seloroh, “Bukankah pengharaman khomer berlangsung dalam beberapa tahap dan tidak serta-merta diharamkan dalam sekali “perintah”, sedangkan babi telah diharamkan sedari mula?”
Saya tertawa geli. Seolah kadar keharaman itu berbeda-beda dan memiliki nilai yang tidak setara antara satu dan yang lainnya. Tapi barangkali, secara taksadar, kami—atau paling tidak saya—mengamini “pembelaan” kawan saya itu. Sebab, hingga kini, saya (atau tubuh saya) tak bisa menerima babi sebagai sesuatu yang layak dikonsumsi. Sementara itu, saya masih bisa menerima bir dan wine sebagai sesuatu layak konsumsi; minuman yang sesekali bisa dinikmati tanpa efek mabuk.
Ah, kami tak berhasil menemukan jawaban yang memuaskan, memang, bahkan untuk diri sendiri. Hanya saja, entah mengapa pertanyaan itu terus saja menggayuti pikiran saya. Barangkali, karena pertanyaan itu muncul pada tahun yang juga “mengandung” babi, yaitu tahun babi tanah.
Atau barangkali, karena ketika saya mejalani Residensi Penulis (Komite Buku Nasional) di Mentawai pada September—November 2018 lalu, tak sekali pun saya bernyali untuk sekadar menyentuh daging babi, ketika kami (saya dan tuan rumah) menikmati makan bersama.
“Silakan…,” kata saya kepada tuan rumah untuk tetap menikmati hidangannya, tanpa perlu merasa bersalah karena tamu mereka tidak berkenan menikmati makanan yang sama. “Saya hanya tidak bisa makan babi.”
Saya merasa tak perlu mengatakan bahwa dalam agama saya babi itu diharamkan. Lagipula, saat itu, saya mulai berpikir bahwa mungkin bukan melulu lantaran agama yang saya warisi dan kemudian saya yakini sedemikian rupa, yang telah mencegah tubuh saya untuk dapat menikmati daging babi. Maka kemudian, saya sekadar menikmati sagu panggang dengan udang dan ikan-ikan sungai yang dimasak dalam bumbung bambu.
Mitos Babi di Mentawai
Dalam beberapa kesempatan tinggal di Mentawai, memang, saya beberapa kali menyaksikan dan mengamati dengan saksama, bagaimana seekor babi disembelih dan diolah. Keempat kaki binatang yang menurut mitos orang Mentawai adalah pemberian langsung dari para leluhurnya dan diturunkan dari langit itu, diikat dan dibaringkan di depan uma.
Lehernya ditusuk dengan sebilah parang yang teramat runcing dan tipis, dan darahnya yang mengalir dari lubang tusukan itu ditampung dalam sebuah panci. Lalu, si babi yang telah mati dan tak lagi berdaya untuk sekadar menguik itu, dibedah dan dikeluarkan isi perutnya, sebelum kemudian tubuhnya yang malang dibakar di atas seunggun api untuk merontokkan bulu-bulunya.
Dan setelah bulu-bulunya hangus dan rontok—yang menguarkan bau tak sedap dalam penciuman saya—tubuh si babi dicincang sedemikian rupa, dan dimasak dalam kuali beserta darah yang tadi ditampung dan jeroan yang telah dibersihkan. Sementara kedua daun telinganya, tidak disertakan dalam rebusan daging babi itu.
“Tidak enak,” kata kawan yang menemani dan menjadi penerjemah saya selama menjalani residensi penulis di Mentawai itu. Jadi, bagian kuping babi itu dipisahkan karena akan merusak rasa masakan jika dicampurkan dalam rebusan. Begitu kawan saya menjelaskan.
Nah, kawan penerjemah saya itu adalah seorang Mentawai. Dia lahir dan besar dan berumah tangga di Mentawai, tepatnya di Dusun Madobag. Meski pengetahuannya tentang kebudayaan moyangnya agak terbatas, tapi ada sesuatu yang “unik” dalam dirinya. Dia mengaku telah “memeluk” agama Islam sejak beberapa tahun terakhir, namun tak pelak ia masih juga menikmati daging babi.
Tentu saja saya tak hendak mencegahnya, mengingatkannya, apalagi melarangnya, untuk tidak mengonsumsi daging babi yang diharamkan agama Islam itu. Sebab, saya toh tidak sedang menyiarkan suatu keyakinan dan tidak memiliki kapasitas untuk melarang orang lain. Saya hanya sedang belajar tentang hidup dan kehidupan orang Mentawai, yang justru mengharuskan saya untuk mengapropriasi, mengafirmasi, dan memahami segala hal yang mereka yakini sampai ke akarnya yang paling dalam.
Lambat laun, saya mendapati bahwa kawan saya ini bukan satu-satunya orang Mentawai yang saya temui, yang mengaku beragama Islam tapi masih juga mengonsumsi babi. Pertanyaan “mengapa” tentu saja tak terelakan dalam kepala saya. Namun, sebelum melontarkan pertanyaan semacam itu, lebih dulu saya mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri: apakah benar bahwa babi “menjadi haram” dalam benak dan pemahaman saya lantaran pengaruh agama saya, atau lantaran kebudayaan yang mengonstruksi dan melekat begitu kuat dalam tubuh dan pikiran saya?
Demi memahami keterkaitan antara babi dan agama atau kebudayaan itu, maka saya melakukan wawancara secara intensif dan mendalam dengan beberapa informan yang telah saya identifikasi dan tentukan. Dan dari hasil wawancara itu, saya mendapati jawaban-jawaban yang menarik sekaligus mencengangkan, yang kemudian saya rangkum dalam beberapa kalimat pernyataan, sebagai berikut.
“Agama kami (memang) Islam, tapi tubuh kami Mentawai. Dan orang Mentawai memakan babi. Tubuh kami suka daging babi. Dalam pesta-pesta harus ada babi. Jadi, tubuh kamilah yang menginginkan dan memakan babi, bukan agama kami.”
Begitulah. Dan rumusan serupa dari orang-orang Mentawai yang saya wawancarai itu, terkonfirmasi kemudian oleh Maskota Delfi—salah seorang dosen Antropologi di Universitas Andalas—melalui artikel jurnalnya yang bertajuk “Islam and Arat Sabulungan in Mentawai”. Apalagi, dalam kebudayaan orang Mentawai, babi—selain juga ayam—merupakan binatang yang amat penting, baik sebagai makanan dalam hidangan berbagai ritual uma, alak toga (mas kawin), tulou (denda), dan keperluan lainnya.
Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, barangkali perlu saya tambahkan pernyataan informan-informan yang dikutip secara cukup panjang oleh Delfi, yang menurut saya, menarik untuk diperhatikan:
“Kata sasareu sipuisilam (pemeluk agama Islam dari luar Mentawai), babi haram. Teteu siburuk (nenek moyang terdahulu) kami juga mengatakan kalau sasareu selalu sebut babi itu haram dan sasareu tidak mau memakannya. Tapi kami lihat ada juga sasareu yang memakannya, Sainias (orang Nias) suka makan babi, Saibatak (orang Batak) juga banyak yang suka makan babi”.
“Jadi, sasareu itu ada yang makan babi, ada yang tidak. Sasareu Sipuisilam tidak makan babi. Kalau di sini, di Mentawai, di Siberut ini, kami semua suka babi …. Kami sudah lama diberitahu kalau babi haram. Ya, babi haram, tapi babi mananam (enak). Kami tidak makan babi yang haram, tapi babi yang mananam yang kami makan”.
Jadi, babi haram jangan kita makan, babi yang mananam saja yang kita makan. Rugi kita kalau babi mananam tidak kita makan. Seperti kata sasareu, rezeki jangan dibuang, itu namanya mubazir. Kalau mubazir tidak boleh, tidak bagus itu. Jadi babi mananam jangan dibuang.”
Atau penyataan informan lainnya yang tak kalah menarik, sebagai berikut.
“Memang arat [dalam kontek ini kata arat berarti agama] saya Islam, kami di Mentawai Siberut ini menyebut orang yang punya arat Islam itu Sipuisilam. Tapi yang Isilam itu kan arat saya. Saya makan babi, anak-anak saya juga makan [babi], semua keluarga saya makan babi. Kami punya babi, sudah kita pelihara baik-baik, kita kasih makan sagu tiap hari, karena kita mau makan dagingnya. Sayang kalau tidak kita makan”.
Kalau kita tidak mau makan dagingnya untuk apa kita susah-susah peliharanya. Kadang kami jual juga kalau ada yang mau beli, biasanya kalau ada lia (ritual), orang beli babi pada kami. Saya makan babi karena saya memang suka makan babi walau arat saya Isilam. Arat Isilam, tapi tubuh saya tidak. Tubuh saya ini Mentawai, makanya saya makan babi. Yang makan babi itu mulut saya, tubuh saya, bukan arat saya.”
Saya merenungi dan mencoba memahami pernyataan-pernyataan itu, dan bagaimana orang Mentawai sampai pada sebuah konsep yang membedakan (secara ekstrem?) antara tubuhnya dan agamanya. Namun kemudian, agaknya saya bersepakat dengan pandangan Delfi yang menyatakan bahwa larangan mengonsumsi babi bagi penganut agama Islam, oleh kebanyakan orang Mentawai—khususnya yang beragama Islam—di Pulau Siberut, sulit untuk dipahami, apalagi untuk dipraktikkan.
Secara sederhana, barangkali dapat dikatakan bahwa larangan itu tidak masuk akal karena tidak bersesuai dan tidak berterima bagi alam lingkungan dan perikehidupan orang Mentawai.
Konstruksi Budaya
Sampai titik ini, kemudian saya memikirkan ulang tentang agama dan kebudayaan yang mengonstuksi keseluruhan diri saya. Adakah agama telah mengonstruksi diri dan kesadaran saya sehingga saya (atau tubuh saya) menolak dan tidak bisa memakan babi?
Ataukah kebudayaan yang melekat dalam diri dan kesadaran saya yang telah mengafirmasi ajaran agama karena pengharaman terhadap babi dianggap bersesuai dan berterima dengan adat dan kebiasaan leluhur saya? Dan bukankah dalam alam lingkungan tempat saya tumbuh—di Serang, Banten—, kemudian menyerap berbagai-bagai nilai kebudayaan di dalamnya, tak pernah saya temui babi ataupun olahan daging babi?
Saya mengingat-ingat bagaimana kesadaran tentang agama dan kebudayaan itu menjadi bagian dari diri saya. Dan meski tidak berhasil mengingat sampai ke dasar atau ke tahap paling awal dalam kehidupan yang saya jalani, saya toh mulai menelusuri ingatan-ingatan yang dapat saya kenangkan kembali.
Salah satunya, ingatan pada pesantren dengan kobong-kobong berbilik bolong yang pernah saya tinggali, pada Madrasah Tsanawiyah yang pernah saya masuki, yang bagaimanapun, tentu pembelajaran di dalamnya telah menjadi bagian dari kesadaran saya hingga saat ini. Barangkali, termasuk kesadaran bahwa babi adalah haram untuk saya konsumsi.
Namun, saya tak dapat mengabaikan kenyataan bahwa dalam alam lingkungan dan kebudayaan yang saya jalani selama ini, saya tak pernah mendapati babi di keluarga saya, baik sebagai binatang liar yang diburu, binatang ternak, atau menu makan. Tidak juga saya mendapati daging babi terhidang dalam pesta-pesta daur hidup yang saya warisi dari kebudayaan leluhur.
Kecuali, sekali pernah saya saksikan seekor babi malang yang dibantai anjing-anjing pemburu dalam arena ngadu bagong di Garut, yang justru membikin saya ngeri dan jatuh kasihan kepada si babi yang terus saja menguik ketakutan sembari melarikan diri ke sana ke mari.
Dalam kebudayaan yang saya resapi, tampaknya babi memang tak pernah menjadi bagian dalam perikehidupan urang Sunda, selain sekadar dianggap sebagai hama, yang oleh karenanya dianggap layak dibantai anjing-anjing dalam arena ngadu bagong itu. Maka, dengan demikian, dalam benak saya menyimpan kesimpulan yang tak lagi dapat ditawar bahwa babi bukan untuk dikonsumsi; babi bukan makanan! Untuk itu, sebagaimana orang Mentawai yang sulit memahami mengapa suatu ajaran agama mengharamkan babi untuk dikonsumsi, saya pun sulit memahami mengapa ada orang yang bisa mengonsumsi babi.
Dalam kesulitan memahami itu, saya teringat salah satu esai Marshal Sahlins yang bertajuk “Food as Symbolic Code”. Melalui esai tersebut, Sahlins menyibakkan kode-kode simbolik atas empat jenis binatang (sapi, babi, kuda, dan anjing) sebagai suatu sistem budaya dalam masyarakat Amerika, yang ternyata menyokong hierarki sosial dalam masyarakat tersebut.
Menurut Sahlins, dalam kebudayaan Amerika yang tentu mengandung makna dan nilai yang diresapi masyarakatnya, keempat binatang itu menempati status dan derajat yang berbeda antara satu dan lainnya; yaitu, stratifikasi sebagai subjek/teman (kuda dan anjing) dan sebagai objek/makanan (sapi dan babi).
Bahkan, di dalam statusnya sebagai teman atau sebagai makanan, keempat binatang itu masih juga dipilah dan ditempatkan pada derajat tertentu guna menyokong hierarki sosial antara yang-kaya dan yang-miskin. Anjing dianggap memiliki derajat lebih tinggi daripada kuda sebab anjing diperbolehkan tinggal dan bahkan tidur bersama si empunya (di dalam rumah/apartemen dan melekat), sedangkan kuda ditempatkan di istal (di luar dan berjarak).
Sementara itu, sapi dianggap memiliki derajat lebih tinggi daripada babi karena daging sapi lebih disukai. Bahkan, bagian paha sapi, misalnya, selalu dihargai lebih mahal tinimbang bagian lainnya sehingga hanya yang-kaya saja yang mampu membeli dan menikmatinya, sedangkan bagian jeroan selalu dihargai dengan murah yang memang diperuntukkan bagi makanan yang-miskin.
Kita tahu, bahwa dalam persoalan makan-memakan-makanan itu, nilai dan makna simbolik dalam suatu kebudayaan tentu akan berbeda dengan nilai dan makna simbolik dalam kebudayaan lainnya. Dan dalam hal itu, bagi saya, agaknya penolakan tubuh saya terhadap babi tidak melulu dilandasi kesadaran pada pengharaman oleh agama, melainkan lebih dipengaruhi oleh nilai dan makna simbolik yang saya resapi melalui kebudayaan.
Atau barangkali, penolakan tubuh saya terhadap babi bertumpu pada kelindan antara agama Islam dan kebudayaan Sunda. Sebab, sekalipun bir atau wine diharamkan—meski tentu saja agama tidak tegas menyebut merek—, tapi alam lingkungan dan kebudayaan yang nilai-nilainya saya resapi, dapat dengan mudah menyediakan minuman sejenis seperti “anggur kolesom cap orang tua” yang biasa dikonsumsi kakek saya sehari seloki. Saya tahu, bahwa minuman itu tidak pernah diperlakukan seburuk memperlakukan babi dalam arena ngadu bagong itu, meskipun pernah saya “salah gunakan” karena menenggaknya lebih banyak tinimbang kebiasaan kakek saya itu.
Dengan demikian, jika orang Mentawai beragama Islam masih juga memakan babi yang mananam, tapi tidak memiliki kebiasaan menenggak minuman hasil fermentasi (karena dalam kebudayaan mereka tidak ditemukan minuman semacam itu), saya justru sebaliknya. Tubuh saya yang juga “kebetulan” beragama Islam, menolak mengonsumsi babi walaupun masih saja menoleransi untuk meminum bir atau wine (astaghfirullahal adziem), karena dalam kebudayaan saya minuman itu mudah saja ditemukan.
Sementara itu, kawan-kawan di berbagai daerah dengan latar kebudayaan lain, mampu menikmati keduanya: memakan daging babi (guling) sembari menenggak wine.








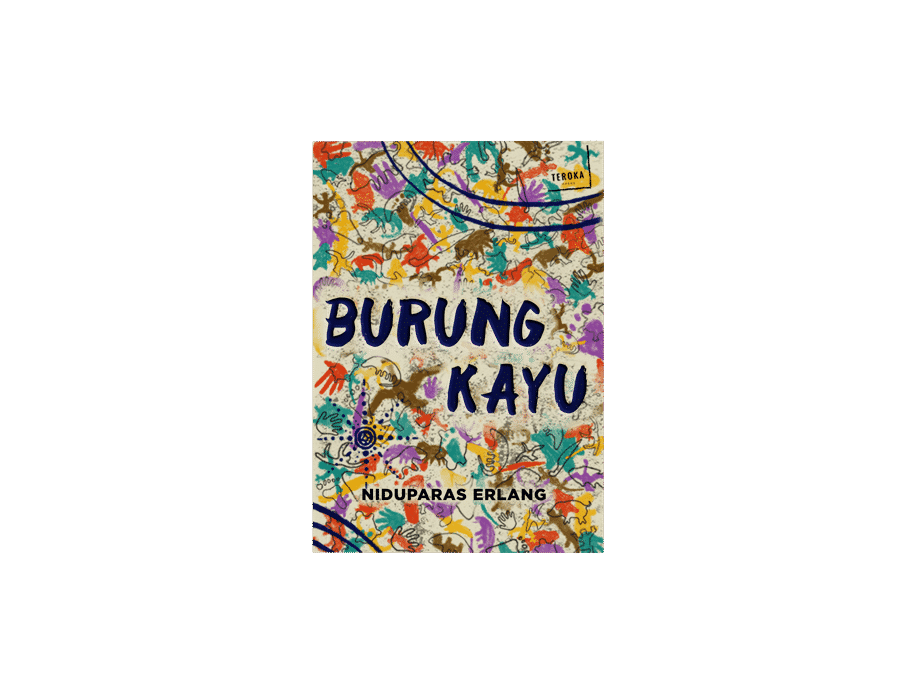








Tulisan yg sangat menarik
“Adakah “citra” haram si babi ini merupakan salah satu keberhasilan guru-guru agama kami, baik di madrasah ataupun di pesantren, dalam menanamkan suatu keyakinan yang tak bisa ditawar-tawar lagi? Sementara soal minuman yang memabukkan, kami masih saja bernegosiasi?”
Rasanya itu bukan hasil penanaman ideologi yg terstruktur misalnya melalui pesantren,
Kebanyakan islam ya taunya islam nggak makan babi.
Sy pribadi (dr keluarga mualaf batak, di tengah lingkungan kristen, rumah sebelahan kandang babi) teramat anti dengan babi tapi masih santai soal minum 😂
Tulisan bagus dan menarik. Kecuali bagian tentang telinga ‘yang tidak enak’ dan ‘merusak rasa masakan…’. Banyak karya etnografi-dan ini rasanya semua orang mentawai dewasa, kecuali narasumbermu-yang bisa menjelaskan kenapa telinga, terutama yang kiri (sikatciu talinga), hewan persembahan maupun hasil buruan tak dimakan.
Terima kasih, Bung Simapea. Dalam hal “telinga” itu, iya, ternyata saya luput mengecek ulang dan luput menyebutkan di sini bahwa telinga hewan itu merupakan bagian yang disemahkan… Koreksi atas hal-hal yang mendetail semacam ini sangat saya perlukan untuk terus-menerus mengonfirmasi catatan-catatan yang saya buat, dan mengecek ulang karya-karya etnografi lain. Terima kasih untuk koreksinya…
Salam hangat.
N.E.