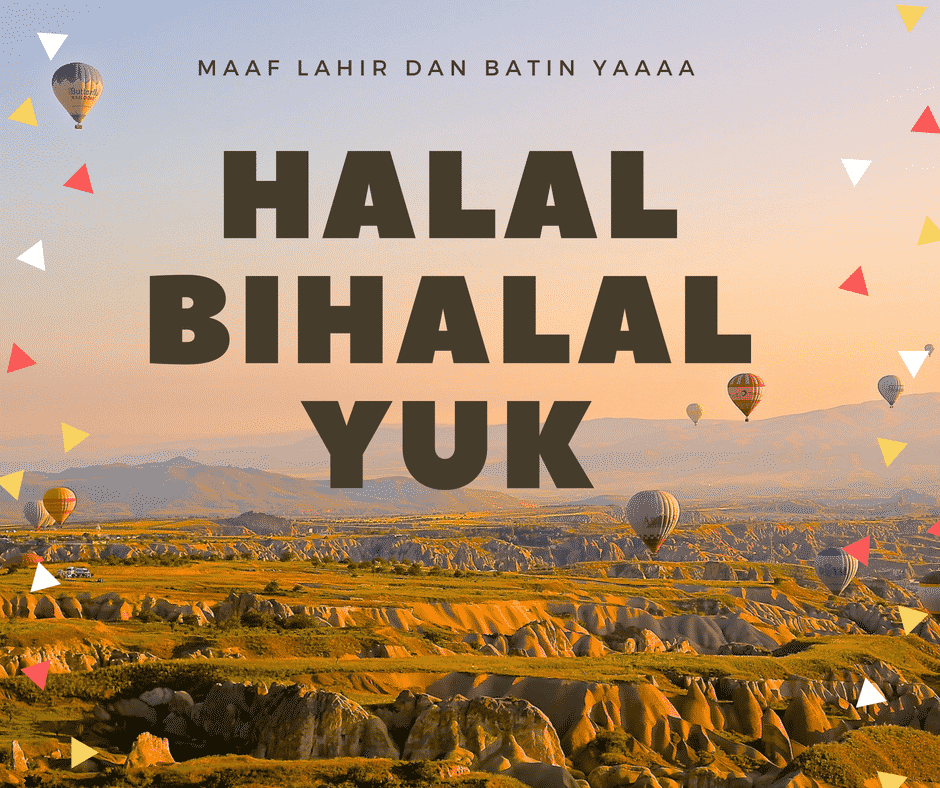Soekarno, Tan Kiem Liong, dan Makan Siang Kiai-Kiai

Pasca peristiwa September 1965, situasi politik Indonesia menjadi rumit dan mencengangkan. Pada awal tahun 1966, Presiden Soekarno menjadi orang yang kesepian. Ia tersingkir dari hiruk pikuk kekuasaan, meski masih menjadi pemimpin bangsa, tapi fungsi politiknya terpangkas habis. Orang besar yang dihilangkan peran pentingnya. Setelah berpuluh tahun berjuang di tengah turbulensi politik, kemewahan kekuasaan dan riuhnya kepemimpinan, jelas Soekarno merasa senyap jika dijauhkan dari panggung politik.
Situasi bertambah rumit pasca terbitnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966. Kekuasaan politik Soekarno secara perlahan berpindah ke tangan Soeharto. Situasi bertambah rumit setelah itu, dengan redupnya kekuasaan Soekarno. Bahkan, presiden Soekarno tidak diperbolehkan masuk istana sekembali keliling Jakarta pada Mei 1967. Sungguh ironis. Sejak saat itu, Soekarno menjadi tahanan kota serta menetap di Wisma Yaso, sampai akhir 1967.
Pada suatu ketika, Soekarno ingin mengobati kangen dengan makan siang bersama kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Pada waktu itu, jarang sekali ada tokoh politik dan militer yang berani membersamai Soekarno, apalagi menjadi tuan rumah untuk kongkow bersamanya.
Seorang pemberani itu bernama Tan Kiem Liong (dikenal sebagai Moh Hassan). Ia Tionghoa muslim yang aktif di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga Menteri Pendapatan, Pengeluaran, dan Penelitian mewakili Partai NU.
Mahbub Djunaidi, menceritakan kisah ini melalui sepucuk esai ‘Soekarnoisme: Suatu Ujian Sejarah’. Kisah-kisah tentang Soekarno yang kesepian, juga kepedulian serta keberanian kiai-kiai NU.
“Aku kepingin ngobrol sambil makan siang dengan kiai-kiai NU. Di manakah mereka itu sekarang? Bagaimana caranya? Kau bisa atur? Dengarkan baik-baik: Cuma makan siang, tidak lebih tidak kurang!,” pinta Soekarno.
‘Di rumah siapa?” Mahbub bertanya.
“Siapa saja. Idham boleh, Djamaluddin Malik boleh. Mana saja yang sudi mengundangku makan siang.” Kita bisa merasakan betapa sepinya Soekarno. Ia terbiasa dengan kerumunan, lalu dihempaskan ke ruang senyap.
Mahbub Djunaidi kemudian pusing tujuh keliling. Tidak ada orang yang berani menemani Soekarno makan-makan, apalagi kongkow berderai tawa. Politisi dan jenderal militer bungkam, mereka menjauh dari Soekarno pasca peristiwa 1965.
Hanya kiai-kiai NU yang berani menemani Soekarno, tidak peduli dengan hantaman politik Orde Baru. Kiai-kiai NU memang dikenal berani, acuh dengan hiruk pikuk kekuasaan, serta mau menemani Soekarno dalam konteks persahabatan dan silaturahim kemanusiaan.
“Maka berputar-putarlah saya menawarkan keinginan yang begitu teramat sederhana ini. Makan siang! Apakah makan siang di saat sekarang ini begitu sulit? Ternyata memang sulit. Orang mesti berpikir seribu kali ketamuan seorang ‘gergasi’ makan siang di rumahnya. Si Polan tidak bersedia. Si Badu keluar keringat dingin mendengar permintaan ini. Di awal tahun 1966, menerima Bung Karno makan siang di rumahnya, sungguh sesuatu yang tak terbayangkan,” demikian kenang Mahbub.
Mahbub Djunaidi hampir patah semangat mencari orang yang mau menjadi tuan rumah untuk gawe kecil ‘makan siang’ bersama Soekarno. Gawe kecil yang membutuhkan keberanian besar dan kenekadan kelas tinggi.
“Untung ada seorang yang punya nyali besar, semata-mata ingin mengabulkan keinginan sederhana seorang sahabat yang melayang-layang antara bumi dan langit. Orang itu adalah Tan Kiem Liong (H. Moh. Hassan), bekas menteri Pendapatan, Pengeluaran, dan Penelitian. Dan saat itu, jadi Menteri Negara entah apa urusannya. Baiklah, katanya. Maka makan siang pun terjadi di rumahnya di Jalan Senopati, Kebayoran Baru. Hanya makan, sesudah itu bubar.”
Dalam kenangan Mahbub Djunaidi, Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syansuri pun ikut menemani makan siang itu. Keduanya jelas tidak peduli dengan ancaman antek-antek Orde Baru yang memagari Soekarno, memenjarakan Bung besar dengan sunyi senyap politik. Tentu, makan siang itu disajikan dengan menu keberanian sekaligus kenekadan yang terhampar di meja.
Mengenai Soekarno yang kesepian, Mahbub Djunaidi mengilustrasikan betapa presiden pertama Indoensia itu, mengalami kegoncangan batin selepas dipangkas kuasanya. Bung Karno mengalami badai psikologis, selepas tersingkir dari panggung kekuasaan. Memang Bung Karno masih terlihat sehat secara fisik, tapi hati dan pikirannya, jiwa dan mentalnya terhantam keras oleh badai politik yang tidak disangka-sangka.
Mahbub mengenang ironi Soekarno: “Siapakah yang bisa membayangkan: seorang penggerak dan pemersatu nation. Seorang musuh nomor satu kolonial, seorang proklamator tanah air yang begini besar, seorang macan Dunia Ketiga, pada suatu saat menghadapi kesulitan minta makan siang bersama teman-temannya?”
Inilah kisah epik makan siang Soekarno bersama kiai-kiai. Makan siang di tengah prahara politik. Makan siang yang selayaknya dikenang hingga kini: siapa saja yang berani membersamai Soekarno ketika terlempar dari kekuasaan. (aa)