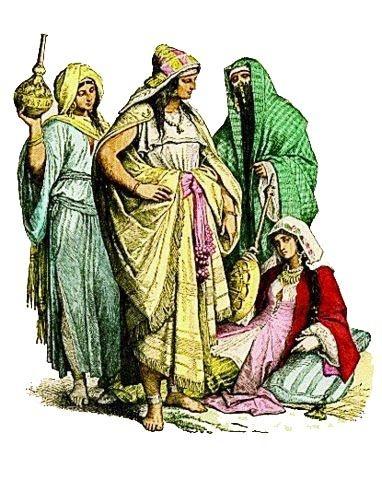Bangsa Arab merupakan bangsa dengan peradaban syair. Mereka merekam semua aktivitas di dalam kehidupan, mulai dari cara hidupnya, agamanya sampai pada rasionalitasnya ke dalam gubahan bait-bait syair. Tak heran jika seorang penyair menjadi barometer intelektualitas Arab masa itu.
Hal tersebut dikarenakan, selain seorang penyair dituntut untuk kreatif dalam menyusun syairnya, ia wajib memahami hal-ihwal yang menyangkut kehidupan bangsanya pada masa lalu. Dengan demikian, selain memiliki dzauq kebahasaan yang tajam, penyair adalah seorang antropolog dan sosiolog. Alasannya sederhana, syair tidak hanya cermin dari produk kesenian, namun di saat yang sama juga sebagai cermin dari intelektualitas.
Sampai-sampai di dalam al-Qur’an terdapat surat dengan nama al-Syu’ara’, yang berarti para penyair. Ini membuktikan bahwa para penyair di masa sebelum Islam mempunyai kedudukan tersendiri di mata bangsa Arab. Dan ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa syair mempunyai pengaruh tersendiri dalam kehidupan mereka.
Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad Saw mendapatkan wahyu, kemudian menyampaikannya kepada umatnya, orang-orang yang tidak beriman menyebut Nabi Saw sebagai seorang penyair. Hal ini tidak lain karena keindahan susunan kalimat yang mampu menyihir baik telinga, hati dan pikiran para pendengar adalah selalu identik dengan syair.
Jawad Ali di dalam al-Mufasshal fî Târîkh al-‘Arab qabla al-Islâm mengungkapkan bahwa syair merupakan cara yang digunakan masyarakat Arab Jahiliah untuk merekam pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam kehidupan mereka ketika peradaban tulisan belum populer masa itu. Syair pula menjadi semacam ensiklopedi Arab yang hidup lewat peradaban oral.
Suatu kabilah biasanya mempunyai para penyair yang meriwayatkan syair-syair yang berkaitan dengan kabilahnya. Bahkan bukan hanya para penyair saja. Para anggota kabilah biasa, yang bukan seorang penyair, juga ikut andil dalam menyampaikan cerita-cerita kabilahnya, kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang pernah diraihnya, kepada generasi selanjutnya melaui syair-syair kaumnya.
Dan menurut Syauqi Dhaif di dalam Târîkh al-Adab al-‘Arabiy, seringkali dijumpai para penyair—dan juga perawi syair—yang meriwayatkan syair dari golongan lain. Sepertinya tipologi yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai intelektual murni. Ia meriwayatkan syair bukan karena fanatisme kesukuan, tetapi karena memang ia mencintai sejarah secara umum atau mencintai syair tanpa memandang siapa penciptanya.
Tradisi oral yang ada pada masyarakat Arab Jahiliah tentunya mempunyai karakter berbeda dengan tradisi literal yang ada setelah masuknya Islam. Dalam tradisi oral, kehadiran seorang pendengar sangat diperlukan ketika sebuah teks diujarkan, agar pesan yang ada dalam teks dapat tersimpan secara baik dalam memori pendengar.
Kondisi ini sangat berbeda dengan tradisi literal. Seseorang bisa menulis kapan pun dan di mana pun tanpa takut pesan yang akan disampaikan hilang. Karena pembaca dapat membuka kembali lembaran-lebaran pesan penulis jika memang dibutuhkan di kemudian.
Karena pesan yang ada dalam tradisi oral lebih rawan hilang, maka muatan-muatan yang dibicarakan cenderung sederhana tanpa menggunakan konsep-konsep rumit. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan mudah untuk diingat.
Merujuk pada pendapat Walter J. Ong, bahwa bangsa Yunani sebelum Socrates lebih sering berbicara keadilan melalui realita-realita aplikatif daripada melalui istilah-istilah konseptual. Sulit dibayangkan dalam tradisi oral terdapat konsep-konsep metafisis ataupun konsep kritik teks. Karena yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana cara menyelamatkan sebuah pesan dari kepunahan.
Dengan demikian, potret kehidupan masyarakat Arab Jahiliah yang dititipkan dalam gubahan-gubahan syair, disampaikan dari generasi ke generasi melalui tradisi oral, masih dalam bentuk yang sederhana. Maksud saya, kita belum banyak menemukan analisa-analisa kritik teks terkait matan syair. Seakan-akan tanpa peduli apakah sebuah syair telah memenuhi standar syair atau tidak, memiliki cacat atau tidak.
Seperti yang diceritakan oleh Ahmad Amin di dalam Fajr al-Islam, apa yang dilakukan oleh para intelektual Arab Jahiliah ketika itu mirip seperti apa yang dilakukan para muhaddis dalam menilai otentisitas hadis. Mereka melakukan Jarh wa al-Ta’dîl untuk mendiagnosa mata rantai sanad. Masyarakat Arab jahiliah menempatkan mata rantai riwayat sebagai ukuran logis sebuah ilmu.
Dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini al-Qur’an turun membawa nafas baru, berhembus di sela-sela jantung masyarakat penyair dengan nadzm-nya yang tak biasa, menyembuhkan hati-hati yang lumpuh dengan ajaran-ajaran langit, mengajak manusia mengenal siapa Dzat yang telah menciptakannya.
Al-Qur’an sepertinya paham betul dengan kondisi masyarakat Arab yang menempatkan syair sebagai barometer intelektualitas. Kitab suci yang terakhir turun ini, meskipun bukan berbentuk syair, memaksa para penyair bungkam seribu bahasa melihat susunan kalimat-kalimat yang berpadu indah dengan mutiara makna-maknanya, mengakui betapa kedahsyatan mukjizat Allah Swt bukanlah kuasa manusia untuk mampu menandinginya.
Karena al-Qur’an begitu memahami masyarakat Arab, proses perkenalan antara keduanya dapat dikatakan cukup mudah. Al-Qur’an berbicara tentang kebiasaan mereka berdagang ke negeri Syam di musim panas dan ke negeri Yaman di musim dingin. Al-Qur’an berbicara tentang tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mereka. Al-Qur’an berbicara tentang berhala-berhala yang mereka sembah.
Dan pada akhirnya, al-Qur’an mengajak mereka untuk berintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan mereka dalam menuhankan yang bukan semestinya.
Setelah al-Qur’an mengenalkan Tuhan yang patut untuk disembah, al-Qur’an mengajarkan tata cara untuk mengabdi kepada Tuhan. Melalui perantara Nabinya, al-Qur’an mengajarkan shalat, puasa, haji dan menetapkan aturan-aturan tertentu, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.
Karena teks-teks al-Qur’an yang demikian terbatas, fungsi seorang Nabi Saw di sini adalah sebagai penyampai maksud al-Qur’an jika terdapat hal-hal yang belum jelas. Al-Qur’an dan ajaran-ajaran Nabi Saw yang termanifestasikan dalam hadis, merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan ketika kita membincang tentang sumber-sumber ajaran Islam. Wallahu A’lam.