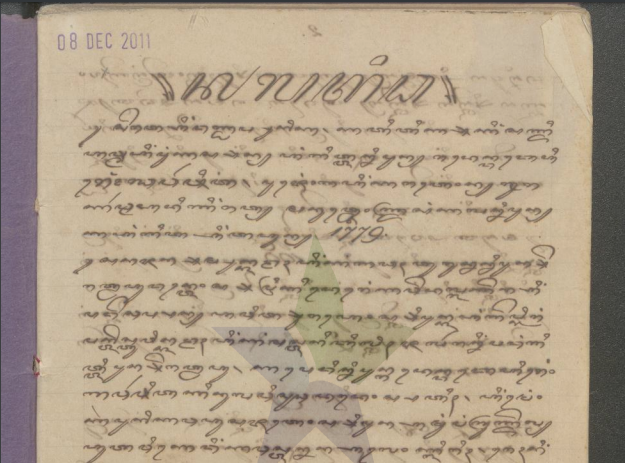
Pemaknaan atas kalabendu kadang disempitkan menjadi zaman yang penuh dengan bencana (disaster). Bayangan makna ‘bencana’ terkadang hanya selesai pada fenomena alam (natural disaster), jarang menyoroti adanya sebuah fenomena sosial yang masif (social disaster).
Pemilihan gaya bahasa ini tentu bukan sebuah kebetulan atau kekosongan, tetapi sebuah refleksi bagaimana kondisi sosial pada masa itu—penulisan Serat Kalatidha—sarat dengan kepentingan dan konflik sosial. Kondisi politik pasca Perang Jawa mengakibatkan adanya friksi di kalangan masyarakat Jawa. Ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Anderson (1976) bahkan menyebut Kalatidha ini sebagai “Poem of a Time of Darkness” yang ditulis sebagai ‘ratapan’ berlalunya kejayaan Jawa setelah Perang Diponegoro.
Diksi kalabendu berakar dari kata kala dan bendu. Kata kala bermakna wektu, mongsa, nalika yang berasosiasi dengan makna waktu (Padmasusastra, 1903; Dirjasupraba, 1931; Purwadarminta, 1939). Adapun kata bendu bermakna nepsu, wewelak, bramantya, yang berasosiasi dengan makna kemarahan dan keinginan (Dirjasupraba, 1931; Purwadarminta, 1939). Apabila dua kata ini digabung akan memunculkan makna sebuah masa yang dipenuhi oleh gejolak nafsu dan keinginan. Jika kata Kalabendu direlasikan dengan ‘bencana’, maka yang dimaksud dengan ‘bencana’ (bañcana/wañcana) oleh Wojowasito dalam Kamus Kawi – Indonesia (1977) salah satunya sebagai tipu daya atau kekecewaan.
Keberadaan kebijakan tanam paksa dan sewa tanah mendorong adanya kapitalisasi lahan di Surakarta oleh lembaga swasta dan perusahaan pertanian (Hanafi, 2015). Kapitalisme lahan membawa perlawanan sosial bagi masyarakat Jawa. Masyarakat petani desa merasa dirugikan karena sebagian lahan pertanian mereka diambil alih oleh pihak kolonial.
Di sisi lain, pihak bangsawan Jawa menerima keuntungan sebagai bagian dari hasil penyerahan hasil bumi kepada kolonial (Kurnia, 2012). Taylor dalam Susanto (2017) juga menuliskan bahwa walaupun proporsi penduduk Eropa sedikit, tetapi mereka memegang jabatan penting dan bisa menentukan selera hingga kebijakan yang berlaku di dalam kota.
Kondisi ini menjadi cermin bahwa Ranggawarsita menuliskan konsep zaman edan sebagai keinginan yang tidak terbendung. Ia menuliskan bahwa keberadaan pemimpin yang utama (ratune ratu utama), patihnya orang yang piawai (patihe patih linuwih), para pejabat kerajaan yang berhati baik (pra nayaka tyas raharja) pun tidak bisa membendung adanya keinginan.
Kalabendu adalah masa yang penuh dengan keinginan individual (beda-beda hardane wong sanegara), menjadi penanda bahwa gejolak sosial yang menghambat kejayaan dan kemakmuran (rubeda kang ngreribeti). Keberadaan monopoli kekuasaan dan kapitalisme menjadi ajang kompetisi para bangsawan dalam mempertahankan eksistensi kekuasaan dan acapkali kurang memperdulikan kondisi masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri dalam teks ini juga menyajikan dilema batin Ranggawarsita sebagai antitesis dalam menyikapi zaman edan. Dalam teks Serat Kalatidha disebutkan bahwa eling lan waspada menjadi jalan menghadapi permasalahan. Ia mengajak pembacanya untuk kembali ingat dan waspada dari adanya kompetisi dan hegemoni.
Sebagai perlawanan, ia menyajikan sebuah pandangan yang tuangkan dalam peribahasa seberapa beruntungnya orang yang terlelap dalam kealpaan zaman edan, masih beruntung mereka yang ingat dan waspada (begja begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada).
Implementasi eling lan waspada pun cukup terbatas mengingat dua hal ini dijalankan atas kesadaran individu. Artinya, ajakan dan pesan yang tersurat dalam teks merupakan wujud persuasif untuk melihat kembali bagaimana kondisi sosial. Namun demikian, sebagai sebuah sintesis atas sejarah untuk melihat masa depan, hal ini menjadi sarana pembelajaran kita dalam berkaca melihat masa depan; melihat tantangan dan peluang dari kisah masalah sosial di masa lampau. Membangun kondisi masyarakat yang humanis setidaknya dibutuhkan kondisi eling atau kesadaran dan waspada sebagai kehati-hatian.
Ranggawarsita sejenak mengingatkan bahwa refleksi eling lan waspada adalah mengembalikan fungsi atas kesadaran manusia. Eling sebagai adalah modal dasar manusia untuk melihat kondisi hati dalam diri manusia. Sebagai makhluk yang berakal, tidak semestinya memiliki tendensi berkompetisi untuk saling menguasai.
Menurutnya, jalan logis adalah berikhtiar tanpa melalu tindakan pragmatis, karena dalam proses usaha itu selalu disertai pertimbangan dan muhasabah. Pertimbangan ini menjadi sarana untuk menimbang bahwa semua orang pada dasarnya memiliki keinginan dan ambisi. Ketika tidak ada pengendalian diri, akan terjadi peningkatan konflik dan kesenjangan sosial. Saling sikut untuk urusan kepentingan pribadi jelas-jelas mengurangi hak orang lain yang sepatutnya dihargai.
Konsep waspada adalah cara pandang kehati-hatian dalam melihat realita bahwa tidak semua keinginan individu itu bisa terwujud. Selalu ada tegangan kepentingan orang lain yang berdampingan dengan keinginan kita. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Freud dalam konsep psikoanalisisnya menyebut ada id (dorongan biologis), ego (kesadaran diri), dan super-ego (keberadaan dorongan dari luar diri). Kewaspadaan dapat dikatakan sebagai cara Ranggawarsita menyeimbangkan dorongan id, ego, dan super-ego.
Membawa wacana mengumbar nafsu maupun makna eling-waspada dalam era kekinian adalah sebuah jalan ‘memotong’ budaya pragmatisme dan egosentrisme. Kegilaan dalam hal memperbesar pengaruh, sosial, ekonomi, dan budaya masih dijalani sebagian pihak. Beberapa orang menempuh jalan pintas dan menafikkan konsep laku dan perasaan dalam meraih tujuan. Tak jarang saling sikut dan bentrokan kepentingan masih dianggap hal lumrah.
Dengan demikian, budaya saling mengalahkan dan menihilkan nilai kemanusiaan inilah yang dikiaskan sebagai zaman edan: tata nilai bagi sebagian orang sudah membeku dikristalisasi dan tidak mencair dalam hati sanubari. Kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya adalah ironi yang kita amati saat ini. Begitulah zaman edan dimana orang yang benar dihadapkan pada kompetisi tidak sehat (sujana sarjana kelu, hambeg jatmika kontit).
Paradigma wañcana sebenarnya adalah refleksi bahwa manusia-lah yang terkadang membohongi dirinya sendiri: seandainya manusia tidak bersaing membabat hutan dan membangun gedung pencakar langit, sungai takkan dangkal dan banjir tidak melalap lahan-lahan pemukiman di dataran rendah. Tidak banyak yang hanyut dalam zaman edan, tetapi penyimpangan sosial segelintir orang inilah seperti memercik api dalam sekam. Semakin dipelihara akan meraja lela. Begitulah Ranggawarsita menuliskan, “mangkin saya andadra, rubeda kang ngreribeti”.















