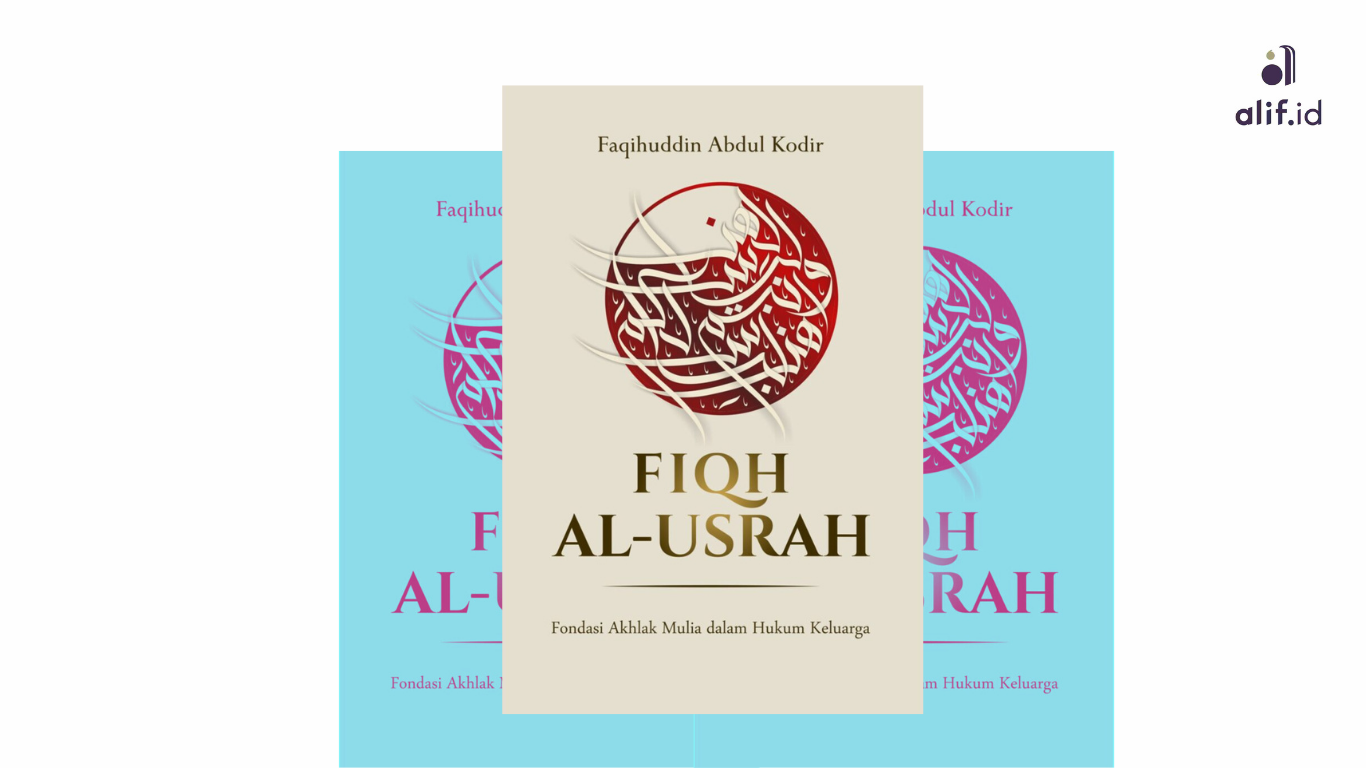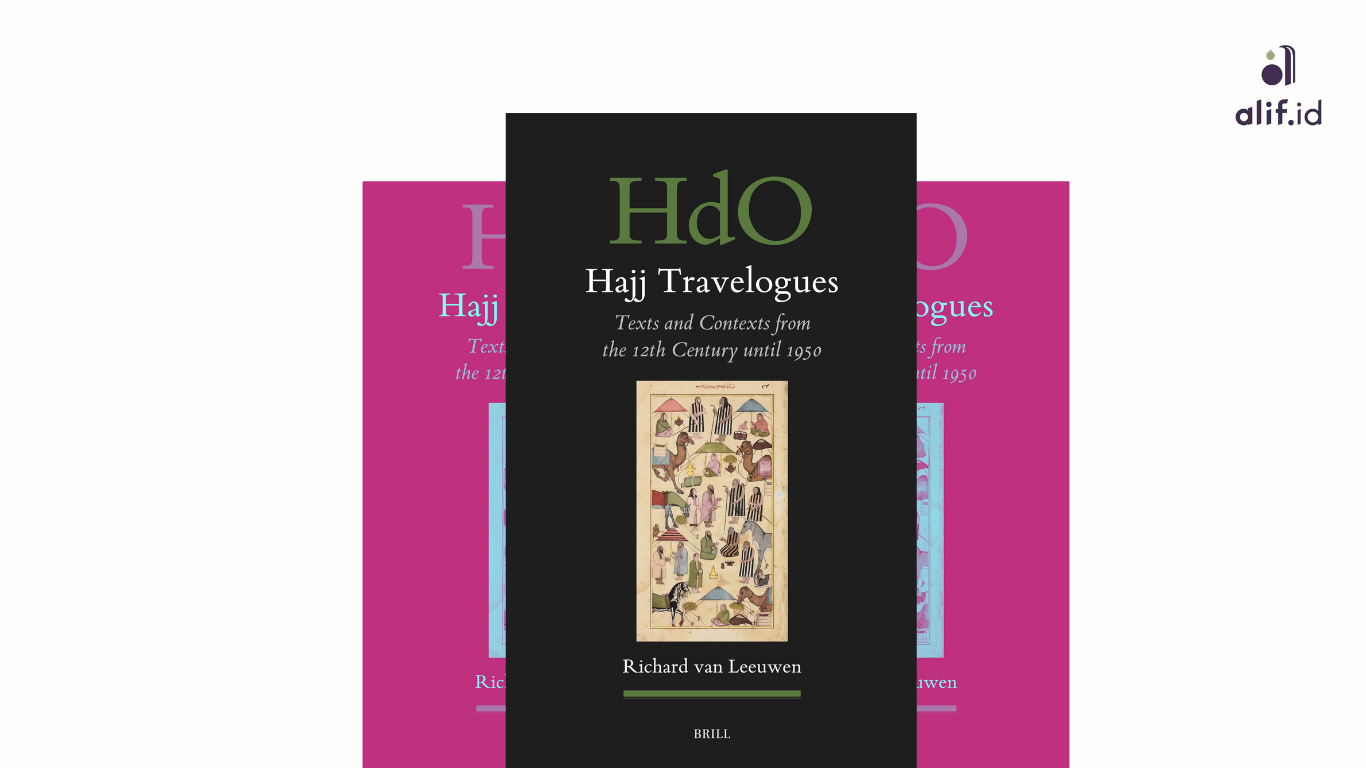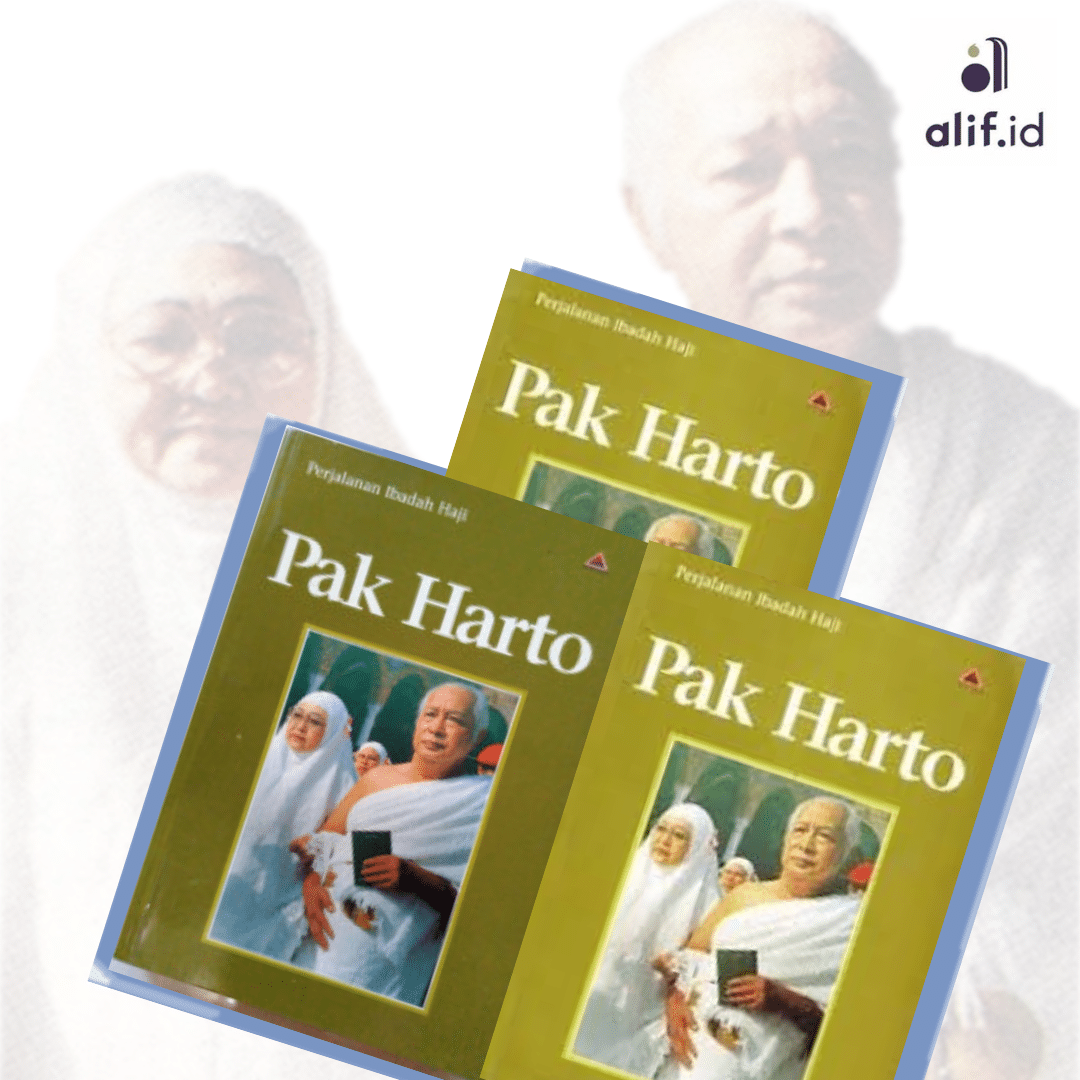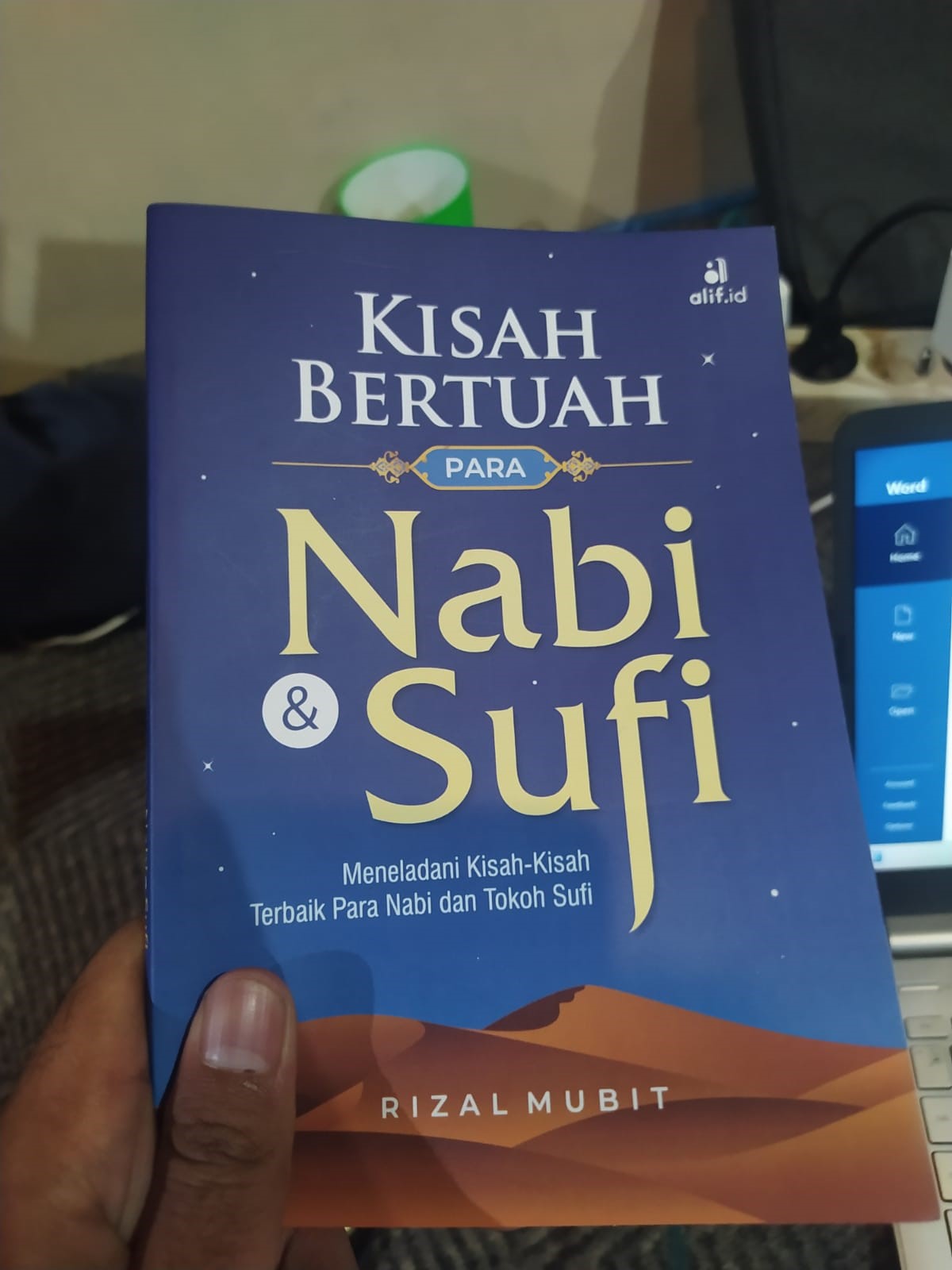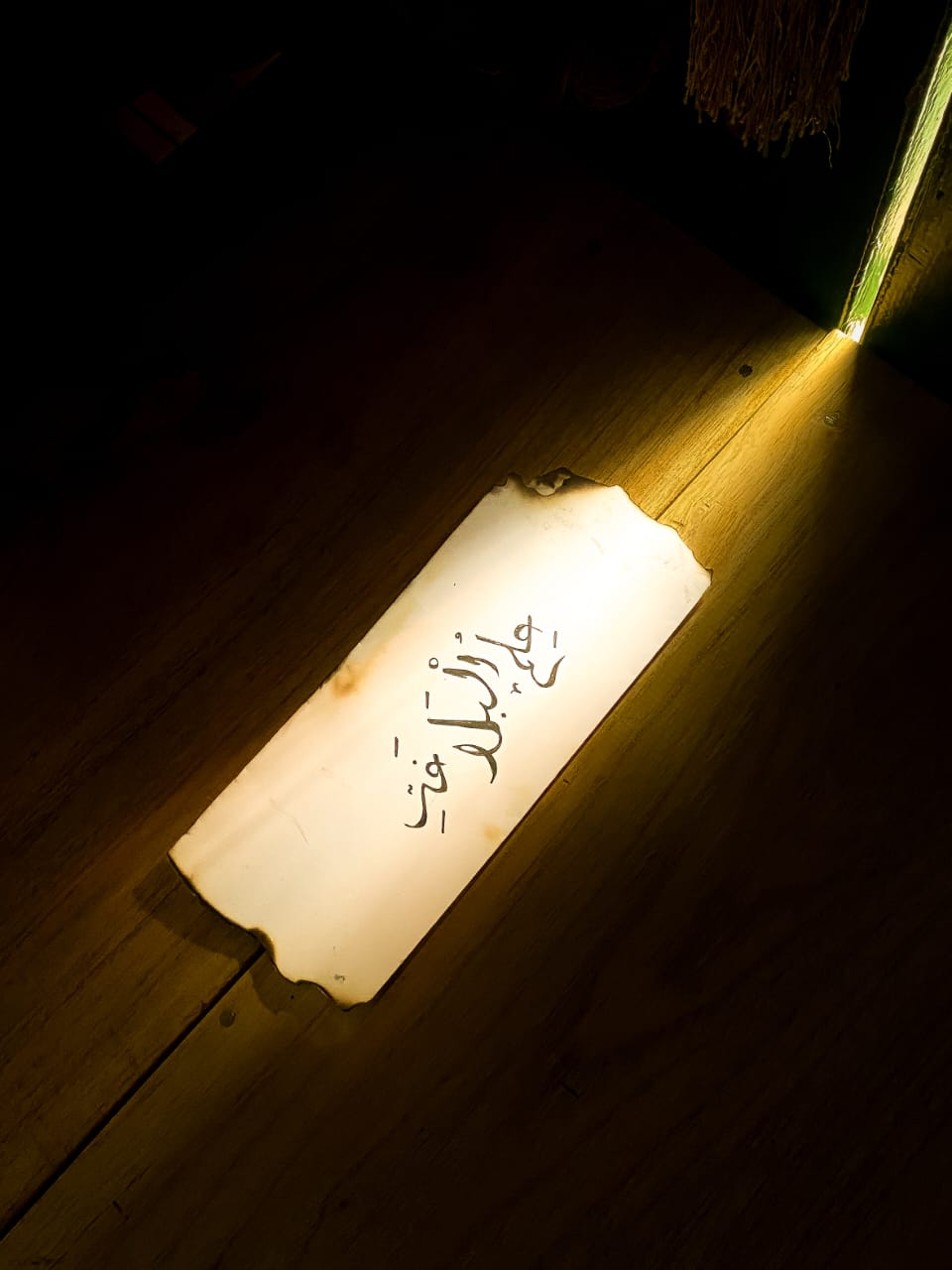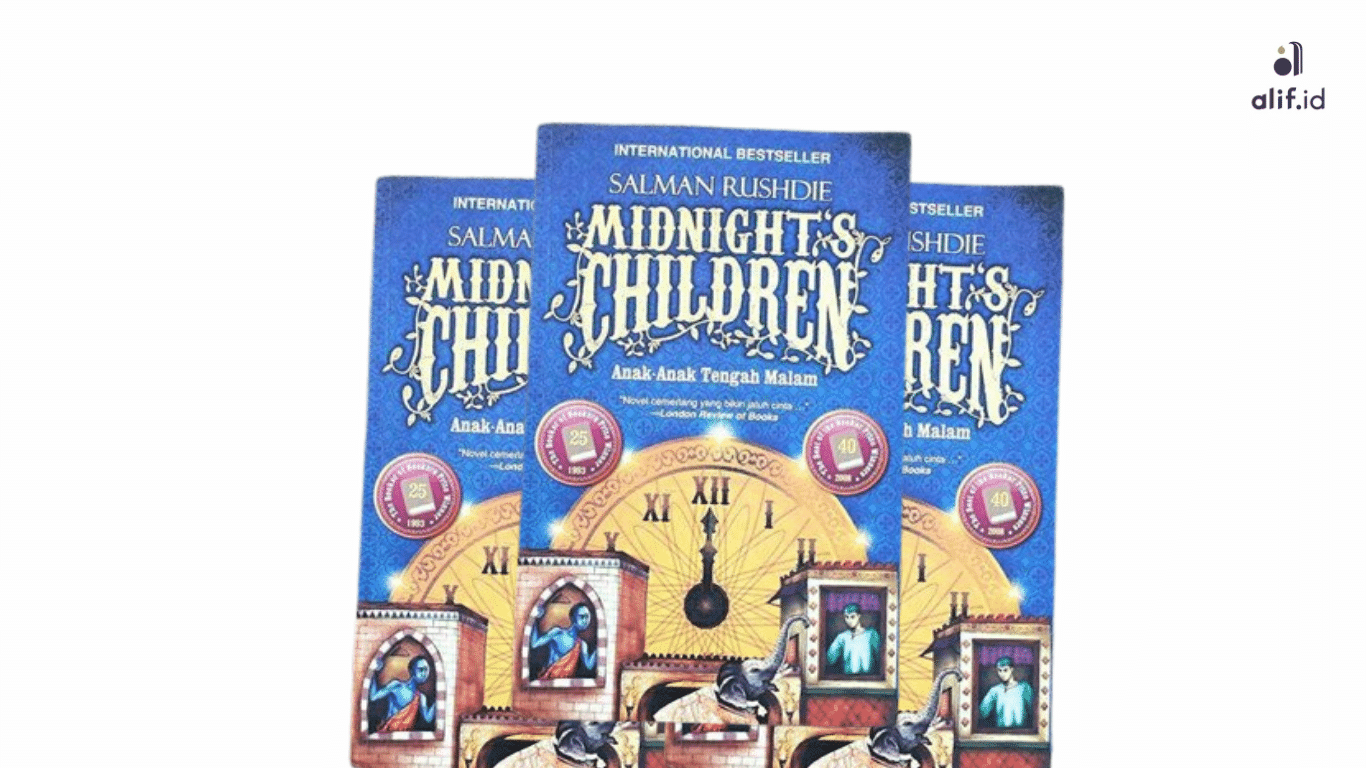
Mari kita mulai esai ini dari luka yang tidak pernah pulih. Dari lapisan-lapisan kulit bumi yang menyimpan bisik-bisik leluhur, yang ditulis dengan darah dan disisipkan di sela-sela sejarah resmi. Dari sisa-sisa tubuh yang terpaksa diam ketika negara bicara nyaring. Karena di sanalah Midnight’s Children hidup: di antara reruntuhan, di antara yang patah dan tak sempat diratapi. Di titik di mana ingatan tidak hanya menjadi tempat persembunyian, tetapi juga kuburan.
Salman Rushdie tidak menulis novel. Ia menjahit sejarah ke dalam daging dan menyisipkan kenangan ke dalam pori-pori bahasa. Ia menulis seperti seseorang yang tahu bahwa kata bisa mengiris lebih tajam dari logam, bahwa metafora bisa meneteskan darah. Dalam kisah Saleem Sinai, sejarah bukan lagi sesuatu yang terjadi, tetapi sesuatu yang membebani.
Saleem lahir pada saat ketika India memproklamasikan kemerdekaannya. “Saya lahir di kota Bombay… pada pukul dua belas malam yang tepat. Tepat di saat India menyatakan kemerdekaannya, aku jatuh ke dunia” (Rushdie, 1980, hlm. 3). Akan tetapi ibarat bayi yang lahir dari rahim yang terlalu lama menahan derita, kelahirannya bukan pesta, melainkan tanda awal dari kemelut panjang. Ia adalah bayi yang “diborgol secara misterius kepada sejarah, takdirku terikat tak terpisahkan pada takdir negeriku” (hlm. 3).
Ia bukan hanya narator. Ia adalah alegori yang hidup, tempat di mana narasi politik dan kesadaran tubuh bertemu dalam konflik yang terus menerus. Dalam tubuhnya, sejarah bukan hanya dikenang, tetapi ditanggung, hingga remuk.
Rushdie menulis dengan cara yang menolak kemapanan. Bahasanya adalah gelombang. Setiap kalimat bisa menjadi badai atau bisikan. Tidak ada struktur linier, karena sejarah—terutama sejarah India dan Pakistan—tidak pernah bergerak lurus. Ia bergerak laksana sungai yang dipaksa berbelok, yang tebingnya runtuh satu per satu.
Saleem adalah anak dari sejarah, tapi juga anak dari perpecahan. Ia adalah satu dari seribu satu anak yang lahir pada tengah malam India merdeka. Mereka masing-masing membawa kekuatan magis: dari telepati hingga kemampuan melihat masa depan. Namun kekuatan-kekuatan itu menjadi simbol yang ironis. Karena tidak satu pun dari mereka dapat mengubah nasibnya. Mereka semua, sebagaimana bangsa mereka, dikurung dalam narasi yang lebih besar dari mereka sendiri.
“Pakistan adalah negeri yang didefinisikan oleh apa yang ia tolak” (ten Kortenaar, 2004, hlm. 155). Dan India, dalam narasi Rushdie, bukanlah negeri ibu yang hangat, tetapi ibu tiri yang kejam, yang menolak mengenali anak-anak yang lahir dari luka. Saleem pergi ke Pakistan dan tidak menemukan rumah; ia kembali ke India dan menemukan reruntuhan. Ia hidup di antara dua kutub yang sama-sama menolak keterikatan emosional. Tidak ada tanah yang cukup lembut untuk diinjak. Tak ada langit yang cukup lebar untuk bernapas.
Rushdie memahami bahwa nasionalisme tidak bisa ditulis hanya dari teks resmi. “Politikus-politikus mengesahkan keaslianku… aku tak diberi kesempatan bersuara” (Rushdie, 1980, hlm. 3). Negara membentuk individu, tapi juga merusaknya. Ia mengangkat simbol, lalu meninggalkan substansinya membusuk.
Dalam analisis Neil ten Kortenaar, novel ini adalah “memoar yang menjelma alegori,” dan Saleem adalah “narator yang tak bisa dipercaya, namun justru karena itu ia menjadi jujur” (hlm. 5). Saleem percaya bahwa Perang India-Pakistan adalah konspirasi terhadap keluarganya, bahwa ia adalah pusat sejarah. Namun justru delusi itulah yang membuka jendela ke dalam psike bangsa: “narasi tentang nasionalisme adalah narasi perihal pusat yang selalu berpindah-pindah, tentang individu yang membayangkan dirinya sebagai penentu takdir kolektif” (ten Kortenaar, hlm. 10).
Dan ketika ia menulis dari pabrik acar, Saleem tidak sedang menulis sejarah; ia sedang mengawetkan duka. “Ia menuliskan sejarah seperti ia menyimpan buah mangga dalam toples: dibumbui, dipelintir, dan dengan rasa nan tajam” (ten Kortenaar, hlm. 6). Ia tahu bahwa sejarah yang tak diawetkan akan membusuk, bahwa kenangan yang tidak diberi ruang akan hilang. Maka ia menciptakan tempatnya sendiri: bukan monumen, melainkan lemari kecil berisi serpihan masa lalu.
Ada satu kalimat yang menggetarkan seperti mantra: “Satu-satunya cara untuk memahami saya adalah menelan segalanya” (Rushdie, 1980, hlm. 4). Dan yang harus ditelan bukan hanya kisah Saleem, tapi juga absurditas, penderitaan, keindahan yang tertutup debu, dan kebisingan yang menutupi doa. Karena India dan Pakistan tidak bisa dibaca seperti buku sejarah. Mereka harus dirasakan seperti luka: ngilu, hangat, dan tak pernah benar-benar sembuh.
Rushdie tidak sedang menulis untuk memuliakan bangsa. Ia sedang menulis dari luka bangsa itu sendiri. Dari irisan-irisan tubuh yang terpecah, dari anak-anak yang kehilangan bahasa, dari ibu-ibu yang menyembunyikan rasa kehilangan di balik tirai jendela. Ia menulis dari ruang yang tidak pernah dikunjungi oleh perayaan nasional: ruang antara rumah dan pengungsian.
“Dalam Midnight’s Children, pertanyaan tentang bangsa dan diri sendiri tidak bisa dipisahkan,” tulis Kortenaar. “Negara tidak lagi menjadi bingkai bagi kehidupan, tetapi menyusup ke dalam tubuh dan jiwa para warganya” (hlm. 9). Saleem tidak bisa membedakan antara tubuhnya sendiri dan tubuh bangsanya. Maka tatkala satu luka berdarah, keduanya merasakan sakit yang sama.
Novel ini bukan tentang kemenangan. Ia adalah elegi. Dan seperti semua elegi yang tulus, ia tak takut untuk menangis. Tidak takut untuk menatap reruntuhan, untuk menggali masa silam, dan untuk mengakui bahwa kadang cinta terhadap tanah air adalah cinta yang menyakitkan.
Itulah mengapa Midnight’s Children tidak pernah benar-benar selesai dibaca. Karena setiap kalinya, ia membuka luka baru. Luka itu bisa bernama Kashmir, bisa bernama Bengal, bisa bernama Lahore. Bisa juga bernama Saleem, atau kita sendiri.
Dan jika kita mau mendengarkan, akan terdengar napas yang tertahan. Napas dari seseorang yang sedang mencoba mengingat. Karena, seperti ditulis Rushdie dengan getir, “Saya harus bekerja cepat, lebih cepat dari Scheherazade, jika saya ingin memiliki makna—ya, makna—apa pun itu” (hlm. 4).
Mungkin makna itu adalah ini: bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan kemenangan dan pidato, ada satu suara pelan yang berbisik dari lemari acar. Suara yang berkata: aku belum selesai. Aku belum selesai.
Dan mungkin, di sanalah kita semua bermula kembali.