
Malam di Jeddah terasa laksana lukisan yang belum selesai, langitnya kelabu tua, bintang-bintangnya berkedip malu-malu di sela awan yang bergulung. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi berdiri di tepi dermaga, kakinya menapak tanah yang masih menyimpan panas siang, seolah bumi sendiri menolak dingin. Kain ihram yang melilit tubuhnya terasa kaku, seperti meminjam jubah seorang asing, dan angin laut yang bertiup membawa bau garam, asap kayu, dan keringat jemaah yang berdesak di sekitarnya. Suara ombak menghantam dinding pelabuhan, bercampur dengan gumam doa dan langkah-langkah yang terburu, seperti detak jantung dunia yang tak pernah diam.
Abdullah bukan orang yang mudah terpukau oleh keramaian. Di Melaka, ia terbiasa dengan pelabuhan yang penuh suara—teriakan pedagang Cina, bisik pelaut Bugis, dan nada tinggi tuan-tuan Inggris yang memesan catatan darinya. Tapi Jeddah ini lain. Di sini, setiap langkah terasa seperti ujian, setiap pandangan dari jemaah lain seperti pertanyaan: Apa yang membawamu ke sini, munsyi? Ia merasa seperti anak kecil lagi, berdiri di depan ayahnya yang keras, yang pernah memukuli tangannya dengan rotan karena huruf-hurufnya tidak rapi. “Kau harus sempurna, Abdullah,” katanya, suaranya seperti batu yang jatuh ke sumur.
Perjalanan laut dari Melaka telah menguras tenaganya. “Aku melihat lautan yang luas, tiada tepinya, dan ombak yang bergulung seperti gunung yang hidup,” tulisnya dalam catatannya (Kisah Pelayaran, hlm. 145). Berbulan-bulan di kapal, tidur di antara karung beras dan peti kayu, ditemani suara derit papan dan doa-doa jemaah dalam bahasa yang asing baginya, membuatnya merasa seperti daun yang terombang-ambing di laut. Di kapal itu, ia bertemu seorang kamitua dari Makassar, yang wajahnya seperti kulit pohon yang retak, yang setiap malam berbicara tentang Ka’bah dengan suara penuh kerinduan. “Kau akan tahu saat melihatnya,” katanya, matanya berbinar di bawah lampu minyak, “bahwa hidupmu sebelum ini hanyalah bayang-bayang.”
Abdullah tidak yakin apakah ia siap untuk kebenaran seperti itu. Ia seorang munsyi, terlatih untuk mencatat dunia dengan pena, bukan untuk menyelaminya dengan hati. Tapi malam ini, dengan bau laut yang menyengat dan suara azan yang melayang dari masjid di kejauhan, ia merasa sesuatu bergetar di dalam dirinya, seperti senar sitar yang tersentuh angin. Ia berjalan menuju penginapan, sebuah rumah batu dengan lantai tanah yang dipenuhi tikar dan lampu minyak yang berkedip. Seorang wanita tua, matanya tersembunyi di balik cadar, menawarkan segelas air zam-zam. “Minum, anakku,” katanya, suaranya serak seperti pasir yang bergesekan. Air itu dingin, sedikit manis, dan saat menyentuh bibirnya, ia teringat ibunya di Melaka, yang dulu menyanyikan lagu-lagu Melayu sambil menjahit di beranda. “Doa itu laksana air, Abdullah,” katanya, “ia tak perlu banyak, asal kau tahu ke mana mengalirkannya.”
Di penginapan itu, di tengah suara batuk, tawa, dan bisik doa, Abdullah bermimpi. Ia melihat Ka’bah, tapi bukan sebagai batu, melainkan sebagai cermin yang memantulkan wajahnya—bukan wajah munsyi yang menulis untuk tuan-tuan Eropa, bukan wajah anak yang tak pernah cukup untuk ayahnya, tapi wajah seorang lelaki yang rapuh, dengan doa yang tersangkut di tenggorokannya. Ia terbangun dengan jantung berdegup, tangannya mencengkeram kain ihram yang basah oleh keringat. Di luar, fajar menyelinap melalui celah jendela, dan adzan subuh memanggil, seperti tangan yang menariknya dari mimpi.
Menuju Makkah
Pagi di Jeddah terasa seperti lukisan yang belum jadi, langitnya kelabu pucat, seolah matahari ragu untuk muncul. Abdullah berjalan di antara rombongan jemaah, kakinya menjejak tanah berdebu yang masih dingin. Bau keringat, minyak kelapa, dan asap dari api unggun yang baru padam bercampur di udara. Ia memegang tongkat kayu yang dibeli dari seorang anak di pelabuhan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia perlu sesuatu untuk menahan dunia yang terasa goyah. Unta-unta di depan berderit di bawah beban peti dan karung, lonceng kecil di leher mereka berdenting seperti nyanyian yang terputus-putus.
Di sisinya berjalan Haji Yusuf, seorang tua dari Banten, yang wajahnya seperti peta yang telah dilipat berkali-kali. “Ini haji pertamaku,” katanya, suaranya pelan namun penuh kehangatan, seperti kayu yang masih menyimpan bara. “Aku menabung tiga puluh tahun untuk ini.” Abdullah mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Melaka, ke malam-malam ketika ia duduk bersama ibunya, mendengarkan cerita tentang nabi-nabi dan kota-kota suci. Ia ingin bertanya kepada Haji Yusuf apa yang ia harapkan dari Ka’bah, apakah Tuhan akan terasa seperti rumah atau seperti bayang-bayang yang tak bisa disentuh. Tapi ia diam, karena pertanyaan itu terasa seperti membuka luka yang belum kering.
Di depan mereka, seorang wanita dari Palembang, yang memperkenalkan dirinya sebagai Mariam, berjalan dengan langkah teguh, kain ihramnya berkibar seperti layar kecil. Saat istirahat di bawah pohon akasia yang kurus, ia berbicara dengan suara yang penuh beban. “Aku meninggalkan suamiku yang sakit,” katanya, tangannya memilin sehelai kain kecil. “Dia menyuruhku pergi, katanya ini untuk kami berdua.” Abdullah mendengarkan, jarinya meraba saku di pinggangnya, tempat ia menyimpan duit perak peninggalan ayahnya. Ia tidak tahu mengapa ia membawanya—duit itu tak berguna di sini—tapi setiap kali ia menyentuhnya, ia mendengar suara ayahnya: Jangan pernah lupa asalmu, Abdullah.
Panas gurun mulai menggigit, matahari tinggi seperti tungku yang membakar pasir hingga berkilau. Keringat menetes di dahi Abdullah, kain ihramnya lengket di kulit. “Aku merasa panas yang tak pernah kualami, seolah matahari ingin menguji hati kami,” tulisnya kemudian (Kisah Pelayaran, hlm. 152). Seorang anak lelaki berlari di sisi rombongan, membawa kendi air yang ia tawarkan dengan senyum lebar. Abdullah memberinya sebutir kurma, dan anak itu tertawa, giginya berkilau seperti kerikil di tepi sungai. “Kau akan lihat Ka’bah besok!” katanya, lalu berlari pergi, seolah membawa rahasia yang terlalu besar untuk disimpan.
Malam tiba, dan rombongan berhenti di sebuah lembah kecil, di mana angin membawa bau debu dan daun kering. Api unggun dinyalakan, nyalanya menerangi wajah-wajah jemaah yang duduk melingkar. Haji Yusuf membaca ayat-ayat dari sebuah kitab kecil, suaranya gemetar namun kuat, seperti air yang mengalir di sela batu. Mariam duduk di dekat Abdullah, tangannya masih memilin kain kecil itu. “Kau pernah merasa bahwa kau tidak layak untuk sesuatu?” tanyanya tiba-tiba, matanya menatap api. Abdullah terkejut, bukan karena pertanyaannya, tapi karena ia tahu jawabannya. Ia selalu merasa tidak layak—tidak untuk ayahnya, tidak untuk tuan-tuan Eropa, mungkin tidak untuk Tuhan. “Setiap hari,” katanya pelan, dan dalam keheningan itu, mereka berbagi sesuatu yang tak perlu diucapkan.
Bintang-bintang muncul, begitu banyak hingga langit tampak seperti kain hitam yang ditaburi permata. Abdullah berbaring di tikar, mendengarkan napas jemaah lain dan suara angin yang berbisik. Ia teringat cerita ibunya tentang seorang musafir yang tersesat di padang pasir, hanya untuk menemukan bahwa setiap langkahnya telah ditentukan. Ia tidak yakin apakah ia percaya, tapi dengan Makkah begitu dekat, ia merasa seperti musafir yang akhirnya belajar melihat.
Momen di Ka’bah
Masjidil Haram terasa seperti jantung dunia, detaknya terdengar dalam langkah ribuan jemaah, dalam doa-doa yang bergumam, dalam hembusan angin yang membawa bau air mawar dan debu. Abdullah melangkah masuk, kakinya menapak lantai marmer yang dingin, licin oleh telapak-telapak sebelumnya. Langit di atas Makkah biru jernih, seperti kaca yang bisa pecah jika disentuh. Di tengah kerumunan, Ka’bah berdiri, hitam dan diam, kain kiswahnya berkilau seperti malam yang diterangi bintang. “Aku melihat Ka’bah, rumah Allah, dan hatiku penuh dengan keajaiban yang tak dapat kugambarkan,” tulisnya (Kisah Pelayaran, hlm. 158).
Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Haji Yusuf berkata bahwa Ka’bah akan membuatnya merasa kecil, seperti anak yang tersesat. Mariam hanya mengangguk saat ditanya, matanya penuh rahasia. Kini, berdiri di sini, Abdullah merasa seperti seseorang yang membuka pintu rumah lamanya, hanya untuk menemukan bahwa dinding-dindingnya telah berubah. Ka’bah bukan hanya batu, bukan hanya kain, tapi sesuatu yang hidup, yang menatapnya dengan pertanyaan: Apa yang kau bawa ke sini, selain dirimu sendiri?
Ia bergabung dengan tawaf, langkahnya pelan, seperti seseorang yang takut menginjak bayangannya sendiri. Suara doa mengalir, kata-kata dalam bahasa Arab, Melayu, dan bahasa-bahasa yang tak ia kenali, bercampur menjadi nyanyian yang kacau namun indah. Seorang lelaki di sampingnya, dengan janggut kelabu, menangis pelan, air matanya jatuh seperti hujan kecil. Abdullah ingin bertanya apa yang membuatnya menangis, tapi matanya kembali tertarik ke Ka’bah, seperti burung yang menemukan sarangnya.
Saat mendekat, tangannya menyentuh kain kiswah, teksturnya kasar namun lembut, seperti kulit ibunya yang dulu memeluknya saat ia kecil. Ia teringat malam-malam di Melaka, ketika ibunya mengajarkannya membaca Al-Qur’an, jarinya menelusuri ayat-ayat di bawah lampu minyak. “Kau harus percaya, Abdullah,” katanya, suaranya seperti angin yang mendorong perahu. Tapi percaya pada apa? Ia tidak pernah yakin, bahkan sekarang, dengan Ka’bah di depannya, ia masih merasa seperti munsyi yang hanya mencatat, bukan merasakan.
Namun, di putaran keempat tawaf, sesuatu bergeser. Mungkin karena panas yang menekan dadanya, mungkin karena doa-doa yang terdengar seperti lagu ibunya, atau mungkin karena ia melihat seorang anak perempuan di sisi kerumunan, matanya penuh cahaya seperti anak di gurun. Tiba-tiba, dadanya penuh, seolah keraguan dan ketakutan yang selama ini ia tahan kini meluap, seperti air yang akhirnya menemukan celah. Ia tidak menangis, tapi matanya panas, dan ia berdoa dengan sesuatu yang bukan kata-kata, sesuatu yang lahir dari tulang-tulangnya.
Ia teringat ayahnya, yang menuntut kesempurnaan, yang pernah memarahinya karena salah menulis. “Kau harus lebih baik,” katanya, matanya seperti laut yang dingin. Di Melaka, Abdullah menjadi munsyi untuk membuktikan bahwa ia cukup baik. Tapi di sini, di depan Ka’bah, ia menyadari bahwa ia tidak perlu membuktikan apa pun. Ka’bah tidak meminta kesempurnaan; ia hanya meminta kehadiran.
Tawaf selesai, dan Abdullah mundur, napasnya tersengal. Ia berdiri di sudut masjid, memandang Ka’bah yang kini diterangi cahaya senja, seperti lukisan yang tak pernah selesai. Haji Yusuf duduk bersila, matanya setengah terpejam. Mariam berdiri tak jauh, tangannya masih memegang kain kecil itu, wajahnya tenang namun penuh rahasia. Abdullah ingin bertanya apakah mereka juga merasakan apa yang ia rasakan, tapi ia diam. Beberapa hal, ia tahu, lebih baik disimpan dalam hati.
Kepulangan
Di pelabuhan Jeddah, laut terbentang seperti kain tua, permukaannya berkilau di bawah matahari senja, namun penuh lipatan gelap. Abdullah berdiri di dermaga, kain ihramnya kini dilipat dalam peti kayu, digantikan oleh jubah Melayu yang terasa akrab namun asing. Angin membawa bau ikan asin dan tar, bercampur dengan suara jemaah yang berpamitan. “Aku pulang dengan hati yang telah berubah, meski aku tak tahu bagaimana menjelaskannya,” tulisnya (Kisah Pelayaran, hlm. 165).
Ia memegang sebutir kurma kering, hadiah dari seorang pedagang di Makkah. Kurma itu kecil, keriput, namun manis saat ia gigit, dan rasanya mengingatkannya pada ibunya, yang dulu membuat kue kurma di dapur kecil mereka. “Doa itu seperti kurma,” katanya suatu sore, tangannya lengket oleh adonan, “kau tak perlu banyak, asal kau tahu cara menikmatinya.” Abdullah tersenyum, tapi senyumnya rapuh, seperti kertas tua yang bisa robek. Ibunya tidak pernah melihat Makkah, tapi ia merasa ibunya telah bersamanya di sana, di setiap langkah tawaf, di setiap detik keheningan.
Haji Yusuf telah pergi dengan kapal liyan, kitab kecilnya masih terselip di pinggang. Mariam berpamitan pagi tadi, meninggalkan sehelai kain kecil yang ia titipkan tanpa kata-kata, hanya anggukan yang penuh makna. Abdullah memasukkan kain itu ke sakunya, di samping duit perak peninggalan ayahnya, dan merasa bahwa benda-benda ini—kurma, kain, duit—adalah jangkar kecil yang menghubungkannya pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia bawa dari Makkah, bukan dalam peti, tapi dalam darahnya.
Ia naik ke kapal, kakinya menapak papan kayu yang berderit, dan saat berdiri di dek, memandang Jeddah yang menjauh, ia menyadari bahwa haji bukan tentang tiba di Ka’bah atau menyentuh kain kiswah. Haji adalah tentang menerima bahwa ia rapuh, bahwa doa-doanya penuh cela, bahwa hidupnya—dengan semua catatan dan pena untuk tuan-tuan Eropa—hanyalah setitik debu. Tapi debu itu, ia tahu sekarang, bisa berkilau jika disentuh cahaya.
Malam tiba, dan bintang-bintang muncul di atas laut. Abdullah bersandar di pagar kapal, mendengarkan ombak yang berbisik, dan untuk pertama kalinya, ia merasa pulang—bukan ke Melaka, bukan ke rumah ibunya, tapi ke dirinya sendiri, seorang musafir yang telah belajar bahwa doa, seperti kurma, tak perlu banyak, asal kau tahu cara membawanya.












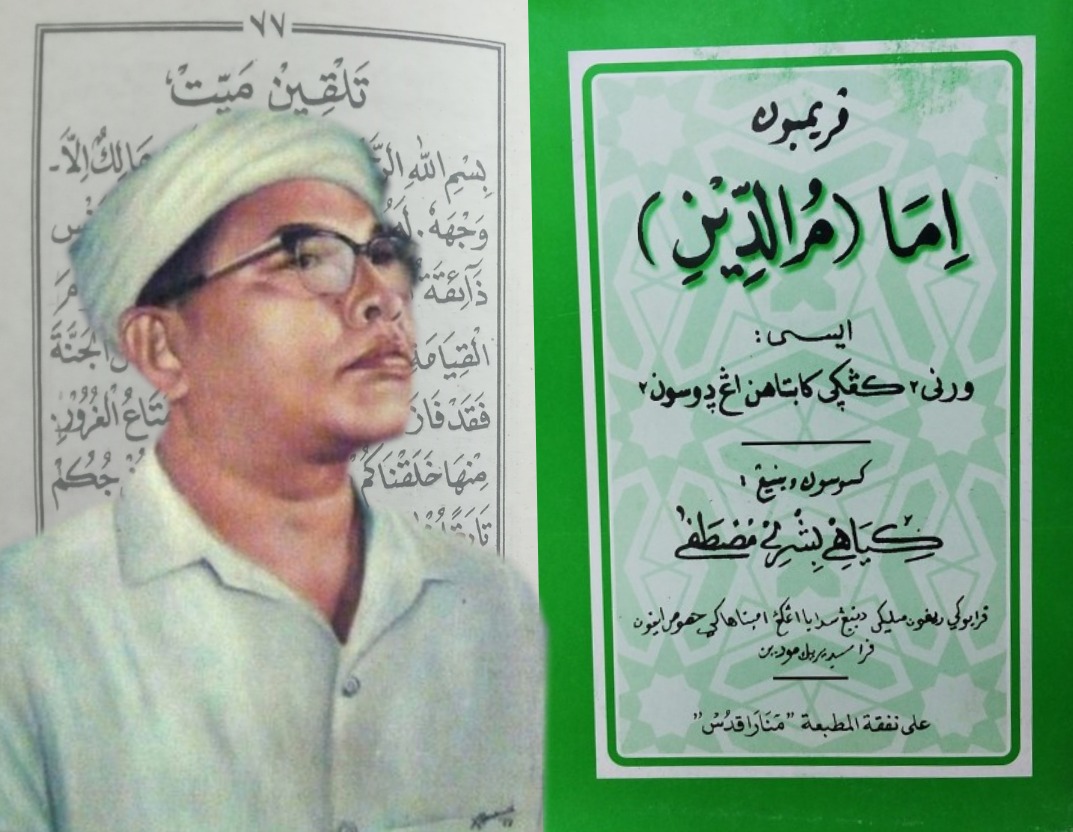



gacormen