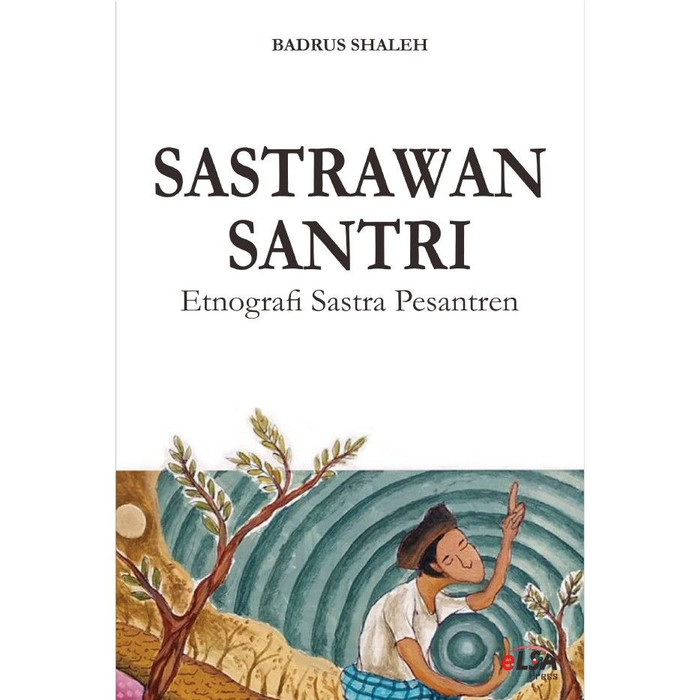Dalam sejarahnya, sastra di Indonesia punya banyak corak. Kerap kali bentuk sastra yang dihasilkan amat bergantung pada latar belakang sastrawan itu sendiri. Denys Lombard, sejarawan sekaligus Indonesianis dari Prancis melihat adanya pengaruh Barat terhadap seni di Indonesia, termasuk sastra.
Gaya-gaya yang diadopsi dari Barat oleh sastra Indonesia di antaranya adalah realisme, eksistensialisme, dan naturalisme. Dalam karyanya, Nusa Jawa Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan, Lombard memang fokus pada penerimaan masyarakat Indonesia, termasuk senimannya, terhadap budaya Barat. Seniman Indonesia bersikap mendua dan akhirnya menghasilkan perdebatan soal sastra Indonesia.
Namun karena fokus pada persilangan dengan Barat, Lombard lupu memperhatikan kelompok sastra lainnya yang terbilang minoritas. Sastra ini disebut minoritas karena dua hal. Pertama, karyanya terbilang kurang dikenal. Kondisi ini tidak lepas dari gejala yang disebut oleh politik sastra oleh Saut Situmorang dalam bukunya, Politik Sastra. Penentuan karya yang dikenal dan laku di pasaran ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu.
Kurang dikenalnya gaya sastra minoritas ini berdampak pada penyebab kedua, kurangnya kajian terhadap sastra minoritas ini. Penyebab kedua ini adalah dampak sekaligus sebab dari terkucilnya sastra minoritas. Kelompok yang termasuk dalam sastra minoritas di antaranya sastra yang dibawa kelompok keturunan Tionghoa, sastrawan perempuan, sastra realisme sosialis pasca-pembredelan Orde Baru, sastra daerah, dan juga sastra pesantren.
Badrus Shaleh, dalam tesis magisternya di Antropologi Universitas Gajah Mada, mengangkat soal sastra pesantren ini. Pembahasan ini masih terbilang jarang. Tidak hanya topik menarik yang masih memiliki kebaruan, tesis tersebut juga dikemas dengan baik oleh Badrus Shaleh dan akhirnya diberi ganjaran penghargaan dari Nusantara Academic Award dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Sastra pesantren menarik diulas karena sebenarnya sudah ada beberapa tokoh besar sebagai wakil dari sastra pesantren seperti Gus Mus, Cak Nun, maupun Ahmad Tohari. Namun sastra pesantren sendiri bisa dibilang kurang berkembang.
Dari sudut pandang kajian mengenai pesantren, tradisi sastra di pesantren juga masih belum mendapat perhatian khusus. Shaleh menyebut beberapa karya yang bisa dibilang klasik mengenai tradisi pesantren dan Islam di Indonesia yang luput membahas tradisi sastra. Misalnya Religion of Java dari Clifford Geertz, Tradisi Pesantren dari Zamakhsyari Dhofier, dan Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat dari Martin van Bruinessen. Alhasil, karya Shaleh ini menjadikan tradisi sastra di pesantren sebagai topiknya tetapi tidak lepas dari kajian agama yang melatarbelakangi tradisi tersebut.
Berbeda dari karya soal sastra lainnya yang umumnya berbentuk kritik sastra, karya ini mengadopsi antropologi sastra sekaligus antropologi agama. Melalui antropologi sastra, Shaleh melihat tradisi sastra pesantren dari tiga arah yakni sisi pengarang, refleksi sastra sebagai pantulan budaya, dan sisi pembaca (hal. 20). Ketiganya dipadukan dengan pendekatan antropologi agama yakni fenomenologi agama (hal. 21) yang membahas pengalaman beragama. Sastra dalam tradisi sastra pesantren dilihat sebagai media yang menghasilkan pengalaman beragama yang unik.
Karya antropologi sulit dilepaskan dengan metode etnografi. Begitu juga dengan karya ini yang tidak hanya membahas karya sastranya, tetapi juga komunitasnya. Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang berupaya menghasilkan deskripsi mendalam, atau yang biasa disebut oleh antropolog kawakan Clifford Geertz sebagai thick description. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Annuqayah Madura.
Bagi para santri, sebenarnya sastra bukanlah hal yang asing. Bila merujuk pada pengertian yang diajukan oleh Alfred Gell, antropolog agama dan seni, sastra adalah teknologi pesona (technology of enchantment) (hal. 104). Pesona dari sastra dapat membantu santri memahami ajaran agama. Bahkan Al-Quran sendiri dapat dilihat sebagai salah satu bentuk sastra, walaupun tentu tidak bisa dianggap sekadar sastra. Namun karena tradisinya yang berbeda dari tradisi sastra lainnya, sastra pesantren menemui masalah seperti halnya yang diutarakan Lombard, seperti yang saya utarakan di awal. Sastra pesantren berhadapan dengan sastra lainnya, termasuk sastra Indonesia, dan tidak terlalu menerimanya.
Penerimaan yang tidak terlalu baik ini karena perbedaan pengalaman yang diperoleh dari sastra itu sendiri. Sastra pesantren adalah sastra yang ditujukan untuk peribadatan dan rohani, bukan hanya sekadar sastra. Pengenalan sastra yang diperoleh oleh santri adalah melalui pendidikan formal mereka di pesantren. Mereka lebih terbiasa dihadapkan pada sastra yang ditujukan untuk mengajarkan ajaran agama.
Di sinilah Shaleh memperoleh temuan yang cukup menarik. Etnografi punya kelebihan untuk tidak terkurung pada satu tempat saja, tetapi menelusuri pergerakan orang yang diamati bahkan di luar tempat tersebut. Shaleh berhasil mengaplikasikan prinsip ini dan akhirnya memperoleh temuan sastrawan santri di luar komunitas formal pesantren, meski masih termasuk dalam lingkungan pesantren. Tidak hanya terbatas tempat, sastrawan santri ini terhubung dengan dunia sastra yang lebih luas. Banyak santri yang membentuk komunitas sastra sendiri dan mengundang sastrawan dari luar pesantren. Komunitas ini juga punya media publikasi untuk karya-karya mereka (hal. 170).
Bisa dibilang penelitian Shaleh ini amat menarik dan menjadi suatu kontribusi tersendiri bagi kajian-kajian yang sudah ada. Kajian mengenai pesantren dilengkapi kajian tentang sastra. Sebaliknya, kajian tentang sastra dilengkapi dengan kajian pesantren. Perpaduan yang unik ini akhirnya membuat karya Shaleh ini amat layak dibaca.
Judul Buku : Sastrawan Santri: Etnografi Sastra Pesantren
Penulis : Badrus Shaleh
Penerbit : eLSA Press, Maret 2020
Tebal : xx + 212 halaman