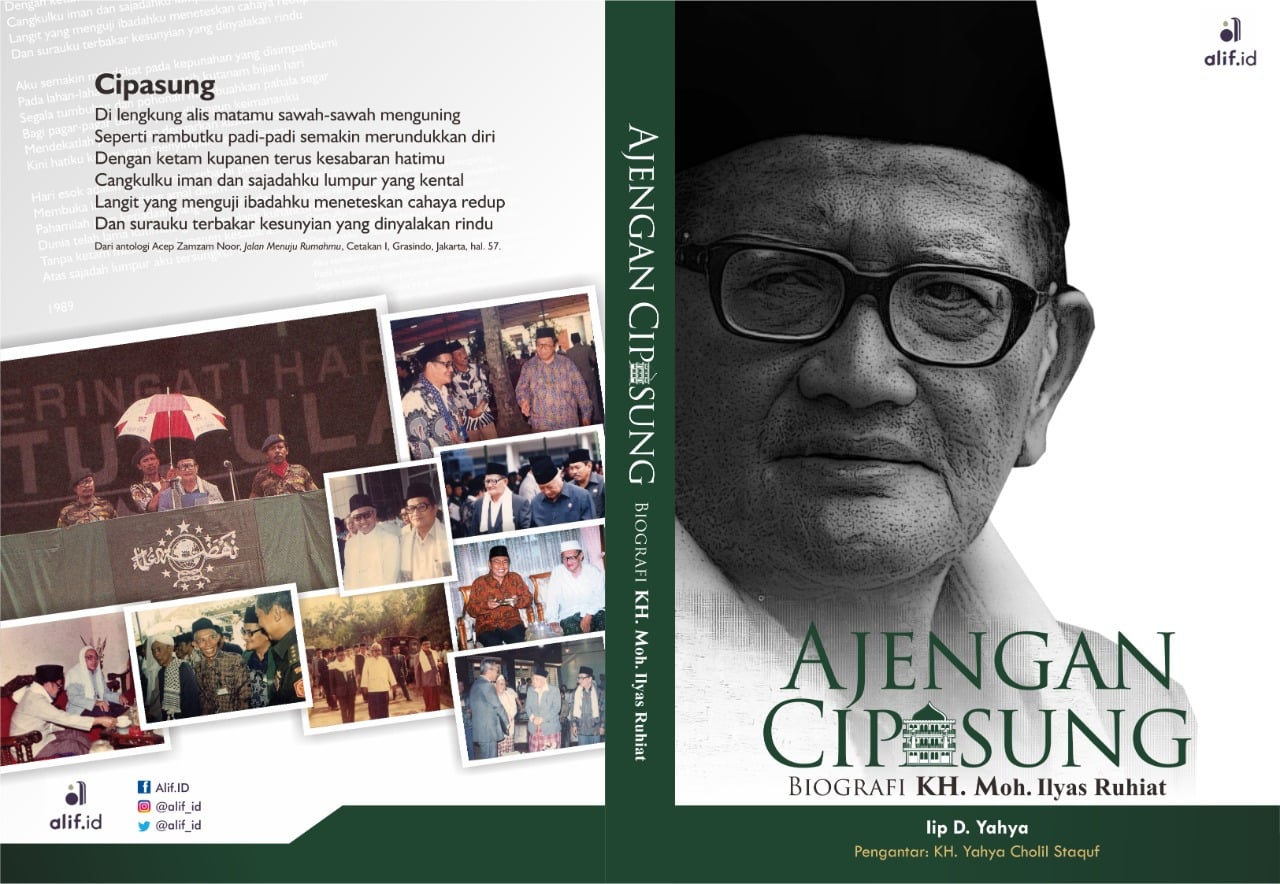Tidak ada pilihan lain di era postmodernisme ini selain kembali pada Alquran dan Hadis Nabi. Bukan sebab Rasululullah Saw telah bersabda bahwa keduanya adalah pedoman agar umat Muslim tidak tersesat. Itu sudah pasti. Namun bahwa postmodernisme adalah hikmah yang pernah hilang dari tangan umat Muslim.
Allah Swt berfirman, “Akan Kami perlihatkan tanda-tanda Kami di ufuk-ufuk dan di jiwa-jiwa mereka…”
Post-modernisme adalah suatu paham atau aliran filsafat yang menandai suatu zaman di antara lapisan sejarah manusia. Dalam fase ini, pengetahuan manusia tidak semata diperoleh dengan cara-cara yang disuguhkan oleh satu fase sejarah manusia sebelumnya, yaitu era modernisme. Manfaat besar yang bisa didapat oleh manusia di zaman postmo ini adalah kelengkapan perangkat epistemologis.
Kelengkapan perangkat epistemologis disebabkan oleh watak inheren postmo itu sendiri, yang mengajarkan umat manusia untuk berlapang dada dan menyambut semua realitas yang disuguhkan oleh kehidupan, tanpa terkecuali. Sebelumnya, di era klasik, sebagaimana diutarakan oleh banyak teori dan diskursus, manusia dikendalikan oleh sistem berpikir yang menekankan pada kepercayaan dan keimanan.
Beranjak memasuki era modernisme, sebagian manusia meninggalkan tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang terus berkembang.
Kata “sebagian” perlu ditekankan di sini karena masih tersisa sebagian lain yang masih mempertahankan tradisi lama. Kata “sebagian” di sini menjadi penanda utama bahwa tradisi baru yang sedang digandrungi oleh sebagian lain tidak cocok bagi sebagian yang lebih nyaman dengan tradisi lama.
Ketidaknyamanan walaupun merupakan asal pangkal dari semua percekcokan namun sekaligus menjadi barzakh dari dua dimensi. Kata barzakh berasal dari bahasa Arab, yang berarti ruang pembatas di antara dua wilayah yang berbeda. Barzakh ketidaknyamanan ini bersifat abadi, karena ia pada akhirnya membatasi era modernisme yang baru bangkit dan mendorong kelahiran era berikutnya, yang kelak kita sebut postmodernisme.
Postmo memang lahir dari ketidaknyamanan akan produk-produk ontologis, epistemologis, maupun aksiologis dari rahim modernisme. Postmo terkadang memerankan diri sebagai wadah yang coba mendamaikan kelompok pendukung modernisme maupun pendukung iman, yang pernah berjaya sebelum modernisme.
Hasrat postmo untuk mewadahi perbedaan memang terkesan heroik, walaupun pada dirinya sendiri menampilkan kelemahan-kelemahan. Titik lemah dari postmo bukan pada harapannya melainkan pada kerja praktisnya. Postmodernisme selalu memaksakan diri untuk melakukan penundaan-penundaan, dan memusuhi klaim-klaim. Sebab, sesuatu yang menyambut entitas-entitas berbeda, pada dirinya sendiri, tidak boleh berpihak kecuali pada perbedaan itu sendiri.
Islam dengan Alquran-nya menyediakan porsinya sendiri yang melegitimasi semangat postmo. Salah satu buktinya adalah kutipan ayat di atas, yang melandasi bangunan filsafat, tidak saja filsafat ketuhanan melainkan fisafat sains, baik eksakta maupun humaniora.
Ayat di atas merangkum sejarah perkembangan nalar manusia sejak awal kali hingga hari ini, sebagaimana sering sekali dibicarakan oleh akademisi kita.
Pertama, “akan Kami perlihatkan tanda-tanda Kami…” adalah fondasi bagi keimanan. Pembicaraan tentang “Kami” merupakan pembicaraan teologis, dimana hanya penting bagi akademisi yang percaya pada keimanan akan Tuhan. Namun, ayat ini tidak berhenti sekadar memberikan tema yang utama dalam teologi, yaitu Tuhan. Sebaliknya, ia juga menyuguhkan tema utama bagi kajian sainstifik.
Kedua, “di ufuk-ufuk dan di jiwa-jiwa mereka” adalah fondasi bagi bangunan sainstifik. Pada akademisi dan sarjana yang tertarik mendalami alam semesta maupun manusia tidak bisa mengabaikan objeknya sendiri, yang dalam ayat Alquran dirangkam menjadi dua terma saja: ufuk dan diri manusia. Ufuk merujuk pada apapun di luar diri manusia dan diri merujuk pada manusia itu sendiri. Keduanya adalah bahan-bahan mentah bagi kerja-kerja sainstifik.
Bila Islam menginformasikan pada umat manusia bahwa Tuhan akan menunjukan tanda-tanda di ufuk dan diri manusia, postmodernisme bekerja untuk menginformasikan kesadaran-kesadaran manusia tentang persoalan-persoalan yang ada di ufuk dan diri manusia. Tidak saja menginformasikan, tetapi juga mengajak agar semua kesadaran tersebut diterima dengan lapang dada.
Kata “mengajak” lagi-lagi perlu ditekankan. Sebab, postmo sebagai satu aliran tersendiri berhadap-hadapan langsung dengan dua aliran sebelumnya: modernisme dan era keimanan. Sebagai sebuah ajakan, postmo membuka diri untuk ditolak, direvisi, dimodifikasi, agar sesuai dengan kepentingan dan hasrat modernisme maupun era keimanan tersebut.
Dalam menyikapi kemungkinan lahirnya penentangan–dalam wujud esktrimnya–terhadap seruan-seruannya, Islam dan postmo menempatkan diri pada sikap untuk terbuka dan prinsip tanpa pemaksaan. Pertama, sikap terbuka berarti selalu siap untuk hidup berbeda dengan “yang-lain,” “yang-berbeda,” “yang-menolak.” Kedua, prinsip tanpa pemaksaan berarti menolak penghabisan, eliminasi, negasi, atas “yang-lain,” “yang-berbeda,” “yang-menolak.”
Lantas, apakah Islam dan postmo yang sedemikian rupa berhenti pada level teoritis? Tidak! Islam dan postmo telah manifes atau mewujud dalam figur-figur kiai. Figur kiai bukan semata sosok manusia biasa melainkan representasi dari Islam dan postmo. Hubungan Islam-postmo dengan figur kiai seperti hubungan sifat dengan dzat; relasi atribut dengan materinya.
Dalam bahasa metaforis, figur kiai adalah salju, sedang Islam dan postmo adalah dinginnya; kiai adalah api, Islam dan postmo adalah panasnya; kiai adalah madu atau susu, Islam dan postmo adalah manis dan hasiatnya.
Namun, terminologi kiai perlu ditegaskan kembali, karena perjalanan waktu mampu menggerus kedalaman maknanya; merusak esensi dan substansinya; menghapus hakikatnya. Kiai adalah bahasa lokal, yang dalam bahasa Arabnya bisa disepadankan dengan kata ulama. Walaupun, penyepadanan ini juga perlu berhati-hati, sebab sebagaimana dialami oleh kata kiai, kata ulama juga mengalami penggerusan kedalamannya. Oleh karena itulah, kiai/ulama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tajalli atau manifestasi dari semangat Islam dan postmodernisme.
Hal paling mencolok dari atribut penting kiai atau ulama adalah pelestariaannya akan semangat penerimaan realitas, penundaan akan kebenaran, dan penegasan sikap. Pertama, penerimaan realitas berarti segala realitas yang pernah, sedang dan akan dipahami manusia adalah tanda-tanda ketuhanan. Kiai selalu menerimanya sebagai pintu masuk untuk memahami ketuhanan.
Kedua, penundaan kebenaran. Kiai berkat kemampuannya untuk menerima realitas secara total mampu bersikap halus dan lembut untuk mengubah sebagian realitas yang dianggapnya kurang pas. Prinsip kedua ini adalah prakondisi bagi atribut ketiga. Dalam suasana prakondisi ini, seni menentukan sikap sangat diperhatikan dengan amat detail.
Kiai tidak berburu-buru menentang sesuatu yang baginya tidak ideal, karena dalam dirinya terpatri prinsip pertamanya, yaitu kesadaran akan tanda-tanda ketuhanan.
Prakondisi ini memang licin, dan tak mudah melewatinya kecuali figur kiai yang benar-benar kiai. Kata “benar-benar kiai” penting ditekankan untuk membedakannya dari kiai-kiai yang sudah tergerus atribut-atribut pentingnya, yang tergerus kedalaman berpikirnya, yang hilang kesabarannya dalam menerima realitas yang tampak kontradiktif. Dalam pra-kondisi ini, kiai mengamalkan semangat Islam dan postmo, yaitu soal penundaan.
Ketiga, penegasan sikap. Dalam level praktis, pengetahuan akan realitas yang beragam, penerimaannya sebagai tanda-tanda ketuhanan, tidak lantas meniscayakan kiai untuk mewakili semuanya dalam praktik. Kiai tahu bahwa dirinya bukan totalitas realitas melainkan bagian dari realitas. Karenanya, para kiai mengambil sikapnya masing-masing yang berbeda satu sama lain.
Kiai dalam kehidupan sosial dan dalam kajian sosiologis akan ditemukan sebagai figur-figur berbeda, dengan kualitas-kualitas akademis berbeda, dan dengan jabatan-jabatan struktural berbeda. Perbedaan figur satu dengan figur kiai lainnya menghapus perbedaan Kiai dengan warga masyarakat pada umumnya. Namun, di level batiniah, kiai/ulama mendapat keistimewaan sendiri, dan hal ini diafirmasi oleh Tuhan dalam Alquran.
Tiga atribut utama kiai (penerimaan, penundaan, penegasan) adalah satu mata rantai yang tidak terputus. Kiai berjalan dalam arus bolak-balik dan tidak berhenti pada satu “stasiun” tersebut. Kita tidak akan menemukan Kiai yang ngotot memaksakan sesuatu tanpa menyadari tentang keharusan dirinya untuk bersikap