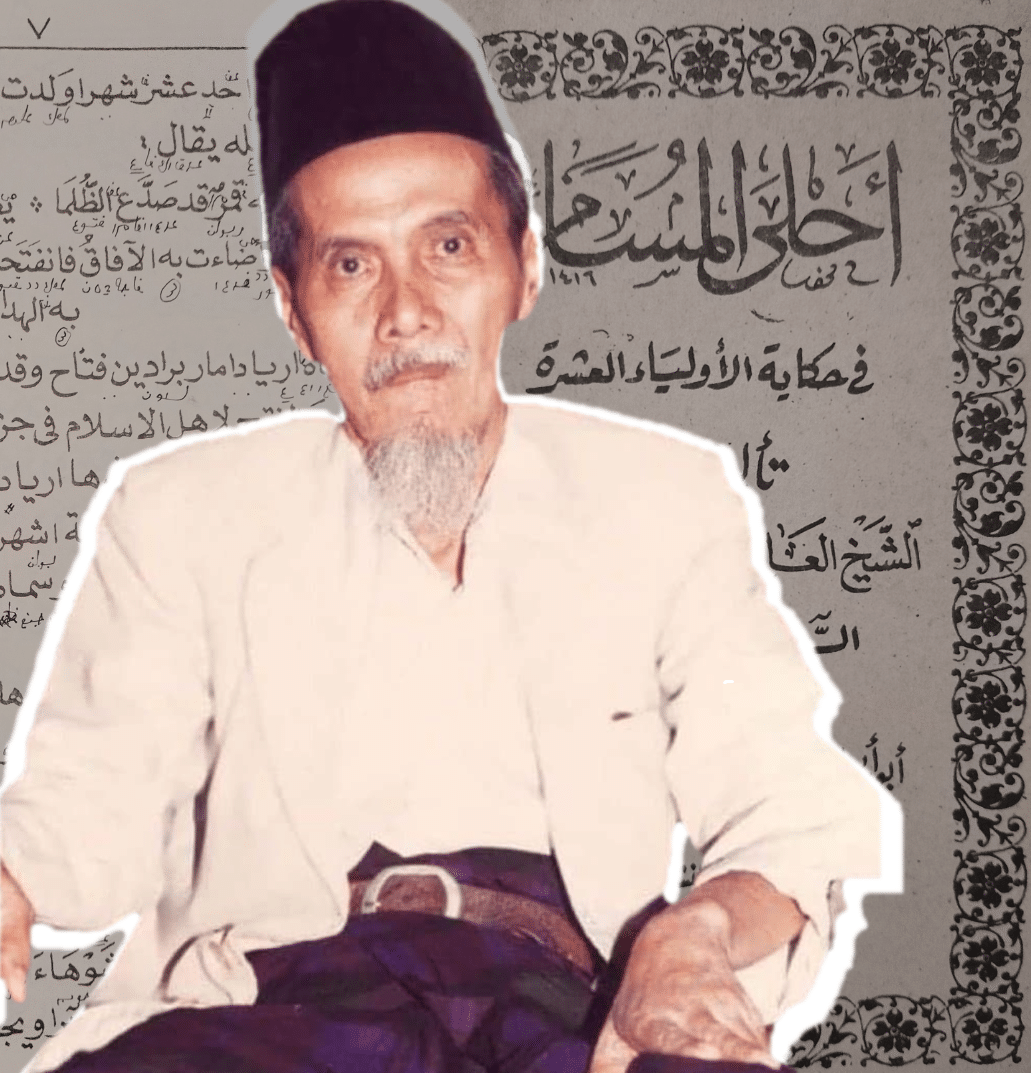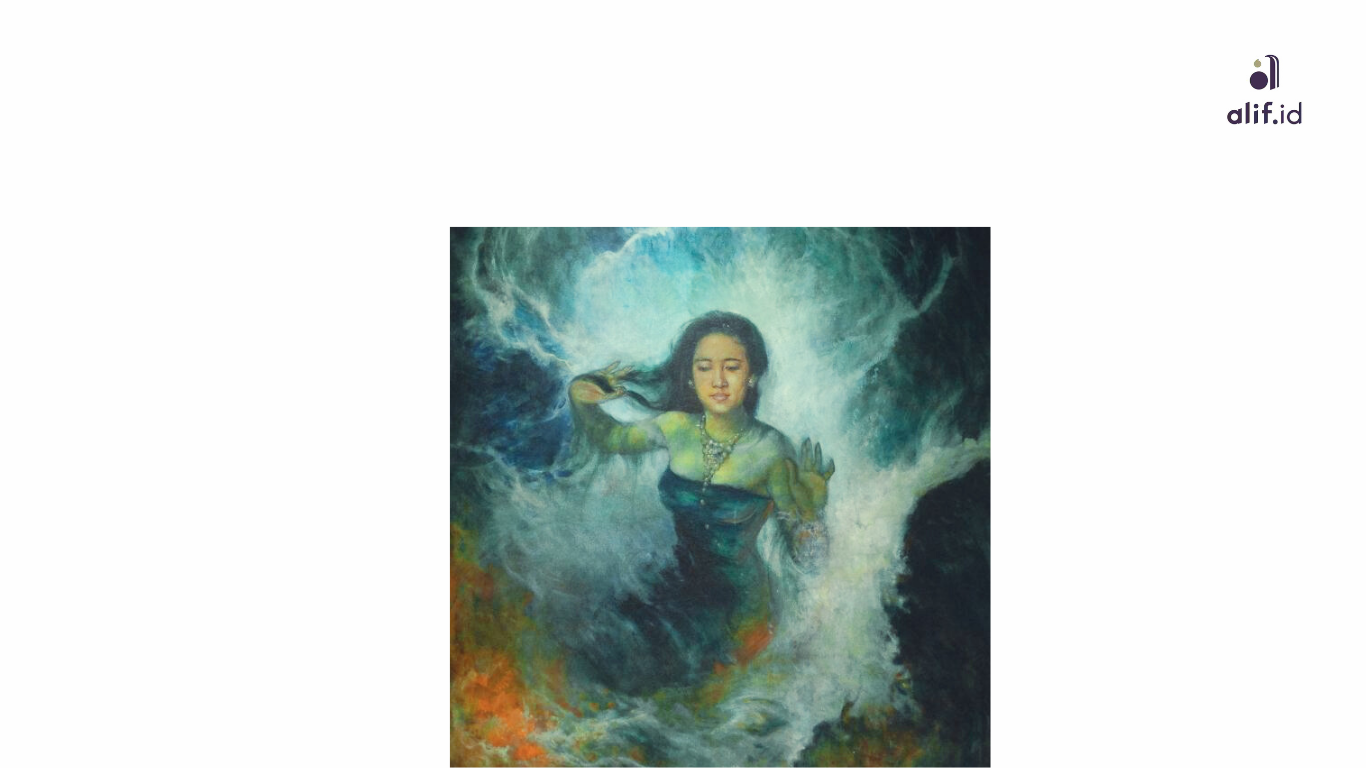Pathet dalam struktur dramatik pagelaran wayang purwa menentukan juga corak kesenian lainnya. Pada komposisi musik-musik tradisional Jawa yang menggunakan instrumen gamelan, yang disebut sebagai gendhing, pathet ini mendasari struktur musik, tembang-tembang, dan suasana yang dibentuk olehnya. Karena memang di samping musik-musik dan tembang-tembang tradisional Jawa itu satu paket dengan kesenian wayang sebagai pengiring, pendukung dan pembentuk suasana, hal ini kembali lagi pada prinsip pertama yang mendasari keseluruhan budaya Jawa tradisional: sangkan-paraning dumadi.
Titi laras atau tangga nada musik tradisional Jawa awalnya adalah laras slendro yang kemudian berkembang menjadi laras pelog. Di sini saya hanya akan menjelaskan laras slendro dimana polanya dipakai juga dalam laras pelog. Seandainya laras slendro terpilah ke dalam 3 pathet, nem-sanga-manyura, maka laras pelog pun terpilah ke dalam 3 pathet, lima-nem-barang.
Tak seperti musik Barat dimana tangga nadanya yang berjumlah 7 dinamakan do-re-mi-fa-sol-la-si-do, di Jawa tangga nadanya yang berjumlah 5 disebut dengan nama bagian-bagian tubuh manusia: laras 1 sebagai penunggul (kepala), laras 2 sebagai jangga (leher), laras 3 sebagai dhadha (dada), laras 5 sebagai lima (bagian tengah tubuh), dan laras 6 sebagai nem (bagian bawah tubuh). Sebagaimana kesenian wayang purwa yang dianggap tak dapat dilepaskan dari diri manusia, konsep musik tradisional Jawa pun juga erat kaitannya dengan diri manusia.
Dalam hal ini, sistem Yoga di India dapat menyingkapkan misteri tubuh manusia yang dipakai dalam konsep musik tradisional Jawa. Bagian-bagian tubuh manusia yang dipakai sebagai penamaan tangga nada Jawa tersebut merupakan titik-titik imajiner yang berada di tubuh manusia. Setidaknya, titik-titik imajiner yang lazimnya berjumlah 7 itu diringkas menjadi 3 yang utama: indraloka, janaloka, dan guruloka.
Sebagaimana suasana pathet nem dalam pagelaran wayang purwa, gending-gending atau musik-musik tradisional Jawa yang memiliki pathet nem biasanya juga penuh dengan suasana dimana kesadaran manusia seolah masih terbatas pada terpenuhinya segala keinginan, ibarat bayi yang akan merengek ketika haus dan akan diam ketika keinginan itu terpenuhi. Apakah komposisi gending-gending dan tembang-tembang yang ber-pathet nem penuh dengan eksplorasi nada 6 perlu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi yang pokok, nada 6 memang mengacu pada bagian bawah tubuh manusia atau yang dikenal pula sebagai indraloka. Seperti halnya konsep pathet, terang dalam hal ini komposisi gending-gending dan tembang-tembang tradisional Jawa menggambarkan pula fase kehidupan manusia, mulai dari awal (purwa), tengah (madya), dan akhir (wasana).
Di samping konsep pathet, konsep sangkan-paraning dumadi sebagai jantung kebudayaan Jawa tradisional gamblang pula terekam dalam konsep padhang-ulihan dalam struktur musik dan tembang tradisional Jawa. Konsep padhang-ulihan ini rupanya juga dipakai dalam seni tari dan seni rupa (seni ukir) Jawa tradisional. Sehingga terdapat rumusan bahwa apapun komposisi musik, gerak, maupun motif gambar mestilah memiliki padhang dan ulihan-nya (Pengetahuan Karawitan I, Martopangrawit, 1975).
Secara harfiah padhang dimaknai sebagai sesuatu yang telah jelas, tapi tak dapat ditentukan akan ke mana atau akan seperti apa pada akhirnya. Taruhlah bahwa kita tiba-tiba menyadari tengah duduk di ruang tamu (padhang). Tapi kita tak tahu pasti akan kemana atau akan seperti apa selanjutnya (ulihan atau pulang). Orang boleh mengatakan bahwa kita akan beranjak ke tempat tidur. Pertanyaannya: ketika sampai atau telah berada di tempat tidur, kita akan seperti apa atau melakukan apa. Dengan kata lain, detail atas ulihan tersebut belum dapat ditentukan apakah akan makan, berolahraga, tidur, dst.
Memang dalam hal ini akan terdapat seribu kemungkinan tentang ulihan tersebut. Tapi filosofi padhang-ulihan dalam berbagai kesenian Jawa tradisional juga membatasi kemungkinan itu, agar tak salah tempat. Ulihan pada akhirnya mesti pula berkaitan dengan kesesuaian atau “jumbuh” dengan tempatnya. Memang sah-sah saja di tempat tidur orang bermain gaple atau makan, tapi bukankah tak jumbuh dengan tempatnya?
Secara teknis padhang diartikan sebagai seleh ringan dimana nada-nada atau motif-motif yang dibunyikan tak terasa berat. Sementara ulihan justru sebaliknya, seleh berat dimana suasana yang dihasilkan akan terasa lega. Dan disinilah seni “kombangan” dalam musik dan tembang tradisional Jawa menemukan fungsinya (“Sambat Sebut”: “Duh Gusti… Trondholo!,” Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Ia adalah penghubung agar padhang tersebut nyambung dengan ulihan-nya. Ibarat perpindahan nada-nada lagu dari satu gatra (baris) ke gatra berikutnya tak berkelok curam atau terasa halus dan pas, lazimnya akan terdapat kombangan sebagai penghubung antara bagian padhang dan ulihan-nya.
Secara filosofis, seandainya konsep padhang-ulihan berkaitan dengan sangkan-paraning dumadi, maka “kombangan” itulah yang juga menjadi fungsi dari berbagai agama dan spiritualitas. Bukankah Ibn ‘Arabi pernah menyatakan bahwa yang menjadi jembatan antara makhluk dan Khalik adalah akhlak (khalaqtul khalqa)? Dan bukankah, bagi orang Islam, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak?
Tembang-tembang Jawa tradisional umumnya disebut sebagai “sekar” dan orang yang sedang menembang disebut sebagai “nyekar.” Sekar secara harfiah berarti bunga dan nyekar berarti menabur bunga. Tembang, karena itu, memiliki konotasi yang berkaitan dengan keindahan. Orang yang menembang, dengan demikian, adalah orang yang tengah memperindah sesuatu, sebagaimana para nabi, para wali, para kyai, dan para guru yang idealnya memperindah tabiat umat atau para pengikutnya.
Taruhlah seorang pesindhen atau waranggana ketika marah dan berupaya menyindir lelakinya yang baginya terlalu egoistis dengan ekspresi yang sarkastis, “Mbadhoka dhewe!.” Tentu hal ini akan terasa tak enak bagi yang mendengarkan dan kemungkinan justru akan menambah masalah baru. Tapi seandainya sang pesindhen menggunakan keterampilannya, suasana barangkali akan lain: “Brambang sak sen lima/ Berjuang labuh priyangga.”
Secara umum seni tembang tradisional Jawa memiliki 3 jenis sekaligus 3 fase sejarah: sekar ageng yang merupakan tembang-tembang yang mendasarkan diri pada karya sastra kakawin di era Majapahit, sekar tengahan yang merupakan tembang-tembang di era akhir Majapahit hingga era awal kerajaan Demak, dan sekar alit yang merupakan tembang-tembang yang lazim disebut sebagai macapat yang berkembang pada zaman akhir Majapahit hingga kerajaan Demak, keraton Ngayogyakarta dan Surakarta.
Seni macapat ini ternyata tak sekedar berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Bali dan Sunda terdapat pula seni macapat yang kemungkinan dibawa pelarian Majapahit dari Jawa ke Bali. Maka tak salah pula seandainya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa macapat identik pula dengan agama Hindu dan kemudian diakomodasi oleh para wali di era kerajaan Demak.
Pada seni macapat ini sangat tampak dijiwai pula oleh konsep sangkan-paraning dumadi. Selain pathet dan konsep padhang-ulihan, seni macapat juga menggambarkan kisah perjalanan manusia mulai dari bayi hingga ke liang lahat. Metrum-metrum yang dipakai, secara kebahasaan, memang mengacu ke fase tertentu kehidupan manusia. Seumpamanya metrum Mijil yang secara harfiah bermakna lahir atau keluar, Kinanthi yang bermakna diiringi, Sinom yang bermakna muda, Asmarandana yang berarti api asmara, Maskumambang yang berarti barang yang berharga tapi belum jelas keberhargaannya, Dhandhanggula yang berarti tempat mengolah gula atau juga burung gagak yang melambangkan kematian dengan harapan yang manis, Durma yang berarti macan yang berkaitan dengan keseraman, Pangkur yang berarti pungkuran atau belakang yang lebih memiliki konotasi tetirah, Gambuh yang berarti paham dan juga kesesuaian, Megatruh yang berarti melepaskan ruh atau mati, dan Pocung yang berarti dikafani. Ini semua adalah gambaran fase umum kehidupan manusia. Tema-tema tembang-tembang macapat biasanya menyesuaikan dengan nama metrum, meskipun kini kebiasaan ini tak begitu mengikat.