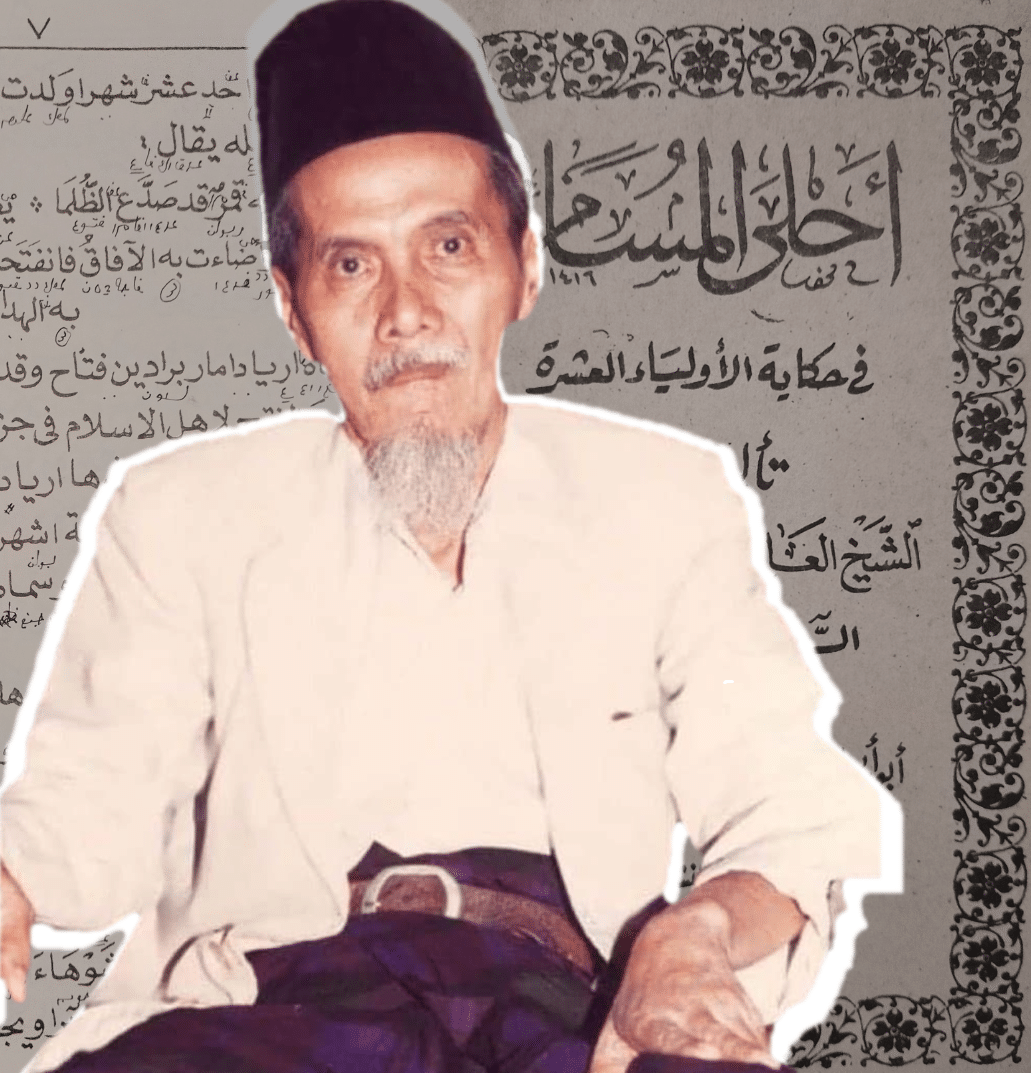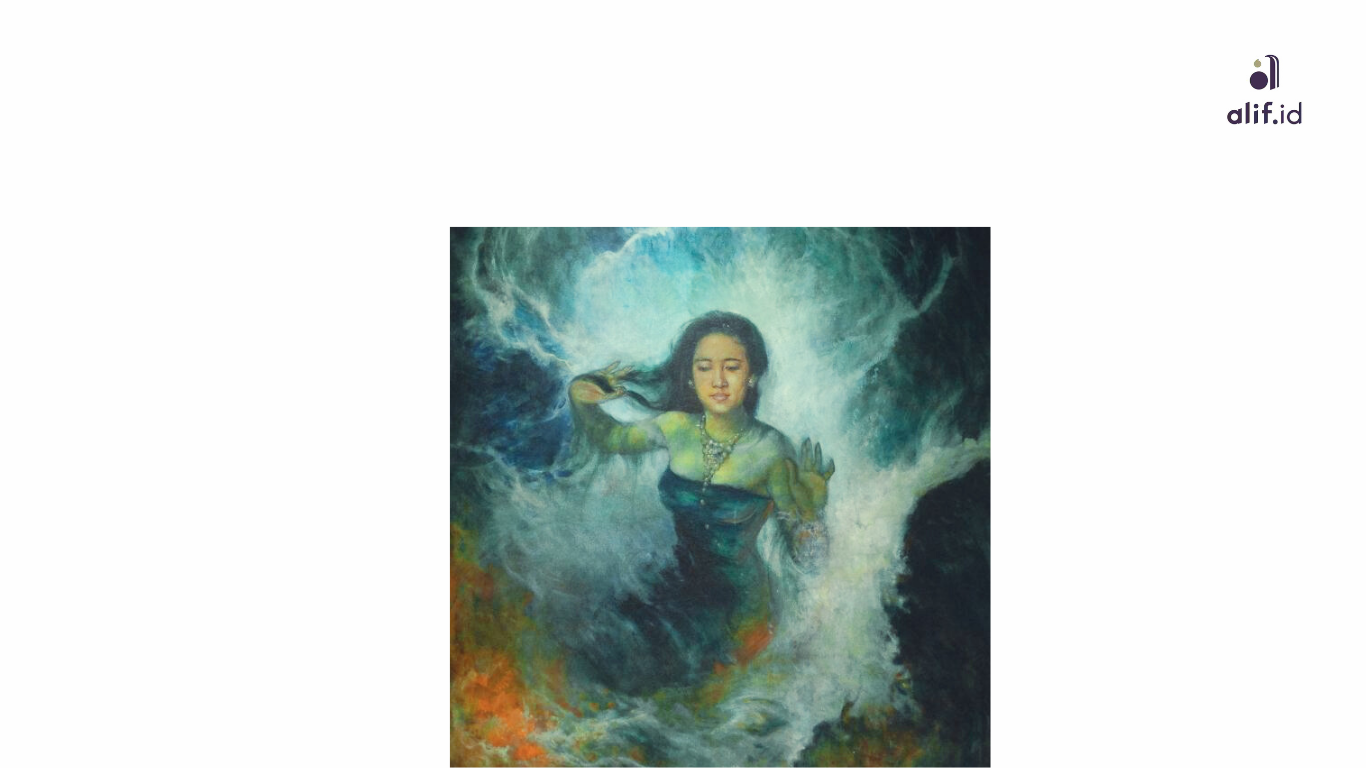Kebudayaan Jawa bersinggungan dengan agama, khususnya Islam, dengan media kesusastraan yang pada akhirnya, dalam telaah saya, turut membentuk apa yang kini dikenal sebagai tipologi Islam Nusantara. Secara historis, Islam Nusantara tak sekedar bertolak dari Walisongo di zaman kerajaan Demak.
Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825-1830 yang dipimpin oleh Pangeran Dipanegara adalah juga tonggak sejarah Islam Nusantara. Sebab, sesudah perang ini Islam yang telah berbaur dengan kebudayaan lokal dan membentuk varian tersendiri menyebar ke seluruh pulau Jawa dan bahkan luar Jawa (Perang Jawa Sebagai Tonggak Historis Islam Nusantara, Heru Harjo Hutomo, https://jurnalfaktual.id).
Kesusastraan Jawa sesudah Perang Jawa sangat tampak mencirikan Islam Nusantara. Setidaknya terdapat beberapa kepustakaan dan karya sastra yang bagi saya merepresentasikan corak Islam Nusantara. Pertama, Serat Wulangreh yang ditulis oleh Paku Buwana IV atau Sunan Bagus. Sunan Bagus sendiri dikenal sebagai seorang raja yang sangat nyantri dan menyukai kalangan santri (Jalan Jalang Ketuhanan: Gatholoco dan Dekonstruksi Santri Brai, Heru Harjo Hutomo, 2011). Di samping ia bermenantukan seorang kyai dari Tegalsari, Kanjeng Kyai Kasan Besari, namanya juga dikenal dalam sanad keilmuan tarekat Akmaliyah. Kedua, Serat Wedhatama yang ditulis oleh Mangkunegara IV.
Berbeda dengan Ranggawarsita, di samping ajarannya tentang nilai-nilai keksatrian cukup memengaruhi jejer seorang prajurit Jawa, Mangkunegara IV sangat tampak menganut corak tasawuf-akhlaqi sebagaimana al-Ghazali (Wedhatama dan“Kuluban” di Bulan Ramadhan, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Dalam kedua karya sastra ini sangat terang dinyatakan tentang sumber hukum yang patut dipegang oleh para anak keturunannya: al-Qur’an, hadis, ijma’, dan kiyas.
Lamun ana wong micareng ngelmi
Tan mupakat ing patang prakara
Aja sira age-age
Anganggep nyatanipun
Saringana dipun baresih
Limbangen lan kang patang
Prakara karuhun
Dalil kadis lan ijemak
Lan kiyase papat iku salah siji
Anaa kang mupakat
Ana uga kena den antepi
Yen ucul saking patang prakara
Nora enak legetane
Tan wurung tinggal wektu
Panganggepe wus angengkoki
Aja kudu sembahyang
Wus salatkatengsun
Banjure mbuwang sarengat
Batal karam nora nganggo den rawati
Bubrah sakehing tata
—Serat Wulangreh
Anggung anggubel sarengat
Saringane tan den wruhi
Dalil dalaning ijemak
Kiyase nora mikani
Katungkul mungkul sami
Bengkrakan mring masjid agung
Kalamun maca kutbah
Lelagone dhandhanggendhis
Swara arum ngumandhang cengkok palaran
—Serat Wedhatama
Ronggawarsita sendiri pun, yang dianggap sebagai seorang pujangga terakbar Jawa yang membabarkan doktrin martabat 7 dan cukup berpengaruh di lingkaran kapitayan, memiliki pula latar-belakang sebagai seorang santri (Gebang Tinatar dan Gelar Santri di Balik Nama Besar Ronggawarsita, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Konon, salah satu karyanya, Wirid Hidayat Jati, dianggap sebagai salah satu kitab rujukan para anak-murid Ki Ageng Djoyopoernomo di aliran Pirukunan Ayu Mardi Utomo (Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account, Andrew Beatty,1999). Bagian tulisan ini akan mengungkapkan persinggungan konsep sangkan-paraning dumadi yang menjiwai kebudayaan Jawa tradisional dengan perspektif Islam Nusantara dimana tasawuf atau sufisme secara otomatis telah menjadi bagian darinya.
Pada dasarnya makna istilah sangkan-paraning dumadi sepadan dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi “Inna lillahi wa inna ilahi raji’un.” Karena memang pada waktu itu para walisongo tak secara saklek memakai bahasa Arab untuk mengajar dan memberi bimbingan agama Islam pada orang-orang Jawa yang masih asing dengan bahasa Arab tapi cukup akrab dengan perkara dzauq. Dan banyak catatan sejarah mengatakan bahwa saat itu Islam dengan sufismenya bukanlah sesuatu yang sama sekali asing dengan spiritualitas orang-orang Jawa yang terlebih dahulu mencecap kapitayan. Atau dengn kata lain, terdapat konstinuitas mistis antara spiritualitas orang-orang Jawa ketika itu dengan sufisme yang memuncak pada masa Sultan Agung dan Pakubuwana II (Mystic Synthesis in Java, M.C. Ricklefs, 2006).
Memang terdapat kalangan yang mengklaim sebagai Islam dan secara membabi buta atau bahkan bodoh menghakimi kebudayaan Jawa tradisional, termasuk kepercayaan mereka, sebagai sesat atau kalau tak demikian, bukan merupakan bagian dari Islam. Perdebatan ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Serat Wulangreh cukup menggigit ketika melawan upaya-upaya yang “masturbasif” seperti itu: “Andhap asor dipun simpar/ Umbag gumunggung dhiri/ Obrol umuk kang den gulang/ Kumenthus lawan kumaki” (Wulangreh dan Deradikalisasi: Menggali Sisi Praktis Islam Nusantara, Heru Harjo Hutomo, https://jurnalfaktual.id). Demikian pula Serat Wedhatama yang menyatakan orang-orang yang hantam kromo terhadap kebudayaan Jawa sebagai “si goblok” (Islam Radikal dalam Filsafat Perwayangan dan Serat Wedhatama, Heru Harjo Hutomo, https://etnis.id).
Si pengung nora nglegewa
Sangsaya denira cacariwis
Ngandhar-andhar angendhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang si pinging
Si goblok yang tak sadar
Semakin berkobar dalam berkoar
Sungguh liar kesasar
Segala ujarnya ambyar
Semakin terlihat kegoblokannya
Si pandai yang jeli mengalah
Menutupi kegoblokan si goblok
Sebenarnya, alasan kalangan yang disebut “pengung” oleh Serat Wedhatama itu sama sekali tak berdasar bahkan seandainya hal itu dikaitkan dengan pemakaian bahasa Arab yang dipandang lebih islami. Sebab, kitab babon (rujukan) ilmu pedalangan gaya Jawa Timuran ditulis dengan huruf pegon: aksaranya Arab tapi bahasanya Jawa. Kitab ini dikenal dengan nama Kitab Gondhil yang setara dengan Serat Kandha dalam pedalangan gaya Jogja dan Serat Pustakaraja Purwa dalam pedalangan gaya Sala. Dengan kata lain, kalangan “pengung” tersebut adalah apa yang kini dikenal sebagai kalangan Islam radikal.
Saya sendiri ketika meneliti peran dan fungsi dalang dalam pagelaran wayang purwa teringat akan al-Ghazali dalam ‘Ajaibul Qulub yang mengibaratkan hati (qalb) sebagai sang jendral dimana bagian tubuh lainnya menjadi bawahan atau tentaranya. Hati inilah yang oleh seorang sufi dari Thusi ini disebut sebagai “latifah rabbaniyah-ruhaniyah.” Bukankah dalam adab pagelaran wayang purwa adalah dalang yang diberi wewenang untuk menggelar pagelaran dan memimpin persuaan (sapatemon) dengan yang menanggap yang merupakan perlambang dari Sang Hyang Manon (Yang Maha Tahu)? Dan bukankah istilah Sang Hyang Manon sendiri diturunkan dari sufisme-filsafati Ibn ‘Arabi yang digelari sebagai kutub ma’rifat (pengetahuan)?
Terang, dalam kebudayaan Jawa, baik tasawuf-akhlaqi maupun tasawuf-filsafi cukup memiliki persinggungan dengannya. Tak salah seandainya dahulu Sunan Kalijaga, yang digelari sebagai Guru Suci Wong Tanah Jawi, memakai kesenian wayang sebagai salah satu medianya untuk berdakwah. Sunan Kalijaga sendiri pun cukup lekat dengan citra wujudiyah sehingga karenanya cukup terasa njawani yang membuatnya juga dianggap laiknya guru bagi kalangan kejawen disamping kalangan santri atau pesantren.
Tentang kemampuannya untuk hidup di dua alam (hayyun fi al-daraini) secara harfiah adalah kemampuannya untuk melintas sekaligus menjaga baik keberlangsungan, kesambungan dan kesinambungan Islam tradisional maupun kejawen atau yang secara khusus saya istilahkan sebagai kapitayan. Dan memang tasawuf wujudiyah terkenal dengan sikap pluralistiknya sehingga melahirkan konsep wihdatul adyan sebagaimana di Andalusia yang menjadi tempat kelahiran Ibn ‘Arabi yang dalam catatan sejarah pernah melahirkan “la convivencia” yang melegenda dimana agama-agama yang berbeda saling berkoeksistensi.
Ibn ‘Arabi sebagai salah satu sufi-filosof terakbar pernah pula meninggalkan gambaran dari salah satu hadis qudsi yang mendasari tasawuf-filsafatinya, dan saya kira turut mengilhami pagelaran wayang purwa tradisional: “Kuntu Kanzan Makhfiyyan, fa ahbabtu an u’rafa, fa khalaqtul khalqa.” Dalam Wirid Hidayat Jati Ronggawarsita keredaksiaan hadis qudsi itu bersambung demikian: “Kang dhingin Ingsun anitahaken kayu aran sajaratul yakin, tumuwuh ing sajroning alam adam makdum azali, nuli cahya aran Nur Muchammad, nuli kaca aran mir’atul kayai, nuli nyawa aran roh ilapi, nuli damar aran kandil, nuli sesotya aran darah, nuli dinding jalal aran kijab kang minangka warananing khalaratingsun.”
Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pagelaran wayang purwa, dan juga kesenian-kesenian tradisional lainnya, adalah proses tergelarnya kehidupan atau sangkan-paraning dumadi. Tuhan, yang diungkapkan dengan kata ganti pertama tunggal, ingin diketahui dan karenanya lalu digelarlah berbagai tahapan atau martabat dimana gunungan, kayu atau kayon dalam pagelaran wayang yang secara teknis menandai babak pagelaran adalah perlambang martabat yang pertama pada proses tanazzul. Persis dengan proses pagelaran wayang purwa dimana yang menanggap ingin “diketahui” yang karenanya digelarlah pagelaran wayang. Di balik segala gebyar pagelaran wayang itulah yang menanggap turut melihat atau menyaksikan dimana kemudian melahirkan konsep wihdatus syuhud di samping wihdatul wujud dalam sufisme. Karena itulah yang menanggap disebut sebagai Sang Hyang Manon dimana panon secara harfiah berarti mata.
Adakalanya dalam perumpamaan pagelaran wayang purwa itu bukan hanya sang dalang yang dapat sapatemon dengan yang menanggap. Wayang pun dapat mencapai keadaan seperti itu. Barangkali, banyak di antara kita yang mempertanyakan bagamana mungkin seorang Bima yang terkenal lugas dan tegas dapat jumbuh dan bahkan manjing ke dalam Dewa Ruci? Kenapa bukan para ksatria yang berperangai halus seperti Arjuna yang merupakan lelananganing jagat atau Yudhistira yang seorang satriya-pinandhita? Sultan Agung dalam Serat Pengracutan ternyata mengungkapkan bahwa Bima adalah salah satu dari ke sembilan ghautsul a’dham yang bergelar Syekh Senan. Bukankah memang secara wijang kawruh sangkan-paraning dumadi khusus dibabarkan dalam lakon wayang Dewa Ruci dimana Bima dengan rambutnya yang masih tergerai panjang sepinggang menjadi sang tokoh utama dan sesudah peristiwa itu rambutnya pun digelung yang kemudian lebih dikenal sebagai Wrekudara?