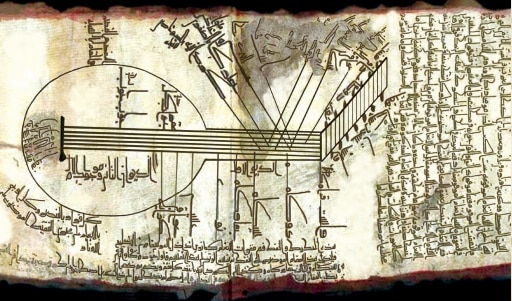Atas nama kemaslahatan, manusia bisa lebih berhak dari Tuhan. Sebab jika tidak demikian, manusia tidak akan mampu memahami dengan ideal mana konsep teologi yang fundamental dogmatic dan nalar legal yang positive casuistic.
Tulisan ini tidak dihadirkan untuk mendiskusikan butir-butir fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang praktik peribadatan di tengah ancaman wabah Covid-19. Sebagai orang awam, kita patuhi saja fatwa-fatwa yang sarat akan kemaslahatan tersebut. Di sini, kita hanya berupaya melihat fatwa-fatwa tersebut dari perspektif lain dengan berdasarkan paradigma legal dan konstruksi filosofisnya.
Hak Tuhan dan Hak Manusia
Dalam beragama, terma fundamental dogmatic merupakan kalam teologis yang mutlak harus diterima apa adanya oleh subjek yang mengimaninya. Tidak akan sah iman manusia tanpa meyakini kebenaran ajaran teologi keagamaannya. Namun tidak demikian dengan nalar legal keagamaan yang positive casuistic. Hal ini karena praktik narasi legal senantiasa mempertimbangkan realita eksternal yang mengitarinya (ma hawla al-hukm).
Dalam literatur ushul fikih, konsep hak antara hak Tuhan dan hak manusia diatur dalam empat tipologi:
Pertama, hak eksklusif Tuhan an sich (huquq al-LLah al-khalishah). Pada hakekatnya adalah hak-hak yang berkaitan dengan keesaan Tuhan, konsep keimanan dan praktik ritual peribadatan. Dalam Mirqah al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul, Mulla Khasr al-Hanafi menyatakan bahwa Tuhan memiliki hak penuh atas apa-apa yang berkaitan langsung dengan eksistensiNya. Di sini, manusia tidak memiliki otoritas apapun untuk menyangsikan segenap hal yang menjadi kemutalakan diriNya.
Kedua, hak ekslusif manusia an sich (huquq al-‘ibad al-khalishah). Manusia memiliki hak-hak kemanusiaannya secara eksklusif dan dapat sepenuhnya direalisasikan berdasarkan hajat primer kebutuhannya. Imam Al-Qarafi dalam al-Furuq menyatakan bahwa hak manusia adalah tentang segala fenomena yang berkaitan dengan kemaslahatannya (haq al-‘abd mashalihuhu). Pada titik ini, manusia memiliki otoritas untuk menentukan apa-apa saja yang dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupannya, baik secara personal maupun sebagai makhluk sosial. Hal demikian dipertegas kembali oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa menciderai hak eksklusif manusia sebagai fenomena hukum adalah sebentuk kejahatan luar biasa.
Ketiga, hak antar keduanya, namun hak Tuhan lebih unggul (ma ijtama’a bainahuma wa haq al-LLah awla). Misalnya, pemberlakuan hukum terhadap pihak yang menuduh orang lain berzina, namun tidak bisa dibuktikan kebenaran faktanya. Dalam esensi legal praktisnya, di satu sisi, pihak yang dirugikan dapat menuntut balik atau meminta ganti rugi atas dalil pencemaran nama baik. Namun, di sisi lain, Tuhan memiliki hak untuk memberlakukan hukuman cambuk terhadap pihak yang menuduh (had al-qadzaf). Dalam fenomena hukum seperti ini, menurut perspektif hukum Islam klasik, hak Tuhan lebih tinggi dan diunggulkan untuk direalisasikan dari pada hak manusia (God’s rights is higher than human’s). Sebab dengan pemberlakuan had al-qadzaf terhadap pihak yang menuduh telah dengan otomatis membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dengan demikian, nama baiknya akan tetap terjaga.
Keempat, hak antar keduanya, namun hak manusia lebih unggul (ma ijtama’a bainahuma wa haq al-‘abd awla). Misalnya, pemberlakuan hukum qishash. Dalam esensi legal praktisnya, di satu sisi, Tuhan memiliki hak agar aturan hukum yang dibuatNya direalisasikan. Namun, di sisi lain, manusia memiliki dua pilihan sekaligus, yakni menuntut pemberlakuan tindakan yang sama (misal: nyawa dibayar nyawa), atau dengan berbagai pertimbangan, memilih untuk melakukan perdamaian (ash-shulh) baik dengan meminta ganti rugi (diyat) dan atau dengan hukuman lain namun tidak sampai menghilangkan nyawa tersangka sekaligus (misal: penjara seumur hidup).
Dalam fenomena hukum seperti ini, manusia, dalam hal ini pihak keluarga korban, secara langsung memiliki hak pilih (haq al-khiyar) dengan tetap berdasarkan pada asas-asas kemaslahatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Hak pilih di sini menegaskan bahwa manusia bisa lebih berhak dari pada Tuhan (human’s rights is higher than God’s). Dengan demikian, tidak memberlakukan hukum qishash sama sekali tidak menciderai kualitas keimanan dan idealitas praktik keagamaan seseorang.
Fenomena dan Filsafat Fatwa
Layaknya fenomena alam, fatwa hukum tidak diam. Perubahan fenomena sebagai realita eksternal (al-waqi’ al-kharijiy) meniscayakan perubahan fatwa hukum agar tetap relevan. Kebebasan dalam pengambilan sikap berhukum yang kritis menyoal perkara praktik keagamaan dan sosial-politik sekaligus merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam literatur ilmu ushul fikih disebutkan bahwa perubahan fatwa hukum dapat dilakukan seiring dengan fenomena (yang dihadapi) sebuah masa dan tempat realisasi hukumnya (manath al-hukm).
Imam Asy-Syafi’i dalam magnum opusnya Ar-Risalah menegaskan bahwa kesadaran manusia terhadap pengetahuan tentang hukum dapat dikonstruksikan dengan dua jalur sekaligus; mengikuti pengalaman sejarah hukum (ittiba’) dan menggali khazanah hukum baru (istinbath). Hal ini perlu disadari agar sanad epistemologi sebuah hukum tidak terputus, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat relevan dengan keadaan kontekstualnya. Imam Asy-Syafi’i percaya bahwa tidak ada satu fenomenapun yang dapat melepaskan diri dari hukum (kullu ma nuzil fa fihi hukm lazim).
Dalam perspektif filsafat hukum Islam, kegiatan manusia dalam proses melacak dan mengkonsepkan sebuah hukum merupakan dalil eksistensial cara ber-“ada” manusia itu sendiri. Kesadaran ini dapat menjadi konstruksi awal nalar hukum bagi manusia. Sehingga manusia memiliki langkah hukum yang progresif agar ia dapat bertindak lebih tepat dalam interaksinya dengan dunia dan masyarakat sosialnya. Sebab hukum tidak semata menyoal ritual individual, namun juga sekaligus kesalehan sosial.
Tindakan sosial, dalam studi fatwa dan fenomena, tidak hadir untuk menegasikan apa-apa yang sudah tersurat dalam teks-teks keagamaan secara sharih (jelas). Melainkan untuk mengafirmasi bahwa pemberlakuan hukum Tuhan senantiasa mempertimbangkan fenomena hukum yang dihadapi oleh manusia secara keseluruhan. Pada titik ini, konsep kemaslahatan sosial dalam fatwa hukum menemukan pijakan paradigmatiknya.
Pernyataan bahwa dalam hukum, manusia bisa lebih berhak dari Tuhan merupakan kesadaran terhadap diservikasi konsep hak (mafhum al-huquq) dalam literatur-literatur keagamaan, khususnya ilmu ushul fikih. Interpretasi ini bukan tanpa alasan argumentatif, karena relasi Tuhan dan manusia bisa hadir dengan pola yang tidak statis. Risalah kenabian yang diturunkan sebagai rahmat mengindikasikan bahwa agama sejatinya memang diperuntukkan sepenuhnya untuk manusia. Maka menjadi absahlah kalam Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Wallahhu a’lam.