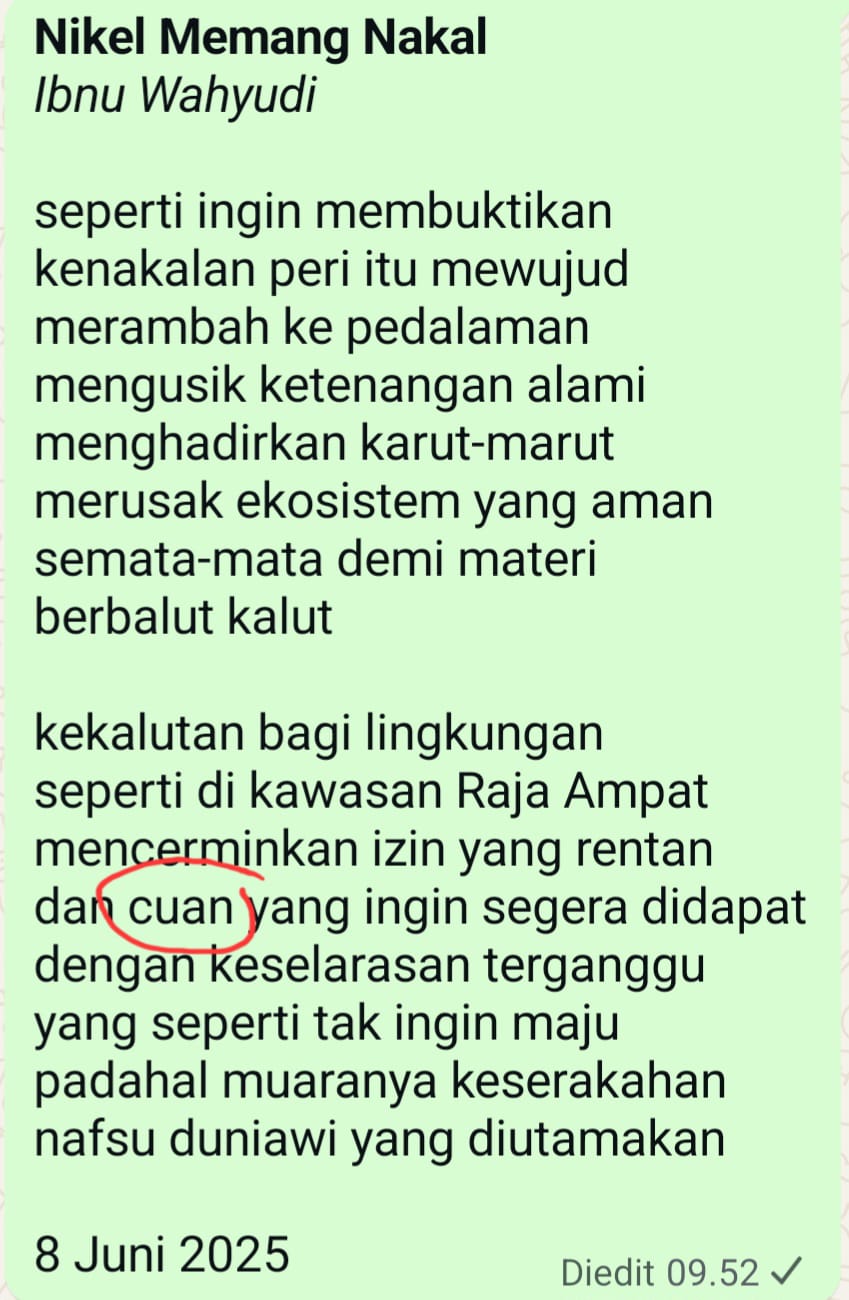Saya mempunyai pandangan agak berbeda mengenai jilbab yang terus menerus mengundang kontroversi belakangan ini. Sementara menghargai pro dan kontra yang ada, saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya secara lebih luas dari sudut panjang sejarah sosial. Menurut saya, obsesi terhadap jilbab yang menguat selama dua dekade terakhir merupakan “serangan balik” dari praktik sekularisme yang otoriter di masa lalu.
Di masa lalu, harus diakui, sekularisme dijalankan secara otoriter. Khususnya di dunia Muslim, bayangan mereka terhadap sekularisme adalah Turki di era Kemal Attaturk. Ketika itu agama diusir dari ruang publik. Simbol-simbolnya, termasuk jilbab, hanya diperkenankan dipakai di ruang privat. Soeharto pernah menerapkan pemikiran sekularisme otoriter ini ketika melarang perempuan berjilbab di sekolah negeri. Pemerintah Prancis masih memberlakukannya hingga kini.
Akibatnya adalah timbul kebencian yang mendalam di sebagian kalangan Muslim. Namun mereka tidak tahu caranya bagaimana mengeksresikan kebencian tersebut kecuali dengan memakai apa yang dilarang oleh sekularisme “garis keras” itu. Mereka memaknainya sebagai perlawanan terhadap dominasi Barat yang kelewatan.
Pada saat yang sama, di sisi sebaliknya, sebagian orang juga masih menganggap jilbab sebagai simbol dominasi patriarkisme agama terhadap kebebasan perempuan. Mereka melihat perempuan berjilbab dengan sinis. Dalam konteks negara-negara Barat, pandangan ini tentu saja bercampur baur dengan berbagai prasangka kultural terhadap kelompok-kelompok imigran yang berasal dari negeri-negeri Muslim.
Dengan kata lain, kontroversi jilbab bukan sekadar perkara penafsiran agama. Lebih dari itu, hal ini merupakan aksi-reaksi dari perkembangan sekularisme yang pernah menjadi norma politik utama dalam pembangunan negara bangsa. Sekarang adalah saat ketika norma politik utama itu menuai serangkan baliknya.
Serangan balik terhadap sekularisme terasa mempunyai legitimasi di tengah krisis neoliberal. Di saat banyak orang merasa hidupnya secara ekonomi semakin susah, tafsir yang lebih longgar terhadap batasan jilbab terdengar seperti ejekan terhadap kehidupan mereka yang justru sedang memperkuat imannya. Pihak yang paling marah adalah siapa lagi kalau bukan kalangan Muslim urban. Kalangan terakhir ini umumnya adalah kelas prekariat yang mudah tersinggung oleh tafsir “liberal”, termasuk mengenai batasan jilbab. Mereka tidak peduli luasanya perdebatan mengena hal ini dalam khazanah keilmuan Islam, karena memang tidak bisa menjangkaunya, tetapi cukup pasti bagi mereka jilbab adalah benteng identitas yang harus dipertahankan mati-matian di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. (RM)