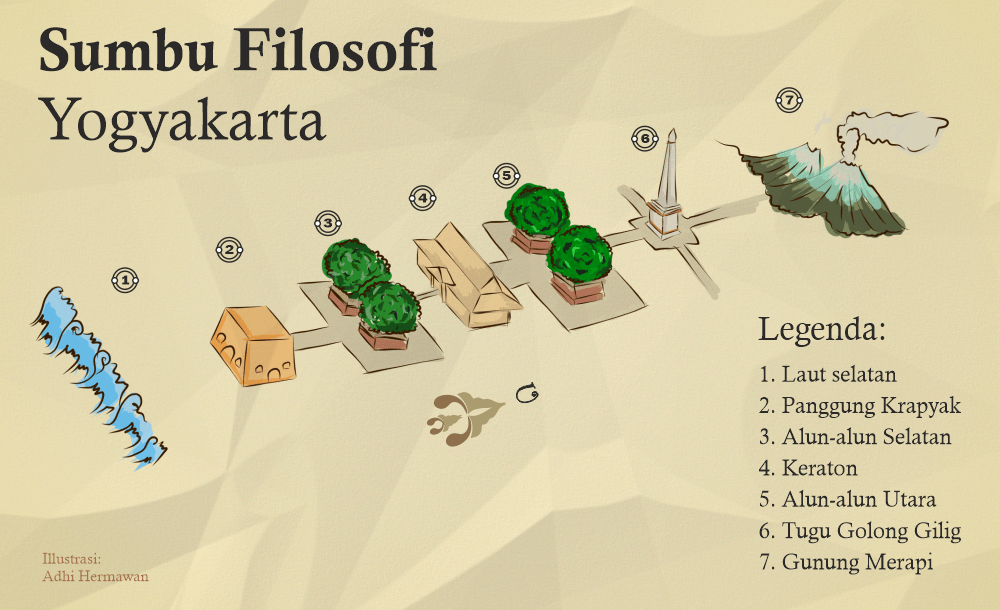Tulisan ini lahir dari diskusi tentang perjalanan ilmu filologi dari masa ke masa dengan teman yang mengambil konsentrasi di bidang ilmu tersebut di UIN Jakarta sekaligus anggota Lingkar Filologi Ciputat (LFC).
Kami juga mengulas sedikit tentang isi buku A Scribes and Scholars: A Guide to the Transmissions of Greek and Latin Literature” karangan Reynold and Wilson (1978). Dari sini, kami mendapati banyak hal yang sangat mengesankan dari perjalanan ilmu ini.
Pada awalnya, ilmu filologi berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh para pustakawan di Alexandria yang mendapati banyak kesalahan teks yang ada dalam media tulis kala itu di perpustakaan. Mereka melakukan pengecekan tentang kebenaran dan kemurnian teks serta memberikan komentar di tepi naskah jika mereka meyakini ada kesalahan dalam penulisan. Seiring berjalannya waktu, ilmu ini bersentuhan dengan ragam kepentingan; agama, ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Dalam perjalanannya, ilmu ini sampai ke Indonesia melalui para filolog dari negeri kincir angin, Belanda. Frederick de Houtman (1603) dengan karangan pertamannya Sprak Ende Woordboek, Inde Maleysche Ende Madagaskarche, dan beserta tokoh barat lainya yang banyak memengaruhi filologi di Indonesia. Meskipun mereka sendiri masih belum sadar seratus persen kalau kegiatan yang mereka lakukan adalah bagian dari filologi tradisional.
Berkaitan dengan dunia filologi, Indonesia memiliki kekayaan berbentuk ‘tutur’ dan ‘tulis’ yang luar biasa. Seperti yang tersebut dalam website badan bahasa kemendikbud RI, setidaknya ada 652 bahasa lisan dari Sabang hingga Merauke.
Itu pun belum semuanya berhasil diidentifkasi oleh pemerintah. Selain itu, ada 12 aksara yang masih ada serta digunakan sebagai media untuk merekam ide serta gagasan serta peristiwa peristiwa penting lainya. Pada masa lalu peradaban bangsa ini biasa menggunakan media berupa batu, lontar, kulit binatang, kulit kayu, daluwang, dan sebagainya.
Dua kata ‘tutur’ dan ‘tulis’ pada paragaraf di atas, sengaja penulis kasih petik sebagai penekanan dalam tulisan kali ini. Sebagai negara modern dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Alfabet-Latin sebagai aksaranya, semestinya tidak lantas membuat “aksara lokal” semakin ditinggalkan. Tidak saja sebagai kekayaan budaya, lebih dari itu “aksara lokal” merupakan bukti kemandirian bangsa dalam berbahasa.
Menurut penuturan kawan-kawan penulis yang aktif dalam kegiatan studi pernaskahan atau “manuskrip”, bangsa Indonesia masa lalu atau Nusantara sebelum dijejali oleh kolonial dengan literasi abjad mereka, yakni A, B, C dan seterusnya, memiliki aksara sendiri dan mandiri yang biasa digunakan dalam segala hal.
Aksara-aksara tersebut meliputi aksara: Jawa, Bali, Sunda, Bugis/Lontara, Rejang, Lampung, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, Kenci Rencong, serta masih ada yang lain termasuk aksara Melayu-Jawi alias Pegon.
Sayangnya, nasib “aksara lokal” tidak semujur dan seberuntung nasib ‘batik’ yang sudah menjadi gerakan pelestarian kebudayaan nasional. Beberapa saat yang lalu, kita memperingati Hari Batik Nasional, yakni pada 2 Oktober 2018. Batik sudah mendapatkan pengakuan internasional, hingga UNESCO pun tak kuasa untuk tidak mengakui batik kekayaan milik bangsa Indonesia ini.
Secara de jure, pada 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Batik resmi menjadi “Warisan Kemanusiaan Untuk Budaya Lisan Nonbendawi” (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humatiy) milik pemerintah dan rakyat Indoensia. Status hukum internasional ini akan jadi dasar yuridis bagi hak milik Indoneisa, jika di kemdian hari diakui oleh Negara lain seperti yang sudah-sudah.
Lalu, bagaimana dengan nasib Aksara Lokal kita? Tidakkah ia juga layak untuk kita perjuangkan menjadi kekayaan bangsa yang diakui oleh dunia internasional juga?
Sudah jamak, dampak globalisasi dengan cepat memengaruhi ‘kepunahan’ sesuatu yang bersifat lokal. Sebut saja arus inggrisisasi, arabisasi, mandarinisasi dan lain sebagainya. Pengaruhnya, perlahan tapi pasti, mengakibatkan “lokalitas” ngos-ngosan untuk bertahan hidup atau bahkan sekarang sedang menggali kubur, menunggu mati, dan hanya tingal kenangan. Tragis!
Sebagai alternatif, hemat penulis, pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memikirkan ‘ke-sekarat-an’ “AKSARA LOKAL” milik bangsa Indonesia. Langkah lebih cepat, sementara ini mungkin dengan melalui Keputusan Presiden (Keppres) menetapkan Hari Nasional “Aksara Lokal” sebagai kelanjutan dari HAI. Di tengah peperangan kebudayaan secara Internasional, Aksara Lokal akan menambah daftar kekayaan lokal bangsa yang patut dikagumi oleh mancanegara.