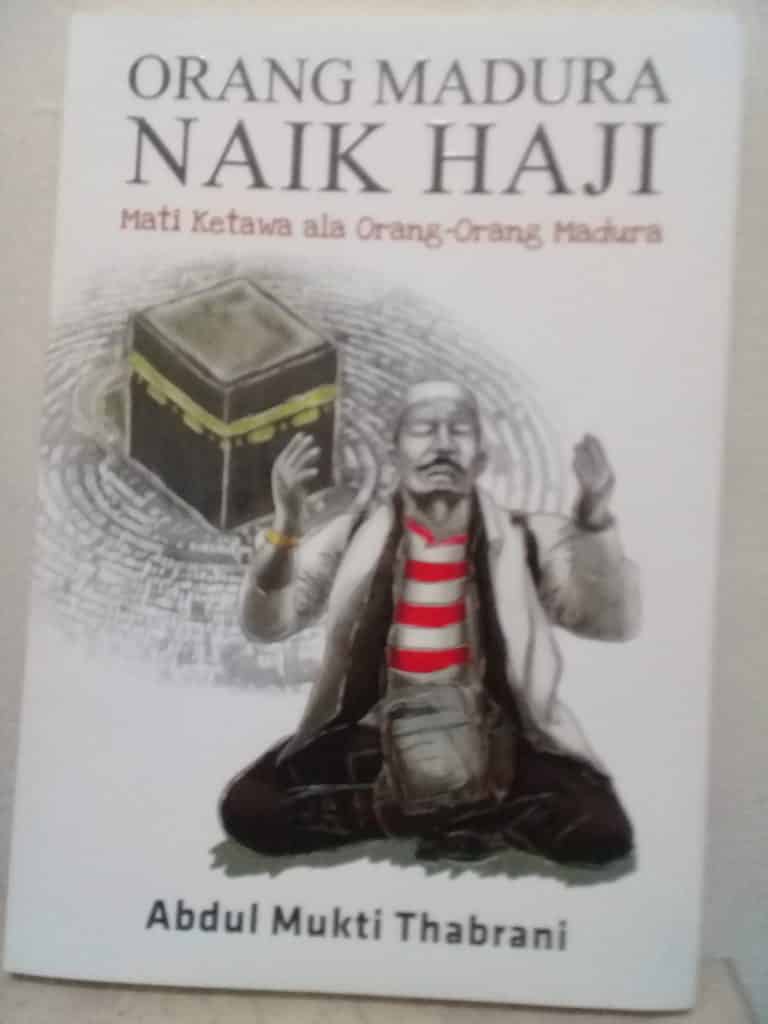
Pelbagai ritual keagamaan menuntut kita untuk menjalaninya dengan serius dan penuh totalitas. Karena, dalam kondisi demikian pada hakikatnya kita tengah melakukan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Sebuah momen yang tidak menyediakan tempat bagi sikap berbau lelucon. Namun, aturan main tersebut sepertinya tak berlaku bagi orang-orang Madura.
Apa sebab, dalam setiap menjalani upacara-upacara atau ritual keagamaan, dengan kepolosan perilakunya, orang Madura selalu meninggalkan jejak jenaka yang mengundang orang lain tertawa terpingkal-pingkal. Seperti buku Orang Madura Naik Haji yang ditulis Abdul Mukti Thabrani.
Buku yang berjumlah 188 halaman tersebut, dengan bahasa yang renyah, berhasil merekam jejak-jejak kelucuan orang-orang Madura saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sepertii yang dialami Mat Halil saat berada di kamar hotel di Makkah.
Suatu waktu, kamar tempatnya berdiam bersama teman-temannya mendadak menjadi Neraka karena AC-nya mati. Mengingat suhu yang begitu panas di Makkah, bisa dibayangkan bagaimana galaunya Mat Halil dan teman-temannya tinggal di kamar tanpa pendingin ruangan. Memperbaiki sendiri AC yang mati itu adalah tindakan gila karena mereka asing dengan benda bernama AC. Artinya pun mereka tak ada yang paham.
Jalan satu-satunya adalah melapor kepada petugas hotel bahwa AC di kamar telah “wafat”. Tapi, siapa yang akan melapor, jika saat laporan harus berbahasa Arab? Ketidak pahaman akan bahasa Arab meenjadi persoalan bagi kelompok Mat Halil. Mereka pun musyawarah, dan hasilnya memutuskan Mat Halillah yang layak menjadi juru lapor kepada petugas hotel, mewakili mereka.
Meskipun Mat Halil merasa hal itu merupakan tugas yang amat berat karena ia tak bisa berbahasa Arab, tetapi demi kekompakan ia bersedia melapor, apapun yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa bahasa Arabnya mati, apa bahasa Arabnya rusak. Namun sudahlah, semua akan indah pada waktunya.
Maka berangkatlah Mat Halil menuju resepsionis hotel untuk melaporkan matinya AC di kamar. Ketika sudah berhadapan dengan petugas yang ternyata benar orang Arab itu, Mat Halil berusaha tenang dan memberanikan diri menyapa dengan sapaan umum, “Assalamu’alaikum, Tuan. Saya mau melapor”. Dengan santai, petugas menjawab salam, lalu bertanya, “Isy fii haj? (Ada apa, Pak Haji?)”. Dengan suara yang mantap, Mat Halil menjawab, “Tuan, hadzaa AC di kamar saya, innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun.” (hlm 131).
Keterbatasan bahasa Arab, yang berujung pada kesalahpahaman tidak hanya dialami Mat Halil dan teman-temannya. Hal ini juga dialami salah seorang jamaah haji, sebut saja Sarnito, asal Kabupaten Pamekasan Madura. Sewaktu di Masjidil Haram, Sarnito dan temannya ditinggalkan oleh rombonganya yang sudah terlebih dulu pulang ke hotel.
Terpaksa ia dan temannya itu naik taksi, sopir taksi yang membawa mereka ternyata orang Badui atau orang pedalaman yang buta huruf. Namun, masalahnya bukan buta hurufnya, tetapi terletak pada ketidaknyambungan komunikasi antara makhluk yang berbeda bahasa dan budaya itu. Sarnito dan teman-temannya tak paham bahasa Arab. Sang sopir, anggap saja Abu Jahal, tidak paham bahasa Madura. Lengkap sudah masalahnya.
Masalah ongkos sudah deal, sepuluh Rial, meski sebelumnya agak sedikit rumit dalam tawar menawar menggunakan bahasa isyarat. Di antarlah Sarnito dan teman-temannya dari masjid terbesar di dunia itu menuju hotel pemondokan Sarnito. Masalah pun muncul ketika Sarnito dan teman-temannya hendak berhenti karena hotel yang mereka tuju sudah dekat.
“Kiri!” teriak Sarnito begitu hotelnya kelihatan. Namun, sopir tidak paham apa itu “kiri”. Teman Sarnito membantu, “berhenti, sudah sampai!”.
Tetap saja keadaan tidak berubah, mobil tetap melaju. Lantas, Sarnito ingat sesuatu. Kecerdasannya seketika muncul di detik-detik terakhir. Ia ingat ketika hendak berhenti membaca Alquran, saat ngaji di langgar dulu, ia melafalkan kalimat yang ia anggap semua orang di dunia ini paham maksudnya. Maka, dengan mantap, Sarnito berterik kepada sang sopir, “Shadaqallahul azhiim.”. Taksi pun berhenti sesuai kehendak Sarnito (hlm 134).
Abdul Mukti Thabrani, telah berhasil merekam perilaku-perilaku “gila”, “ajaib”, “sinting” orang Madura ketika hendak berangkat haji atau umroh sampai kembali lagi ke Tanah Air. Tentu saja, membuat kita terpingkal-pingkal sampai mengeluarkan air mata membacanya. Seperti kelakuan Sarmadin saat berada di atas pesawat. Ketika antre naik pesawat, Sarmadin sedikit pun tak menggubris pramugari yang memintanya tertib, antre, dan duduk sesuai dengan boarding pass yang ia pegang (sejak dulu, orang Madura dikenal susah diatur, termasuk si Sarmadin, kecuali oleh kiai dan gurunya).
Di dalam pesawat Sarmadin langsung memilih tempat duduk bussines class yang kursinya lebih lapang dan nyaman. Bukan apa, karena Sarmadin sudah terbiasa bila naik angkot ia duduk di kursi paling depan. Pramugari pun hanya bisa tersenyum melihat tingkah Sarmadin. Setelah pesawat akan take off, seorang pramugari yang cantik dan cerdas menghampiri Sarmadin dan berkata dengan lembut, “Maaf, Pak Haji. Boleh lihat nomor kursinya? Oh, maaf, Pak, kursi ini untuk yang jurusan Hongkong, yang jurusan Makkah di belakang Pak, mari saya antar”. Dan, Sarmadin pun menyerah (hlm 73).
Masih banyak cerita-cerita lain yang didedahkan Abdul Mukti Thabrani perihal kelakuan orang Madura, yang mengundang gelak tawa, saat melaksanakan haji atau umrah. Yang pasti, sangat sayang bila tidak disimak dengan baik.
Pertanyaannya, adalah pelajaran yang bisa diambil dari cerita-cerita dimaksud? Tentu ada, karena setiap suatu peristiwa selalu terselip pelajaran yang berharga, tergantung kejelian kita dalam menangkap suatu peristiwa atau kejadian dalam hidup ini. Buku Orang Madura Naik Haji ini setidaknya menyiratkan tiga hal.
Pertama, sebagai putra Madura, Abdul Mukti sebenarnya, diam-diam, hendak melakukan protes. Terhadap siapa? Kepada kaumnya sendiri yang terkadang bersikap berlebih-lebihan di dalam melakukan ritual keagamaan, dalam hal ini adalah ibadah haji dan umrah. Bagi sebagian besar masyarakat Madura menjadi hal lumrah, saat mengantar keberangkatan ibadah haji, dengan pawai atau konvoi yang membuat jalanan macet. Ketika kembali dari Tanah Suci penyambutannya pun lebih meriah; pawai mobil dan motor yang jumlahnya mencapai ratusan, hadrah dan drum band, petasan yang memekakan telinga. Intinya, lebih semarak, heboh bin meriah.
Bagaimana jika di antara pawai yang membuat macet jalanan itu ada orang yang sakit, hendak melahirkan dan hajat lainnya? Sama sekali tak terlintas di benak orang Madura, karena sudah larut dalam kemeriahan. Kedua, ibadah haji atau umrah bukan hanya laku ritual semata. Lebih dari itu, seperti pemaparan Abdul Mukti, dengan haji Tuhan hendak mendewasakan wawasan dan pikiran, bahwa umat Islam sebenarnya diinginkan maju, modern dan tak gagap dengan budaya dan peradaban. Agar pengalaman Mat Halil dan Sarnito seperti cerita di atas tidak terulang kembali.
Ketiga, di balik keluguan dan kepolosan tingkah orang Madura ternyata tersimpan kecerdikan tak terduga yang secara kasat mata, terlihat bodoh. Inilah kesan lain bagi saya dalam karya Abdul Mukti Thabrani. Hal ini dapat kita simak dari kisah “surban peras” Kiai Sukri. Seperti kebanyakan orang berhaji, Kiai Sukri pun merasakan hal yang sama, bahwa kurang afdal apabila orang pulang dari ibadah haji atau umrah tidak membawa air Zamzam.
Sebab, seperti sabda Rasulullah SAW, air Zamzam merupakan minuman dari segala makanan, obat dari segala obat, dan berkah dari segala berkah. Orang pun berlomba membawa air Zamzam sebanyak mungkin, kalau perlu semua koper berisi air mukjizat ini. Sayang keinginan para jamaah haji, termasuk Kiai Sukri, untuk membawa air zamzam sebanyak-banyak terhalang peraturan muatan saat menaiki pesawat.
Tapi, Kiai Sukri tak kalah akal. Sebelum pulang ia cuci sorban, sajadah, dan bajunya dengan air zamzam. “Nanti sesampainya di kampung,” kata Kiai Sukri dengan mantap, “Serban, sajadah, dan baju ini akan saya lempar ke sumur, dan air sumur itu akan menjadi air zamzam. Juga serban yang satu ini, akan saya celup ke bak air, lalu akan saya peras. Dan perasannya akan saya suguhkan kepada para tamu. Bukankah serban ini sudah saya cuci dengan air Zamzam? Iya, kan? Banyak barakahnya, kan?”, kata Kiai Sukri penuh kemenangan (hlm 147).
Apakah sumur dan air bak yang sudah tercelup dengan surban Kiai Sukri, yang dicuci dengan air Zamzam, masih mengandung nutrisi terbaik dunia dan penuh berkah sama dengan aslinya? Hanya Kiai Sukri dan Tuhan yang tahu jawabanya. Wallahu ‘alam.




















Buku Orang Madura Naik Haji diterbitkan Diva Press.
kalau mau pesan biku ini hrs hub siapa ?