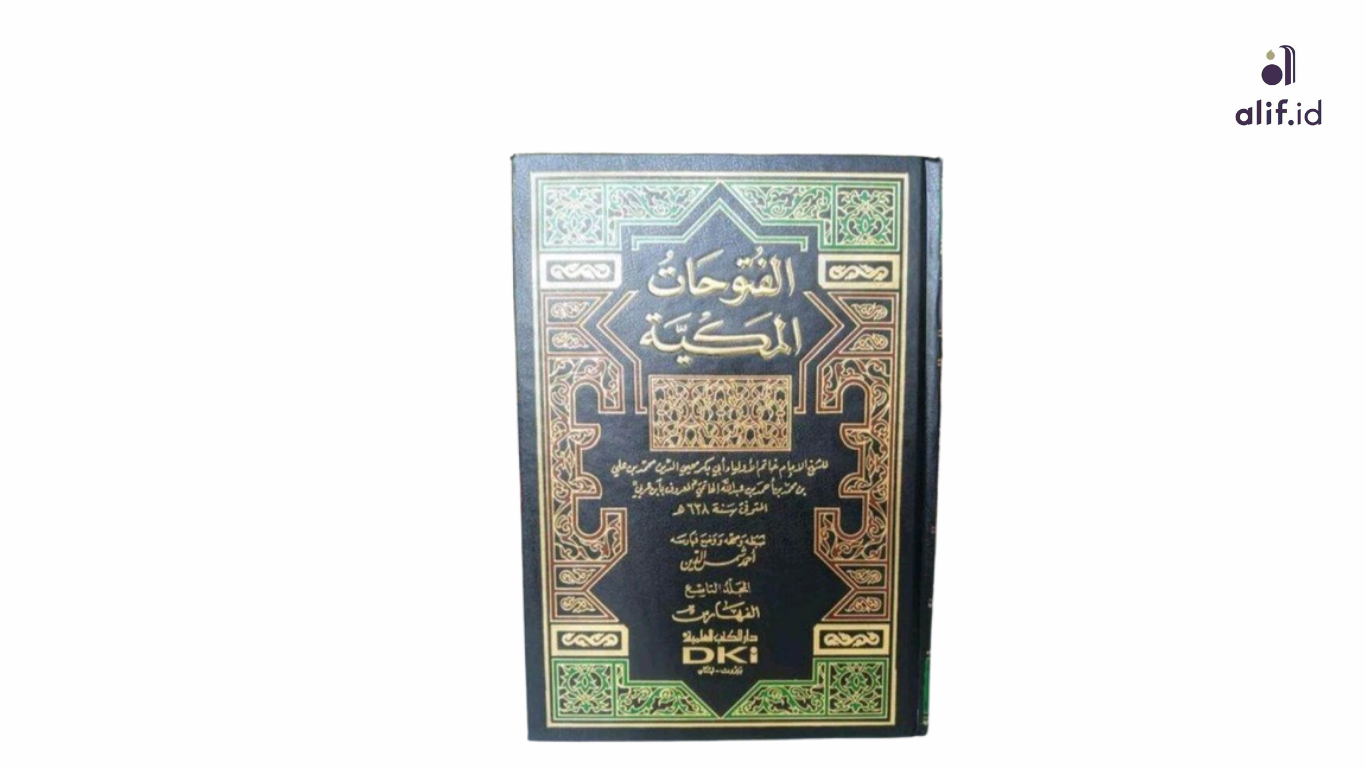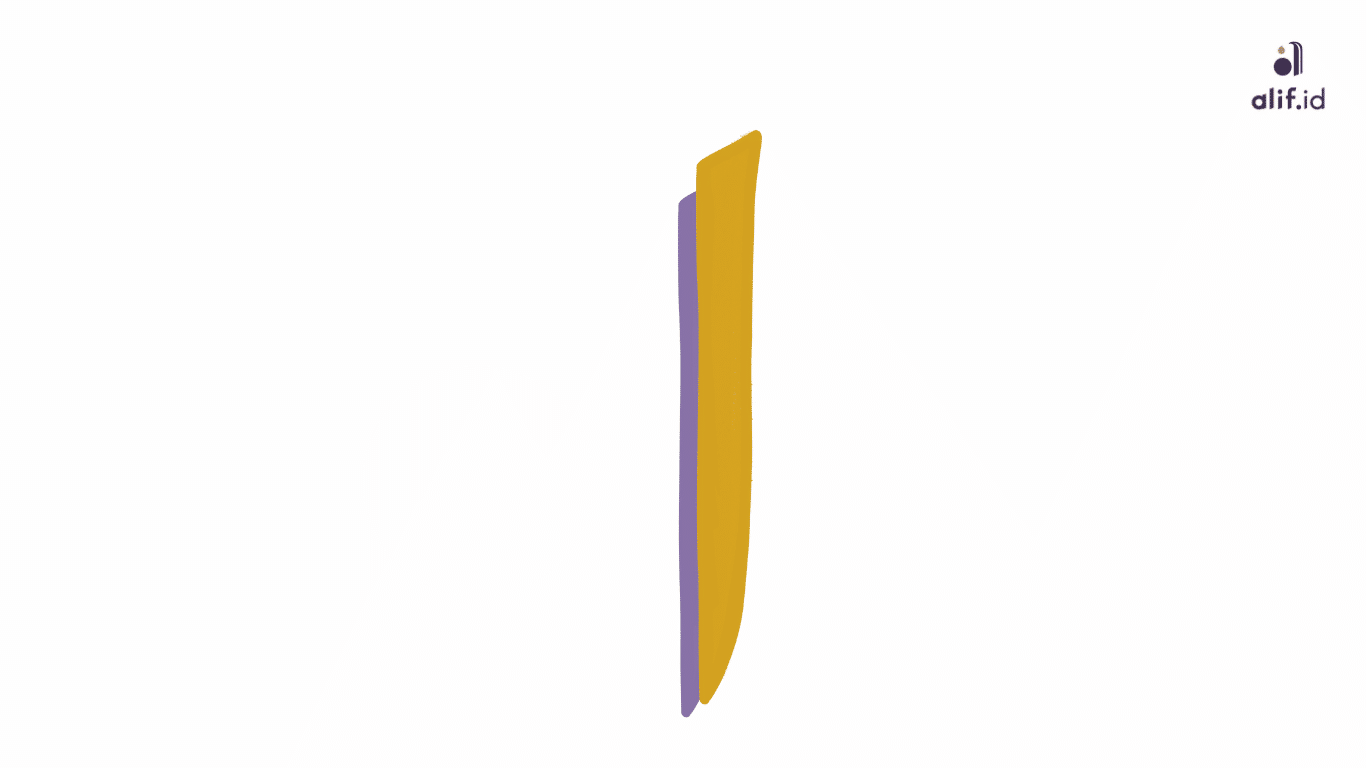Pepatah lama mengatakan, beda kelapa beda santan, beda kepala beda pemikiran. Terlebih yang akan kita sajikan adalah tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sejatinya sangat sulit dipisahkan dari subyektivitas. Yaitu tentang asmara, atau al-‘isyq dalam bahasa Arab. Maka tulisan ini sama sekali tak hendak meringkus hal yang luas tak bertepi menggunakan kata-kata, dengan segenap keterbatasannya.
Kata Plato, asmara adalah gerakan jiwa yang hampa nan tanpa motif. Jika Anda merasa hampa, tapi moro-moro terasa ada yang berkacamuk dalam benak, itu berarti Anda sedang diterpa badai asmara. Konsepsi Plato tentang asmara agaknya tak jauh beda dengan jawaban seorang tabib ketika ditanya oleh Ibn Aisyah. Kata tabib itu, cinta adalah kesibukan kalbu yang sedang hampa.
Demikian pula menurut Aristoteles sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H.) dalam Raudlat al-Muhibbin wa Nuzhat al-Musytaqqin. “Asmara adalah kepandiran yang menimpa hati yang kosong, yang tak disibukkan oleh urusan perniagaan atau industri.” Berdasar pendapat ini, agaknya penganggur adalah golongan paling rentan terserang oleh penyakit yang konon mirip dengan melankolia ini.
Filsuf lain yang tercatat juga pernah bicara tentang asmara adalah Diogenes. Dalam pandangannya, asmara adalah pilihan buruk yang menimpa jiwa manusia. Dari konsepsinya ini mulai tampak sisi asmara yang tak mengenakkan. Sisi suram yang barangkali tak pernah terbayangkan atau bahkan tak ingin diketahui oleh banyak orang, terutama mereka yang sedang kasmaran. Pointnya, bahwa cinta itu identik dengan keburukan.
Sisi ini makin tampak dalam konsepsi yang diajukan oleh Phytagoras. Bahwa asmara adalah keserakahan yang terlahir dari dasar hati. Ia bergejolak dan berkembang, mendominasi dan mengundang hadirnya kerakusan. Konsekuensinya, semakin asmara itu menguat, orang yang ditimpanya akan semakin teradiksi, semakin kecanduan tiada terkira. Selanjutnya asmara akan membawanya terus-menerus terjerembab dalam ketamakan, tak henti-hentinya memikirkan dalam angan-angan untuk mendamba, dan terus mendamba. Dan sial, pada akhirnya, sang cinta akan mencampaknya dalam kepiluan yang mencekam.
Konsepsi serupa diriwayatkan Mudhaffar bin Yahya. Betapa tidak, alih-alih menjanjikan kebahagiaan, menurut riwayat Mudhaffar, cinta pada akhrinya justru akan berujung kebinasaan. Sesuatu yang sejatinya sangat dihindari manusia. Katanya, sebagian filsuf berkata: “Tak kudapati kebajikan yang paling menyerupai kebatilan, tidak pula kebatilan yang paling menyerupai kebajikan, melebihi cinta. Guraunya serius. Seriusnya adalah gurau. Bermula dari permainan, namun dipungkasi oleh kebinasaan.” Konsepsi ini pun mengandaikan asmara yang penuh paradoks.
Seorang pujangga klasik yang penggalan syairnya bertebaran dan kerap menjadi contoh syair-syair terbaik dalam pejalaran Sastra Arab di pesantren, al-Mutanabbi, melukiskan cinta yang yang menggelisahkan itu. “Apalah cinta itu melainkan sebuah kelengahan dan ketamakan. Hati menyerahkan diri padanya, lalu dibuatnya menderita.” Barangkali pandangan ini yang kemudian mengilhami sebuah lirik lagu, “percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara.”
Sementara Socrates dengan tegas menyebut asmara sebagai sebuah kegilaan. Bentuknya bisa beraneka ragam. Sebagaimana kegilaan itu sendiri yang juga beraneka ragam. Begitu pula jawaban Ali bin Abdullah al-Qummi saat ditanya oleh Abu Zuhair al-Madini. Katanya, cinta adalah kegilaan dan kehinaan. Ia pun menambahkan, asmara adalah penyakitnya orang-orang cerdas.
Bagi orang-orang Arab juga tak jauh beda. Sebagaimana dituturkan Abu al-Fadl al-Marwarrudzi, orang-orang Arab memandang, “Kalaulah asmara bukan termasuk jenis kegilaan, pastilah ia merupakan ekstraksi dari sebuah sihir”. Lamun demikian, Al-Ashma’i justru memuji pandangan ini. Ia berujar, “Orang-orang sudah banyak bicara tentang cinta. Tapi tak ada yang lebih padat dan indah dari apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan Arab ketika ditanya tentang cinta. Kata mereka cinta adalah hina dan gila.”
Senarai pandangan tersebut dinukil dari aneka sumber dan jalur transmisi oleh ulama kelahiran Irak, Abu al-Faraj Abdurrahman atau lebih masyhur dengan nama Ibn al-Jauzi (w. 597 H.) dalam Dzamm al-Hawa. Sekadar tambahan, karyanya ini banyak menjadi rujukan cendikiawan berikutnya ketika membahas tentang tema serupa. Ibn al-Jauzi sendiri termasuk ulama yang sangat berpengaruh. Konon, sebagian majelisnya dihadiri hingga ratusan ribu orang. Sebuah sumber menyebut ia adalah pengarang produkti. Sekitar dua ribuan jilid kitab telah terlahir dari jemarinya. Bahkan ia juga mengaku telah menginsafkan sekitar seratus ribu orang. Pun telah mengislamkan 20 ribuan orang.
Dalam Dzamm al-Hawa, Ibn al-Jauzi memberi catatan bahwa pandangan orang-orang Arab tersebut kurang tepat. Bahwa yang mereka ungkap sebetulnya adalah buah atau konsekuensi dari asmara, dan bukan asmara itu sendiri. Menurutnya, yang lebih tepat, asmara adalah kecenderungan jiwa yang ekstrem terhadap suatu objek yang selaras dengan prefrensi bawaan jiwa. Semakin keras memikirkan objek tersebut, semakin terbayang pula wujudnya. Jiwa pun akan terus berangan-angan tentangnya. Saking kerasnya, aktifitas berpikir ini kemudian melahirkan penyakit.
Sementara Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H.) dalam Adab al-Dunya wa al-Din mengatakan, asmara adalah ketertarikan secara fisik baik pada bentuk atau gerak-gerik suatu objek. Sebabnya tiada lain adalah ketakamakan. Al-Mawardi mungutip al-Makmun, “Mulanya asmara adalah sendagurau dan ketertarikan mendalam. Lalu ia menguat seiring menguatnya ketamakan. Siapa yang berhasarat, akan patuh pada kekasihnya, meskipun untuk itu ia harus membayar mahal.” Lebih dari itu, al-Mawardi mengakui, asmara memiliki tenaga yang mendorong dua jiwa saling menyatu kendati raga keduanya telah berpisah. Ia mendesak ruh-ruh yang saling cinta untuk bersenyawa kendati jasad telah tercerai-berai.
Sampai di sini, tak kita jumpai asmara yang katanya agung itu. Di manakah ia yang katanya indah, menggembirakan, menentramkan, dan menyejukkan jiwa? Mengapa ia justru terkonsepsi sebagai sesuatu yang tak enak bahkan untuk sekadar didengar? Mengapa ia justru membuat gusar, menjadi penyakit, bahkan mengantarkan pada kebinasaan? Jika benar demikian, masihkah kita ingin kasmaran? Masihkah kita ingin mencampakkan diri pada kegilaan yang menyiksa itu?
Omong-omong, apa pentingnya berbicara asmara hari ini? Kenapa tidak bicara agama, pendidikan, politik atau ekonomi keumatan saja? Atau hal-hal yang berhubungan dengan Pandemi yang belakangan memporak-poranda banyak lini kehidupan kita? Untuk menjawabnya, simak dan renungkan senandung al-Sya’bi berikut. “Bila kau tak pernah kasmaran dan tak pernah tahu apa itu cinta, maka kau dan keledai liar di padang sahara itu sama saja.”