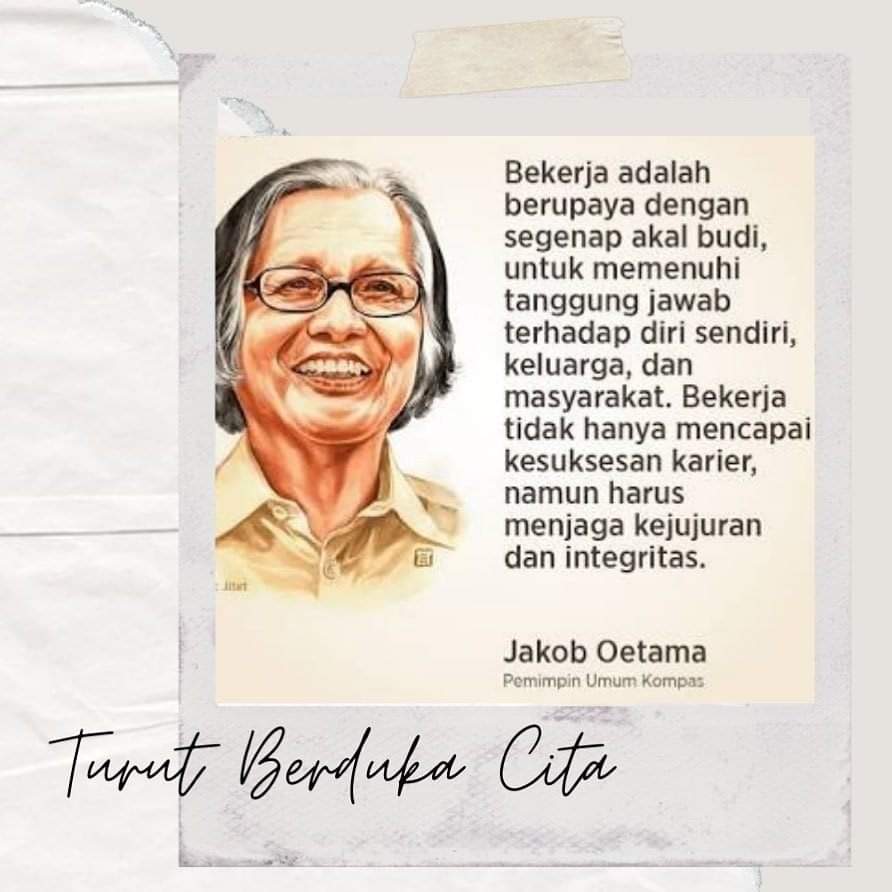Era sekarang, jargon hijrah cukup bergaung dalam kehidupan keagamaan, sosial, ekonomi, juga politik, bahkan menjadi lifestyle beberapa segmen masyarakat. Di antara manifestasinya bisa dirunut dari yang paling superfisial seperti dalam berkomunikasi memakai diksi tertentu. Semisal, panggilan ke sesama dengan sebutan akhi (saudara), ukhti (saudari), antum (anda).
Demikian pula labelisasi produk atau perilaku dengan syar’i (kompatibel dengan syariat). Pun dalam ngaji atau taklim menamainya dengan liqa’, halaqah, daurah, dan jalsah. Tidak ketinggalan tampilan fisik baik pakaian maupun “ornamen” seputar wajah menjadi “destinasi” sentral bagi para penghijrah. Subyeknya digelari pelajar hijrah, mahasiswa hijrah, artis hijrah, pengusaha hijrah dan lain-lain.
Misinterpretasi dan Anomali Hijrah
“Stakeholders” hijrah kontemporer masih ada yang memaknai hijrah berupa pergerakan pisik menuju ke suatu tempat tertentu, seperti ajakan “pelanjut” NII/DI/TII Kartosuwiryo maupun agitasi gerombolan ISIS/DAESH. Model hijrah demikian adalah sebentuk luapan emosional tanpa konsiderans nalar keagamaan yang matang, dan pasti gagal. Sejarah Indonesia mencatat kegagalan tersebut. Beberapa bulan lalu sebelum wabah korona melanda, tersiar kabar ratusan ISIS -mengaku sebagai WNI- yang sebelumnya bangga dan merasa kafah karena telah hijrah menuju negara khilafah ISIS di Suriah dan Irak. Walakin, setelah khilafah ISIS hancur, mereka katanya “menyesal” dan sambat ingin dipulangkan ke Indonesia, namun ditolak pemerintah. Mereka sudah kehilangan status kewarganegaraannya.
Ada juga mengaku berhijrah tanpa berpindah lokasi, tapi diikuti upaya mengalienasi diri dan eksklusif dalam masyarakatnya. Hal ini potensial tersemainya benih intoleran menuju radikal dan terorisme seperti terjadi selama ini di bumi pertiwi. Tentu motif alienasi di atas berbeda secara diametral dengan sejarah yang dijelaskan Nurcholish Madjid dalam magnum opusnya Islam Doktrin dan Peradaban (1995). Madjid menegaskan, kelompok pesantren mempunyai semangat alienasi. Tapi alienasi dari kolonial yang justeru terbukti menjadikan pesantren sebagai pesaing sekolah formal kolonial, bahkan menjadi “reservoir” terpenting kesadaran kebangsaan dan patriotisme.
Ada juga model hijrah “kekanak-kanakan” yang terbaca dari sikap jumawa dengan merasa paling syar’i. Semisal saat sebelum hijrah merasa “kotor”, tapi setelah hijrah merasa otoritatif dan dekat dengan Tuhan yang terindikasi dan terdeteksi dari ucapannya yang stigmatik ke liyan. Sehingga muncul kritikan “sebelum hijrah, merasa sebagai pendosa; setelah hijrah menuduh liyan sebagai pendosa dan membencinya”.
Saat ini juga marak investasi bodong karena tergiur keuntungan tinggi dan cepat. Tercatat, investasi ilegal tahun 2016 sebanyak 71 kasus, tahun 2017 sejumlah 80 kasus, tahun 2018 ada 108 kasus, dan tahun 2019 naik drastis 444 kasus. Investasi bodong telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti Ghaniyyu100, PT Kawasan Kurma Indonesia, dan investasi MeMiles yang membuat geger pada awal 2020. Modus di atas akan semakin mulus -karena melemahkan deteksi akal kritis- apabila para penipu menggunakan nomenklatur syariah yang “berbalut” hijrah seperti yang dilakukan PT Kampoeng Kurma yang berlabel syariah dengan janji akan dibangun masjid, pesantren, tahfidz, kolam renang dan pacuan kuda.
“Menjual” hijrah sebagai penglaris bisnis adalah “hijrah” karena tuntutan pasar, akan terjatuh pada komodifikasi hijrah. Daya merugikan lebih besar bila ada unsur penipuan.
Berbagai malahijrah di atas pada satu sisi bersifat paliatif, sekedar meringankan beban mental sementara penghijrah yang sebelumnya “galau”, tapi sebenarnya menipu (deceptive). Sedang pada sisi lain, akan menodai makna hijrah dan bisa membuat petaka di masyarakat. Munculnya malahijrah selain karena ada pihak yang memanfatkan untuk bisnis maupun politik, juga disebabkan pelaku hijrah tidak menggunakan pertimbangan nalar yang matang.
Dalam dunia marketing dikenal apa yang dalam psikologi disebut impulse buying, yakni keinginan untuk membeli tanpa pertimbangan yang matang. Di antara penyebabnya kata David Levis dalam bukunya Impulse: Why We Do What We Do Without Knowing Why We Do It (2013) karena jaringan bisnis besar telah meningkatkan seni dan ilmu persuasi hingga ke derajat yang sebelumnya tak terbayangkan.
Demikian pula dalam konteks hijrah, muncul yang saya namakan “impuls beragama”, artinya pada saat seseorang timbul kesadaran untuk menjadi pribadi saleh, lalu datang tawaran hijrah yang kuat mempengaruhinya dari lingkungan maupun medsos, maka dengan cepat akan dipilihnya tanpa menalar kritis dan berdiskusi dulu dengan ahli agama.
Kalau sudah demikian, karena beragama adalah naluriah, maka mereka akan mudah mengikuti impuls dari naluri tersebut. Repotnya lagi, kalau naluri sudah berada di garda depan, maka “akal” pun akan menjadi follower setia sebagai pembenar, bukan sebagai suluh yang kritis. Tentu kalau hijrah bersifat demikian, kualitasnya berbanding lurus dengan gaya hidup ikut-ikutan karena tren, sama-sama tidak substansial dan potensial menyimpang, karena nalar kritis dibuang.
Ramadan dan Hijrah Cinta
Bulan Ramadan ini dipastikan banyak orang “mendekati” Tuhan atas nama hijrah. Terlebih Ramadan kali ini diliputi dengan pandemi korona. Maka tidak diragukan lagi orang-berbondong-bondong menuju “Tuhan”. Mereka bisa mendadak “sadar agama”. Fenomena ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika. Survei di Amerika membuktikan bahwa 44 persen memandang, pagebluk ini menuntun orang agar kembali kepada Tuhan.
Dengan demikian, sudah seharusnya disyukuri fenomena tersebut. Kalaupun mereka mendadak beragama, harapannya tidak hanya karena mereka takut mati dan takut kehilangan harta, tapi bisa mengarah ke mi’raj menuju “stasiun” yang lebih atas, yakni hijrah kepada cinta atas nama Tuhan.
Diharapkan cinta atas nama Tuhan ini akan menampilkan diri sebagai pribadi religius yang toleran terhadap liyan dan nyegoro terhadap perbedaan. Tidak hanya berhenti di situ, tapi juga menjadikannya memandang orang lain tidak hanya melulu dengan perspektif beda mazhab atau aliran (tentu beda tidak apa-apa, yang problem adalah manakala mengungkit perbedaan di medsos, pasti akan menimbulkan reaksi), tapi juga memandang dari kacamata kemanusiaan.
Dalam kacamata kemanusiaan yang berbasis cinta atas nama Tuhan, siapa pun dia, maka akan selalu dipandang dari aspek kemanusiaannya, bukan alirannya atau golongannya seperti yang disinyalir Noorhaidi Hasan terhadap Salafi radikal (https://youtu.be/LlEW74CvitI).