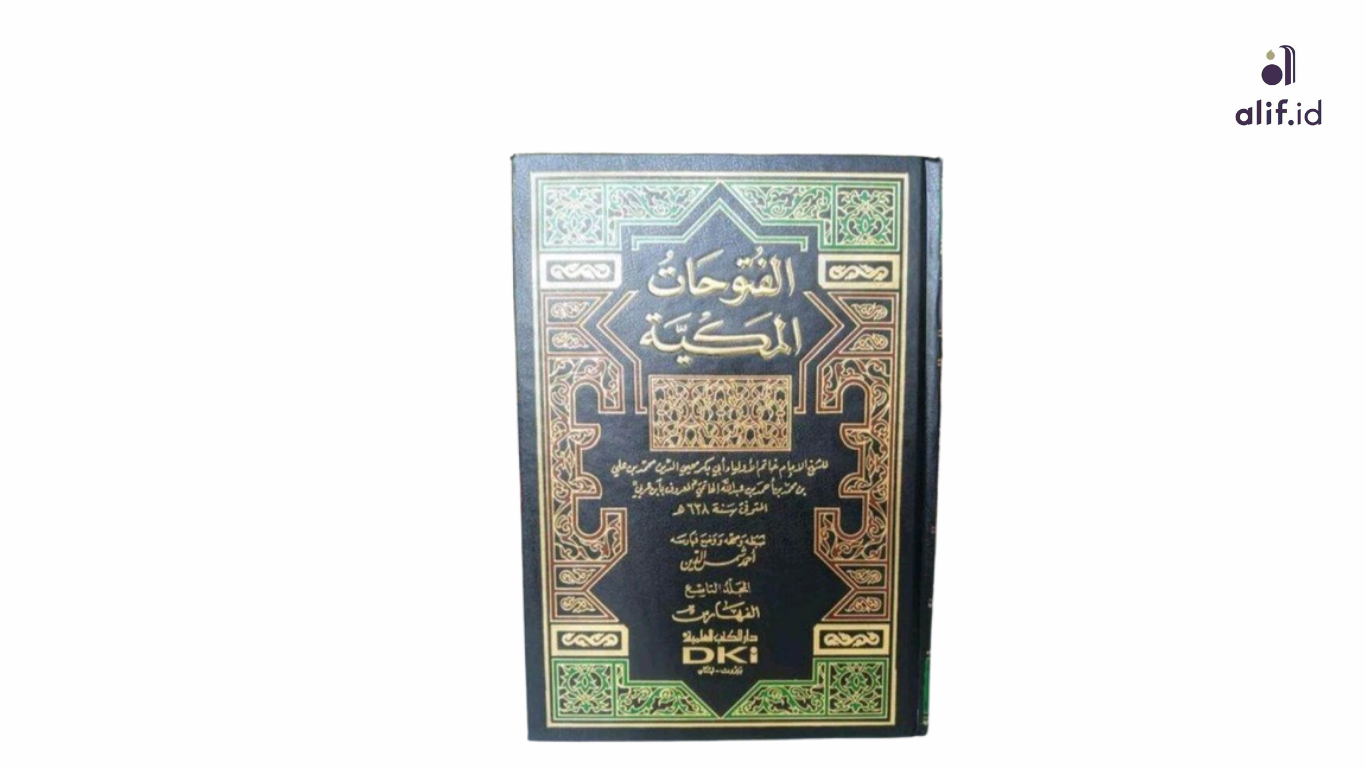Dalam sebuah tulisan yang disiarkan di situs ini pada Jumat, 21 Desember 2018 dengan judul Sufi dan Sufisme di Barat, Ulil Abshar Abdalla (dikenal sebagai Gus Ulil) memberikan satu ciri dari gerakan tradisionalisme yang didirikan oleh Renè Guènon. Gus Ulil menulis:
“Para pengikut filsafat ini, termasuk Prof. Nasr sendiri, menampakkan rasa ketaksukaan yang tanpa tedeng aling-aling kepada segala hal yang sifatnya modern”.
Kalimat di atas dan kalimat-kalimat lainnya yang memuat ide bahwa, para tradisionalis – sebagaimana tulis Gus Ulil – “antipati” dan “membenci” segala hal yang modern, menimbulkan kerancuan. Sebelum kita menganalisis kerancuan yang ditimbulkan ide tersebut baiknya kita telusuri lebih dulu dari mana kata modern masuk ke dalam bahasa Indonesia.
Kata modern yang telah masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris “modern”. Merriam-Webster’s Advanced Learner’s Dictionary mengartikan kata ini dengan “of or relating to the present time or the recent past : happening, existing, or developing at a time near the present time.”
Artinya kurang lebih: “segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu saat ini atau masa lalu yang dekat : terjadi, wujud, atau berkembang pada waktu yang dekat dengan saat ini.” Frasa “dekat dengan saat ini” sangat relatif.
Sebuah bentuk pemerintahan yang ada saat ini bisa jadi telah berlangsung sejak 73 tahun yang lalu seperti di Indonesia, namun ia tetap disebut sebagai pemerintahan modern, seperti dalam kalimat “Indonesia’s modern [=present] government was formed over 73 years ago.”
Yang artinya: “Bentuk pemerintahan Indonesia modern (sebagaimana saat ini berlangsung) telah berdiri sejak 73 tahun yang lalu.” Bahkan Ricklef menyebutkan bahwa Indonesia modern dimulai sejak 1200 M karena pada masa itu Islam mulai tumbuh di nusantara, yang pada masa kini menjadikan pemeluknya adalah mayoritas (Ricklefs 2001).
Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) memberikan dua makna untuk kata ini: “1. terbaru; mutakhir. 2. n sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman”.
Pada makna yang pertama, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang diciptakan pada masa-masa kini dinilai sebagai hal modern. Seperti pada kalimat “Dengan hadirnya internet di kampung itu, warga kampung itu bisa menggunakan perangkat komunikasi yang modern”.
Sedangkan pada makna yang kedua, yang biasanya lebih sering digunakan orang, yang modern adalah cara pandang dan pemikirannya, yang biasanya dicirikan dengan semakin rasional dan sering dianggap lawan kata dari “terbelakang”, “kampungan”, dan “kolot”. Hal ini seperti pada kalimat: “Orang-orang di kampung itu masih percaya pada mitos-mitos dan belum modern”.
Dengan demikian, bila benar apa yang dituliskan Gus Ulil, maka seorang tradisionalis akan hidup dengan rasa antipati dan tak suka pada banyak sekali hal termasuk, pesawat terbang, Facebook, internet, dan mobil misalnya hanya karena mereka dianggap sebagai sesuatu yang bersifat modern. Hal ini akan menjadikan mereka orang yang paling merana di muka bumi, bila setiap ada sesuatu termutakhir di bidangnya muncul, sehingga menjadikannya modern, mereka akan merasa tidak suka dan antipati terhadapnya.
Bila demikian seharusnya Prof. Nasr, bila beliau jujur dengan sikap antipatinya seperti tulis Gus Ulil, tidak menggunakan pesawat terbang dan memilih untuk menggunakan kendaraan yang tidak modern. Namun sebagaimana ungkap Prof. Nasr, beliau menggunakan pesawat untuk keperluan transportasinya (Nasr and Jahanbegloo 2010, 27).
Lalu, muncul pertanyaan, apakah yang dimaksudkan bahwa para tradisionalis membenci segala hal yang bersifat modern, yang – seperti ditulis Gus Ulil – salah satunya diwakili oleh Seyyed Hosein Nasr? Sebenarnya mudah untuk mengetahuinya dengan merujuk kepada tulisan Prof. Nasr sendiri. Dalam sebuah perbincangan yang akhirnya dibukukan dengan judul In Search of the Sacred, Prof. Nasr secara gamblang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tradisionalisme, yang pusatnya adalah “tradisi”, yang beliau kontraskan dengan modernisme.
Beliau menulis:
“…‘tradition’ means truths of sacred origin revealed originally, … coming from God … with their elaboration and transmission within a historical religious civilization” (h. 181). Artinya: “ ‘Tradisi’ berarti kebenaran-kebenaran yang asal-muasalnya sakral yang diwahyukan dengan valid sejak semulanya, … berasal dari Tuhan … dengan beragam bentuk elaborasi dan transmisi dalam sebuah ruang sejarah dari peradaban yang tunduk pada Tuhan.”
Dengan demikian, tradisionalisme, yang dimaknai dengan “suatu pandangan yang didasarkan pada tradisi”, mencakup di dalamnya kemungkinan-kemungkinan wujud keberagamaan yang sangat beragam selama memenuhi dua unsur penting tradisi yaitu, kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan dan kesinambungan yang terjaga terus-menerus dari sumbernya (h. 181).
Lalu beliau melanjutkan dengan apa yang dimaksud sebagai lawan dari tradisionalisme yaitu modernisme. Beliau menulis:
We, that is, the traditionalists like myself, use the term ‘‘modernism’’ not in a vague way as characterizing just things that happen to be around today, but as a particular way of looking at the world, a worldview that began in the Renaissance in the West with such components as Renaissance humanism, rationalism, et cetera. … modernism rejects the primacy of absolute and ultimate truth. … it takes the absolute away from God.
(Nasr dan Jahanbegloo 2010, 182)
Yang artinya:
Kami, yaitu para tradisionalis seperti diriku, menggunakan term “modernisme” tidak dalam arti yang rancu sebagai karakter dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar masa kini, tapi sebagai satu cara pandang tertentu pada dunia, sebuah cara pandang yang dimulai pada Era Kebangkitan di Barat dengan unsur-unsur seperti humanisme ala Era Kebangkitan, rasionalisme, dan lainnya. … modernisme yang menolak kemahakuasaan mutlak dan kebenaran tertinggi. … dia [modernisme] mengambil sifat mutlak dari Tuhan.
Dari sini terlihat bahwa yang dibenci oleh kelompok tradisionalis, paling tidak sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Nasr, adalah suatu cara pandang tertentu yang ia namai dengan modernisme, bukan modernitas atau modern, paling tidak, tidak seperti apa yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang baru.
Tampaknya Gus Ulil perlu menambah kehati-hatiannya dalam menulis supaya tidak memberikan ciri pada sebuah kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sendiri maksudkan.
Atau paling tidak, Gus Ulil tidak menggunakan kalimat yang rancu seperti “… ketaksukaan … kepada segala hal yang sifatnya modern” untuk menyebutkan kelompok yang “hanya” membenci “modernisme” sebagaimana dijelaskan di atas. Wallahu a’lam