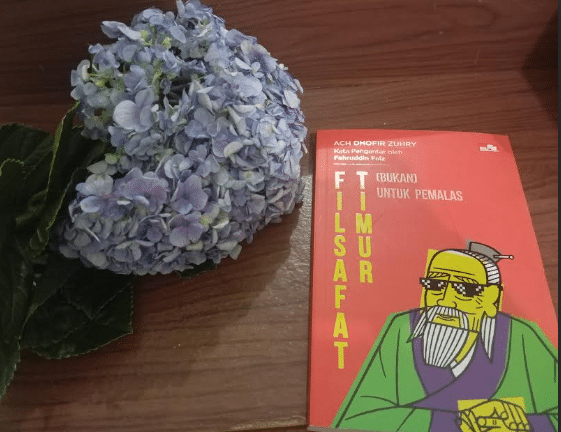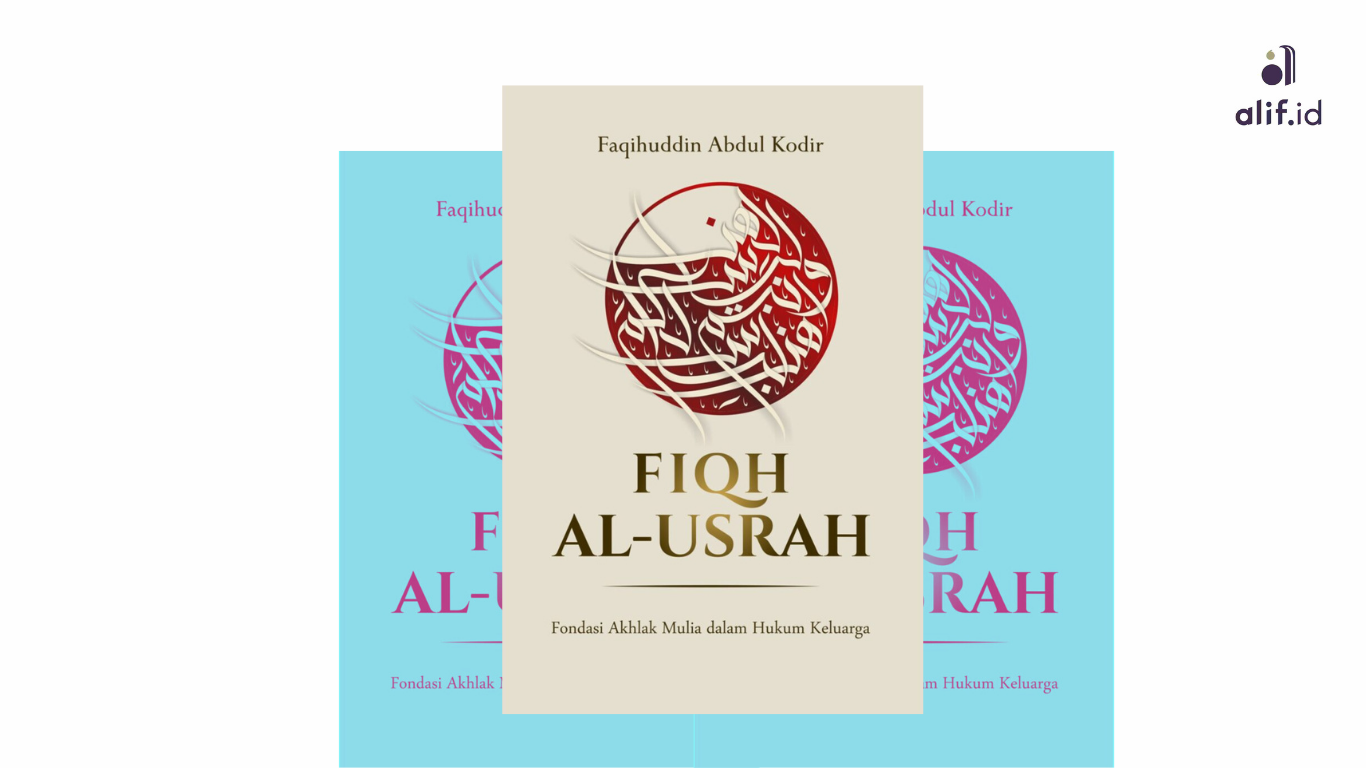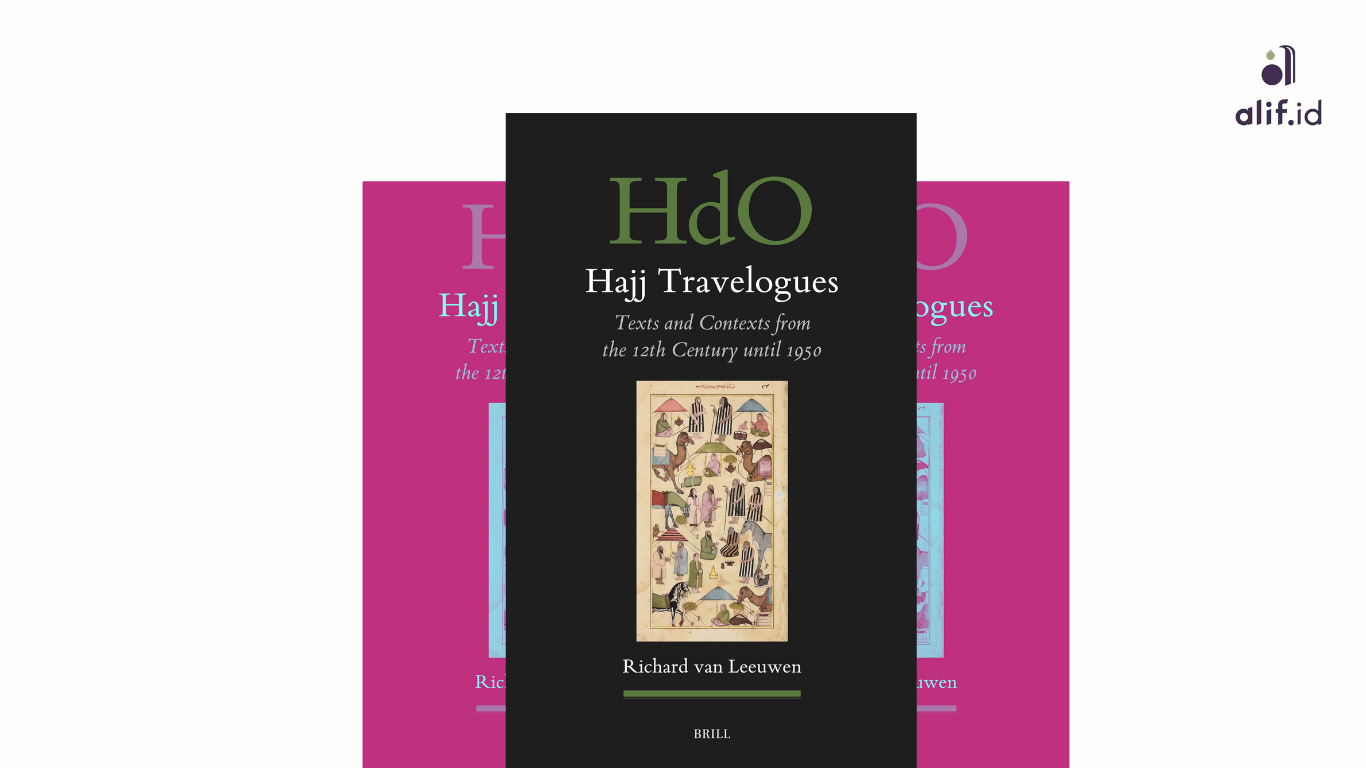Buku anak memuat beragam masalah. Kita bisa menemukan perihal perang, politik, kapitalisme, diskriminasi, dan feminisme. Masalah itu dikemas dalam bahasa dan cerita yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak.
Pengenalan perlu dilakukan agar anak mengetahui sebab dan akibat dari berbagai sengkarut persoalan di dunia ini, lalu membantunya untuk dapat berpikir lebih jernih. Menunda segala pendapat agar tidak lekas mengatakan benar-salah, baik-buruk dalam melihat segala sesuatu. Kita bisa yakin, anak akan mampu memahami persoalan besar itu, lewat pengisahan.
Twenty-Four Eyes (1952) gubahan Sakae Tsuboi adalah bacaan remaja yang menarik. Buku itu menyajikan banyak persoalan: Pendidikan, dampak perang, kehidupan anak-anak, kebudayaan, dan kemiskinan. Tebalnya hanya 244 halaman tapi memuat penceritaan dalam rentang waktu kurang lebih dua puluh tahun. Kita akan menemukan banyak cerita yang menguras beragam emosi.
Sakae Tsuboi sangat pandai menuliskan perubahan karakter para tokoh, dari mulai masa anak-anak hingga dewasa. Para tokoh juga disajikan amat menarik. Bu Guru Oishi, tokoh utama, menjadi saksi atas kehidupan dua belas muridnya: Kotsuru, Masuno, Kotoe, Matsue, Fujiko, Misako, Sanae, Nita, Isokichi, Tadashi, Takeichi, dan Kichiji. Kisah hidup yang mengundang decak kagum, bahagia, juga air mata.
Yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah kisah salah satu murid, yaitu Fujiko. Ia adalah anak seorang bangsawan yang hidup dalam kemakmuran. Namun, akibat dampak perang, kehidupannya menjadi berbalik 180 derajat. Ia dan keluarganya mengalami kesulitan bahkan untuk sekedar makan.
Akibat perubahan itu, Fujiko dijual oleh orang tuanya. Ia diperlakukan seperti perabot atau pakaian demi bisa membeli makanan untuk sehari-hari. Fujiko yang dibesarkan tanpa pernah harus bekerja keras, kini harus merasakan pahitnya kehidupan dengan profesi seorang pekerja seks.
Selain menjalani paksaan dari orang tuanya, ia juga harus menanggung sejuta cemooh dan pandangan rendah dari banyak mata masyarakat. Yang dilihat masyarakat dari para pekerja seks adalah kotor, hina, dosa, dan beragam asumsi lain.
Nasib Fujiko mungkin dimiliki oleh jutaan perempuan di berbagai belahan dunia. Para pemilik umpatan rata-rata tidak pernah mau bersabar sejenak untuk menengok cerita di balik para pekerja seks. Padahal, prostitusi tidak hanya soal tubuh, seksualitas, dan uang, tapi terselip agama, kekerasan seksual, intrik politik, penghianatan, dan perdagangan manusia,.
Nidah Kirani, tokoh dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur (2016) gubahan Muhidin M. Dahlan mengisahkan titik temu antara agama dan pekerja seks. Mula-mula ia sebagai muslim yang taat secara syari’at, lalu pertemuannya dengan beragam kemunafikan dari orang-orang yang mengaku paling ber-Tuhan dan konflik batin yang ia rasakan membawanya pada jurang prostitusi.
“Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama.” Adalah kutipan dari R.A Kartini (1789-1904). Kita menyetujui keluhuran pesan-pesan yang dibawa agama. Tapi, dalam prakteknya, pesan bisa dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak.
Di Mesir, kita menjumpai Firdaus dalam Perempuan di Titik Nol (1977) gubahan Nawal El Saadawi. Perempuan itu dikisahkan menjadi pelacur lantaraan jebakan dari keadaan. Situasi yang dialaminya lahir dari budaya patriarki yang meletakkan perempuan dalam posisi tidak berdaya baik dihadapan pendidikan, ekonomi, agama, dan masyarakat.
Budaya itu membuat perempuan tidak berkemampuan untuk mandiri dan berani membela hidupnya. Yang terjadi, perempuan hanya dipandang sebagai properti atau objek seks yang bisa dipindah tangankan dari satu orang ke orang lainnya.
Di balik pekerja seks ada kekerasan. Remy Sylado dalam novelnya berjudul Namaku Mata Hari (2010) mengisahkan hidup Margaretha Geertruida Zelle, penari eksotis, pelacur, sekaligus spionase Jerman-Prancis. Pilihannya menjadi pelacur tidak datang dari langit. Ia pernah mengalami kekerasan seksual di masa sekolah, lalu kekerasan mental dan fisik yang dilakukan oleh suaminya, Rudolph MacLeod. Lalu traumatik kematian anaknya akibat penyakit yang ditularkan sang suami.
Di Indonesia, kita bertemu tokoh Mainah atau Mae dalam novel Jatisaba (2017) gubahan Ramayda Akmal. Pekerja seks bermula dari sindikat perdagangan manusia yang banyak terjadi pada orang-orang pedesaan yang terhimpit ekonomi. Kisah itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lydia Cacho yang ditulis dalam Bisnis Perbudakan Seksual (2021).
Cacho memaparkan bahwa dalam lingkar prostitusi, ada jejaring yang sudah tersusun secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Dalam bukunya itu, ia menuliskan bahwa para perempuan pekerja seks sebenarnya tidak menyukai komodifikasi seksual. Tetapi, secara halus mereka dimanipulasi oleh para germo untuk percaya bahwa mereka menyukai profesi tersebut.
Manipulasi itu dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan memberikan pemahaman bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah hanya dengan menjadi pelayan seks.
Ketika salah satu pekerja seks sudah sadar dan ingin keluar dari lingkaran tersebut, sang germo tidak akan mengizinkan. Cacho menceritakan cerita sadis saat terjadi percobaan untuk kabur. Perempuan itu akan dibunuh lalu tubuhnya dijadikan sup untuk dimakan oleh anak-anak dan perempuan yang tersisa. Hal itu dilakukan agar dapat memberikan efek jera pada para pekerja yang berniat untuk melarikan diri.
Barangkali, kisah yang diceritakan Lydia Cacho dalam Bisnis Perbudakan Seksual (2021), lalu kisah Nidah Kirani dalam Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur (2016), Firdaus dalam Perempuan di Titik Nol (1977), Margaretha Getruida dalam Namaku Mata Hari (2010), Mae dalam Jatisaba (2017) adalah nasib yang dialami oleh banyak pekerja seks.
Kita bisa percaya, tidak ada perempuan yang benar-benar menginginkan menjadi pekerja seks. Mereka tidak melakukan atas dasar kenikmatan apalagi kebahagiaan, tetapi didalamnya mengandung manipulasi, rasa sakit, kemunafikan, penghianatan, kekerasan, dan keterlibatan banyak pihak.
Di hati terdalam mereka pasti ada doa yang mengharapkan siapapun tidak mengalami apa yang telah mereka rasakan. Kita membayangkan perasaan itu seperti penggalan lirik lagu Iwan Fals berjudul Doa Pengobral Dosa (1981): “Dalam Hati yang Bimbang berdoa/ Beri terang jalan anak hamba/Kabulkanlah Tuhan.”