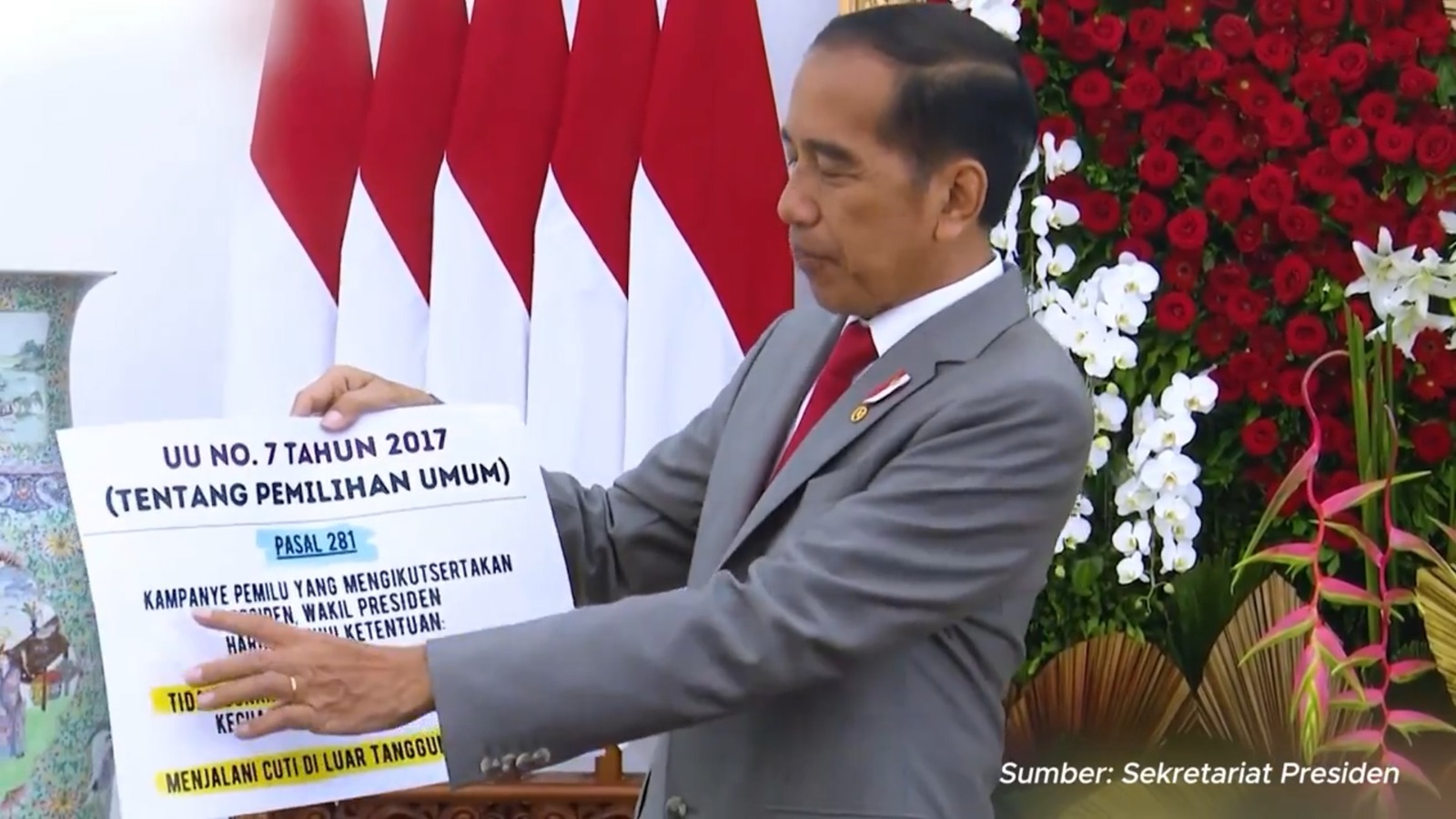![Sejumlah warga Gaza mengaku kebingungan setelah tempat tinggal mereka hancur akibat bom yang dilancarkan oleh pihak Israel. [foto: AFP]](https://alif.id/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-11-at-05.31.38.jpeg)
Sementara hingga hari ini, 10 Nopember 2023, sudah lebih dari 10 ribu orang meninggal dunia di Gaza di mana hampir separuhnya adalah anak-anak, sejumlah orang masih berdebat tentang apakah Hamas adalah organisasi teroris atau bukan. Seolah lupa bahwa Hamas telah memenangkan pemilihan umum Palestina yang diselenggarakan pada 2006, negara-negara Barat yang besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman tetap menganggap Hamas adalah teroris yang karena itu serangan terhadap mereka di Gaza adalah sah. Apakah ini merupakan sebuah contoh bagi demokrasi sekuler?
Palestina, seperti juga entitas politik lainnya, terdiri dari berbagai kelompok yang saling bersaing. Di antara yang paling berpengaruh adalah Fatah dan Hamas. Sementara Fatah bercorak sekuler, Hamas adalah gerakan Islam politik. Fatah setuju dengan solusi “dua negara”, sedangkan Hamas tidak percaya dengan itu. Bagi mereka, keberadaan negara Israel di tanah Palestina adalah penjajahan yang harus dilawan, termasuk dengan senjata. Satu-satunya solusi adalah intifadah.
Akan tetapi, Hamas menyepakati demokrasi. Mereka ikut pemilihan umum 2006. Dibanding dengan Fatah yang nepotis dan korup, Hamas dianggap lebih memberi harapan. Akhirnya, mereka memenangkan 76 kursi dari 132 kursi parlemen Palestina, sementara Fatah hanya mendapatkan 43 kursi saja.
Negara-negara Barat tidak mengakui kemenangan Hamas itu, sehingga Presiden Mahmoud Abbas dari Fatah yang telah berkuasa sejak 2005 hingga hari ini pada dasarnya tidak mempunyai legitimasi di hadapan rakyatnya sendiri. Meski mempunyai otoritas untuk mengirim wakil-wakilnya dalam hubungan internasional, posisi Abbas di mata rakyatnya sangat lemah. Problematik ini mau diatasi dengan pemilihan umum, tetapi tidak pernah berhasil. Israel yang didukung oleh negara-negara Barat selalu mengintervensi rencana pemilihan umum dalam rangka memastikan keberlanjutan pendudukannya di Palestina. Pokoknya, bagi Israel, jangan sampai Hamas memenangan pemilihan umum.
Sementara itu, publik global terus menerus disuguhi gambaran tentang Hamas sebagai organisasi teroris. Kenyataan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok pejuang yang mempertahankan jengkal terakhir tanah airnya tidak pernah diakui. Di bawah hegemoni jejaring media pro-Israel yang menggurita, cerita tentang Gaza sebagai “penjara terbuka terbesar di dunia” tidak pernah dijadikan berita. Persepsi ini semakin mantap dalam bayang-bayang proyek global war on terror pasca peristiwa 11 September 2001. Hamas disamakan begitu saja dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Al-Qaida, dan Jamaah Islamiyah.
Kembali ke soal paradoks demokrasi, sejak awal negara-negara Barat memang alergi dengan Islam politik. Mereka mendorong Islam agar seperti Kristen yang mengalami sekularisasi. Pengalaman Eropa Barat yang berhasil melepaskan diri dari kungkungan agama mesti diterapkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, mereka tidak percaya, setidaknya curiga, keikutsertaan kalangan Islam politik dalam demokrasi. Jika mereka menang, maka itu harus dibatalkan. Alasannya bisa dicari kemudian.
Persis ketika demokrasi hanya ditempatkan dalam kerangka sempit politik sekuler, paradoks dimulai. Ironisnya itu hanya diberlakukan terutama kepada Islam, sebab demokrasi Israel di bawah Netanyahu atau demokrasi India di bawah Narendra Modi yang sangat teokratik tidak dipermasalahkan, setidaknya dibiarkan. Paling jauh fenomena Israel atau India kontemporer di mana Yahudi dan Hindu mendikte demokrasi hanya dinarasikan sebagai populisme kanan.
Tentu negara-negara Barat tidak berarti anti-Islam, sebab mereka menyayangi Islam moderat. Seperti Fatah di Palestina, faksi-faksi Islam moderat di mana-mana adalah sekutu Barat yang utama. Proyek moderasi akan didukung sebagai wujud nyata keterlibatan agama-agama dalam perdamaian dunia. Pertanyaan apakah hal itu sesuai dengan norma dan prosedur demokrasi atau sebaliknya bisa dicari argumentasinya nanti.
Kenyataannya, apa yang menimpa Hamas di Palestina pada pemilihan umum 2006 bukan hal yang baru pertama kali terjadi di negara Muslim. Sebelumnya, pada tahun 1991 di Aljazair, Front Islamique du Salut (FIS) juga memenangkan pemilihan umum, tetapi lalu dibatalkan oleh kekuatan militer. Yang lebih baru adalah kemenangan Mohamed Moorsi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir pada 2012. Setelah berapa bulan menduduki pemerintahan, dia dikudeta, bahkan lalu dipenjara hingga meninggal dunia di balik jeruji pada 2019. Seperti Hamas, FIS dan Ikhawanul Muslimin adalah organisasi Islam politik yang akan terus ditulis dalam literatur-literatur sekuler sebagai kekuatan-kekuatan yang mengancam demokrasi, meski memenangkan demokrasi.
Paradoks demokrasi sekuler, oleh karena itu, tidak akan mengakui adanya genosida di Gaza yang hingga hari ini telah merenggut lebih dari 10 ribu jiwa. Mungkin itu dilihat sebatas statistik seperti persentase persepsi atau opini publik dalam laporan survei menjelang pemilihan umum. Mungkin tidak ada yang menggetarkan dari jerit 160 anak yang meregang nyawa setiap jam di Gaza. Semuanya hanya dipandang angka-angka belaka.