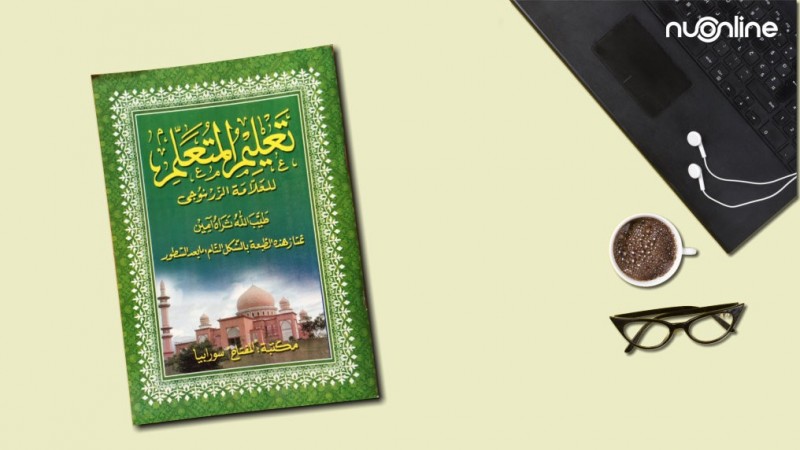
Syaikh Said Ramadan al Buty pernah melempar kritik keras kepada Husain Haikal, atas karakteristik penulisan sejarah Nabi Muhammad yang dirasa terlalu rasional dalam bukunya Hayatu Muhammad. Husain Haikal bisa jadi memilih karakter ini karena dunia modern lebih siap menerima cerita-cerita yang masuk akal dibanding cerita-cerita yang irasional.
Kisah Isra’ Mi’raj misalnya, digambarkan oleh Husain Haikal sebagai perjalanan ruh semata menuju Sidratul Muntaha. Unsur-unsur mukjizat dihilangkan oleh Husain Haikal sehingga bukunya tampak lebih ilmiah. Terkait hal ini, beberapa pakar menyebut bahwa ini dilakukan oleh Husain Haikal agar buku ini dapat diterima oleh orang-orang barat yang cenderung rasionalis. Tetapi bagi Al-Buty, unsur irasionalitas telah menyatu dengan identitas umat Islam sehingga tak semestinya dicerabut.
Beragama memang perlu menggunakan akal (rasio) tetapi sisi irasional dalam Islam menjadi urgen untuk diyakini. Ada beberapa hal dari ajaran agama yang akal tidak akan bisa menjamahnya, sehingga peran hati (iman) menjadi penentu utama. Dalam sejarahpun, beberapa kali Nabi menujukkan hal-hal irasional yang tidak dapat dinalar dengan akal dan hanya berpatokan pada iman, semisal perjanjian Hudaibiyah. Poin-poin perjanjian Hudaibiyah secara akal sangat merugikan, memojokkan dan mendiskrimasi muslimin, tetapi karena persetujuan atas perjanjian ini dikawal oleh wahyu, maka akal musti diletakkan terlebih dahulu untuk kemudian menggantinya dengan peran hati. Dan secara de facto, sejarah telah menjawab bahwa perjanjian ini justru menguntungkan umat Islam.
Mukaddimah di atas cukup untuk menjadi gambaran bahwa Islam meskipun sangat menghargai akal, tetapi tak benar-benar melepaskan diri dari unsur irasional. Sehingga di kalangan pesantren, unsur-unsur irasional ini menjadi warna tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Di sinilah kitab Ta’lim Mutallim mengambil tempat, ia hadir menambah legalitas pesantren sebagai komunitas yang mempercayai unsur rasional dan irasional secara bersamaan, bahkan di kalangan pesantren tertentu, unsur irasional menempati tempat yang melebihi unsur rasional.
Ta’lim Muta’allim lahir dari kegelisahan Burhanuddin Al-Zarnuji terhadap hilangnya nilai-nilai budi di kalangan para pencari ilmu, kecemasan itu menjadi alasan terkuat baginya untuk menulis kitab ini. Para pencari ilmu yang notabene cemerlang di dalam masa belajarnya, bisa mendadak tidak mampu berperan lebih di masyarakat setelah ia pulang. Kematangan ilmunya selama masa perantauan seperti hilang taringnya saat terjun di masyarakat. Oleh az-Zarnuji, kasus ini dianggap terjadi karena abainya mereka terhadap unsur irasionalitas yang turut menentukan kiprah intelektualitas seseorang.
Kelompok rasionalis mungkin akan menganggap bawa intelektualitas akan direngkuh dengan belajar dan kesungguhan semata. Tetapi Az-Zarnuji telah menyihir kaum sarungan (pesantren_ dengan paradigma baru bahwa ada unsur besar lain yang menunjang intelektualitas seseorang dan unsur itu murni melibatkan hati. Az-Zarnuji menyebutkan misalnya, hormat kepada guru dan keluarganya, berdiri saat mereka berjalan, menyayangi anak-cucu dari sang guru juga menjadi penentu dari terbukanya intelektualitas seseorang.
Redaksi beliau dalam Ta’lim Mutaallim sebagai berikut:
Bentuk dari menghargai guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak memulai cakap dengannya kecuali diizinkan, tidak banyak bicara di hadapannya, tidak bertanya saat ia bosan, menjaga waktunya, tidak mengetuk pintunya tetapi menunggunya keluar.
Kalimat magis tersebut sarat akan muatan akhlak dan diyakini oleh az-Zarnuji dapat menunjang kemapanan keilmuan seseorang. Az-Zarnuji secara umum telah berhasil mendoktrin pondok-pondok dalam mengaplikasikan tatanan akhlak baru di atas standar akhlak pada umumnya. Dan hebatnya, pemahaman akan unsur irasionalitas sebagai penunjang keilmuan ini benar-benar diyakini di kalangan pesantren sebagai hal yang nyata dan faktual. Standar akhlak lain ala Az-Zarnuji yang sarat nilai semisal; jangan meletakkan pena di atas buku, seyogyanya meletakkan kitab tafsir di susunan teratas, tidak memakan makanan pasar dan lain sebagainya.
Poin-poin akhlak di atas dikuatkan oleh Az-Zarnuji melalui kisah Khalifah Harun al Rasyid yang menyaksikan putranya menuangkan air untuk sang guru (Imam Al-Asmu’i) sementara sang guru meratakan air di kakinya. Khalifah tidak berkenan dengan kejadian ini dan mengatakan kepada Imam Al-Asmu’i saat itu: Kenapa tidak kau suruh anakku menyiram dengan tangan kanan dan meratakannya di kakimu dengan tangan kirinya? Seroang raja hebat, bergelimang harta, berkedudukan, tetap mempercayai bahwa unsur irasionalitas memiliki peran terhadap keilmuan anaknya
Tapi meski begitu, Az-Zarnuji tak melupakan begitu saja unsur rasional, ia juga menuliskan teknik-teknik belajar yang tepat dalam Ta’lim Mutallim untuk mengasah akal para pencari ilmu. Dalam bab al-Jiddi wa al Muwadlobah wa al-Himmah beliau menuturkan:
“Wajib bagi pencari ilmu untuk mempelajari pelajarannya, mengulang-ulang di awal dan akhir malam, karna waktu antara maghrib dan isya serta waktu sahur adalah waktu yang diberkahi… wajib bagi pencari ilmu untuk memiliki hasrat yang besar dalam belajar, karena manusia akan terbang dengan impiannya seperti burung terbang dengan sayapnya.”
Maka Az-Zarnuji membuka mata muslimin secara khusus, bahwa kematangan intelektual selain ditentukan dengan belajar, juga terdapat unsur irasionalitas yang juga turut andil mendorong keberhasilan belajar seseorang. Kedua unsur ini musti berjalan beriring tanpa menanggalkan salah satunya. Dan di dunia pesantren, kita mendapati keduanya berjalan secara mesra dan harmonis. Paradigma yang telah mengakar di pesantren adalah bahwa irasionilatas juga turut berperan pernting dalam menunjang intelektualitas, sesuai apa yang diajarkan oleh Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Muta’allim. Unsur irasionalitas ini di kalangan pesantren biasa disebut dengan barokah.















