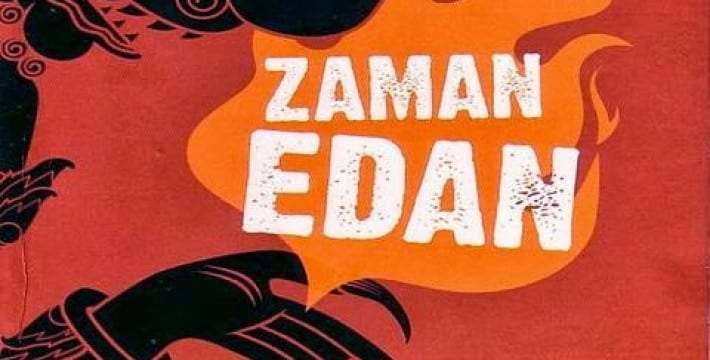
DISADARI atau tidak, peradaban kita sedang terjun bebas ke titik nadir. Sejak tergilagila pada diri sendiri (jadi antroposentrik dengan laku narsistik), manusia mulai melatih diri memutus hubungan dengan dunia makro (metafisik) yang “sulit dimengerti.”
Kemenangan para pegiat Aristotelian, Newtonian, Cartesian, dan Kantian, dalam menggusur yang sakral dalam kehidupan abad modern, ternyata berdampak serius pada peradaban manusia. Hari ini, kita bisa membuktikan dan ikut menanggungnya.
Segala yang non-fisik, tak ilmiah. Maka wajar bila manusia cenderung sulit mengerti betapa nun di belakang hidup kita dulu, pernah ada sesosok avatara pengendali tanah, air, api, udara—yang notabene adalah unsur tubuhnya sendiri. Sejatinya, itu bukan mitos. Tapi sangat logos, bahkan ada.
Masalah manusia sekarang ada pada terputusnya hubungan antara ia, alam, dan tuhan. Barangkali jika ditelusur, hanya tinggal segelintir saja dari manusia yang hidup di zaman modern, bisa melakukan komunikasi dengan; ruang, waktu, matahari, rembulan, angin, tanah, lautan, api, hewan, tetumbuhan, dll. Sementara saat bersamaan, manusia tak bisa menafikan peran serta mereka dalam kehidupannya. Tanpa kerja cerdas tumbuhan memasak udara dari karbon dioksida, misal, manusia tinggal seonggok kerangka dibalut daging membusuk.
Dalam Secret Life of The Plant karya Peter Tompkinn & Christopher Bird (2008, h. 3) tertulis, “Ketika tanah menjadi kering, akar-akar akan berpaling ke arah tanah yang lebih lembab, menemukan jalan mereka ke dalam saluran yang terkubur dalam tanah, mengembang, dan dalam kasus tanaman alfalfa rendah, ia mampu mengembang sejauh empat puluh kaki, membangkitkan energi yang dapat melubangi tembok beton.
Belum ada orang yang menghitung jumlah akar sebatang pohon, tapi sebuah penelitian terhadap tanaman gandum hitam menemukan jumlah total akar ada sekitar 13 juta dengan panjang keseluruhan sekitar 380 mil.
Pada setiap sulur akar ini terdapat bulubulu akar yang halus, dan diperkirakan berjumlah sekitar 14 milyar dengan total panjang sekitar 6.600 mil, hampir seukuran jarak dari kutub ke kutub bumi.” Sungguh luarbiasa!
Supaya pembahasan terkait dunia yang centang prenang ini tak melebar, mari kita batasi kajian seputar bagaimana seharusnya manusia menyikapi tanah dan tetumbuhan—dua hal yang jelas sangat berdekatan dengan hidup manusia.
Diriwayatkan dari al-Baihaqi, al-Buzari dan al-Darimi dari Ibn Umar r.a, katanya:
“Pada suatu hari kami dalam perjalanan bersama Rasulullah Saw. Tetiba datang seorang badui. Rasulullah pun bertanya, “Hendak ke mana engkau?” Jawabnya, “Mau menemui keluargaku.” Berkata Rasulullah, “Maukah engkau saya tunjukkan sebuah kebaikan?” Jawab badui itu, “Kebaikan apakah itu?” Jawab Rasulullah, “Supaya engkau merasakan mengakui tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah utusan-Nya.” Orang badui itu pun bertanya, “Apa tandanya engkau utusan Allah?” Jawab beliau, “Tandanya adalah pohon yang berdiri di ujung lapangan itu.”
Setelah orang badui tersebut melihat ke arah pohon, tetiba pohon tersebut bergerak ke kiri dan kanan, ke depan dan ke belakang, sehingga tercerabut akarakarnya, lalu melompat-lompat menuju ke arah Rasulullah Saw, dan akhirnya berdiri tegap di hadapan beliau.
Lalu dengan suara tegas pohon itu berkata, “Aku mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya.” Perkataan ini diulangi pohon itu sampai tiga kali. Menyaksikan itu, si badui langsung bersyahadat. Pohon tersebut kembali ke tempat semula dan terlihat biasa lagi. (Iskandar dalam Peter & Christopher, 2008).
Itu baru salah satu kisah mengagumkan Nabi Muhammad Saw dengan pepohonan. Masih ada cerita yang lain. Dalam Sejarah Madinah karya Dr. Nizar Abazhah, 2009 (h. 51) terbitan Dar al-Fikr-Damascus-Syria, terdapat sebuah kisah yang tak kalah mengesankan.
“Masjid Nabi (Nabawi) waktu itu sebetulnya sebuah lapangan yang dilingkari tembok. Beralaskan tanah, beratapkan langit. Di tengah masjid, sekarang ada dua ruang dengan atap seperti payung yang bisa dibuka. Dahulu pada zaman Nabi, di tempat itu ada pohon kurma. Bila Nabi berbicara di hadapan jamaah yang memenuhi masjidnya, Beliau akan berdiri di bagian masjid paling depan, dan bersandar pada batang pohon kurma itu, di sebelah kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi.
Pada tahun ke-7 dan ke-8 Hijriyah, ketika kaum Muslim mulai membludak dan memadati masjid, beberapa sahabat antara lain Sa’d ibn Ubadah dan Tamim al-Dari mengusulkan agar dibuat tempat khusus untuk Nabi berdiri sehingga kelihatan sampai ke belakang. Maka pada tahun itu pula Beliau mengirim utusan kepada seorang perempuan untuk menyampaikan pesan, “Suruhlah budak Najjarmu membuatkan aku penyangga tempat duduk kala berbicara di hadapan orang banyak.”
Titah Nabi disambut dengan antusias oleh si Najjar. Dibuatlah sebuah mimbar dari pohon tamaris ghabah. Setelah rampung, Nabi menunjuk tempat yang pas untuk meletakkannya. Mimbar itu berundak tiga, dan nabi sering duduk di undakan ketiga.
Pada suatu Jumat, setelah mimbar rampung dibuat, Beliau yang mulia keluar dari pintu kamarnya. Lantas berjalan menuju mimbar, dengan melewati pohon kurma itu. Ketika Beliau menaiki mimbar untuk berkhutbah, tetiba banyak orang mendengar rintihan yang sangat memelas.
Tangisan itu mengguncangkan tanah yang menjadi alas masjid. Debu-debu dari tembok masjid berjatuhan. Suara tangisan itu makin lama kian keras. Para sahabat pun ikut menangis, sambil tidak tahu dari mana sumber tangisan itu.
Nabi turun kembali dari mimbarnya. Beliau mendekati pohon kurma, lalu meletakkan tangannya yang mulia pada batang kurma itu, mengusap, dan kemudian memeluknya. Pelahan, suara tangisan itu mereda dan akhirnya tenang kembali. Para sahabat mendengar Nabi berbicara kepada pohon kurma itu, “Maukah kamu aku pindahkan ke kebunmu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukmin, atau aku pindahkan kamu ke surga. Setiap akar kamu minum dari minuman surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu?”
Rupanya kurma itu memilih yang kedua, karena Nabi bersabda, “Af’al insya Allah! Af’al insya Allah! Af’al insya Allah!” Kemudian Nabi bersabda, “Demi Allah, yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalau tidak aku tenangkan batang kurma itu, dia akan terus merintih sampai hari kiamat karena kerinduannya kepadaku.”
Dari Bumi ke Langit
Dua kisah tentang bagaimana Nabi berkomunikasi secara diameteral dengan pepohonan, jadi bukti betapa dunia kita hari ini telah jungkir balik. Alam atau lebih mudahnya lingkungan sekitar kita, telah kehilangan pamor dan kehormatan di mata manusia. Dunia kita tak lagi menaruh perhatian serius pada upaya penyelamatan lingkungan dengan cara terpadu (permaculture). Padahal industri adalah jalan pintas rusaknya wajah alam kita sekarang.
Revolusi Industri yang bergolak di Inggris pada dua abad lampau (1750-1850), menabung dampak serius yang masih berlangsung hingga kini. Dalam ranah ekonomi. Revolusi Industri berdampak munculnya pabrik-pabrik, lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi rendah sehingga harga barang dan upah buruh pun anjlok, perdagangan dunia semakin timpang, tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perseorangan, dan matinya industri rumah tangga.
Dalam ranah politik. Munculnya kaum borjuis, sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru penguasa industri. Dari sinilah lahir imperialisme modern, yaitu upaya mengembangkan kekuasaan berlandaskan kekuatan ekonomi, mencari tanah jajahan baru, bahan mentah serta mengembangkan pasar bagi industri.
Gerakan penjajahan terencana ini tersistematisasi dalam sistem demokrasi yang kelak menemu jalan terang dengan kehadiran nasionalisme. Selain itu, liberalisme juga pelahan merebak ke antero dunia—setelah awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung Revolusi Agraria dan Revolusi Industri.
Dalam ranah sosial. Akibat berkembangnya industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota. Terjadilah urbanisasi besar-besaran dari pedesaan. Anak-anak petani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Kota-kota besar pun menjadi padat dan semakin sesak. Para buruh hidup berjejalan di tempat tinggal yang kumuh dan kotor.
Tidak hanya itu, dalam pekerjaan, mereka menjadi objek pemerasan majikan. Buruh bekerja rata-rata 12 jam sehari, namun tetap miskin. Apa lacur. Kemiskinan pun berakibat langsung pada meningkatnya kejahatan, ketergantungan pada minuman keras, pengangguran. Alhasil perempuan dan anak pun ikut bekerja. Sementara jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk mereka sangat tidak manusiawi.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa Revolusi Industri menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi hasil-hasil produksi melalui perdagangan bebas yang kemudian melahirkan konsep liberalisme. Hal ini berimbas pada negara-negara koloni, seperti juga wilayah-wilayah di Asia yang menjadi jajahan bangsa Eropa. Termasuk Indonesia.
Ketika Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal dari Inggris, berkuasa di Indonesia (1811–1816), ia berupaya memperkenalkan prinsip-prinsip liberalisme di Indonesia. Kebijakan yang diberlakukannya, antara lain, memperkenalkan sistem ekonomi uang, memberlakukan pajak sewa tanah untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, serta menghapus perbudakan.
Ketika Inggris menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda, dibuatlah perjanjian bahwa Belanda akan tetap memberlakukan perdagangan bebas. Oleh karena itu, banyak perusahaan Inggris yang berdiri di Indonesia.
Pengaruh Revolusi Industri juga sampai ke negeri Belanda dan memengaruhi sikap mereka terhadap tanah jajahan. Politik imperialisme Belanda yang awalnya menggunakan tata cara kuno, yaitu pemerasan, kekerasan, dan penyedotan kekayaan Indonesia di kemudian hari, mendapat protes dari kaum humanis Belanda yang berpaham liberal, seperti Max Havelaar (Mulatuli, nama pena Ernest Douwes Dekker). Maka muncullah Politik Etis di Indonesia pada 1901, yang dipelopori Pieter Brooshooft (wartawan koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer, yang berisi:
Irigasi (pengairan), membangun pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian koloni Belanda di Nusantara, agar komoditas yang mereka tanam bisa melipatgandakan keuntungan bagi Kerajaan Belanda.
Emigrasi, yakni mengajak penduduk bertransmigrasi dengan tujuan agar terjadi persebaran penduduk dan pemerataan industri. Edukasi, memperluas pengajaran dan pendidikan. Targetnya, supaya lebih banyak tenaga kerja lokal yang bisa diberdayakan untuk mengelola industri yang sedang dibangun dan dikembangkan.
Alhasil, Politik Etis tetap tinggal nama saja. Sebab pada kenyataannya, bangsa Indonesia masih berada dalam jerat yang sama dalam formasi berbeda. Upaya pembaratan ini menuai hasil gemilang.
Para petani sebagai contoh, secara pelahan tapi pasti, mulai kehilangan haknya sebagai pemilik lahan. Termasuk kemampuan mereka bercocok tanam yang telah dialihkan menjadi serba modern. Kearifan lokal dalam bertani pun luntur satu demi satu. Hubungan harmonis petani dengan tanah sawah dan ladangnya, raib ditelan kerakusan dan penindasan.
Bertani bukan lagi sebuah laku mulia yang dialamatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak secara baik dan benar. Tanaman dianggap sebagai barang dagangan belaka demi memenuhi hasrat meraup pundi kekayaan sebanyak mungkin.
Sehingga keberkahan dan kebaikan sebuah tanaman yang diciptakan Allah untuk mengabdi pada manusia, tak lagi terasa. Proses ini, terus berlangsung hingga sekarang. Wajar bila ada begitu banyak orang di negeri kita saja misalnya, yang tak lagi bisa memahami apa bedanya makan untuk hidup atau hidup untuk makan.
Kotakota yang terus tumbuh karena disokong oleh transmigrasi, memaksa begitu banyak orang untuk berpindah ruang. Desa dianggap kuno dan tempatnya kekolotan. Sementara kota dicitrakan sebagai simbol “kemajuan zaman” yang terus bergerak.
Segala anasir yang terjadi di dalamnya, dianggap sebagai dinamika pertumbuhan. Bukan kemerosotan. Anakanak petani yang kehilangan penghormatan pada sawah orangtuanya, juga kehilangan kemampuan bercocok tanam demi menghidupi diri sendiri dengan kedua tangannya.
Mereka terus berlomba dan bersusah payah menjadi warga kota, sambil terus melupakan kebaikan (thayyib) mengahasilkan makanan bagi diri sendiri dan keluarganya. Mereka pun tak lagi peduli bagaimana makanan itu telah tercemari begitu banyak kerusakan melalui pupuk kimia, cara mengolah tanah, dan betapa makanan yang kemudian diasupnya halal atau tidak. Keberkahan hidup pun tak lagi menjadi tujuan utama. Bumi sebagai Ibu dan Langit sebagai Bapak, tinggal kenangan.
Sekarang ini, hanya 55 persen kalori tanaman dunia dimakan manusia secara langsung; sisanya menjadi pakan ternak (sekitar 36 persen) atau diubah menjadi bahan bakar hayati dan produk industri (kira-kira sembilan persen). Meski banyak orang makan daging, produk susu, dan telur dari hewan yang dipelihara di area penggemukan, hanya sebagian kecil kalori dari pakan ternak yang sampai ke kita melalui daging dan susu.
Dalam setiap 100 kalori biji-bijian yang kita berikan kepada hewan, kita hanya mendapat sekitar 40 kalori baru dari susu, 22 kalori telur, 12 kalori ayam, 10 kalori babi, atau 3 kalori sapi.
Jika kita mencari cara yang lebih mangkus guna menghasilkan daging dan beralih ke pola makan yang mengurangi daging—bahkan sekadar mengganti daging dari sapi yang makan biji-bijian ke daging ayam, atau sapi yang makan rumput—sejumlah besar makanan di seluruh dunia dapat kemudian dikonsumsi langsung oleh manusia. (Jonathan, 2014)
Manusia yang melupakan fitrahnya sebagai makhluk mulia, jelas akan terus melakukan perusakan pada diri sendiri. Ia bahkan tak lagi mengerti bahwa kita diminta oleh tuhan untuk membina dan menjalin hubungan mesra dengan alam, khususnya bumi. Corak berpikir semacam ini sudah sangat sulit ditemukan dalam kehidupan kita sekarang, kecuali segelintir orang saja yang masih mau melakoninya dengan susah payah.
Kita sering membaca-mendengar seputar kisah bangsa besar di masa lalu. Tentang bagaimana mereka lahir, tumbuh, membiak, berkembang, membesar, mendunia, dan menyejarah. Tapi sedikit saja yang kita ketahui soal bagaimana semua yang mereka lakukan, menguap begitu saja dalam kehancuran.
Apa yang menyebabkan semua adab besar nan unggul yang pernah ada kemudian punah? Kenapa selalu artefak belaka yang mereka sisakan? Apakah biang keladi kehancuran mereka? Siapa pula yang menjadi pelanjut tongkat estafet semua peradaban itu sebelum sampai ke tangan kita? Apa sejatinya yang mereka wariskan pada kita?
Kenapa bangsabangsa besar itu raib begitu saja? Apakah yang terjadi pada mereka, juga kita alami hari ini? Adakah benturan antara agama dan negara juga membuat mereka goyah dan terbelah—lantas kemudian punah?
Jika memang benar semua bangsa unggul itu telah mencapai puncak azimut kejayaan dalam segala bidang (termasuk pengetahuan & spiritualitas), lantas kenapa mereka merosot ke titik nadir? Tak cukupkah dua anasir peradaban itu bagi mereka? Sementara kedua hal itulah yang dikejar sekuat tenaga oleh Abad Modern yang kita hidupi hari ini.
Jejak yang ditinggalkan nenek moyang kita dari masa lalu, tak sepenuhnya bisa ditelusuri. Bukan tak mungkin, hal yang sama juga terjadi pada kita dan generasi mendatang. Malah bisa jadi lebih tragis dari itu. Sampai hari ini, tak satu pun kita bisa memastikannya. Semua butuh diuji dan dibuktikan. Sejarah yang akan menjawabnya. Sayang, sedikit sekali manusia yang mau menyelam ke dalam sejarah. Cicero, filsuf Yunani pernah berkata,
“Orang yang menafikan sejarah dalam hidupnya, maka dia adalah kanak-kanak seumur hidupnya …”
Harus diakui, kini wajah dunia kita jadi buruk rupa kerana ada milyaran orang yang melakukan sesuatu tapi bukan berdasar kemampuannya. Ada banyak zombie di manamana. Manusia tinggal atribut belaka. Mereka tak lebih dari onggokan daging yang melekat pada tulang belulangnya.
“Aku melawan saudara kandungku; aku dan saudara kandungku melawan sepupuku; aku, saudara kandungku, dan sepupuku, melawan klan lain.” Bunyi pepatah kuno itu kini kita saksikan di depan mata. Perang pecah di manamana. Sedari tepian Afrika, hingga Timur Tengah. Manusia telah kehilangan harga dirinya yang sejati selaku makhluk mulia.
Jadi atas kepentingan apakah Abad Modern ini dikembangkan? Dari manusia untuk manusia? Sayangnya, tidak. Apa yang kita alami dan rasakan, jauh panggang dari api. Padahal Nabi Muhammad Saw pernah menitipkan pesan bahwa, “Permulaan akal, setelah iman/agama, adalah menunjukkan kecintaan kepada manusia.”
Kita harus bisa menjawab dari mana muara kerumitan hidup manusia hari ini. Kita bahkan harus menaikkan keberanian beberapa tingkat untuk angkat bicara, bertindak, dan menyelamatkan begitu banyak korban yang masih dan akan terus berjatuhan akibat degradasi alam yang kita picu sendiri




















