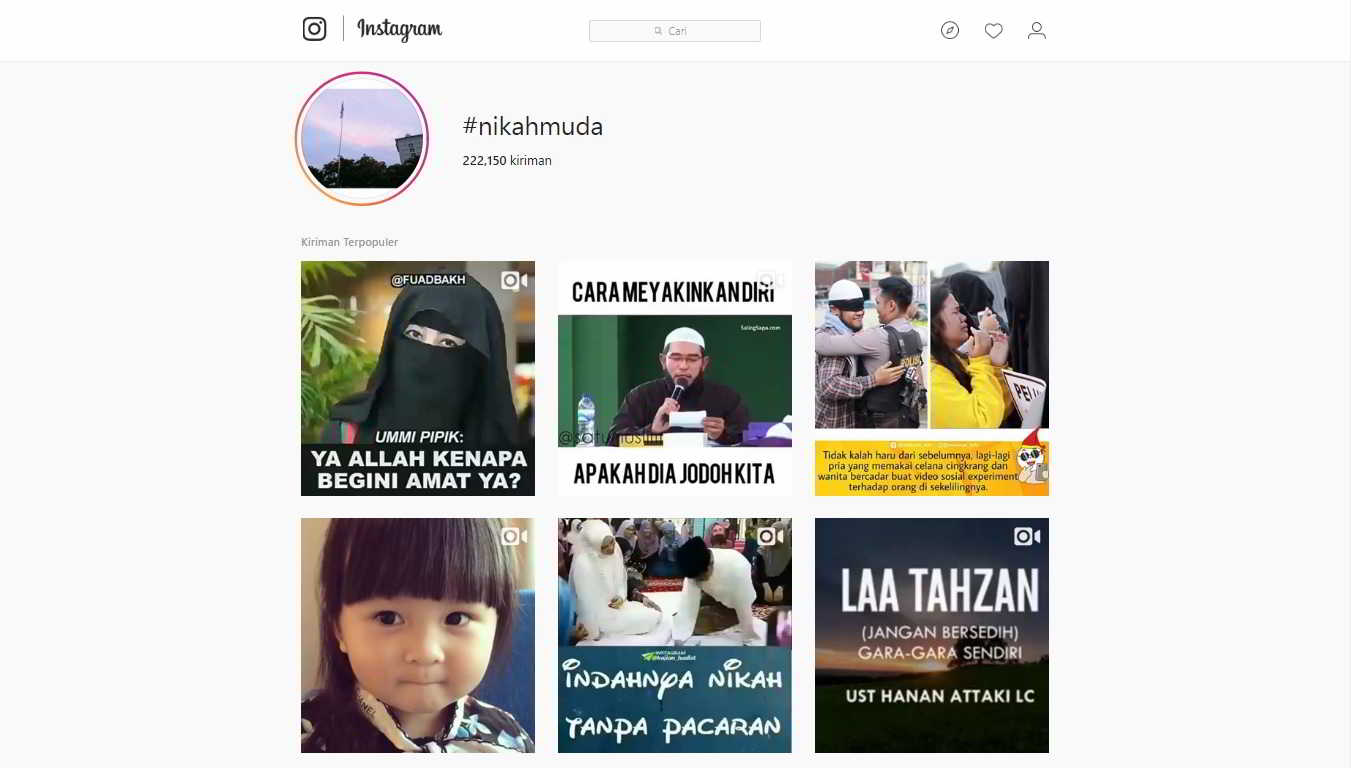Di Hari Bumi 22 April, Mari Kita Belajar Literasi Ekologis dari Kartini Gunung Kendeng

Berbeda dengan peringatan hari Kartini pada tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan kegiatan seremonial seperti karnaval, peragaan busana, atau membaca puisi, hari Kartini tahun ini kita rayakan dalam suasana yang berbeda. Sebabnya tak lain dan tak bukan karena pandemi Covid-19.
Keadaan ini mestinya mampu mengubah paradigma berpikir kita dari sekedar perayaan simbolik menuju pemahaman esensial ‘perjuangan’ yang disuarakan oleh Kartini, yaitu keprihatinan akan cengkeraman feodalisme dan budaya patriarki yang terjadi pada saat itu. Keprihatinan ini yang kemudian mendobrak kesadaran akan pentingnya literasi yang menjadi kunci kearifan dan pola pikir futuristik bangsa ini.
Tugas dan perjuangan Kartini untuk bangsa ini telah purna dan sempurna, dan kini tongkat estafet perjuangan itu beralih ke tangan kita dengan tantangan yang tentu saja berbeda dengan apa yang ada di zaman Kartini. Meski demikian, selayaknya kita mampu merefleksikan makna perjuangan itu, dan perjuangan dalam bentuk literasi ekologis bisa menjadi salah satu bentuknya. Terlebih, peringatan hari Kartini tahun ini menjadi istimewa karena diikuti dengan peringatan hari bumi 2020 yang jatuh pada tanggal 22 April. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa kesadaran ekologis yang dimiliki bangsa ini masih sangat minim.
Terlalu kompleks permasalahan yang kita hadapi sehingga kita sendiri sulit untuk menguraikannya satu persatu, semua saling berkelit kelindan, dari yang paling sederhana terkait kesadaran individu hingga regulasi pemerintah yang semuanya masih menyisakan pekerjaan rumah bersama. Belum lagi kerusakan alam yang memicu terjadinya berbagai bencana beruntun yang sebenarnya bisa dicegah jika ada kesadaran ekologis masal.
Satu hal yang menggembirakan adalah munculnya usaha-usaha untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di tengah masyarakat. Meski kebanyakan berupa kerja sukarela dan inisiatif lokal, namun dampak yang diberikan cukup signifikan. Salah satu yang patut kita apresiasi adalah kesadaran ekologiserempuan-perempuan yang tinggal di pegunungan Kendeng utara yang kemudian dikenal sebagai Kartini Kendeng.
Perjuangan mereka untuk menyelamatkan pegunungan Kendeng bukan semata penolakan atas industrialisasi dan kapitalisme global, tapi lebih pada kesadaran ekologis yang futuristik, bahwa jika gunung, lahan pertanian dan tanah kelahiran mereka dialihfungsikan itu sama artinya dengan menciptakan ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya menjadi pemicu berbagai bencana alam. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan menanggung akibat krisis ekologis ini.
Bagi mereka, Kendeng layaknya ibu yang senantiasa mengasihi anak-anaknya. Mata air yang ada di Kendeng ibarat air susu yang terus diberikan pada bayi-bayi mereka hingga pada saatnya mereka disapih dalam kefanaan. Bahkan di musim kemarau ia tetap menyusui anak-anaknya dengan penuh kasih. Mereka sadar sepenuhnya bahwa selamanya mereka akan tetap menjadi bayi yang bergantung pada ibu mereka hingga tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali penghormatan setinggi-tingginya pada Kendeng, ibu ekologis mereka.
Selain sebagai bentuk proteksi akan keberlangsungan kehidupan masyarakat, kesadaran ekologis ini merupakan kritik atas cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia dalam posisi tertinggi ekosistem yang terbukti justru banyak membawa kerusakan. Egoisme dan kerakusan manusia justru mengantarkan pada eksploitasi alam yang berlebihan, bahkan sindiran alam melalui berbagai bencana seakan tidak mampu menumbuhkan kesadaran akan ketergantungan manusia pada alam.
Hal ini yang tergambar dalam ‘syair ibu bumi’ yang populer di kalangan Kartini Kendeng: ‘Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili’ (Ibu bumi sudah memberi, Ibu bumi disakiti, Ibu bumi yang akan mengadili). Syair yang kemudian dilantunkan dengan tambahan kalimat tauhid ‘Laa ilaaha illallah, Muhammadur rasulullah’ ini mengandung makna yang sangat dalam terkait kesadaran ekologis. Bagi mereka, ada hubungan kosmologis yang suci antara Tuhan, manusia dan alam.
Salah satu cara untuk menghidupkan hubungan kosmologis yang suci ini adalah dengan selamatan atau brokohan yang selalu digelar sebagai bentuk syukur atas apa yang mereka dapatkan di musim panen. Upacara ‘gumbrengan’ juga merupakan bentuk syukur dan terima kasih para petani Kendeng pada binatang ternak yang membantu mereka dalam bertani. Sungguh merupakan simbol hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia dan alam. Bahkan kendi yang menjadi simbol ‘tanah’ dan ‘air’ tetap mereka pertahankan dalam kehidupan sehari-hari.
Perjuangan mereka untuk mempertahankan pegunungan Kendeng bisa jadi menguatkan hipotesa kedekatan dan keterikatan perempuan dengan alam, namun terlepas dari itu, etika ekosentris yang mereka anut dengan memposisikan alam raya secara ‘proporsional’ adalah bentuk lain dari semangat perjuangan Kartini, hingga tidak berlebihan jika kemudian mereka mendapatkan julukan sebagai Kartini Kendeng.
Dari mereka kita belajar literasi ekologis yang tidak hanya didengungkan melalui kampanye-kampanye verbal, namun diterjemahkan dalam gerakan nyata. Bahkan dengan bangga mereka mensyukuri status mereka sebagai petani, profesi yang sering kali dipandang sebelah mata.
Bagi mereka, menanam tidak semata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, merawat bumi dan ekosistem sebagai tempat berkembang dan berlanjutnya kehidupan. Mereka percaya bahwa dengan menjaga alam, maka alam akan menjaga mereka.