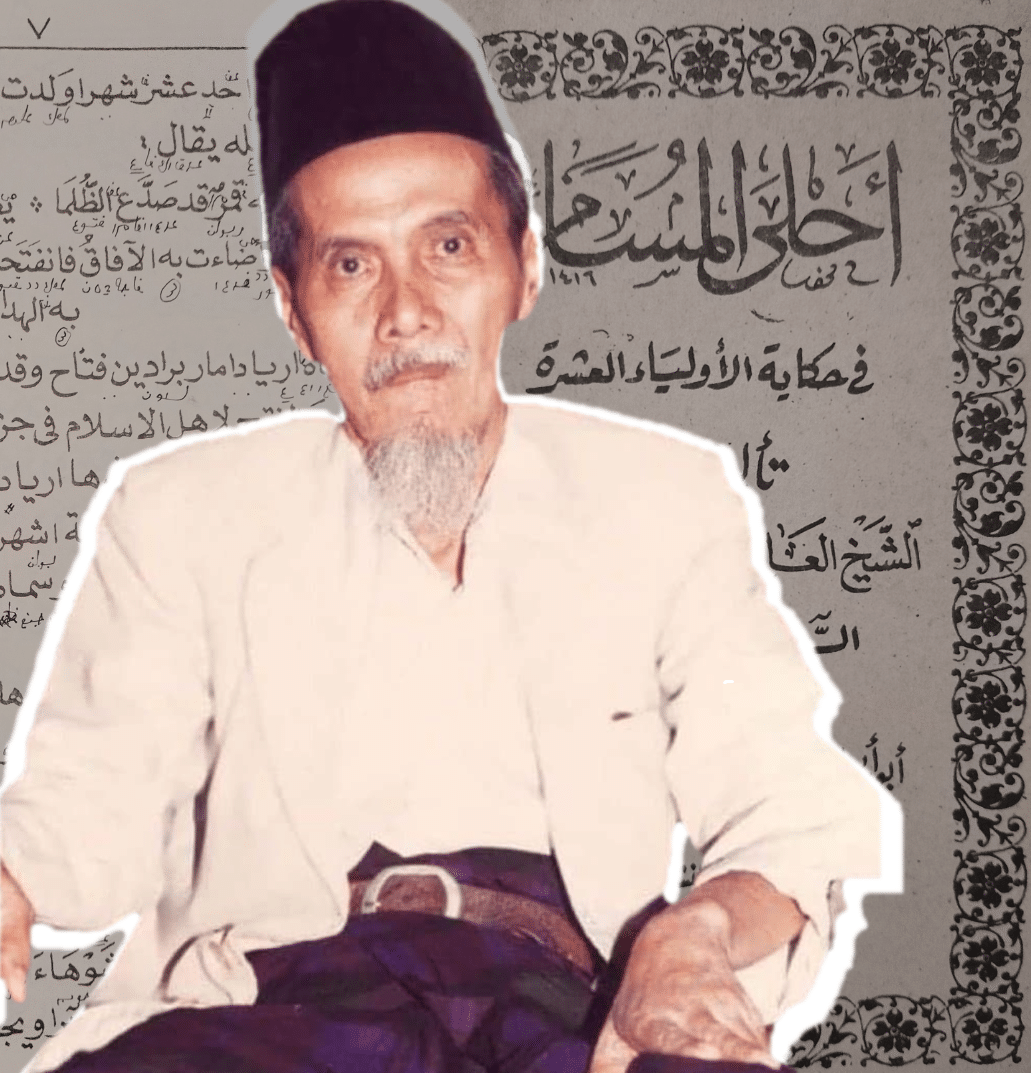Kebudayaan Jawa pada dasarnya tak mengenal konsep pertunjukan (performance) ataupun pameran (exhibition) yang lekat dengan corak kesenian modern dan pascamodern. Istilah yang khas untuk pertunjukan kesenian tradisional di Jawa lazim disebut sebagai “pagelaran.” Wayang purwa sepertinya sangat mengeramatkan istilah “pagelaran” ini dimana dahulu tuntutan moral-spiritual seorang dalang tak sekedar bisa menggelar, tapi diharapkan juga bisa menggulung (isa nggelar kudu isa nggulung). Hal ini seturut dengan struktur dramatik wayang purwa (gagrak Sala) yang terpilah menjadi 3 pathet: pathet nem, pathet sanga, dan pathet manyura.
Konsep pathet ini memiliki fungsi yang pokok dalam kesenian wayang purwa dan kesenian-kesenian tradisional lainnya seperti karawitan dan tari-tari tradisional. Pathet kerap diasosiasikan dengan babak yang berhubungan dengan waktu. Seumpamanya suasana yang tercipta dalam pathet nem tentu berbeda dengan suasana pada pathet sanga maupun manyura. Ibarat fase kehidupan manusia, pathet nem merupakan suasana bocah dimana segala persoalan kehidupan belum muncul dan menjadi kendala yang berarti.
Pada adegan jejer sepisan, identifikasi masalah mulai menampakkan diri yang terkadang sampai harus menciptakan konflik yang bersifat semu. Karena itulah adegan perang yang terjadi di pathet nem ini disebut sebagai “perang gagal” dimana perang yang terjadi tak mencapai klimaks. Karena itulah terdapat tembang dari masa silam yang mengartikan pathet nem ini sebagai awal mula kehidupan (purwaning tumitah).
Midhanget swara anjerit
Ki jabang mijil karuna
Lir garantang tangise
Yeku purwaning tumitah
Anom neng alam donya
Mulane pathet nem iku
Tinata karya bebuka
Pathet sanga kemudian datang dengan suasana yang bersifat riang sekaligus penuh kekhidmatan. Ibarat manusia yang mengalami fase kemudaan yang sarat dengan upaya pencarian jati diri, adegan gara-gara, dimana para panakawan menghibur junjungannya, tiba dengan diakhiri dengan adegan kapandhitan yang penuh dengan wejangan-wejangan kehidupan.
Mangun sukaning cipta di
Kawengku ponang pathetan
Wiwit mathet leng-lengane
Nutupi ingkang babahan
Hawa sanga purwanya
Leng sanga pamethikipun
Mila ngaran pathet sanga
Seandainya suasana pada pathet nem belum terasa bergelombang, suasana pathet sanga menjadi bergelombang dan penuh warna sampai tiba saatnya manusia mulai merenungi kehidupannya dengan simbolisasi adegan kapandhitan yang akan mengantarnya pada suasana mencekam pathet manyura. Di sinilah drama kehidupan manusia berakhir dan menjadi terang segala sesuatunya. Segalanya menjadi kebenaran dan tak lagi sekedar pengabaran.
Konflik, perang, kebengisan dan kepedihan benar-benar terjadi yang berujung kematian. Di sini fase kehidupan manusia telah sampai pada usia tuanya. Taruhlah perang antara Bima dan Gathutkaca yang sampai harus menghunjamkan kuku pancanaka (nujah) dan memlintir kepala para musuhnya. Semua adegan pembunuhan ini hanya terjadi di pathet manyura yang identik dengan waktu sehabis tengah malam, ketika banyak orang dan khususnya para bocah nyenyak tertidur.
Manguwuh peksi manyura
Wancine andungkap gagat rahina
Saniskara woding pagelaran
Kang becik ketitik kang ala ketara
Awit iku apranyata
Gotek ingkang windu pamayang
Om awignam astu mana
Secara umum konsep pathet dalam pagelaran wayang purwa menyingkapkan perjalanan kehidupan seorang manusia, mulai dari niat yang menanggap hingga ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh sang dalang sebagai wakil atau utusan yang menanggap. Proses tergelarnya kehidupan pun terejawantahkan menurut pesanan yang menanggap. Adakalanya pagelaran menjadi tak sebagaimana yang diharapkan dan karena hal ini, maka sang dalang bukanlah metafora tentang Tuhan yang tepat. Justru, yang menanggap pagelaran itulah yang dianggap sebagai metafora tentang Tuhan yang disebut sebagai Sang Hyang Manon (Teologi Wayang Purwa, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).
Istilah “pagelaran,” dengan demikian, merupakan pembabaran konsep sangkan-paraning dumadi. Sebab, pada dasarnya wayang sendiri tak dapat dilepaskan dari manusia. Ia adalah bagian dari jagat kita sendiri. Keseluruhan pagelarannya adalah perumpamaan tentang dari mana, akan ke mana, dan bagaimana manusia melalui sangkan-paran tersebut. Idealnya, sangkan itulah yang semestinya menjadi paran-nya, sebagaimana raga para wayang yang akan kembali ke kothak, jiwa para wayang yang akan kembali ke sang dalang, dan kekuasaan serta kewenangan sang dalang (pamurba wisesa) yang akan kembali ke yang menanggap (Sang Hyang Manon). Seperti halnya mengitari seutas gelang, titik awal sudah sepatutnya menjadi titik akhir.
Jadi, pada akhirnya, semua berpulang pada manusia sendiri, apakah ia akan kembali ke sangkan yang merupakan paran-nya atau memilih pilihan lainnya. Karena itulah sang dalang bukanlah metafora yang tepat tentang Tuhan. Seandainya Tuhan adalah laiknya sang dalang, tentunya tak ada pagelaran wayang purwa yang rusak atau tak sebagaimana yang diharapkan. Gagalnya sebuah pagelaran membuktikan bahwa dalam kehidupannya manusia dapat pula mengalami kegagalan atau paran-nya tak sesuai dengan sangkan-nya dimana dalam bahasa agama dikatakan celaka atau tak selamat.
Sampai di sini, satu hal yang patut dipertanyakan adalah lantas siapakah yang pantas dipersalahkan dan menerima hukuman atau sebaliknya, mendapatkan pujian dan ganjaran: wayang, dalang, ataukah yang menanggap? Uniknya, dari konsep pagelaran ini, celaka dan selamat tersebut tak mesti terjadi esok. Tapi, saat ini dan di sini pun hal itu sudah berlaku.
Dari konsep “pagelaran” ini sejatinya sang dalang—atau orang yang memproklamirkan diri sebagai dalang—sudah pasti bisa menggelar meskipun tak menyadarinya. Karena itulah, sangkan yang semestinya menjadi paran adalah sebuah tuntutan atau idealitas: bahwa sang dalang, ketika bisa menggelar, mesti pula bisa menggulung. Hal ini berlaku baik secara metaforis maupun hakiki.
Untuk mengatasi tuntutan moral-spiritual yang berat ini, anggah-ungguh atau subasita dalam keseluruhan pagelaran biasanya di akhiri dengan ungkapan: “Kondur dhumateng ingkang amengku gati” atau “Kondur dhumateng para pamiarsa.” Pamiarsa adalah penonton dimana di baliknya juga terletak Sang Hyang Manon (Yang Maha Tahu) atau yang punya hajat (Ingkang Amengku Gati). Terkadang, ada anggapan bahwa juri teragung adalah para penonton, tapi sebenarnya adalah Sang Hyang Manon selaku yang memiliki hajat. Dengan kata lain, sang penentu pada akhirnya bukanlah para penonton dimana tingkat kebenaran mereka adalah benering wong dan bukanlah kebenaran hakiki atau benering-bener yang hanya dimiliki oleh Ingkang Amengku Gati. Bukankah dalam peristiwa sehari-hari banyak kita saksikan dan alami hal-hal yang menurut standar kita tak layak, tapi tetap saja terjadi dan berlangsung tanpa kita dapat mengubahnya?