
Bahasa Melayu telah menjadi pilihan para wali ketika mereka pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan Islam di dunia Melayu-Indonesia. Kemudian, sekitar abad ke-6 H/12 M. mungkin juga lebih awal lagi, Melayu sudah digunakan sebagai linguafranca, tetapi belum memperoleh status sebagai penyampai wacana apiritual dan religius.
Jejak-jejak para ilmuan dan sufi Muslim yang paling klasik bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan para pemikir sufi Melayu setelah abad ke-7 H/13 M.
Bahasa Melayu berkembang dengan luar biasa sebagai sebuah media bagi konsep-konsep dan ide-ide filosofis dan metafisis di tangan Hamzah al-Fansuri, seorang intelektual terbesar dari Melayu. Al-Fansuri, “Ibnu ‘Arabinya” dunia Melayu ini, adalah orang pertama Melayu yang menuliskan semua aspek fundamental ajaran sufi.
Dia pula yang pertama menghasilkan karya yang sistematis-spikulatif di Melayu. Sebelum Al Fansuri, kita tahu bahwa tiadanya karya yang sebanding dalam bidang sastra Melayu secara umum.
Al-Fansuri sendiri mengakui pandangan bahwa semua karya tasawuf yang dikenal sebelumnya ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Dia mengatakan dalam buku pertamanya, Syarabul Asyiqin, bahwa dia menuliskannya dalam bahasa Melayu agar mereka yang tidak paham dengan bahasa Arab dan Persia juga bisa mendiskusikan topik tersebut. Kemungkinan kitab Syarab Al-Asyiqin adalah buku paling awal tentang tasawuf di Melayu.
Menurut Osman dalam Sayyed Hossein Nasr (ed.) Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, Manifestasi, bahwa dalam karya-karya Al-Fansuri, termasuk tiga karya prosanya, Asrar Al-‘Arifin, Syarab, dan Al-Muntahi, dan aneka syairnya luar biasa signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari sudut pandang litertur Melayu, dia memperkenalkan bentuk-bentuk puisi baru ke dalam bahasa Melayu, yakni ruba’i dan sya’ir.
Kedua, mulai dari penciptaan istilah-istilah dan konsep-konsep teknis yang baru dalam bahasa Melayu, dia membuat bahasa ini sepenuhnya memadai untuk membahas doktrin-doktrin filosofis dan metafisis yang sangat mendalam yang telah diinformasikan oleh para sufi terdahulu.
Dia mungkin tidak menyusun formulasi-formulasi baru. Akan tetapi, kemampuannya menguraikan doktrin-doktrin ini untuk pertama kalinya dalam bahasa Melayu adalah cukup signifikan bagi intelektualitas Melayu belakangan.
Kitab Al-Hikam dari Ibnu ‘Atha Allah Al-Iskandari telah diterjemahkan oleh Syekh ‘Abd Al Malek. Terjemahan tersebut diberi judul Hikam Melayu, dan baik terjemahan maupun komentar tentang Hikam yang asli dari Ibn ‘Atha Allah ditemukan dalam Hikam Melayu.
Abdur Ra’uf Singkel adalah seorang wali sufi populer yang menterjemahkan Alquran ke dalam bahasa Melayu. Abdul Ra’uf juga menulis sebuah kitab tentang fikih (yurisprudensi) yang diberi judul Mi’rajul Thullab.
Da’ud bin Abdullah Al-Patani (w. 1845) adalah salah seorang pengarang yang sangat produktif, yang mengarang berbagai ragam pokok bahasan yang luas, selalu menggunakan bahasa Melayu. Karya-karyanya tersebut banyak dipelajari di Patani, Malaysia dan beberapa wilayah di Sumatera.
Syekh Abdus Samad dari Palembang, yang dikenal sebagai penafsir utama Al-Gazali di dunia Melayu-Indonesia, menerjemahkan Bidayatul Hidayah-nya Imam al-Ghazali, menjadi terkenal dalam sastra Melayu pada abad ke-12 H/18 M, ketika Abdus Samad menerjemahkan dan meringkas magnum opus dari al-Ghazali ini, yang dikenal pada kalangan orang-orang Melayu sebagai Siyarul Salikin.
Nuruddin Raniri, mengarang sebuah kitab fiqih yang mengkaji masalah-masalah ibadah dan ritual yang ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu kitab “al-Shirath al-Mustaqim” pada tahun 1054 H (1644 M), kitab tersebut telah tersebar luas dan sangat populer di kalangan Muslim Nusantara, serta dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan hukum di pelbagai Negara-Kesultanan di Nusantara.
Syekh Arsyad Banjar, adalah salah seorang ulama produktif yang mengarang banyak kitab, beberapa diantaranya berbahasa Melayu. Syekh Arsyad Banjar mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Sultan Banjar pada masa itu, yaitu Sultan Tahmidullah anak dari Sultan Tamjidullah (juga bergelar Sunan Nata Alam, memerintah 1761-1801 M), untuk menulis sebuah kitab yang berisi kajian fikih (yurisprudensi) Islam madzhab Syafi’i dalam bahasa Jawi (Melayu), agar dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh masyarakat muslim Kesultanan Banjar.
Kitab ini berjudul “Sabil al-Muhtadin fi al-Tafaqquh bi Amri al-Din” (berarti “Jalan Para Pencari Petunjuk dalam Mempelajari Perkara Agama”). Berisi kajian tentang fiqih ibadah menurut madzhab Syafi’i, mencakup kajian tentang bersuci, sembahyang, zakat, puasa, haji, perburuan, dan makanan. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu beraksara Jawi, dan dicatat sebagai kitab fiqih ibadah terbesar berbahasa Melayu klasik dalam sejarah khazanah literatur Islam Nusantara.
Di museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan terdapat Kitab Injil Perjanjian Lama Jilid II atau Kitab Kudus yang berbahasa Melayu dan bertuliskan Arab Melayu (Pegon) yang ditulis pada tahun 1886 M. Kemungkinan kitab ini dibuat untuk menarik minat warga Kalimantan Selatan, sebagai sarana dakwah para pendeta Kristen. Karena dahulu orang-orang Banjar yang berdiam di provinsi ini kebanyakan menulis dan membaca menggunakan aksara Arab dan Arab Melayu.
Lebih jauh lagi, dengan bukti ini menurut Prof. Sumanto Al Qurtuby bisa diduga bahwa penulisan bahasa Melayu dengan huruf Arab Pegon ini bukan hanya populer di kalangan muslim dan pesantren-pesantren saja, tetapi juga di masyarakat umum non-Muslim.
Bahasa Melayu sejak dahulu telah menjadi linguafranca masyarakat Asia Tenggara. Kiranya tidaklah berlebihan ketika Indonesia dan Malaysia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka, segera setelah kedua Negara ini meraih kemerdekaannya.
Namun, menurut Gus Mus, kiai dan tokoh NU ini bahwa Arab Pegon saat ini nyaris sudah dilupakan orang. Salah satu “maha karya” orang Islam Nusantara ini sudah “tidak terawat” dan terdesak dari lalu-lintas komunitas masyarakat Nusantara, kecuali di pesantren.








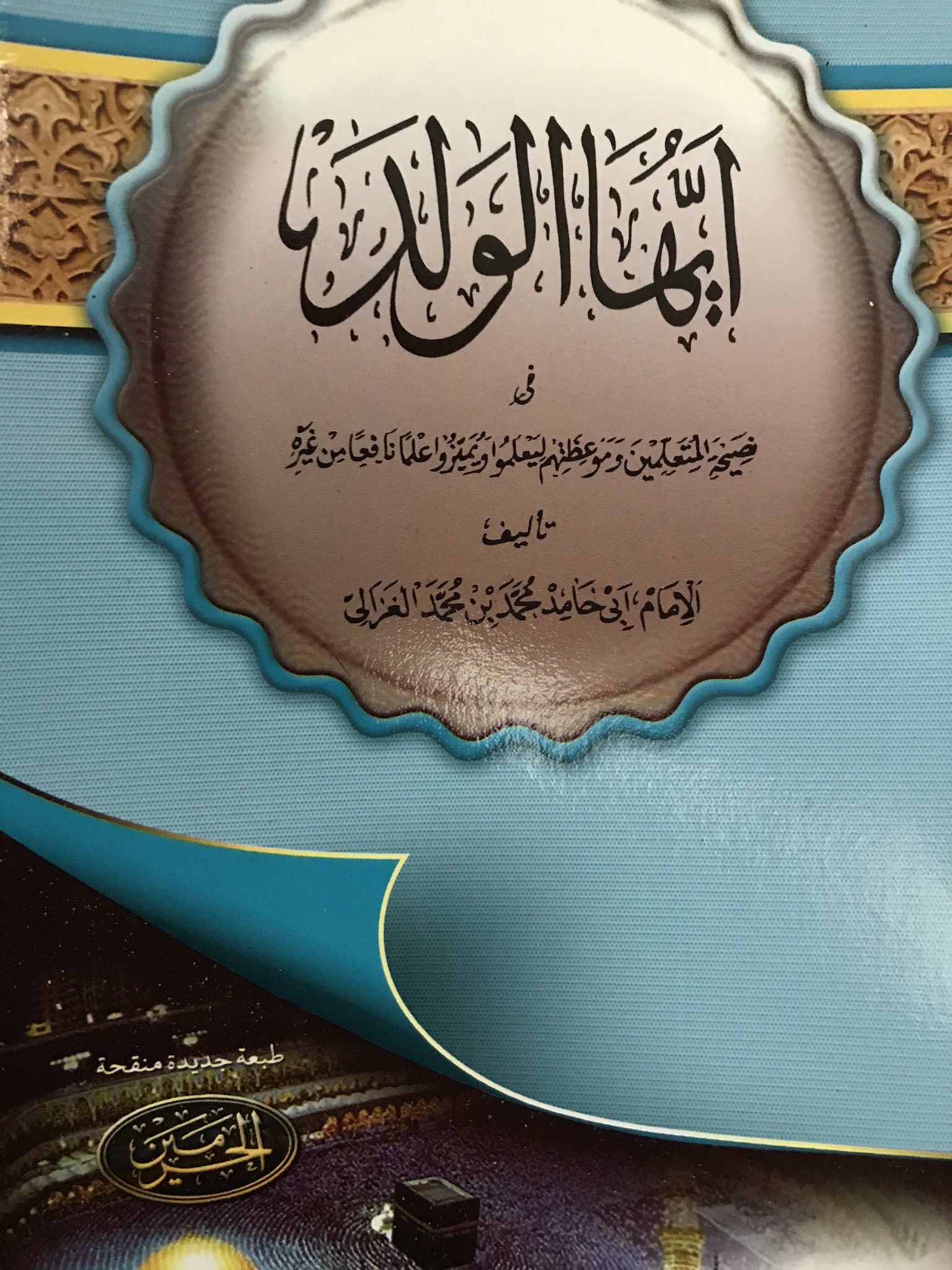
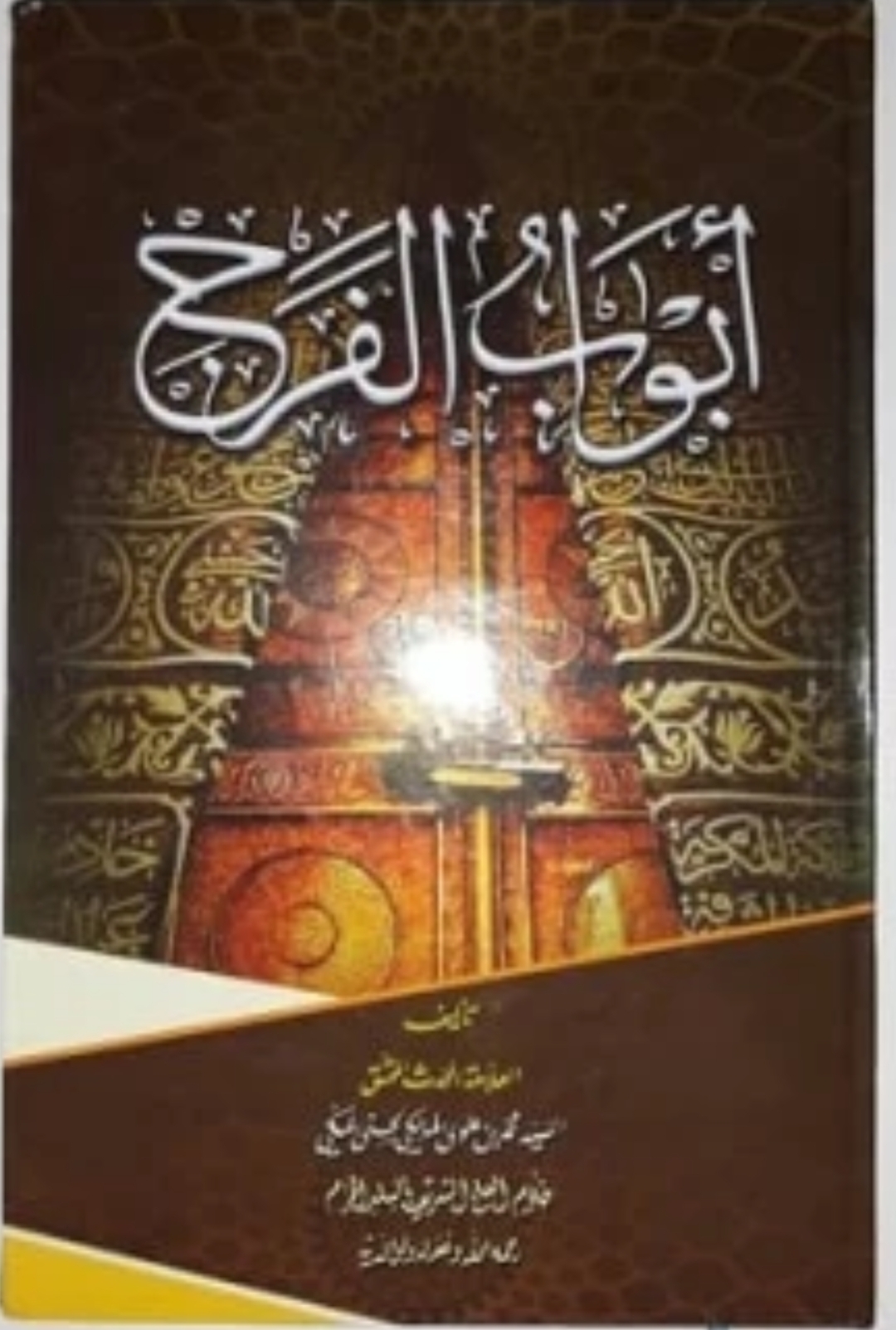











Dalam bukunya Bilik-Bilik Pesantren, Nurcholish Majid menyebutkan bahwa kebiasaan kaum santri menulis dalam huruf Pegon membuat masyarakat santri bisa berkomunikasi di antara mereka tanpa diketahui orang lain. Menurut beliau, ini terbukti ketika pada masa revolusi melawan Belanda dulu, semua hubungan, termasuk notulen rapat2, banyak yang menggunakan huruf Pegon. Contohnya, ketika NU mengadakan rapat di Mediun dengan TNI, pada waktu itu diwakili oleh Jend. Sudirman, hasil rapat yang berupa fatwa wajibnya jihad melawan Belanda ditulis dengan huruf Pegon.
Saya pernah mendengar kalau tulisan arab pegon ini juga sebagai strategi pendidikan kreasi para ulama terdahulu, sebagai siasat atas pelarangan Penjajah Belanda utk pribumu melakukan belajar-mengajar. Belanda membiarkan pribumi membaca Quran dan kitab2 dg tulisan arab krn menyangka pribumi tidak tahu makna dari yang dibacanya. Maka, pribumi yg membaca arab pegon, disangka bahasa arab shg dibiarkan saja oleh Belanda.
Apakah cerita ttg hal ini ada riwayat yang menguatkan ya? wallau a’lam..
Dalam bukunya Bilik-Bilik Pesantren, Nurcholish Majid menyebutkan bahwa kebiasaan kaum santri menulis dalam huruf Pegon membuat masyarakat santri bisa berkomunikasi di antara mereka tanpa diketahui orang lain. Menurut beliau, ini terbukti ketika pada masa revolusi melawan Belanda dulu, semua hubungan, termasuk notulen rapat2, banyak yang menggunakan huruf Pegon. Contohnya, ketika NU mengadakan rapat di Mediun dengan TNI, pada waktu itu diwakili oleh Jend. Sudirman, hasil rapat yang berupa fatwa wajibnya jihad melawan Belanda ditulis dengan huruf Pegon.