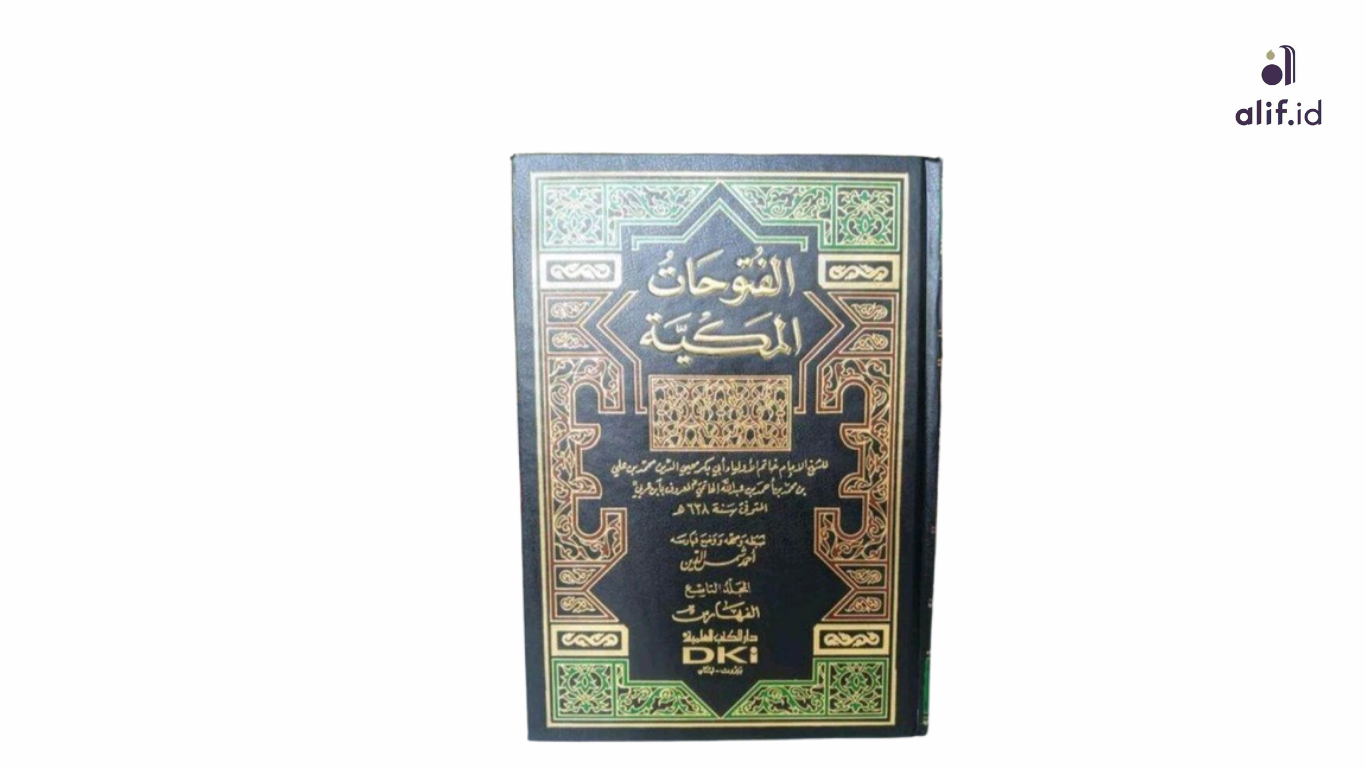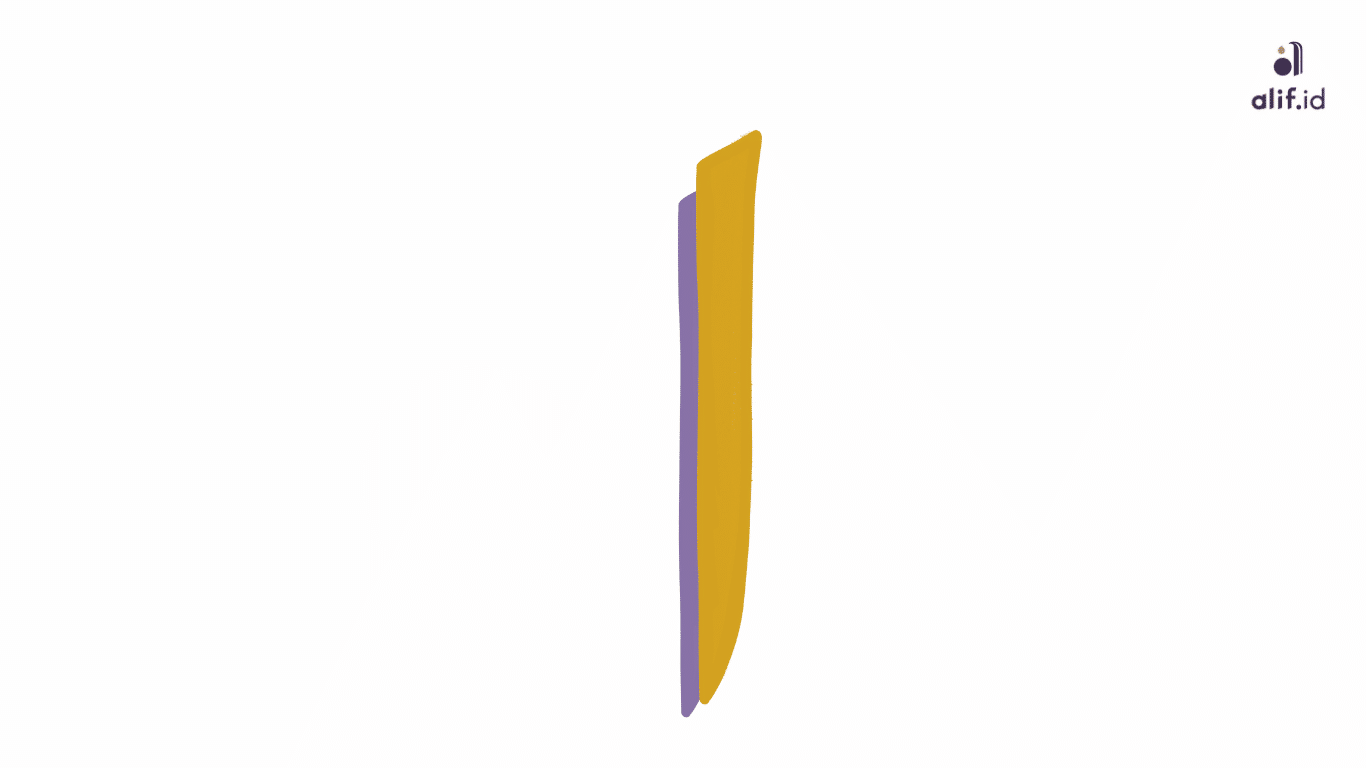Sejak Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan status pandemi global virus korona pada tanggal 12 Maret 2020, masyarakat dunia disibukkan oleh virus yang telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan menginfeksi lebih dari satu juta orang ini. Salah satu langkah yang dilakukan untuk memutus rantai penyebarannya adalah dengan anjuran social distance maupun physical distance. Hashtag (#dirumahaja) pun menghiasi berbagai lini media sosial.
Saya sendiri sudah sebulah lebih tidak keluar rumah, sejak pemerintah Iran menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan meliburankan berbagai kegiatan belajar-mengajar. Jangan tanya betapa jenuhnya saya. Apalagi, penyebaran virus korona ini terjadi tepat ketika Iran sedang menyambut pergantian musim dingin ke musim semi. Musim yang sangat dinanti-nanti, saat alam menunjukkan komolekannya.
Pucuk-pucuk daun muda yang mulai menghiasi ranting kering dan birunya langit musim semi hanya dapat saya pandangi dari balik jendela kamar apartemen. Ransel yang tergeletak di sudut ruangan seolah melambai, menanti untuk diajak kembali berpetualang oleh sang empunya. Sungguh cobaan berat bagi seorang traveler seperti saya. Saat cuaca cerah, badan sehat, anggaran siap, tapi harus berada di titik nol kilometer. Bahkan, untuk sekedar menikmati udara segar di taman dekat rumah pun rasanya sulit.
Tak mudah berdamai dengan situasi seperti ini. Apalagi suguhan berita terus menerus menjejali memori. Seiring jumlah korban yang makin bertambah, kerinduan pada kampung halaman pun kian menderu. Terlebih, saat mendengar satu demi satu teman yang mulai kembali ke tanah air. Saya membayangkan keterasingan. Membayangkan dalam posisi keluarga korban. Bahkan, membayangkan kalau saya sendiri yang harus mengalami. Ternyata benar, persepsi yang kita bangun, jauh lebih menyiksa ketimbang menghadapi kenyataan itu sendiri.
Kehadiran virus korona memang telah melahirkan kecemasan global. Dunia seperti bertarung dengan musuh yang tak terlihat. Sebagian besar penduduk bumi bertiarap di rumah-rumah mereka. Dengan penuh rasa cemas menantikan hari-hari berakhirnya masa karantina. Para pahlawan medis berjuang langsung di garda depan, tak jarang sampai berujung pada kematian. Sementara, banyak buruh yang harus kehilangan pekerjaan. Kecemasan ekonomi pun turut menghantui dunia. Tak ayal, bagi sebagain orang rasa cemas ini menyeret pada keputusasaan.
Di tengah kegalauan inilah, syair-syair Rumi seperti oase yang menyejukkan. Saya kembali membuka lembaran-lembaran puisi Rumi dalam buku Matsnawi Maknawi. Sebuah bait begitu indah untuk direnungkan, terutama di hari-hari duka ini.
Ketika seluruh harapanku musnah
Tuhan pemilik kemuliaan tengah memanggilku: “La Tayasu”, usahlah berputus asa
Tuhan telah siapkan jamuan pesta
Ia hanya sedang menyentil kita seraya menyapa: “La Taqnatu”, usahlah berputus asa
Andai pun kita berada dalam jurang keputusasaan
Tuhan selalu ada untuk membimbing kita ke jalan-Nya
(Rumi, Matsnawi, jilid 6 bait 4741-4743)
Syair-syair Rumi di atas mengajak kita untuk tetap optimis meski berada di titik paling buruk sekalipun. Berpijak pada pandangan dunia agama, Rumi memberikan pencerahan, ketika kita mulai kehilangan harapan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan peluang kepada kita untuk menjadi lebih kuat dan tegar. Karena di balik musibah, ada hikmah yang dapat kita raih. Dalam syair lainnya, secara lebih jauh, Rumi meyakinkan bahwa bersama derita yang kita rasakan, ada kasih sayangNya.
Rasa sakit dan penderitaan adalah peti harta karun, tempat Rahmat Tuhan bersemai
Seperti saat kau lepas kulit biji yang keras, kau dapati bagian yang lembut dan halus
Duhai kawan, bertahanlah dalam gelap dan dingin
Berdamailah dalam kesedihan dan rasa sakit
Itulah sumber mata air kehidupan dan kecintaan pada Tuhan
Karena kemuliaan itu harus kau temui dalam onak dan duri
(Rumi, Matsnawi, jilid 2, bait 2261-2263)
Rumi dalam puisi di atas, memberikan kata kunci yang menarik, bahwa musibah dan penderitaan dapat berubah menjadi rahmat Tuhan. Lebih jauh Rumi juga menjelaskan, ketika kita mampu melampaui rasa sakit itu, derita akan menjadi petunjuk. Lalu bagaimana mengelola musibah menjadi rahmat? Bagaimana mengubah derita menjadi kemuliaan?
Carl G. Jung dalam bukunya “Man and his Symbols” menjelaskan bahwa penderitaan dapat membangunkan kesadaran kita bahwa kehidupan ini perlu perubahan. Karena, seringkali kesadaran manusia baru akan muncul ketika ia terluka. Penderitaan seharusnya tidak menjadikan kita semakin terpuruk. Bahkan, dalam tingkatan selanjutnya, kita tak hanya dapat bertahan mengahdapi penderitaan, tetapi juga memahami dan memaknainya.
Ya, penderitaan yang mampu melahirkan kesadaran inilah yang akan membuka rahmat Tuhan. Kesadaran untuk melihat masalah secara lebih jernih. Kesadaran untuk melakukan perenungan dan evaluasi. Kesadaran untuk memahami kembali tujuan hidup. Kesadaran untuk berprasangka baik kepada pemilik hidup dan mati. Dan tentunya, kesadaran sejati akan diikuti dengan kesadaran sosial atau berbuat ihsan kepada sesama. Sebagaimana firman Tuhan dalam surat Al mulk ayat kedua: “(Dialah) yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”.
Dalam ayat tersebut kita diingatkan bahwa output dari sebuah ujian adalah mampu memperbaiki kualitas amal kita, baik yang bersifat kedirian maupun sosial. Rasanya pesan ini sangat relevan di tengah wabah korona yang tengah mendunia. Kesadaran kita untuk lebih peka terhadap sesama semakin diperlukan.
Kesadaran sosial ini telah banyak dicontohkan oleh mereka yang jiwanya terpanggil. Betapa harunya saat saya melihat sebuah liputan. Sejumlah dokter dan perawat yang awalnya terinfeksi korona dan sembuh, mereka beramai-ramai menyumbangkan plasma darahnya untuk mengobati pasien kritis. Sungguh luar biasa. Setelah tim medis ini bekerja siang malam dengan resiko tertular, mereka tetap tak merasa puas beramal.
Di luar rumah sakit, kesadaran sosial pun mulai bermunculan dalam berbagai bentuk. Mulai dari penggalangan dana, lelang amal, sampai mereka yang bahu membahu membuat perlengkapan medis, seperti: masker, pakaian APD, hand sanitizer, bahkan ada yang mengunjungi rumah sakit untuk sekedar memberikan bunga atau makanan kepada para tim medis.
Tak perlu berkecil hati, bagi yang belum mampu memberikan sumbangan materi, masih bisa berkontribusi dengan tetap tinggal di rumah dan tidak menyebar berita hoax. Tentu akan ada banyak godaan, seperti godaan mudik, reuni, atau bahkan godaan menikmati ibadah bersama. Kesadaran kita untuk tetap tinggal di rumah dan mengabaikan hasrat dan kepentingan pribadi, sangat bermakna di tengah wabah korona ini.
Dengan tetap di rumah, kita memberi ruang yang lebih aman kepada mereka yang harus bekerja di luar rumah. Kita juga tidak membebani rumah sakit dengan lonjakan kasus di luar kapasitas. Sehingga tim medis bisa menangani pasien secara lebih intensif. Dengan begitu, kita telah membantu memutus rantai penyebaran virus.
Lebih dari musibah apapun, fenomena virus korona ini sangat menuntut kepekaan kita kepada sesama. Di belahan bumi mana pun kita tinggal, mari tetap saling berbagi dan memupuk rasa empati. Seperti puisi Saadi yang terpampang di pintu masuk gedung PBB dan hari-hari ini kerap didengungkan oleh para pemimpin dunia.
Anak adam satu badan satu jiwa, tercipta dari unsur yang sama. Bila satu anggota terluka, semua merasa terluka. Kau yang tak berduka atas luka sesama, tak layak menyandang gelar manusia.