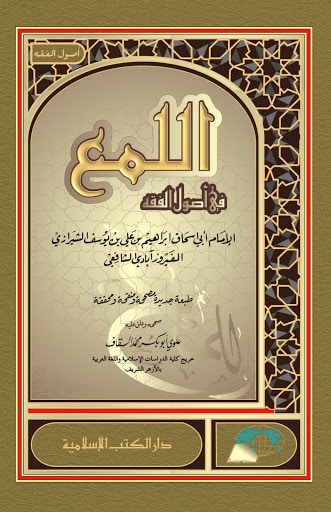Salah satu keputusan penting yang dihasilkan bahtsul masail dalam Munas NU di Banjar, 27 Pebruari-1 Maret 2019, adalah menghapus sebutan “kafir” untuk non muslim Indonesia. Ini sungguh keputusan yang luar biasa.
Dalam acara bedah buku “Menemani Minoritas”, karya Dr. A. Najib Burhani, yang lalu saya mengatakan: “Kita perlu merekonstruksi atas sejumlah terminologi keagamaan. Salah satunya adalah kata “Kafir’. Kata ini sangat krusial dalam isu-isu keagamaan dan relasi antar warga negara. Ia mengandung makna peyoratif dan diskriminatif.
Dalam konteks relasi sosial ia harus dikembalikan pada makna genuinnya. Yakni orang yang mengingkari atau menolak kebenaran, kebaikan dan keadilan. Jadi ia bukan lagi bermakna suatu identitas komunitas suatu agama selain komunitas agama dirinya.
Mengenai keyakinan biarlah menjadi urusan dan pilihan individu. Keputusan benar atau tidak diserahkan kepada Tuhan.
Saya kira menarik mengutip pandangan Asghar Ali Engeneer, intelektual dan aktivis dari India.
Ia mengatakan: “Kata “Kafir” tidak hanya bermakna ketidakpercayaan religious, tetapi menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Orang kafir adalah orang yang mengkari adanya Tuhan dan secara aktif menentang usaha-usaha pembentukan masyarakat egaliter, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan”.
Terminologi “Kafir” sebagai non muslim hanya ada dalam suatu sistem kekuasaan politik yang mendasarkan diri pada agama tertentu dan kewarganegaraannya didasarkan pada agama, bukan pada tempat/negara di mana dia dilahirkan dan secara hukum dinyatakan sebagai warga negara tersebut.
Istilah “kafir” dengan konotasi non muslim tidak relevan diterapkan dalam negara bangsa.
01.03.19