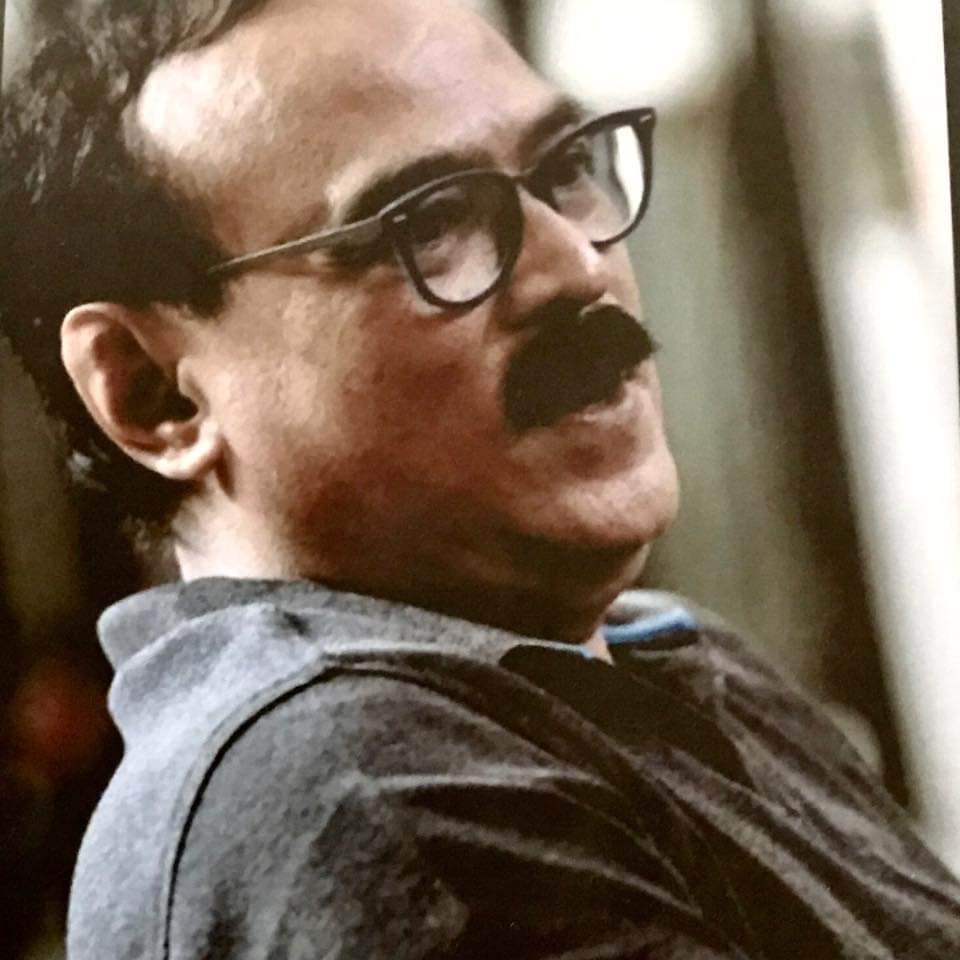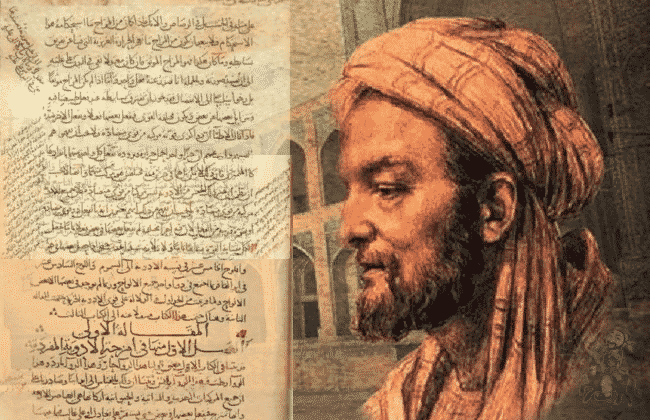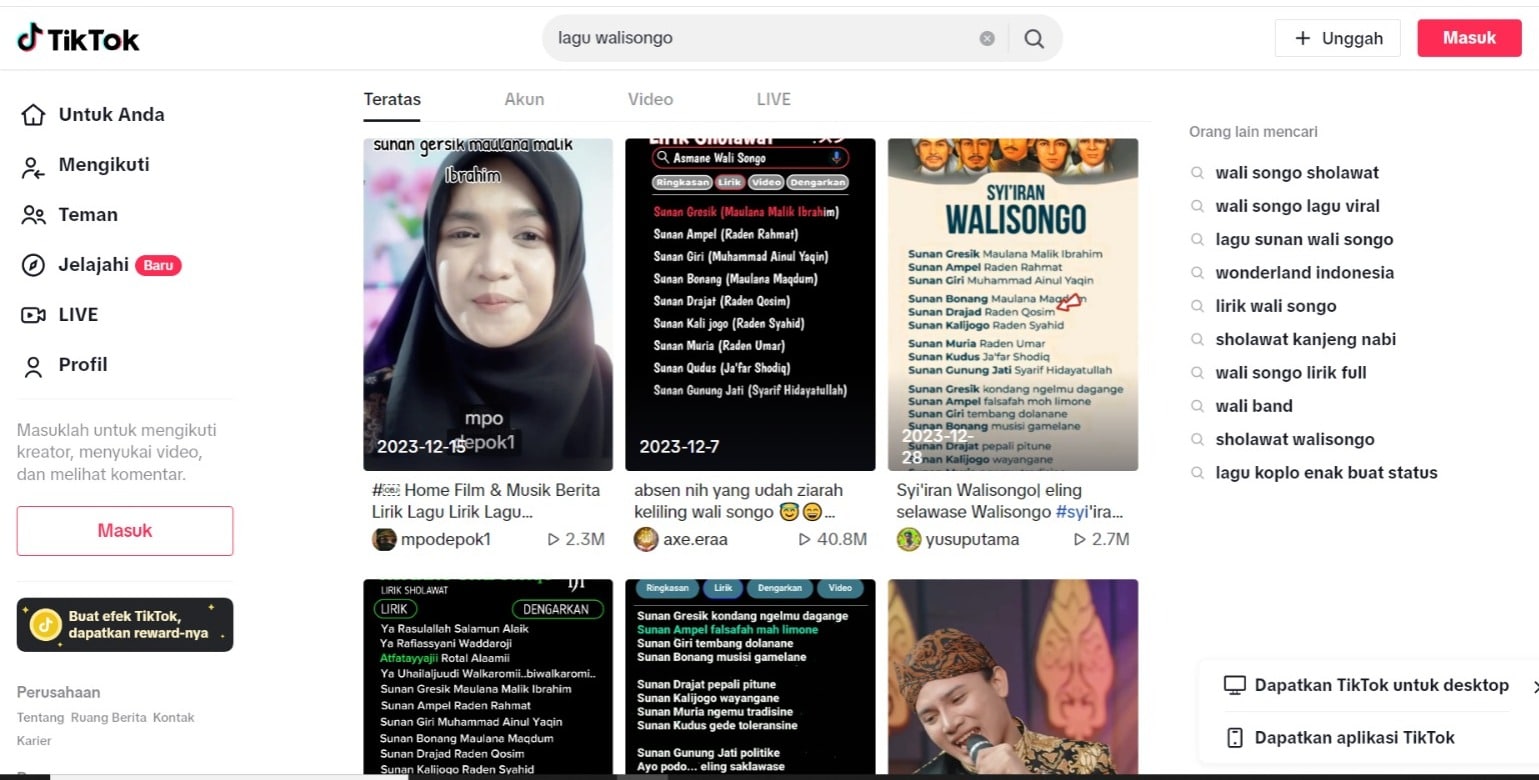Everything we do is music
—John Cage
Apakah benar klaim yang menyatakan bahwa musik adalah bahasa universal? Andaikata musik diartikan sebagai yang secara tak kritis seperti kita kenali sekarang, bebunyian yang terstruktur dan enak di kuping, maka ia tak bersifat universal.
Seumpama saya, sampai hari ini tak pernah membiarkan jenis house music –-maaf— singgah ke kuping dan merasuk ke bawah-sadar. Sebagaimana yang Hans-Georg Gadamer katakan, ketika manusia berhadapan dengan objek tertentu, ia tak pernah kosong.
Ia, manusia, sudah memiliki kerangka tertentu yang memengaruhi penilaiannya. Ia tak pernah dapat benar-benar lepas dari konteks ketika ia “dibentuk.” Persinggungan kita dengan lingkungan, bacaan-bacaan yang pernah kita lahap, dan kenangan-kenangan yang pahit barangkali, membatasi bawah sadar kita untuk menerima tanpa reserve apapun yang mampir ke kuping sehingga kita punya kuasa untuk berkata “tak”—atau bahkan meludah.
Orang mengatakan, pada akhirnya, seperti seni pada umumnya, musik pun adalah masalah selera (taste). Tapi pertanyaan saya, seandainya musik tergantung pada masalah selera, bagaimana kemudian, pertama, menjelaskan tentang mutu dari sebuah karya musik dan kategorisasi semisal musik tinggi (adiluhung) dan musik rendah? Kedua, seandainya selera memang cukup dominan dalam menakar sebuah karya musik, lantas apakah selera tersebut terberi (given) atau terbentuk (constructed)?
Tak ada contoh yang paling tepat untuk menelisik masalah selera selain kuliner. Dari kuliner kita belajar tentang bagaimana selera itu terbentuk. Sudah jamak diketahui bahwa orang Jogja terkenal dengan kulinernya yang berasa manis. Atau orang Jawa Timur yang terkenal dengan seleranya pada yang pedas. Ketika mencicipi kuliner Jogja, orang Jawa Timur umumnya akan menilainya kurang pedas dan menggigit.
Dalam etnomusikologi pun kerap kita dengar ungkapan penilaian pada karya-karya musik etnik yang seturut dengan kuliner yang berasal dari daerah setempat. Karawitan Sunda, sebagaimana kulinernya, sering dirasakan segar dan manis di kuping.
Sementara iringan musik pada kesenian Reog Ponorogo berasa pedas di kuping hingga seolah mampu menggelegakkan Jiwa. Minimal, banyak orang akan terprovokasi dan kemudian turun ke gelanggang entah sekedar untuk ngedreki (menggoda dengan tarian) para jathil (para dara penunggang kuda kepang) ataupun menggigit dan memanggul dhadhak merak (Singabarong) untuk menunjukkan keperkasaannya.
Di sinilah pada akhirnya selera bukanlah salah satu perangkat kemanusiaan yang bersifat bawaan (natural). Konteks lingkungan budaya ternyata memengaruhi dan membentuk selera seseorang. Ukuran atau pun kriteria yang bersifat universal kemudian masuk seiring dengan adanya sekolah dan pendidikan seni.
Untuk fungsi praktis proses belajar-mengajar, maka dibuatlah semacam “aturan baku” pada kesenian. Hal ini sejalan dengan proyek modernisme yang ingin segala sesuatunya terukur. Pada kancah dunia pemikiran, universalitas yang digadang-gadang oleh modernisme tumbuh seiring dengan semangat kapitalisme-imperialisme-kolonialisme dalam dunia politik.
Knowledge is power pada akhirnya menjadi sepenggal “slogan-bawah-meja” yang menguak ambisi orang-orang Barat dengan modernismenya. Proyek mooi indie dalam dunia seni rupa dan antropologi, di samping memuat aspek estetis-epistemologis belaka, ternyata juga memiliki aspek politis.
Ketika Belanda, lewat Du Chattel dan Raden Saleh, mencitrakan Indonesia sebagai sesuatu yang molek dan eksotis, maka ia telah membentuk pula identitas Indonesia, menahbiskannya sebagai “kau” (Indonesia/Timur) yang berbeda dengan “aku” (Eropa/Barat).
Dengan kata lain, Indonesia, dalam proyek mooi indie, tak pernah memiliki kuasa untuk membicarakan dirinya sendiri laiknya bayi. Senantiasa orang Belanda, atau orang-orang Jepang, yang menjadi semacam “orangtua” atau “kakak tertuanya” yang seolah tahu apa yang terbaik bagi “anak” ataupun “adiknya.” Dan kisah besar mooi indie berakhir ketika menjadi “anak” atau “adik” berarti menjadi “hamba sahaya” (budak jajahan) yang tak pernah mendapatkan keuntungan apapun kecuali permen dan manisan.
Pada dunia musik etnik, modernisme—lewat kolonialisasi Belanda di Indonesia—melenyapkan pula apa yang saya sebut sebagai “intertonikalitas” seperti halnya pelenyapan “intertekstualitas” pada kesusastraan Jawa klasik. Tonika pada istilah “intertonikalitas” tak saya maknai sebagai nada dasar pada umumnya di dunia musik teknis.
Sebagaimana “text” yang pada dasarnya memiliki arti rajutan, jalinan atau tenunan serupa serat, (lihat artikel ini), “tone” pada istilah tonika memiliki arti pula “vibrasi.”
Maka, “intertonikalitas” yang saya perkenalkan ini adalah sebentuk estetika khas musik etnik nusantara di mana dalam perspektif modernisme lazimnya akan divonis sebagai sebentuk plagiarisme.
Seumpama pada karawitan Jawa, Ladrang Mugirahayu yang diciptakan oleh K.R.T.H. Wiryodiningrat pada sekitar tahun 1940, ketika Belanda diserbu oleh pasukan Nazi Jerman, ternyata merupakan transposisi dari Ladrang Grompol yang telah tercipta terlebih dahulu dan tak jelas siapa komposernya. Perbedaannya, Ladrang Mugirahayu digarap dengan pathet manyura dan Ladrang Grompol digarap dengan pathet 9 (Catatan Pengetahuan Karawitan I, Martopangrawit, 1975).
Atau untuk lebih kontemporer, musik akapela Sujiwo Tejo, “Nadian,” yang memiliki intertonikalitas dengan lagu Impen-impenan yang merupakan lagu rakyat klasik masyarakat Banyuwangi yang kerap mengeksplorasi laras slendro barang miring. Demikian pula salah satu musiknya yang diberi tetenger “Ingsun,” yang ternyata memiliki pula intertonikalitas dengan lagu tema film The Godfather karya komposer Italia, Nino Rota.
Raison d’Etre dari intertonikalitas ini pada dasarnya menyingkapkan kemustahilan tentang adanya titik awal sekaligus titik akhir pada sebuah komposisi musik. Setiap karya musik merupakan “vibrasi” dari karya-karya lainnya. Untuk itulah kenapa John Cage secara khusus membuat sebuah komposisi musik yang terkenal dengan sematan tanda 4’33. Ia ingin meretas batas musik yang selama ini dikenal oleh banyak orang.
Cage ingin mengembalikan pengertian musik pada pengertian arkaisnya yang, celakanya, sering dinilai sebagai hal-hal yang non-musikal: lenguhan nafas, gerit sepatu, batuk para audiens, desau angin, dan sebagainya. Tapi saya kira, yang tak tersentuh oleh Cage pada komposisi 4’33-nya adalah sesesap suara purba yang tak mungkin dijumput untuk direkonfigurasi: dering keheningan. (SI)