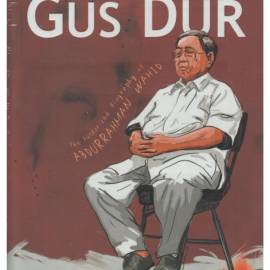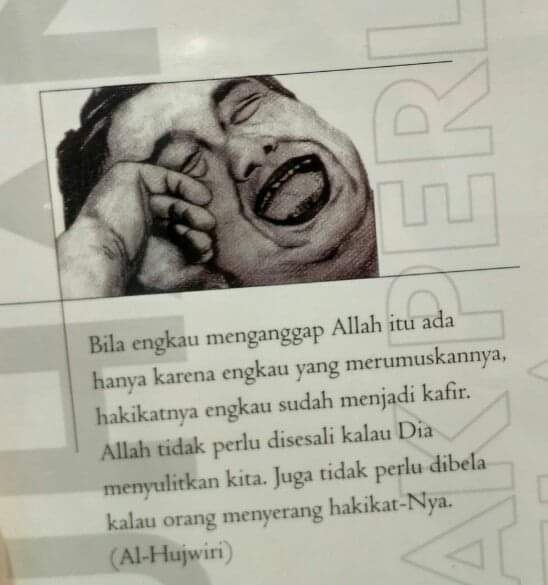Gus Dur (1973) pernah membuat esai ringkas berjudul “Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia”. Gus Dur kesulitan mengajukan teks-teks sastra modern di Indonesia bercerita kehidupan di pesantren. Ketokohan kiai dan santri masih jarang digarap sebagai pengisahan apik oleh para pengarang. Gus Dur cuma bisa memastikan pengarang “bermazhab” pesantren adalah Djamil Suherman.
Gus Dur sudah mengajukan nama tapi tak memberi penjelasan atau apresiasi atas teks-teks sastra garapan Djamil Suherman. Di alinea awal, Gus Dur menulis: “Sebagai objek sastra, pesantren boleh dikata belum memperoleh perhatian dari para sastrawan kita, padahal banyak sekali di antara mereka yang telah mengenyam kehidupan pesantren. Hanya Djamil Suherman yang pernah melakukan penggarapan di bidang ini, dalam serangkaian cerita pendek di tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan.”
Gus Dur tak berniat memanjangkan tulisan itu setelah puluhan tahun berlalu. Esai terkesan dibiarkan saja tanpa lanjutan. Kalimat-kalimat itu ditulis Gus Dur jauh sebelum kemunculan novel Perempuan Berkalung Surban (2001) dan Geni Jora (2004) garapan Abidah El Khalieqy. Gus Dur juga tak perlu membahas novel Negeri 5 Menara (2009) garapan Ahmad Fuadi.
Di halaman awal novel, Ahmad Fuadi ingin memberi kesan tentang kepesantrenan: “Novel ini terinspirasi oleh pengalaman penulis menikmati pendidikan yang mencerahkan di Pondok Modern Gontor. Semua tokoh utama terinspirasi sosok asli, beberapa lagi adalah gabungan dari beberapa karakter yang sebenarnya.” Novel itu laris di pasar. Para santri tergoda membaca dan melakukan proses semaian identitas bersama arus sastra pesantren.
Zaman telah berubah. Kalimat-kalimat lawas dari Gus Dur bisa “disanggah” dengan menambahi keterangan atau pengajuan ide lanjutan. Pada masa lalu, Gus Dur cuma bisa menemukan sekian teks sastra untuk pembuktian ada pengisahan religius. Gus Dur memilih cerpen Robohnya Surau Kami garapan AA Navis dan Di Bawah Lindungan Ka’bah garapan Hamka.
Kemunculan sekian teks sastra itu belum sampai ke pengungkapan hidup kejiwaan pesantren. Gus Dur menganggap para pengarang cenderung cuma “memantulkan nostalgia dalam lingkungan pesantren.”
Gus Dur berlaku sebagai pengamat sastra, sanggup membuat kalimat-kalimat keras dan kritis. Di akhir esai, Gus Dur berpesan: “Kalau ada juga sastrawan kita yang merasa terpanggil untuk menggarap kehidupan pesantren sebagai objek sastra nantinya, terlebih dahulu harus diyakininya persoalan-persoalan dramatis yang akan dikemukakannya. Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka.” Gaung dari kalimat-kalimat itu masih terdengar sampai sekarang meski lirih.
Barangkali Gus Dur tak membaca novel berjudul Student Soelaiman (1935) garapan Muhammad Dimjati. Novel bertokoh santri, menceritakan kehidupan di pesantren. Para santri mengaji dan menjalani keseharian untuk membentuk identitas di negeri jajahan. Santri bernama Soelaiman ingin berubah dan berilmu. Sejak di pesantren, keinginan melanjutkan pembelajaran ke Al Azhar (Mesir) selalu memicu mimpi-mimpi indah berkaitan intelektualitas, iman, kebangsaan, keluarga, dan dakwah. Tokoh santri dalam novel itu sejenis oposisi dari dominasi orang terpelajar berpendidikan corak Barat. Pengarang sengaja menggunakan sebutan “student” pada kalangan santri berbahasa Arab.
Renungan Soelaiman: “Maka terbajang-bajang dalam kalboenja endah tercantoem betapa senangnja kelak doedoek dibangkoe sekolah tinggi Al Azhar, bertjampoer gaoel dengan studenten bangsa Djawa, Sumatra, Semenandjoeng, India, Perzi, Arab, Mesir, Sjerie, Maroko, Tripoli, Afghanistan, Turki… menoentoet ‘ilmoe disana, seajoen seboeai bernaoeng dalam pandji agama Islamijah, bertjita-tjita hendak memadjoekan si’ar Islam dinegeri masing-masing bila telah mendapat idjazah loeloes peladjarannja kelak.” Renungan itu mengingatkan kita pada kebimbangan pribumi untuk bersekolah dengan capaian intelektualitas, religiositas, dan kebangsaan.
Pada masa 1930-an, kaum terpelajar cenderung berlagak Barat ketimbang bereferensi pendidikan Islam. Perbedaan misi dan capaian dua mazhab pendidikan itu sempat masuk dalam polemik di kalangan sarjana, sastrawan, guru, dan kaum pergerakan.
Pemicu polemik itu Sutan Takdir Alisjahbana, “si pemuja Barat”. Soetomo (1932) pernah mengingatkan: “Saja rasa dan saja berjakin, bahwa mengadjar dan mendidik rakjat itoe akan tertjapai sepenoeh-penoehnja, apabila kita kembali lagi ke tjara pesantren.”
Barangkali novel lawas dan langka itu tak berhasil diperoleh atau dipelajari oleh Gus Dur. Teks-teks sastra gubahan Djamil Suherman masih mungkin dilacak menjadi sumber bacaan bagi Gus Dur saat mengajukan tulisan sastra dan pesantren. Gus Dur sudah berikhtiar merintis perbincangan pesantren dalam kesusastraan Indonesia tapi tak memberi keterangan representatif. Tulisan Gus Dur tak memuat informasi cerpen atau buku dari Djamil Suherman. Kini, kita bisa mengimbuhi tanpa harus “mengganggu” esai milik Gus Dur. Pada 1963, novel Djamil Suherman berjudul Perjalanan ke Akhirat diterbitkan oleh NV Nusantara, Bukittinggi. Novel dicetak ulang di tahun 1985 oleh Penerbit Pustaka (Bandung) dengan mengikutkan keterangan pendek.
Djamil Suherman dilahirkan di Surabaya, 24 April 1924. Beliau bertumbuh di lingkungan pesantren. Sejak 1950-an, si santri itu rajin menulis cerpen, esai, puisi, dan novel. Kumpulan cerpen awal berjudul Umi Kalsum, berisi cerpen-cerpen bercap pesantren, 1963-1984. Tahun demi tahun berlalu. Djamil Suherman semakin dijuluki sebagai pengisah pesantren melalui novel Perjalanan ke Akhirat (1963) dan Pejuang-Pejuang Kalipepe (1984).
Beliau juga menerbitkan buku puisi berjudul Nafiri (1983). Pada 1985, pembaca sastra di Indonesia masih disuguhi novel Sarip Tambak-Oso: Kisah Kasih Ibu, diterbitkan Mizan, Bandung. Kita belum bisa memastikan sekian teks sastra garapan Djamil Suherman sesuai keinginan Gus Dur atau terakui pelopor sastra pesantren di Indonesia.
Pada masa 1970-an sampai sekarang, pembaca mulai menekuni teks-teks sastra bertema pesantren atau bercerita dengan latar dan persoalan-persoalan agama. Kemunculan Perempuan Berkalung Surban, Ayat-Ayat Cinta, dan Negeri 5 Menara tak bisa mengelak dari pengaruh etos sastra kesantrian Ahmad Tohari dan Zawawi Imron. Dua pengarang besar beridentitas santri itu representasi pesona kepesantrenan dalam geliat sastra di Indonesia.
Ahmad Tohari melalui esai berjudul Sastra Pesantren, Sastra Dakwah (1997) menjelaskan: “… sastra pesantren sesungguhnya sudah hadir sejak masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-12, sekaligus merupakan bagian tak terpisahkan dari sastra Indonesia.”
Kalimat itu terkesan “berani” dan bergerak jauh ke belakang ketimbang penjelasan Gus Dur. Sebutan “sastra pesantren” diakui Ahmad Tohari adalah gejala baru dalam kesusastraan modern di Indonesia pada masa 1980-an dan 1990-an. Tulisan itu muncul berbarengan keluhan para pengamat dan pembaca sastra bahwa terbitan novel-novel mutakhir di Indonesia kurang bermutu sastra. Ahmad Tohari tampak menambahi keterangan secara lugu: “… lebih sedikit lagi novel bersemangat pesantren, novel-novel menjadikan tauhid sebagai basis kreativitas.”
Seruan dan penjelasan tentang para santri menggarap sastra dan kemunculan geliat pengisahan pesantren itu perlahan terbukti. Suguhan teks-teks sastra dari para pengarang berjuluk santri terus meramaikan jagat kesusastraan Indonesia. kita mengenali mereka itu pujangga, cerpenis, dan novelis: A Mustofa Bisri (Gus Mus), Emha Ainun Nadjib, Acep Zamzam Noor, Jamal D Rahman, dan Mathori A Elwa. Kini, pengarang-pengarang baru terus bemunculan berkisah segala hal berkaitan pesantren, kebangsaan, kemanusiaan, dan kebinekaan.
Mereka adalah alumni pesantren. Para pengarang itu santri meniti jalan sastra untuk berkontribusi demi agama dan berfaedah bagi penguatan agenda-agenda kebangsaan. Zawawi Imron (1997) mengingatkan bahwa gerak sastra di kalangan santri dan pengisahan pesantren di jagat kesusastraan Indonesia mesti bermuara ke tauhid. Kesadaran tauhid itu memungkinkan santri menjadi juru bicara kesusastraan di Indonesia, sejak ratusan tahun silam sampai sekarang. Begitu.