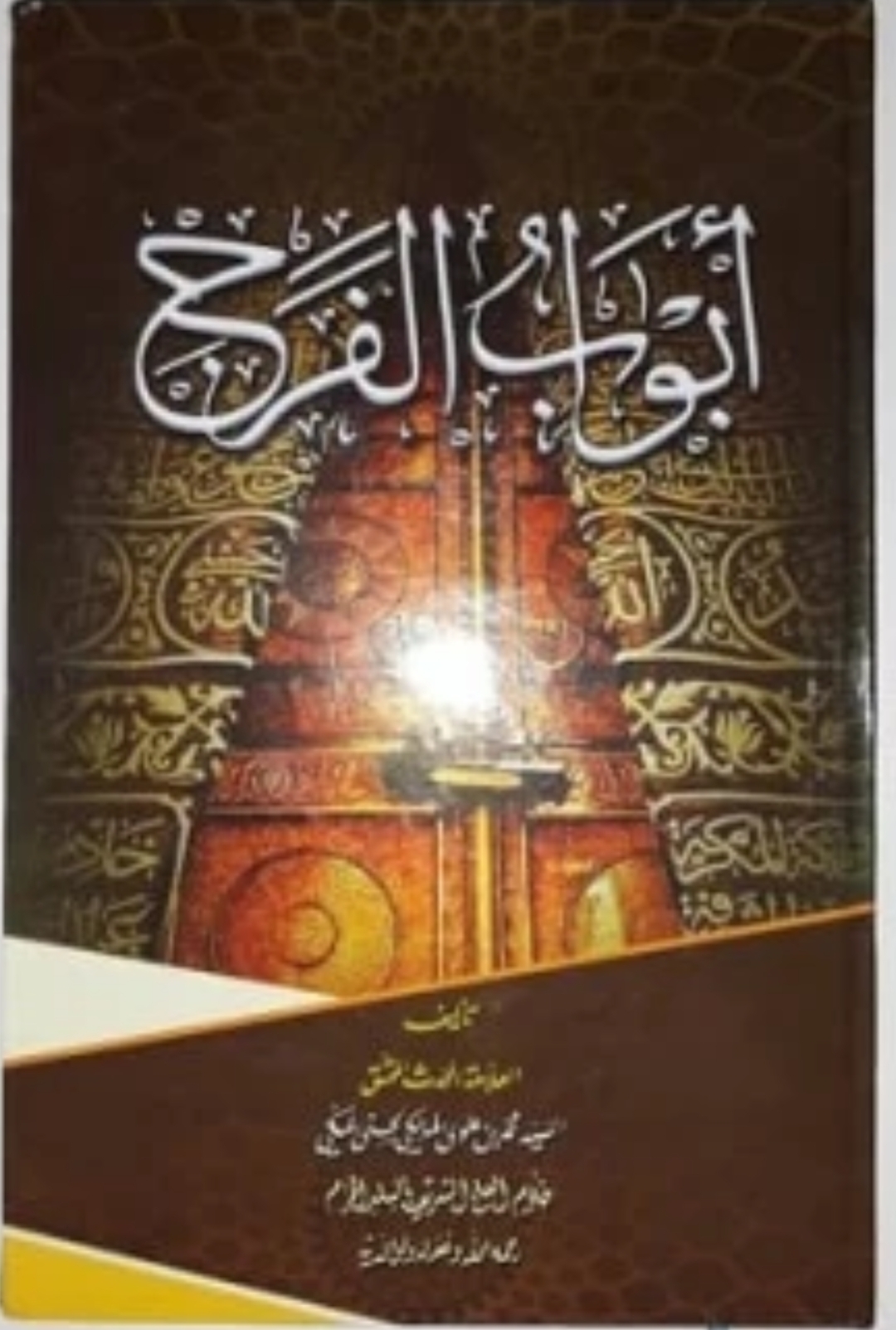Dunia pesantren dan NU di Jogja pernah punya sosok yang digemari. Ahmad Mudjab Mahalli, namanya. Lahir di Bantul 25 Agustus 1958. Masih muda, tapi sudah panggil “kiai”. Sangat istimewa.
Dulu, panggilan kiai begitu mahal. Panggilan “gus” pun tidak sepopuler sekarang, karena waktu itu, Gus Dur masih sugeng. Ya, panggilan Gus jadi memasyarakat, di laur pesantren, baru terjadi setelah Gus Dur Wafat.
Mudjab Mahalli aktif menerjemah dan menyadur, dari bahasa Arab ke bahasa kita, tentunya selain ceramah dan seabreg kegiatannya sebagai pengasuh pesantren.
Dia dijuluki Gus Dur dari Jogja, karena memiliki banyak kemiripan: tubuh gemuk, kacamata tebal, bicara ceplas-ceplos, dan tak tertinggal humor yang segar.
Saya pernah sekali sowan di rumahnya, mungkin tahun 2001, di rumahnya Pesantren al-Mahalli, Jejeran, Bantul. Di antaranya obrolannya waktu itu bagaimana agar anak-anak senang belajar ngaji (baca Al-Qur’an).
“Carilah metode-metode belajar ngajin yang membuat anak senang. Bagaimana membuat anak senang? Ya, harus dekat dengan dunianya. Misalnya kasih contoh nama-nama binatang,” begitu kira-kira Kiai Mudjab mengatakan.
“Contohnya, ’alif’ fathah ‘A’, ‘sin’ dlomah ‘su’, dibaca ‘asu’.”
“Contoh lagi, ‘ba’ fathah ‘ba’, ba kasroh ‘bi’, dibaca ‘babi’.”
Begitu Kiai Mudjab mencontohkan. Kami yang mendengarkan tertawa terbahak-bahak. “Kok ada kiai macam begini,” kataku dalam hati.
Tentu saja, contoh mengaji gaya seperti tidak akan dipraktikkan dalam sebuah metode baca Alquran, karena yang akan muncul adalah kontroversi. Yang sedang beliau katakan sebenarnya adalah mendidik, mengajar anak-anak haruslah menyenangkan, santai, dekat dengan dunianya, dan tidak kaku.
Kiai Mudjab, waktu itu, sudah resah dengan model-model pendidikan yang hanya memandang peserta didik obyek semata. Dengan metode hafalan, doktrinasi, dan hampir sama sekali tidak memandang anak sebagai anak yang punya dunianya sendiri: bermain-main. Metode begini, satu sisi, cepat hasilnya, tapi di sisi lain, mencerabut anak dari dunianya dan menumpulkan daya apresiasi dan analisis anak yang juga harus tumbuh.
Gairah Kiai Mudjab dalam menerjemahkan kitab-kitab (bahasa Arab) menjadi buku-buku (bahasa Indonesia) atau menjadi karya saduran, itu juga dilatarbelakangi agar agama mudah dipelajari. Kiai Mujab tidak setuju agama Islam ekslusif, hanya dapat dimengerti oleh kalangan pesantren yang belajar bahasa Arab saja.
“Kekayaan literatur dalam tradisi Islam harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” begitu kira-kira Kiai Mudjab bersuara.
Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, literatur Islam dalam bahasa Arab harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bukankan berabad silam, ulama pendahulu, para pendakwah sudah melakukannya? Semangat inilah yang menggerakkan Kiai Mudjab memiliki karya terjemahan dan saduran tidak kurang dari 150 judul buku.
Ada satu nama yang tidak boleh dilupakan atas kesuksesan Kiai Mudjab dalam dunia kepenulisan, yaitu Mahbub Djunaidi. Dalam sebuah kisah di fatmimie.blogspot.co.id karya pertama Kiai Mudjab yang berjudul Mutiara Hadits Qudsi diterbitkan oleh Al-Ma’arif, Bandung tahun 1980, dapat menarik perhatian penulis Mahbub Junaidi yang waktu itu sudah senior.
Mahbub menghadiahi Mudjab muda sebuah mesin ketik, sambil menuliskan surat:
“Ke mana sarjana-sarjana kita? Sekarang banyak orang membawa ijazah, melamar pekerjaan. Setiap melamar, setiap itu pula ia ditolak. Padahal ada satu perusahaan besar membutuhkan beribu-ribu karyawan dan karyanya tidak pernah ditolak. Perusahaan mana itu? Dunia tulis menulis. Siapa yang menolak karya tulis? Tidak laku sekarang, kan laku besok. Kamu masih muda, tekuni nulis.”
Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pengasuh pesantren, penceramah, dan dunia kepenulisan, Kiai Mujab tidak meninggalkan dunia sosial kemasyarakatan. Ia bukan tipe kiai yang duduk manis depan santrinya saja. Bahkan Ia aktif di Partai Kebangkitan Bangsa hingga menjadi ketua di kepengurusan tingkat provinsi. Namun ia tidak bersedia menjadi “anggota dewan”, ia memilih sebagai “King Maker”. Politisi seperti ini hari ini dapat ditemui pada sosok Gus Yusuf Tegalrejo, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.
Keterbukaan Kiai Mudjab juga terlihat dari pesantrennya. Di tengah sebagian kalangan muslim menolak program Keluarga Berencana (KB), Pesantren Al-Mahalli, dijadikan sebagai pesantren pelopor program KB. Kiai Mudjab mendirikan Pesantren al-Mahalli, tahun 1982, tidak lama setelah pulang mondok. Pesantren ini juga menjadi tempat “persembunyian” para aktivis dan demonstran yang dikejar-kejar rezim Orba, yang pada waktu itu memang sedang ganas-ganasnya.
Sayang sekali, kiai Mudjab wafat di usia muda. Ia menghembuskan nafas terakhir di bulan suci Ramadan, tahun 2003. Almarhum masuk deretan tokoh NU dan ulama pesantren yang wafat di usia yang masih produktif: Kiai Abdul Wahid Hasyim, Kiai Mahfud Shiddiq, Pak Subhan ZE, Gus Yusuf Muhammad, Gus Ishom Hadzik,dll.