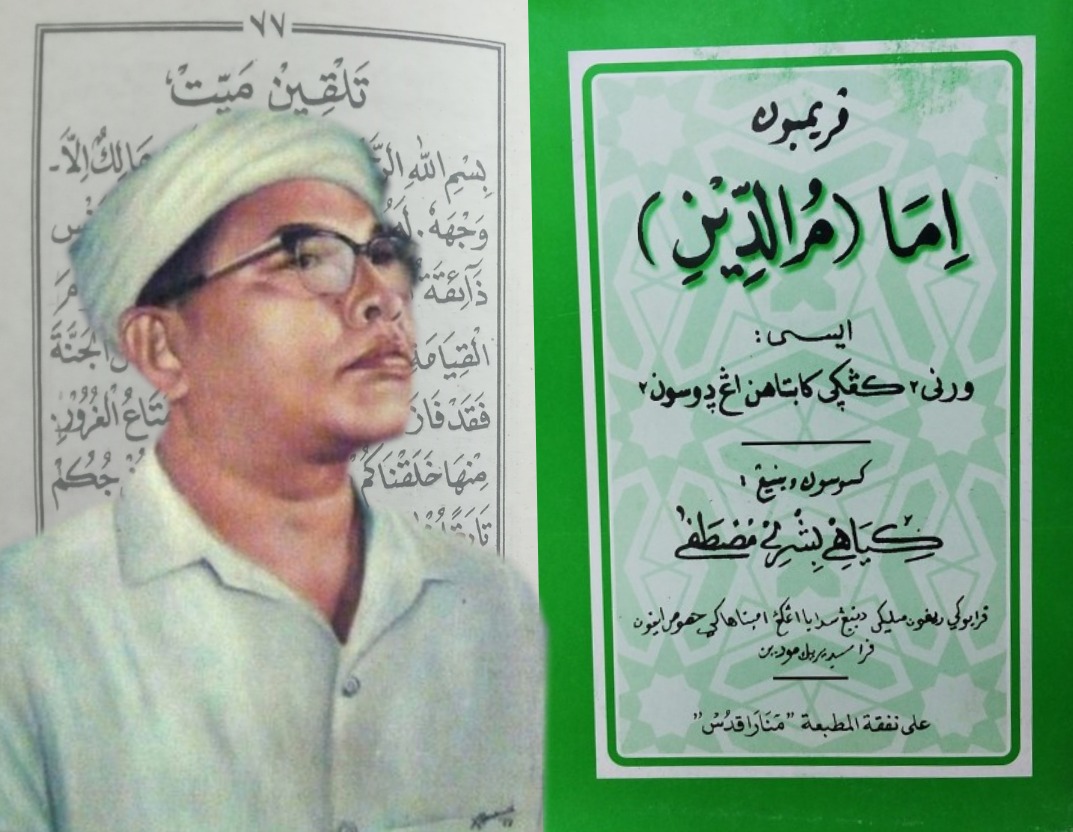Hasan al-Basri lahir di Madinah, pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan Umar bin Khattab (tahun 21 Hijriyah). Keluarganya berasal dari daerah Misan, suatu kampung di perbatasan antara Basrah dan Wasith. Ayahnya bekas budak sahabat Nabi, Zaid bin Tsabit, yang kemudian berjodoh dengan seorang istri, yang juga bekas budak di rumah Ummu Salamah (istri Rasulullah). Ketika semakin beranjak dewasa, Hasan al-Basri justu lebih tertarik untuk berburu ilmu daripada pundi-pundi harta yang menurutnya telah banyak menggelincirkan hidup manusia dari zaman ke zaman.
Dalam sepanjang sejarah kemanusiaan, perburuan akan harta dan kekuasaan, seringkali membuat manusia terlena hingga terperangkap oleh sifat tamak dan serakah. Ia lebih mengutamakan sikap hati-hati (wara’) agar tak terpedaya oleh ambisi dan nafsu-nafsu duniawi. Di usianya yang ke-14 Hasan al-Basri sudah menetap di Bashrah bersama keluarganya yang telah dimerdekakan. Dari kota Bashrah (Irak) itulah kelak menjadi rujukan bagi nama “al-Bashri” di saat ia beranjak dewasa.
Ketika etos keilmuan menurun di masa kepemimpinan Bani Umayyah, orang-orang berbondong-bondong mendatangi kediaman Hasan al-Basri untuk menuntut ilmu. Kemampuannya dalam menelaah dan menafsir teks-teks Alquran dan sunnah Rasul, membuat seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali bahkan berkomentar: “Ucapan Hasan al-Basri memiliki bobot kualitas yang mendekati ucapan Rasulullah. Fatwa yang disampaikannya berbanding lurus dengan keagungan fatwa yang diucapkan para sahabat Nabi.”
Di antara para sufi terkemuka, tidak jarang memiliki sanad yang menjurus kepada Hasan al-Basri. Berbagai cabang pemikiran dalam sejarah Islam, seperti teologi, hukum Islam, dan tasawuf berpangkal dari ajaran dan pemikirannya. Meskipun ia tidak mewariskan karya tulis (sebagaimana Ali bin Abi Thalib), namun pemikirannya yang brillian dijadikan rujukan bagi ribuan muridnya, serta menjadi sandaran bagi para penulis dan pemikir muslim hingga saat ini.
Tidak sedikit cendekiawan muslim menilai, bahwa pemikiran Hasan al-Basri memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri ketimbang para sahabat dan ulama yang meninggalkan karya tulis sekalipun. Terkait dengan corak pemikiran yang saling bersinambung di seluruh dunia, Hasan al-Basri pernah menegaskan, “Pada dasarnya, dunia ini adalah jembatan di mana kita sedang menyeberanginya, karena itu kita tak perlu bersusah-payah mendirikan bangunan jembatan yang baru.”
Dalam konteks lain, seringkali kita temukan adanya harmoni dan kesenyawaan dari satu pemikiran ke pemikiran lain, dari satu profesi dengan profesi lain, bahkan dari generasi masa lalu kepada generasi masa kini. Bandingkan ketika Profesor Nasarudin Umar berkata, “Tak ada perubahan yang sejati, kecuali jika kita berani memulainya dari diri sendiri.” Menurut penulis, ungkapan itu bukanlah sesuatu yang “aktual” jika kita merunut relevansinya dengan pernyataan Aa Gym mengenai 3M (Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan saat ini). Tapi, sesungguhnya Aa Gym juga bukanlah menyampaikan suatu fatwa baru jika kita pernah membaca hadis Nabi: “Ibda’ binafsika” (Awali dari dirimu sendiri).
Itulah yang dimaksud “jembatan” bagi Hasan al-Basri, bahwa sejatinya kita hanya memodifikasi ungkapan bijak dari generasi masa lalu yang mendahului kita. Dan bagi siapapun yang berpaling dari pernyataan bijak itu, maka boleh jadi masa lalu akan lebih aktual ketimbang masa kini. Bahkan, Rasulullah sendiri dengan ajaran Islam-nya merupakan pelengkap dan kebulatan dari ajaran-ajaran kebijaksanaan para nabi terdahulu.
Dalam hubungannya dengan iklim politik Indonesia yang semakin memanas akhir-akhir ini, selayaknya kita mencermati petuah-petuah Hasan al-Basri yang sangat krusial dan komprehensif. Terlebih bagi politisi dan penguasa korup, Hasan al-Basri sempat menyindir: “Jika orang-orang jahat dan zalim itu dibukakan hijab dan topengnya, niscaya mereka akan menyibukkan diri berdandan untuk menutupi aib dan keburukannya.”
Hasan al-Basri seringkali menggunakan kata “akal” dalam konteks pemikiran yang memengaruhi tindakan manusia. Baginya, orang berakal itu banyak bicara dalam kalbunya ketimbang ucapan melalui mulutnya. Orang berakal bisa saja menjadi ahli ilmu tapi belum tentu menjadi ahli ibadah, begitupun seorang ahli ibadah belum tentu juga menjadi ahli ilmu.
Suatu hari, seorang pemuda dengan angkuhnya mendatangi Hasan al-Basri, lalu dia menyatakan dirinya telah melakukan banyak dosa dan keburukan. Namun, pemuda itu merasa tetap eksis, hartanya bertambah, mengalami kesuksesan. Seakan Tuhan membiarkan dan tak bakal menghukumnya. “Padahal konon, setiap dosa ada balasannya? Kenapa Tuhan tidak menghukum saya, Syekh?”
Hasan al-Basri terdiam sejenak, menatap wajah sang pemuda seraya menjawab, “Wahai anak muda, sebenarnya Tuhan telah memberimu hukuman tanpa kamu sadari…”
“Siapa bilang? Hidup saya baik-baik saja, kok?”
Hasan al-Basri menghela nafasnya dengan pandangan menerawang. Ia menjelaskan secara mendetil bahwa Tuhan memberi hukuman bisa dalam bentuk apa saja. “Jika Anda tidak punya kenikmatan dalam beribadah, itu pun bagian dari hukuman Tuhan. Jika Anda tak punya gairah untuk mempelajari Alquran. Jika Anda selalu bermalas-malasan, dan tak pernah bangun malam untuk beribadah. Jika lidahmu enggan untuk bertasbih dan menyebut asma Allah. Jika Anda kehabisan waktu, serta sibuk dalam urusan wanita dan mengejar popularitas. Jika Anda lebih mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Jika ucapanmu lebih cenderung pada kebohongan, gosip dan ghibah. Semuanya itu tak lepas dari hukuman yang diberikan Tuhan kepada Anda…”
Si pemuda merasa tergetar hatinya. Selanjutnya, Hasan al-Basri menguraikan pentingnya mengoptimalkan kebaikan pada bulan-bulan utama, seperti puasa di bulan Ramadhan. Jika manusia abai dan dipalingkan dari kesempatan-kesempatan berbuat baik, maka akan dicabutlah keberkahan atas nikmat yang dimiliki, seperti kekayaan, kesuksesan, bahkan kesehatan, anak-anak dan keluarganya. “Ketahuilah, bahwa hukuman Tuhan yang paling berat, ketika kenyamanan dan kelapangan hati, sudah tak dimiliki lagi dalam hidup Anda selama ini,” ujar Hasan al-Basri.
Jadi pada prinsipnya, boleh saja pintu-pintu dunia dibukakan. Boleh juga harta dan popularitas diraih. Namun, keberkahan dan kenikmatannya dicabut, hingga apa-apa yang dimilikinya tidak membawa kebahagiaan dalam hati manusia.
Seseorang bisa juga hidup mewah dan glamor, menjadi politisi, penguasa dan memenangkan pemilu, hingga banyak orang menyanjung dan mengaguminya. Melalui ilmunya, ia dibiarkan meraih kunci untuk membuka pintu-pintu urusan duniawi. Namun, ketika Tuhan telah mengunci hati dan kalbunya, segala kemewahan dan kemegahan itu sama sekali tidak membawa kedamaian dan kebahagiaan, seperti yang diharapkannya.
Jadi pada prinsipnya, nikmat itu adalah soal rasa. Tidak ada karunia sebanyak apapun yang bisa dirasakan kenikmatannya, jika manusia tidak pandai mensyukurinya. Kemudian, Hasan al-Basri menutup pembicaraannya, “Wahai anak muda, tidak ada hukuman yang paling berat, kecuali ketika Allah telah berpaling dan meninggalkan Anda.”
Sungguh, merupakan hikmah kebijaksanaan dari petuah sang maestro sufi generasi pertama, yang pada hakikatnya tetap valid, sekaligus dapat dijadikan sandaran bagi teladan kita semua yang hidup di era milenial ini. (*)