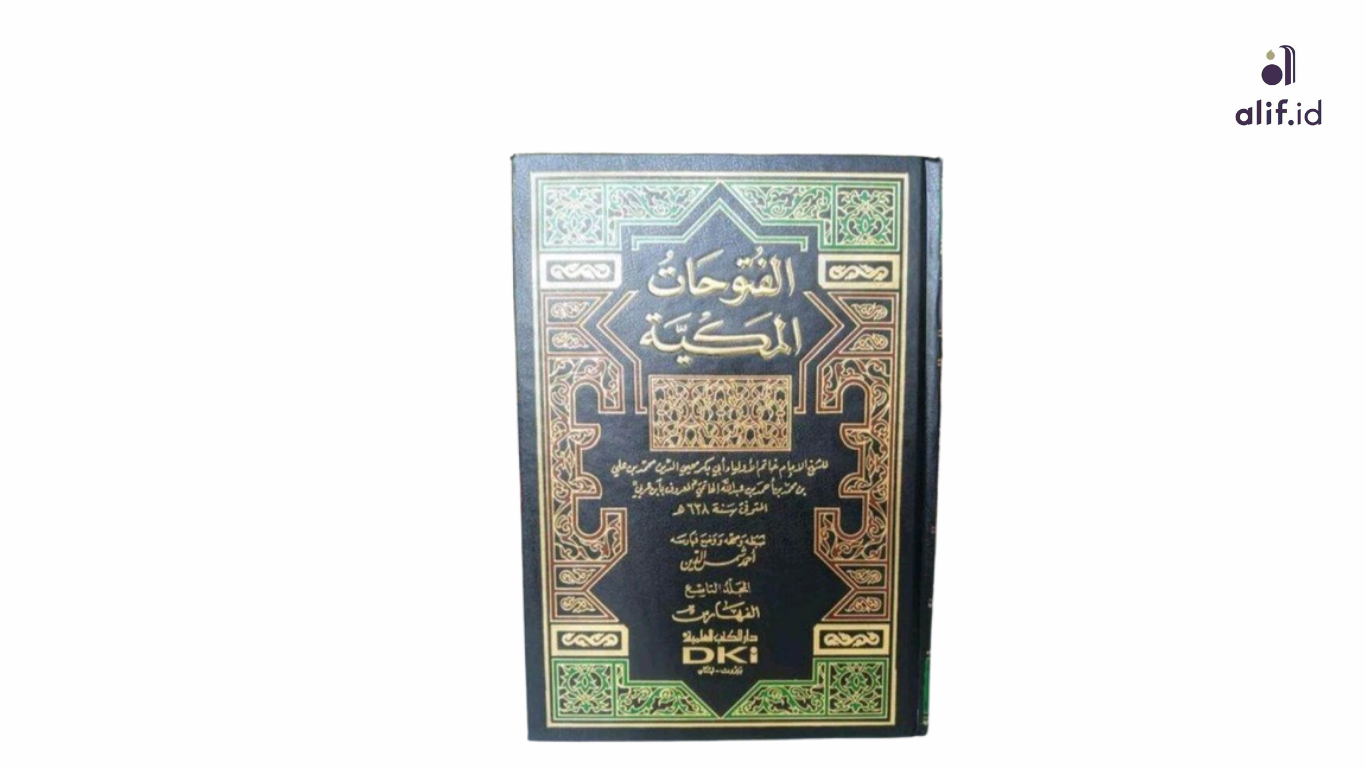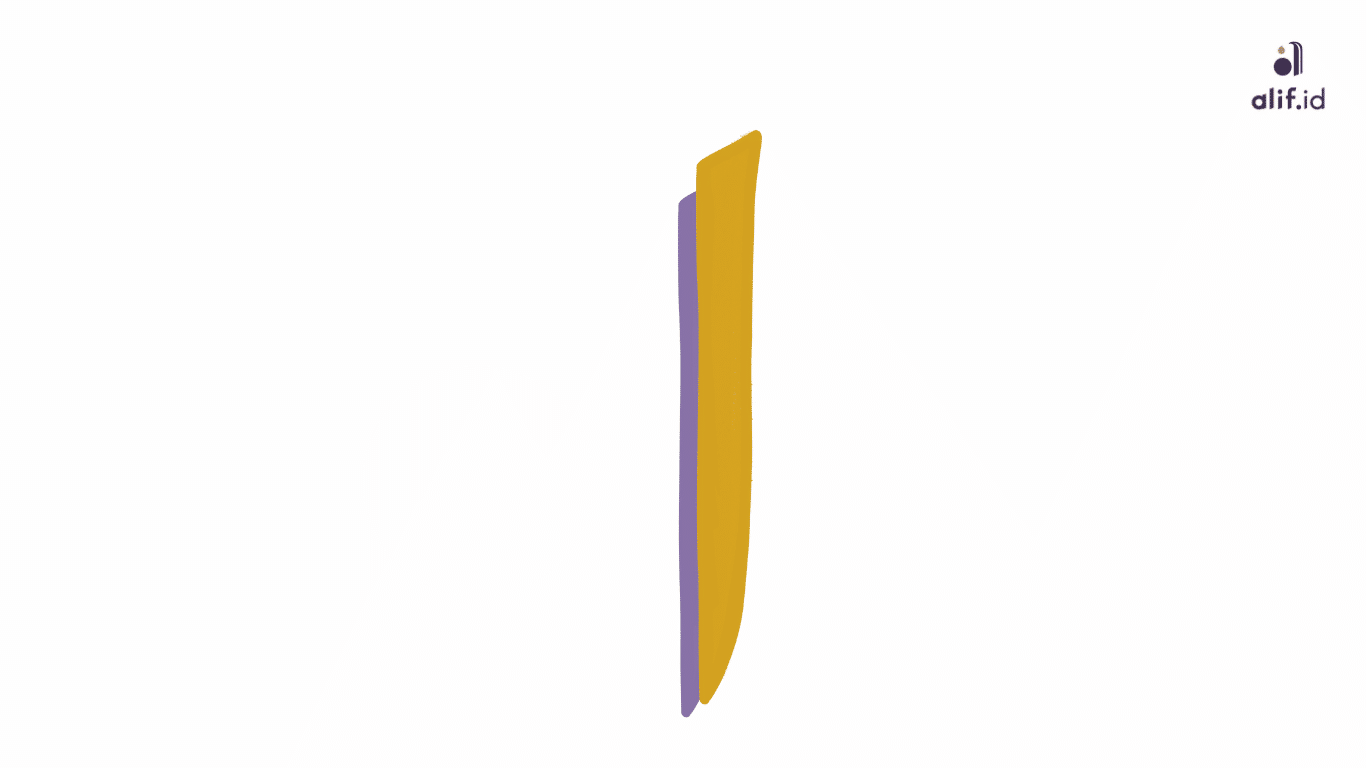Seorang seniman dan hazrat atau mistikus punya cara yang sama misalnya saat memandang langit dan seekor burung yang terbang di angkasa. Perbedaannya dengan kebanyakan orang bukan hanya terletak pada caranya memandang yang mungkin lebih dari satu cara. Tetapi juga pada apa yang ia gunakan untuk memandang, yaitu segenap jiwanya.
Menautkan antara realitas atau obyek yang dipandang dengan jiwa atau nous yang dimiliki itulah rahasia besar seorang seniman dan hazrat karyanya bisa berabad-abad tak lekang oleh waktu. Hasil karya yang demikian itu disebut oleh Ibnu Arabi sebagai creating atau af’al al-‘ala, yaitu keterlibatan nous Tuhan dalam diri manusia.
Demikian yang disampaikan Ayhesa Agheri, pemerhati Ibnu Arabi dari Pakistan semalam di PP. Kaliopak, anggitan Kiai Muhammad Jadul Maula. Maka tak mengherankan jika Ibnu Arabi misalnya menyebut arsitektur al-Hamra, istana Indah bercat merah yang terletak di sebuah bukit kecil di kota Granada, Spanyol, sebagai salah satu yang maha karya, yaitu sebuah nous Tuhan.
Yang menarik dari bunda Ayhesa yang akademisi, selain menyuguhkan teori, ia juga menceritakan pengalamannya yang amat memukau, terkait keterlibatan dirinya di dunia sosial. Pengalaman spiritual itu didapatkan saat bertahun-tahun ia merawat anak-anak yang terkena wabah diare, hingga suatu ketika ada yang meninggal dalam pelukannya.
Saat itu, ia begitu dalam ikut merasakan dan mengalami penderitaan orang lain di dalam dirinya, hingga kemudian ia merasa tiba-tiba seperti “ditarik” ke alam kasih sayang Tuhan dan mendapatkan anugrah kasyaf hingga terbuka hijab.
Ia pun tak menyangka, mampu melihat hal-hal gaib dan mendapat pengetahuan laduni, diantaranya bisa membaca kitab-kitab klasik dan mendapatkan jawaban dari pergulatan batinnya melalui kitab-kitab tasawuf, terutama dari Ibnu Arabi, serta perjumpaan mistikal dengannya.
Memang, bagi al-Ghazali, dalam Misykatul Anwar, manusia yang bisa menggabungkan makna batin dan zahir, pada mulanya dari aktifitas sosial. Karena maqam wara’ dalam mencapai hakikat, jalan itu salah satunya harus ditempuh dengan al-Iffah, yaitu jalan kasih sayang, dan turut merasakan keterperihan nasib orang lain. (33).
Kembali ke persoalan kreatifitas, menurut Ayhesa, terlibat dalam kemelut sosial, juga bagain dari kreatifitas dan dalam kreatifitas itu orang akan sampai pada tingkatannya masing-masing. Maka punya guru atau mursyid untuk menapaki jalan kreatifitas itu juga bagian dari keniscayaan.
Bagi Ibnu Arabi, soal kreatifitas ini, berdasarkan dalam Futuhatul Makiyahnya, manusia, kita ini, punya potensi untuk tidak saja bertemu dengan roh para Nabi, yang paripurna dengan sifat ru’ufnya, tapi juga sangggup menyerap semua asma dan sifat Ilahi. Karena dalam tiap diri kita mencakup realitas alam (majmu’ul alam) dan mencakup subtantif nous, yaitu mukhtasar al-Ilah, semacam miniatur Tuhan. Tetapi diri sering tak menyadari realitas dan wujud ini dikarenakan mahjub (Juz 2, 331).
Dalam doktrin Ibnu Arabi, lebih lanjut, –sebagaimana termaktub dalam Fushushul Hikam– menjadi manusia paripurna atau insan al-Kamil tidak melulu terletak pada pencapaian dimensi emosi atau spiritualnya yang tanpa wujud konkrit di dunia nyata, akan tetapi ia berjalan seiring dengan sebuah kreatifitas dan sebuah karya, sebagai bukti pemelihara dan pelestari alam. (Juz 1, 50).
Statemen Ibnu Arabi ini seperti mempertegas, bahwa jalan tarikat atau rohani, bukan melulu dzikir dan mabuk langit, tetapi juga creating; af’al al’ala.
Dengan kata lain, tanpa sebuah karya yang bermanfaat bagi umat manusia, maka jalan spiritual itu seperti omong-kosong. Kenapa demikian? Karena tiap diri, selain sebagai abdul rab; hamba Tuhan, juga abdul nazhar; hamba berpikir dan abdul af’al; hamba berbuat. (135, 136).
Jadi menjadi manusia seutuhnya—selamanya adalah menjadi manusia kreatif dari dunia yang tak bisa dibatasi ini, juga selamanya orang akan terlibat dengan tafsir yang dibangun dari pengalaman—tafsir yang tak akan bisa stabil sepanjang masa. Selamat berkarya!
Dalam Kereta Taksaka menuju Cirebon. 14 Juli 2018.