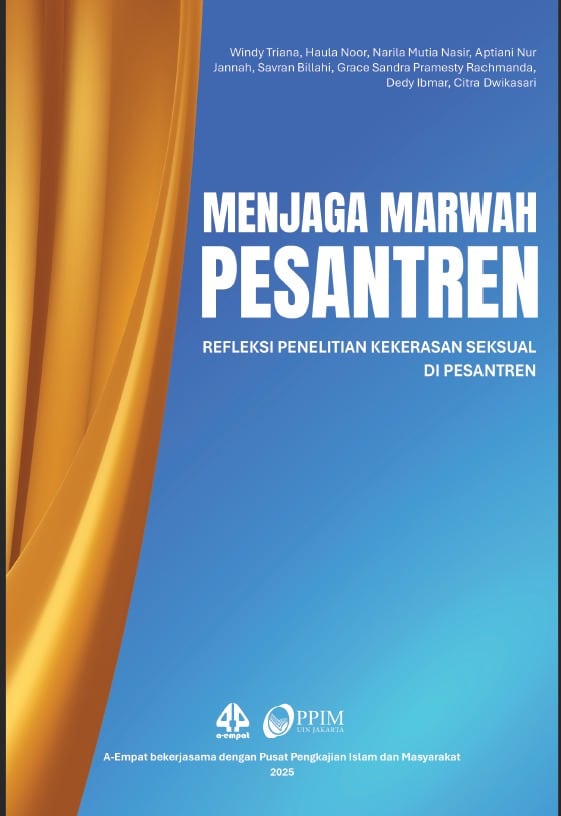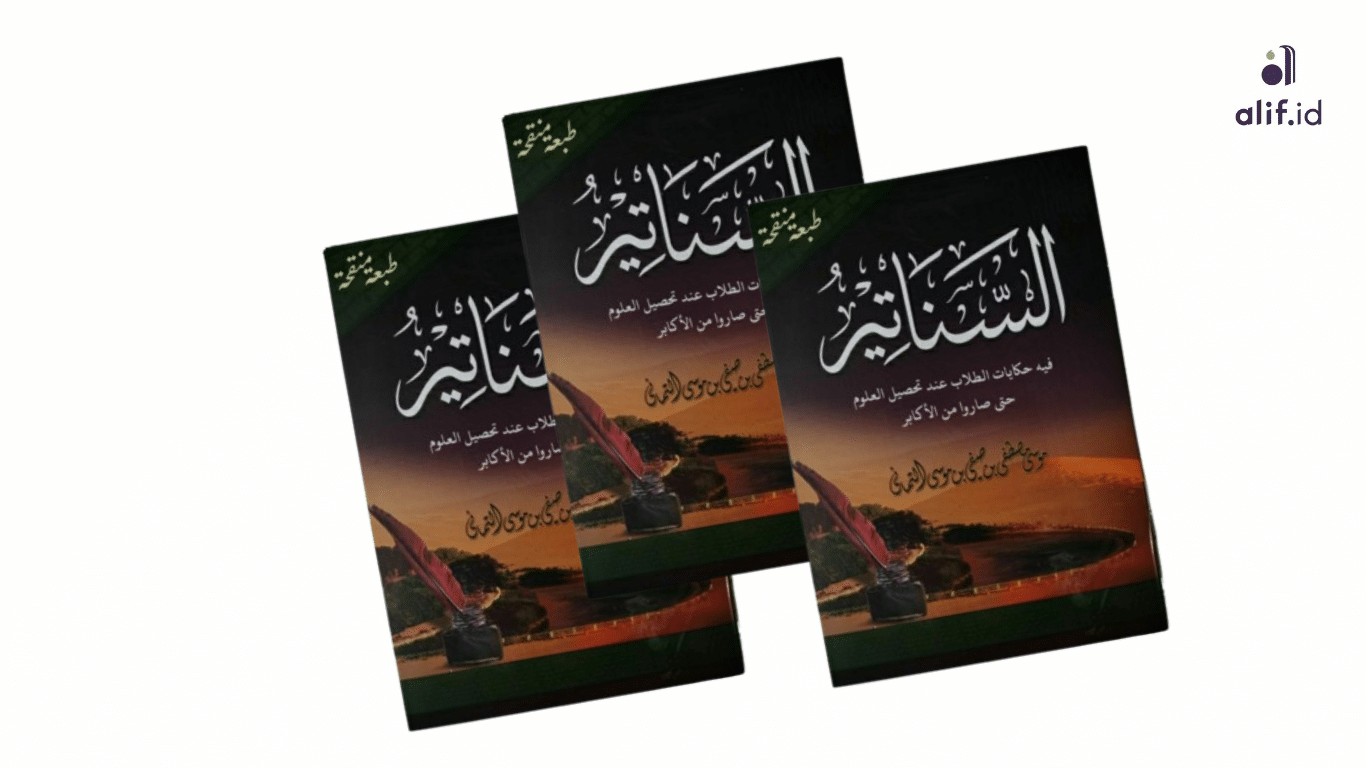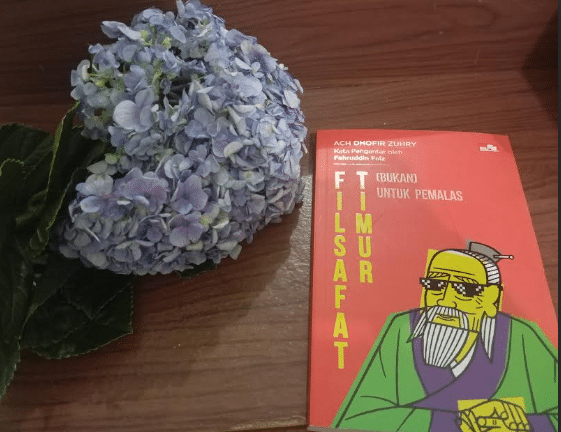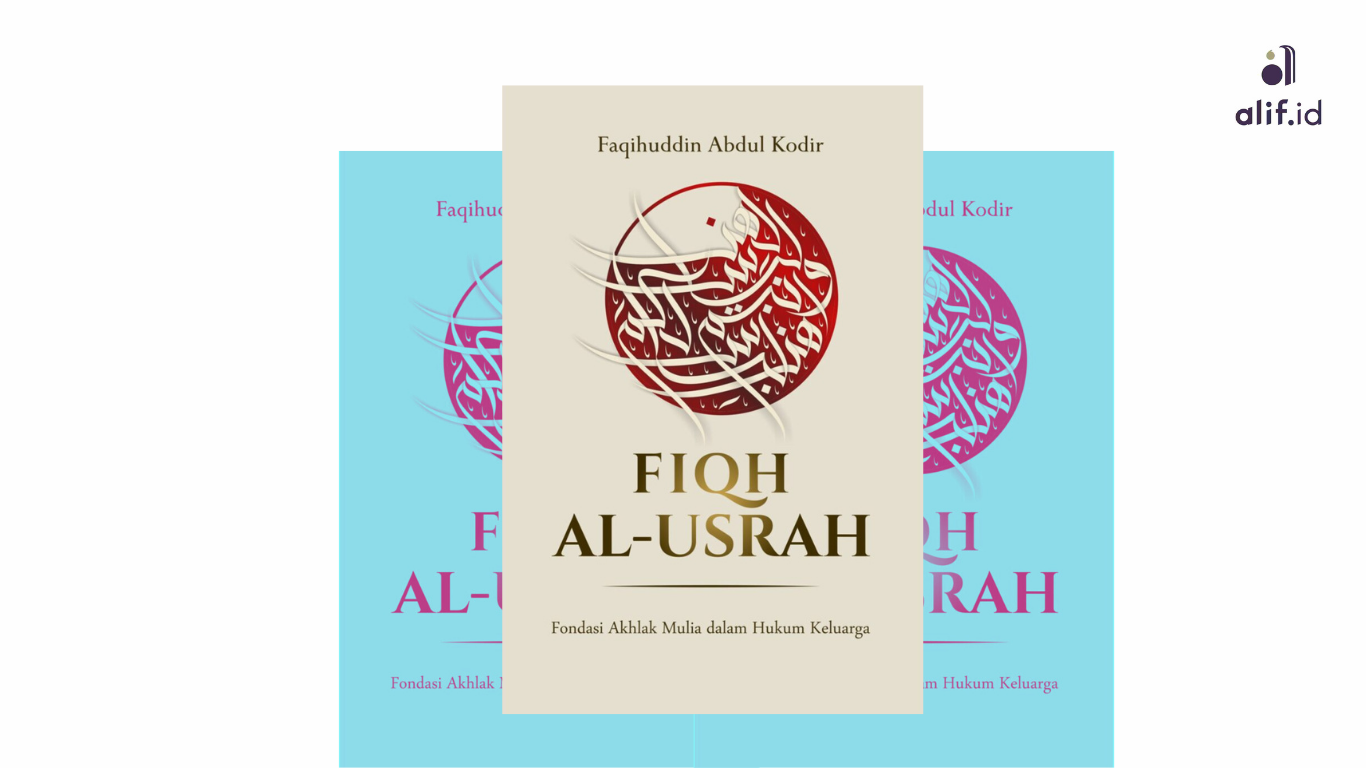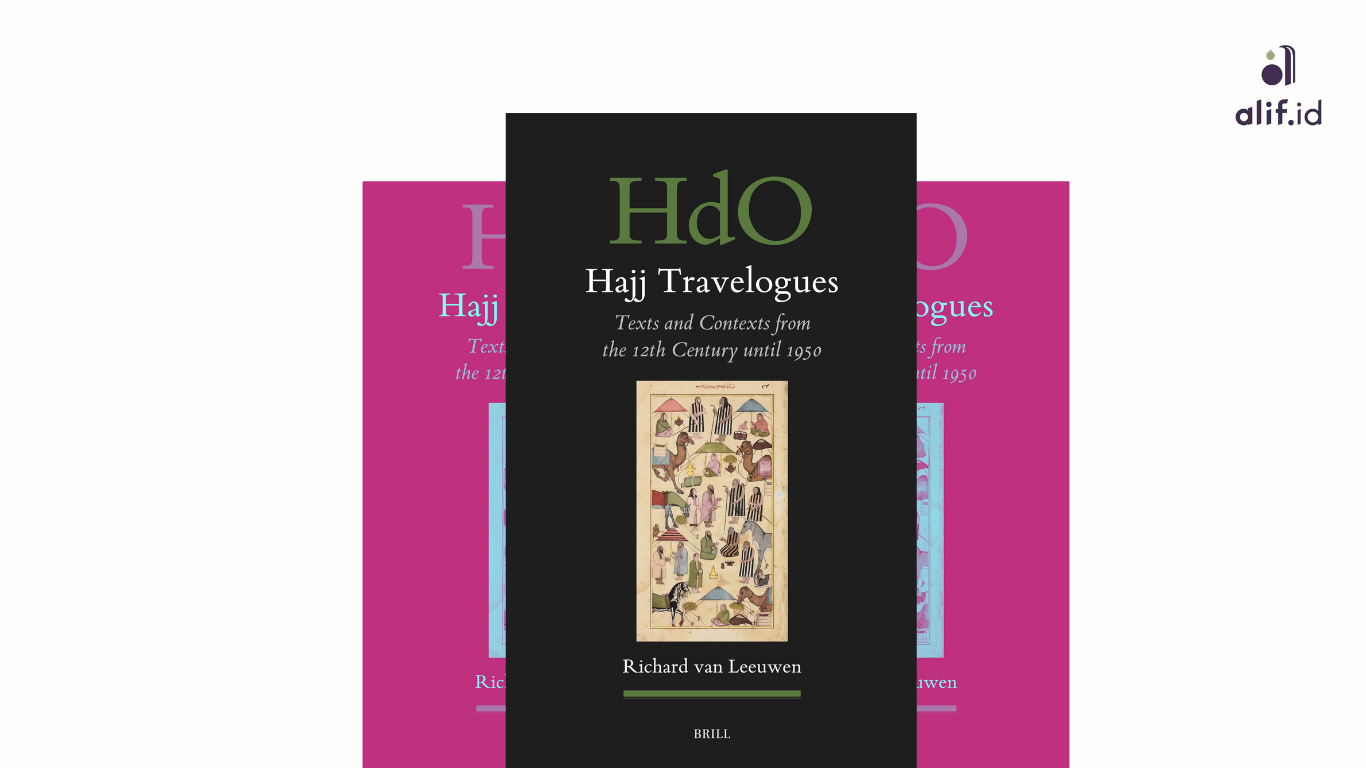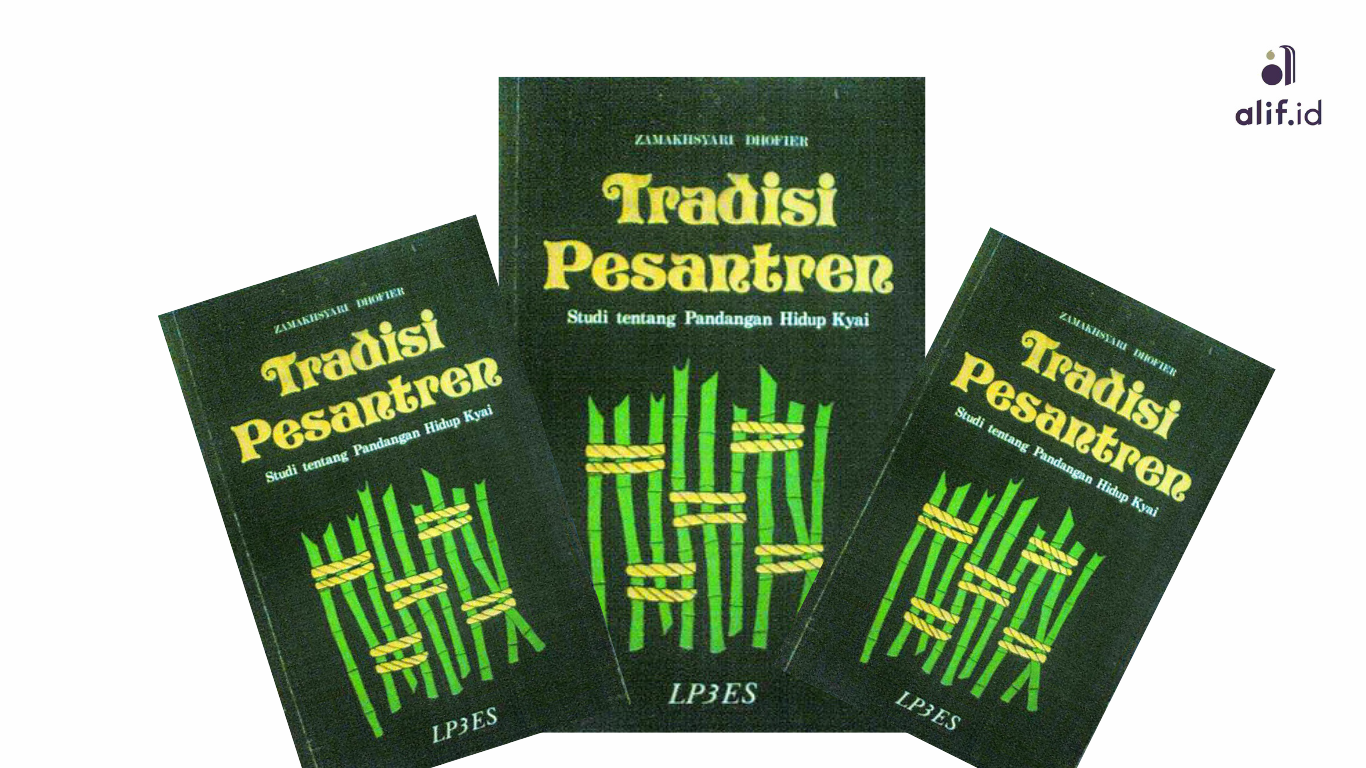
Buku “Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia”, karya Zamakhsyari Dhofier ditulis berdasarkan pengamatan antropologis pada dua pesantren berpengaruh di Indonesia, yakni Pesantren Tegalsari dan Pesantren Tebuireng dalam rentang waktu September 1977 dan September 1978. Pesantren Tegalsari terletak di Kelurahan Siderejo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Pesantren Tebuireng berada di Kelurahan Cukir, Jombang, Jawa Timur.
Zamakhsyari Dhofier mencoba mengulik peran sosial yang diambil oleh para kyai di tengah masyarakat dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Pembacaan tersebut didasari atas adanya gejala dualisme pola hidup, yakni “elitisme Islam perkotaan” dengan pola “kebersamaan hidup sederhana pedesaan”. Meskipun demikian, menurut Dhofier, kekuatan terbesar para kyai dalam struktur masyarakat Indonesia dewasa ini bukan disebabkan oleh jumlah pengikut NU yang terbesar, namun karena para kyai memiliki hubungan sosial, kultural, dan emosial yang lebih kuat dibandingkan dengan kalangan yang disebut dengan “kaum cerdik pandai”.
Hal tersebut bisa terjadi karena para kyai membangun relasi sosial yang lebih intim dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup di tengah masyarakat, memecahkan persoalan keseharian, dan menjadi teman hidup masyarakat itu sendiri. Posisi kyai tidak hanya mengambil peran dalam konteks Islam politik, tetapi lebih mempertimbangkan peran sosial di kehidupan nyata masyarakat, memberikan kemanfaatan secara kultural agar menjadi masyarakat yang berdaya dan lebih baik lagi.
Kombinasi Ulama Timur Tengah dan Cendekia Barat
Pada perkembangannya, terdapat dua poros pendidikan yang memberi warna sejarah pendidikan pesantren di Indonesia. Pertama, poros pendidikan yang terhubung dengan jaringan Timur Tengah. Meskipun terlihat adanya kuatnya kontrol Belanda atas hubungan ulama Indonesia dan ulama Timur Tengah, namun masih melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Hamzah Fansyuri, Syamsuddin as-Sumaterani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili.
Pasca dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 tokoh-tokoh seperti Syeikh Ghani Bima, Syekh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang secara leluasa belajar ke Mekah dapat merengkuh posisi penting. Generasi ini yang mendorong kebangkitan religius (religious revivalism) sebagai bagian “proto-nationalism” (kesadaran kebangsaan awal sebelum munculnya gerakan nasional formal).
Poros Timur Tengah terdidik ini memunculkan gerakan baru dalam hal melonjaknya prosentase jemaah haji dari Indonesia sebesar 50% dari seluruh jamaah haji luar negeri antara tahun 1911-1914. Peluang berhaji ini dimanfaatkan oleh jemaah haji yang masih muda untuk melanjutkan pendidikannya. Pada fase selanjutnya, semua aktivitas ini berimbas pada terjadinya proses penyebaran Islam ke daerah-daerah perdesaan di Indonesia. Dalam tiga dasarwarsa terakhir abad ke 19, terjadi lonjakan intensitas kehidupan Islam, meliputi sembahyang lima waktu, jemaah haji, dan mengenyam pendidikan.
Keterlibatan dalam jejaring Timur Tengah ini menguatkan peran ulama Indonesia dan berperan aktif dalam aspek intelektualisme dan spiritualisme di seluruh dunia Islam. Hal ini juga berpengaruh terhadap watak Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang bercorak modernisme Timur Tengah, yang disamakan dengan corak keagamaan penganut Muhammadiyah. Bertambahnya jumlah haji, guru ngaji, murid pesantren juga berdampak pada tumbuhnya kesadaran proto-nasionalisme.
Seiring dengan menguatnya pengasuh kebangunan Islam (Islamic revivalism), tumbuh juga ketertarikan muslim Indonesia terhadap pikiran-pikiran Imam Syafi’i, Abu Hasan al-Asy’ari, dan Imam Junaed. Ketiga sosok ini yang menguatkan bangunan tradisionalisme Islam Indonesia sejak tahun 1200, bukan dikarenakan terlalu banyaknya elemen non-Islam yang berasal dari kepercayaan animisme maupun Hindu Budhisme sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz.
Walhasil, ketokohan ulama Indonesia di Timur Tengah mendapatkan pengakuan, yang antara lain dengan menjadi pengajar tetap di Masjid Mekah, seperti Syekh Nawawi (Banten), Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfudz (Termas). Bahkan, pelajar dari Indonesia dianggap sempurna proses pembelajarannya ketika telah mendapatkan bimbingan langsung dari ulama kelahiran Indonesia tersebut. Tradisi pembelajaran ini kemudian berimbas sampai pada semakin berkualitasnya kiai yang pulang ke tanah air sehingga meningkatkan mutu pesantren dan menciptakan sistem baru dalam pendidikan.
Keberhasilan para ulama di Timur Tengah tersebut meresahkan pemerintahan jajahan, sehingga memerintahkan Snouck Hourgronje melakukan penelitian selama 6 bulan di Mekkah. Dari sana Hougronje memberikan saran agar memberikan perimbangan agar tercipta poros baru pendidikan, yang dapat mengimbangi pengaruh ulama yang berpendidikan Timur Tengah. Maka, menjelang abad ke-20, Belanda menginisiasi sekolah yang dikembangkan oleh Belanda guna memperluas pengaruhnya dan untuk memberikan pengaruh tandingan terhadap eksistensi pesantren yang luar biasa.
Dhofier mencatat bahwa sampai pada tahun 1890 jumlah pesantren bertambah, namun 20 tahun kemudian ketertarikan masyarakat bergeser ke arah sekolah-sekolah tipe Belanda, yang mana melahirkan golongan terdidik Indonesia sebagai oposan dari kedudukan kyai sebagai kelompok cendekiawan dan priyayi baru.
Poros ini merupakan poros kedua setelah poros jaringan Timur Tengah. Sayangnya, poros baru yang diciptakan Belanda ini justru menjadi “boomerang” bagi pemerintah kolonial Belanda. Kedudukan sebagai pemimpin baru tidak membuat mereka berpaling dan tetap mempertahankan budaya keindonesiaan mereka, meskipun tidak dapat menggantikan posisi dan peran kyai sebagai pemimpin keagamaan masyarakat. Justru, kombinasi kyai-priyayi ini yang membangun kesadaran masyarakat untuk melepaskan belenggu dari keterjajahan masyarakat Indonesia dari kolonialisme Belanda.
Genealogi Keulamaan di Indonesia
Jejaring ulama di Indonesia dengan ulama dunia tidak hanya terbatas pada Timur Tengah saja dengan cara mengadakan hubungan surat-menyurat dengan ulama yang ada di Saudi Arabia, namun juga mengundang ulama dari India dan membawa kitab-kitab tafsir, fikih dan lain-lain. Meski baru pada abad ke-19 pesantren-pesantren melahirkan ulama berkaliber internasional yang mengajar di Mekkah dan Madinah, kontribusi mereka dalam genealogi intelektual Islam di Indonesia patut dicatat, mengingat bahwa para intelektual Indonesia di Saudi Arabia berkelompok dan memilih berguru kepada ulama asal Indonesia.
Zamakhsyari Dhofier mencatat enam ulama terkemuka yang memiliki peran krusial atas perkembangan genealogi keulamaan di Indonesia pada masa berikutnya, yang antara lain,
- Syekh Ahmad Khatib Sambas (dikenal sebagai seorang pemimpin tarekat, meski juga merupakan sarjana dalam Islam yang menguasai hampir semua cabang pengetahuan Islam).
- Syekh Nawawi Banten (ulama penulis tafsir Marah Labib dan juga menulis usul fikih dan fikih.
- Syekh Abdul Karim (pemimpin tarekat Qadariyyah wan Naqsyabandiyah).
- Syekh Mahfudh at-Tarmisi (dikenal sebagai isnad—mata rantai—sah dalam transmisi intelektual pengajaran Shahih Bukhari).
- Kyai Khalil Bangkalan (dikenal sebagai ahli tata bahasa Arab, fikih, dan tasawuf)
- Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari (seorang ulama besar yang dianggap paling alim di Indonesia pada pertengahan pertama abad ke-20).
Pada masa Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dicatat sebagai momentum terbesar dalam pergerakan Islam di Indonesia. Sekira tahun 1945-1747, Hadratus Syekh memaklumatkan dua fatwa yang sangat penting berisi tentang (1) perang melawan Belanda adalah jihad dan (2) larangan kepada kaum muslimin Indonesia menggunakan kapal-kapal Belanda dalam melakukan perjalanan haji. Kampanye tersebut terbilang berhasil karena pengaruhnya yang luar biasa di kalangan pengikut Islam tradisional.
Tongkat estafet perjuangan berikutnya dilanjutkan oleh putranya, Kyai Wahid Hasyim (lahir 1914), yang bertugas mengawal kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Wahid Hasyim dididik agar menguasai dunia kepesantrenan secara menyeluruh sekaligus diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan Barat agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dengan perspektif ilmu pengetahuan modern.
Sejarah mencatat, Kyai Wahid Hasyim ditunjuk sebagai bagian dari Tim Sembilan sewaktu BPUPKI merumuskan Pembukaan UUD’45. Hal tersebut sekaligus sebagai penanda keikutsertaannya dalam membidani lahirnya NKRI.
Mengawal Paham Ahlussunnah Wal Jama’ah
“Para Kyai berpendapat, bahwa usaha untuk mengejar kemajuan tidaklah harus dilakukan dengan membuang tradisi keagamaan yang benar. Adalah sangat berbahaya menafsirkan Qur’an dan Hadis hanya menurut pendapatnya sendiri” (Dhofier: hal. 232).
Apa yang dikatakan Zamakhsyari Dhofier di atas merupakan bagian terpenting dari pembahasan dalam keseluruhan buku ini. Bahwa ekspresi paham keagamaan para Kyai, sebagai representasi otoritatif pesantren—dalam kasus buku ini adalah Pesantren Tegalsari dan Pesantren Tebuireng—mencerminkan sikap keagamaan yang ortodoks sekaligus ikhtiyat (memiliki corak kehati-hatian).
Dua karakter tersebut, dalam pembacaan saya, menjadi pondasi utama mempertahankan corak beragama ala ahlusunnah wal jama’ah. Yakni sebuah deklarasi model religiusitas yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad dan ijma’ ulama, yang tidak hanya berpegang kepada Qur’an dan Hadis.
Kegigihan dalam memegang ajaran ahlusunnah wal jama’ah model ini dilengkapi dengan berbagai anasir keilmuan yang diajarkan di lingkungan pesantren, yang bersumber dari berbagai macam kitab, mulai dari pengetahuan bahasa Arab dan hukum-hukum Islam yang dikembangkan oleh Imam Syafi’i. Distingsi ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa model ahlusunnah waljamaah yang diajarkan di pesantren berbeda tidak hanya dengan kelompok Syi’ah namun juga dengan kelompok Islam-Modern.
Secara spesifik, K.H. Bisri Musthofa dalam Risalah Ahlusunnah Wal-Jama’ah menjabarkannya sebagai paham yang berpegang teguh terhadap (1) dalam bidang hukum Islam, menganut ajaran salah satu madzhab empat, yakni madzhab Syafi’I; (2) dalam bidang tauhid, menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dan (3) dalam bidang tasawuf, bersandar pada argumen keagamaan Imam Abu al-Qosim Al-Junaid.
Perujukan terhadap pendapat ulama-ulama klasik tersebut bukan berarti menerima kejumudan berpikir, akan tetapi kebutuhan mereka dalam berkonsultasi dengan cendekiawan otoritatif yang terlebih dulu dalam memberikan pandangan keagamaannya pada masa sebelumnya. Cara ini dipandang sebagai rantai transmisi pengetahuan agama Islam paling baik dan sah untuk tetap menjaga otentisitas ajaran.
Lagipula, mempertimbangkan pendapat ulama tidak dalam artian menempatkannya sebagai kebenaran tunggal tanpa dikaji terlebih dahulu, sehingga bukan sesuatu yang taken for granted. Kompleksitas ilmu-ilmu keagamaan memerlukan sandaran berupa ulama yang otoritatif mengenai masalah-masalah syari’ah, hingga akhirnya dapat dikontekstualisasikan dengan problematika masyarakat modern.
Bahan Bacaan
Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Edisi Revi (Jakarta: LP3S, 2011)
Turmudi, Endang, ‘The Kiai in The Context of Socio-Poltical Change’, in Struggling for the Umma (ANU Press, 2006), pp. 149–73 <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbk2d.14>