
Diskusi tentang batasan aurat wanita akhir-akhir ini mengemuka. Terlebih faktanya di Indonesia dan belahan negeri lainnya, praktik berjilbab atau menutup aurat pun cukup variatif. Ada yang sangat tertutup, ada pula yang cukup longgar dan agak terbuka.
Menengok jauh ke belakang, Muktamar NU ke-8 di Jakarta pada 12 Muharram 1352 H/7Mei 1933 M sebelum Indonesia merdeka pun permasalahan ini sudah dibahas oleh Nahdlatul Ulama. Muktamar NU memutuskan, bahwa hukum keluarnya wanita bekerja dengan terbuka muka dan kedua tangannya diperselisihkan ulama. Pendapat mu’tamad menyatakan haram, sementara pendapat lain membolehkannya. Bahkan menurut mazhab Hanafi boleh dengan terbuka (telapak-pen.) kakinya bila tidak ada fitnah. (Tim LTN PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2015 M, [Surabaya, Khalista: 2019 M], cetakan kedua, ed.: A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha AM, halaman 131-132).
Nah, tulisan ini berupaya menelusuri sejauh mana khazanah mazhab Hanafi memberikan kelonggaran terhadap wanita muslimah dalam urusan menutup auratnya.
Prinsip Utama Mazhab Hanafi
Dalam perspektif mazhab Hanafi, prinsip utama dari masalah aurat wanita adalah wanita itu sendiri merupakan aurat yang harus ditutup rapat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena perempuan perlu membukanya dalam muamalah sosial kesehariannya. Berpijak prinsip asal ini maka telapak kaki pun tidak boleh ditampakkan dan dilihat oleh laki-laki non mahram. Dalam hal ini pakar fikih Hanafi Muhammad bin Husain bin Ali at-Thuri al-Qadiri (wafat setelah 1138 H/1726 M) menjelaskan:
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ. إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُمَا عُضْوَانِ. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ لِلْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَجَانِبِ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ إِبْدَاءِ الْوَجْهِ لِتُعْرَفَ فَتُطَالَبَ بِالثَّمَنِ وَيُرَدَّ عَلَيْهَا بِالْعَيْب. وَلَا بُدَّ مِنْ إِبْدَاءِ الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَدَمَ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ.
“Hukum asal dalam hal melihat wanita adalah bahwa wanita itu sendiri adalah aurat yang harus ditutup, berdasarkan sabda Nabi SAW: ‘Wanita adalah aurat yang tertutup’. Hal ini mengecualikan apa yang dikecualikan oleh syariat, yaitu dua bagian tubuh wanita. Sebab wanita harus keluar untuk muamalah kesehariannya dan bertemu dengan laki-laki ajnabi atau yang bukan mahramnya, maka ia harus menampakkan wajahnya agar dikenali sehingga dalam jual beli ia dapat dimintai uang pembayaran dan didikembalikannya barang dagangan kepadanya ketika ada kerusakan.
Demikian pula ia harus membuka telapak tangannya untuk mengambil dan memberikan barang kepada orang lain. Ketentuan ini berkonsekuensi pada hukum lainnya yaitu bahwa telapak kaki wanita tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. (Muhammad bin Husain bin Ali at-Thuri al-Qadiri, Takmilah al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq, [Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 1418 H/1998 M], cetakan pertama, tahqiq: Zakariyya ‘Umairat, juz VIII, halaman 351-352).
Qaul al-Ashah Mazhab Hanafi: Telapak Kaki Wanita Bukan Aurat
Namun demikian, dalam salah satu riwayat—yang kemudian menjadi qaul al-ashah dalam mazhab—Abu Hanifah menyatakan bahwa kedua telapak kaki wanita boleh dilihat oleh laki-laki non mahram. Kenapa demikian? Sebab terkadang wanita perlu membuka telapak kakinya ketika berjalan telanjang kaki atau hanya memakai sandal. Sebab, tidak setiap waktu perempuan dapat menemukan khuff (semacam sepatu) yang dapat menutup kedua telapak kakinya secara rapat.
Selain itu, syahwat laki-laki saat melihat telapak kaki perempuan tidak sebesar syahwat melihat wajahnya. Karenanya, ketika wajah wanita jelas-jelas tidak dinilai sebagai aurat padahal dapat mengundang syahwat yang lebih besar bagi laki-laki yang memandangnya, maka telapak kaki wanita lebih utama untuk dianggap sebagai bukan auratnya. Dalam konteks ini pernyataan pakar fikih Hanafi asal Kota Margilan Uzbekistan Burhanuddin Abu al-Hasan Ali bin Abu Bakar al-Farghani al- Marghinani (530-593 H/1135-1197 M), yang kemudian dijelaskan oleh pakar fikih asal Kota Aleppo Suriah, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini (762-855 H/1361-1451 M), menegaskan:
(وَيُرْوَى) الرَّاوِي هُوَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (أَنَّهَا) أَيِ الْقَدَمَ (لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ) لِأَنَّهَا تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ الْقَدَمِ إذَا مَشَتْ حَافِيَةً أَوْ مُتَنَعِّلَةً فَرُبَّمَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ، عَلَى أَنَّ الِاشْتِهَاءَ لَا يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ إلَى الْقَدَمِ كَمَا يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَجْهُ عَوْرَةً مَعَ كَثْرَةِ الِاشْتِهَاءِ فَالْقَدَمُ أَوْلَى (وَهُوَ الْأَصَحُّ) أَيْ كُوْنُ الْقَدَمِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ هُوَ الْأَصَحُّ
“Diriwayatkan, perawinya al-Hasan bin Ziyad al-Lu’lu’i (w. 204 H/819 M) dari Abu Hanifah, sungguh telapak kaki wanita bukanlah aurat. Karena seorang wanita perlu menampakkannnya ketiak berjalan dengan kaki telanjang atau memakai sandal, maka terkadang ia tidak menemukan khuff (semacam sepatu yang dapat menutup rapat kakinya). Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa syahwat lelaki saat melihat telapak kaki wanita tidak sebesar saat melihat wajahnya. Karenanya, jika wajah wanita saja jelas-jelas tidak dinilai sebagai aurat, padahal dapat mengundang syahwat yang besar bagi laki-laki yang memandangnya, maka telapak kaki wanita lebih utama untuk dianggap sebagai bukan auratnya. Dan riwayat yang menyatakan bahwa telapak kaki wanita bukan aurat adalah pendapat al-ashah atau pendapat yang lebih sahih.” (Al-Maulawi Muhammad Umar Nashir al-Islam ar-Ramfuri, al-Banayah Syarh al-Hidayah, [Beirut, Dar al-Fikr: 1411 H/1990 M], cetakan kedua, juz II, halaman 140).
Nah dari sini diketahui, bahwa dalam perspektif Fikih Hanafi telapak kaki wanita tidak dihukumi sebagai aurat sehingga laki-laki non mahram boleh melihatnya justru berangkat dari keperluan perempuan membuka telapak kakinya dalam kondisi tertentu. Ini penting diutarakan, bahwa kebolehan melihatnya justru berangkat dari keperluan dan kebolehan menampakkannya.
Abu Yusuf al-Hanafi: Lengan Tangan Wanita Boleh Dilihat Lelaki Non Mahram
Demikian pula terkait kedua dzira’ atau lengan wanita, apakah boleh dilihat? Dalam hal ini Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari (113-182 H/831-798 M), murid langsung Abu Hanifah dan ulama yang pertama kali menyebarkan mazhabnya menyatakan, bahwa lengan tangan wanita—dari ujung jari-jari hingga siku—boleh dilihat oleh ajnabi. Sebab ketika memasak, mencuci baju (dan mungkin aktifitas keseharian lainnya), ia perlu menampakkan kedua lengannya atau menyingsingkan lengan bajunya. Pakar fikih Hanafi sekaligus ahli hadits ini seperti diabadikan dalam berbagai literatur mazhab, membolehkan laki-laki melihat kedua dzira’ atau lengan tangan perempuan—dari ujung jari-jari hingga siku—:
وَذُكِرَ فِي جَامِعِ الْبَرَامِكَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى ذِرَاعَيْهَا أَيْضًا، لِأَنَّهَا فِي الْخُبْزِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ ذِرَاعَيْهَا أَيْضًا
“Disebutkan dalam Jami’ al-Baramikah, diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa laki-laki juga boleh melihat kedua lengan perempuan merdeka yang bukan mahramnya. Sebab, seorang perempuan juga perlu menampakkan kedua lengannya—baca: menyingsingkan kedua lengan bajunya—saat memasak roti dan mencuci baju.” (Syamsuddin as-Sarakhsi, al-Mabsuth, [Bairut, Dar-al-Ma’rifah, tth.], juz X, halaman 153).
Keterangan senada juga dikutip dalam al-Muhith karya Ibn Mazah juz halaman 176; al-Fatawa al-Hindiyyah karya Syekh Nizamuddin Burhanpuri dkk juz V, halaman 406; dan al-Bahr ar-Raiq juz VIII halaman 352.
Catatannya, lagi-lagi kebolehan melihat kedua lengan tangan—dari ujung jari-jari hingga siku—perempuan non mahram, justru berangkat dari kebolehan perempuan itu membukanya dalam aktifitas keseharian, memasak, mencuci dan semisalnya.
Ibn Mazah al-Hanafi: Kebolehan Melihat Gigi Depan Wanita Non Mahram
Kecuali al-Bahr ar-Raiq, dua kitab yang barusan disebut: al-Muhith dan al-Fatawa al-Hindiyyah sepakat mengutip pendapat sebagian ulama hanafiyah yang membolehkan laki-laki melihat gigi depan (tsanaya) perempuan. Sebab, tentu gigi depan pasti tampak ketika berbicara dengan orang lain—baca: laki-laki non mahram—dalam berbagai hubungan muamalah sosial. Pakar fikih asal Transoxania Asia Tengah, Ibn Mazah al-Marghinani (551-616 H/1156-1219 M) menjelaskan:
قِيلَ: فَكَذَلِكَ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى ثَنَايَاهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ يَبْدُوا مِنْهَا عِنْدَ التَّحَدُّثِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمُعَامَلَاتِ
“Dikatakan, demikian pula dibolehkan melihat gigi depan perempuan merdeka. Sebab giginya tentu terlihat ketika berbicara dengan orang laki-laki non mahram dalam berbagai aktifitas muamalah.” (Burhanuddin Abu al-Ma’ali Mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz ibn Mazah al-Bukhari, al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh an-Nu’mani, [Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 1424 H/2004 M], tahqiq: Abdul Karim Sami al-Jundi, cetakan pertama, juz V, halaman 334).
Nah, dalam kasus ini lagi-lagi kebolehan melihat gigi depan perempuan justru berangkat dari kondisi di mana umumnya gigi depannya tampak ketika berbincang dengan laki-laki non mahram dalam aktivitas muamalah kesehariannya.
Al-Fatawa al-‘Alamkariyyah: Betis Wanita Boleh Dilihat Lelaki Non Mahram
Bagaimana dengan betis perempuan non mahram yang sempat menjadi perdebatan sengit di beberapa WAG (WhatsApp Group) bahtsul masail? Dalam hal ini dari ulama Hanafiyah, atau sekurang-kurangnya dalam literatur fikih Hanafi, ada pula pendapat yang membolehkan laki-laki melihat betis perempuan non mahram.
Al-Fatawa al-Hindiyyah atau yang populer disebut al-Fatawa al-‘Alamkariyyah, himpunan fatwa mazhab Hanafi yang disusun oleh 500 ulama Hanafiyah dari Asia Selatan, Irak dan Hijaz pimpinan Syekh Nizhamuddin Burhanpuri atas perintah Raja India keturunan Timurlenk, Muhammad Aurangzeb Alamgir (1027-1118 H/1619-1707 M), dijelaskan:
قِيلَ: وَكَذَلِكَ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى سَاقِهَا إذَا لم يَكُنْ النَّظَرُ عن شَهْوَةٍ
“Dikatakan: ‘Demikian pula boleh melihat betis perempuan merdeka bila melihatnya tidak berangkat dari dorongan syahwat’.” (Nizham dkk, al-Fatawa al-Hindiyyah, [Bairut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 1421 H/2000 M], cetakan pertama, tahqiq: Abdul Latif Hasan Abdurrahman, juz V, halaman 406).
Kemudian pendapat dalam al-Fatawa al-‘Alamkariyyah dimasukkan pula dalam ensiklopedi fikih kontemporer karya Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah negeri Kuwait sebagai berikut:
وَقِيل: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى السَّاقَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ.
“Dikatakan: ‘Boleh melihat betis perempuan non mahram bila melihatnya tidak berangkat dari dorongan syahwat’.” (Tim Ulama Wizarah al-Auqaf, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, [Kuwait, Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah: 1421 H/2001 M], cetakan pertama, juz XL, halaman 345).
Namun sayang, baik al-Fatawa al-‘Alamkariyyah maupun al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah tidak menyebutkan argumentasi kebolehannya secara jelas. Selain itu, sejauh pembacan penulis, belum ada literatur mazhab Hanafi yang menjelaskannya secara terang benderang.
Meski demikian, melihat beberapa permasalahan serupa, seperti kebolehan laki-laki non mahram melihat telapak kaki, lengan dari ujung jari sampai sebatas siku, dan gigi depan perempuan karena alasan keseharian sering diperlukan menampakkannya, maka penulis menduga bahwa terbukanya betis perempuan alasan serupa semestinya juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Terlebih daerah munculnya pendapat itu yaitu negeri India, punya keidentikan dengan Indonesia, dimana masyarakatnya plural, tidak seragam sebagaimana Hijaz dan sekitarnya, dan wanitanya juga tidak begitu terkurung dirumah, bahkan beraktifitas keseharian di luarnya, seperti bekerja di pasar, sawah, ladang dan semisalnya yang memang secara faktual sering diperlukan menyingsingkan pakaian bawahnya hingga terlihat sebagian betisnya.
Syarat Tidak Adanya Syahwat
Semua kebolehan melihat beberapa bagian tubuh perempuan non mahram seperti telah diuraikan di atas bukan diberlakukan secara sembarangan, tetapi harus benar-benar sepi dari syahwat. Bukan dari dorongan syahwat, bukan pula mengundang syahwat. Kebolehan melihatnya hanya berlaku bila dalam kondisi normal tanpa dorongan nafsu syahwat. Bila ia yakin atau punya dugaan kuat melihatnya akan mengundang syahwat, maka hukumnya haram.
وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ. فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ اشْتَهَى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا … وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ اشْتَهَى. لِأَنَّ أَكْبَرَ الرَّأْيِ فِيمَا لَا يُوقِفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ كَالْيَقِينِ. وَذَلِكَ فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْاِحْتِيَاطِ.
“Ini semua dalam kondisi bila melihat bagian-bagian tubuh perempuan bukan mahram tersebut sepi dari syahwat. Sehingga apabila tahu melihatnya akan menimbulkan syahwat, maka ia tidak halal melihatnya sedikitpun … Demikian pula haram bila ia mempunyai dugaan kuat bila melihatnya akan menimbulkan syahwat. Sebab status dugaan kuat dalam hal yang belum diketahui hakikatnya sepadan dengan level meyakininya. Demikianlah prinsip dalam urusan yang didasarkan pada kehati-hatian.” (Ibn Mazah al-Bukhari, al-Bahr al-Muhith, juz V, halaman 334-335).
Ketentuan fikih semacam ini selaras dengan spirit al-Quran yang memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan mengendalikan syahwatnya. Allah SWT berfirman:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. (النور: 30)
“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga farjinya dari hal-hal yang haram. Hal itu lebih baik bagi mereka. Sunggu Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kalian lakukan.” (QS. An-Nur: 30)
Demikian pula dalam ayat berikutnya Allah SWT memeritahkan wanita beriman untuk menundukkan pandangan, menjaga syahwatnya dan tidak mengumbar tubuhnya kecuali dalam kadar yang diperbolehkan oleh syariat. Allah SWT menegaskan:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: 31)
“Dan katakanlah Muhammad kepada kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya; menjaga kemaluannya; tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak dari mereka; hendaklah mereka melekatkan kerudungnya pada kerah gamisnya (sekira antara ujung kedurung dan pangkal kerah gamisnya tidak menyisakan celah yang dari situ jenjang lehernya menjadi tampak/kelihatan; dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak laki-laki mereka, anak laki-laki suami mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, wanita-wanita muslimah, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan nafsu terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kaum wanita beriman itu memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung.” (QS. An-Nur: 31)
Aplikasi Prinsip Ihyiyath atau Kehati-hatian dalam Beragama
Mungkin muncul pertanyaan, lalu apa fungsinya pendapat-pendapat ulama yang cukup longgar di atas? Tidakkah bertentangan dengan ketegasan Allah SWT dalam al-Quran di atas?
Bagi penulis, pengetahuan tentang beberapa pendapat mazhab Hanafi dalam permasalahan aurat wanita di atas dan ketegasan Allah SWT dalam al-Quran tidaklah bertentangan. Semuanya berfungsi untuk kehati-hatian kita di tengah praktik beragama yang cukup beragam di Indonesia. Sebagai orang yang sering menemui sebagian muslimah Indonesia yang belum berjilbab atau berkerudung menutup aurat secara ideal, hendaknya kita tidak langsung menyalah-nyalahkan dan bahkan memvonisnya pasti masuk neraka. Karena beberapa bagiannya memang terakomodir dalam khazanah mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah. Pun bagi pelakunya para muslimah tersebut, hendaknya juga memupuk semangat dan tekat untuk semakin meningkat dalam menutup aurat sampai taraf yang ideal atau mendekatinya.
Hal ini selaras dengan spirit qurani yang mendorong laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga nafsu syahwatinya. Bukankah yang demikian itu bagian dari upaya panjang kita dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT secara paripurna? Wallahu a’lam. (RM)












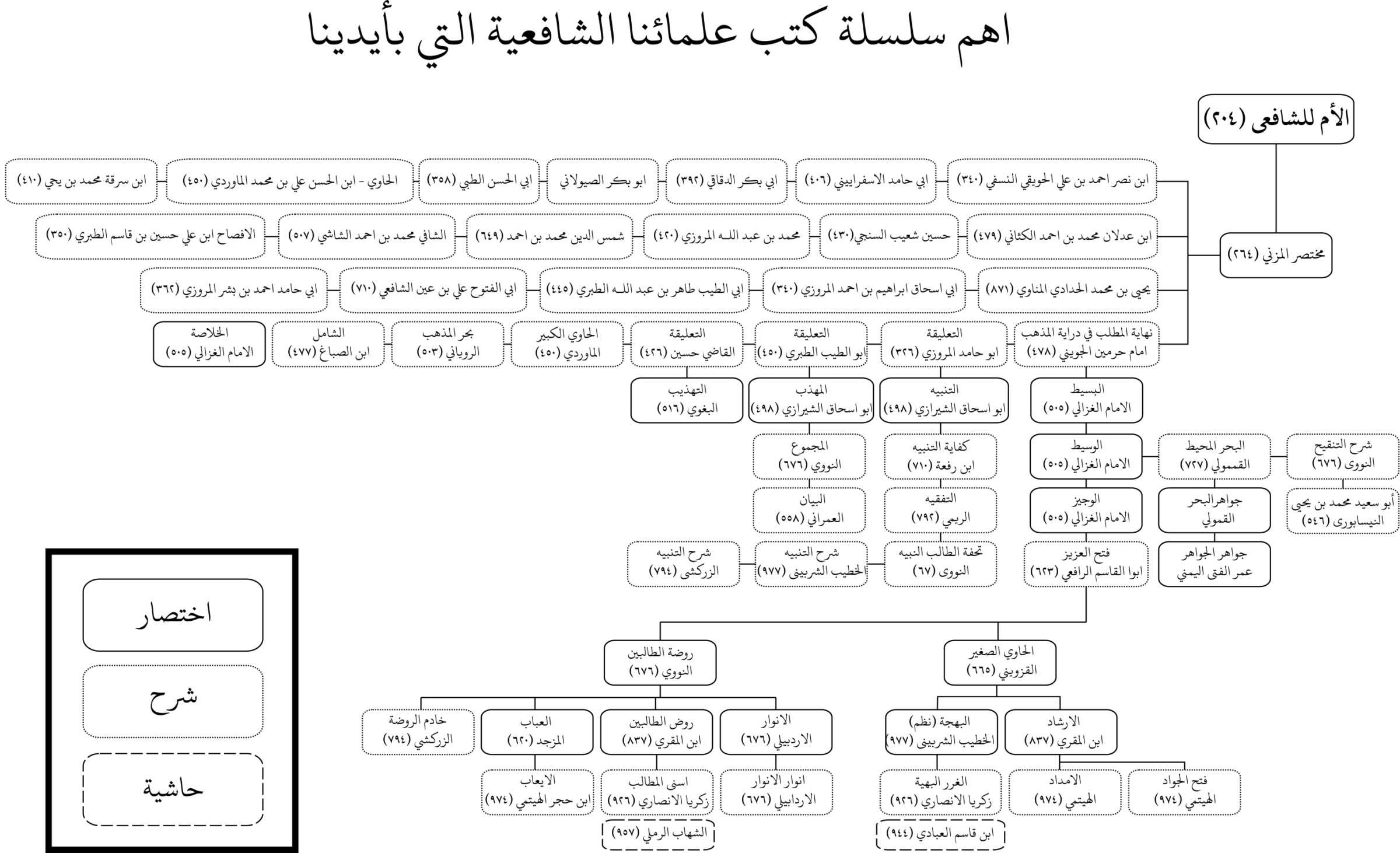








Jadi apakah memang krn kondisi dan selama itu kita tetap menjaga pandangan menjaga hawa nafsu boleh mandi bareng dg teman2 d kosan, ga berbuat yg aneh2 dan macam2