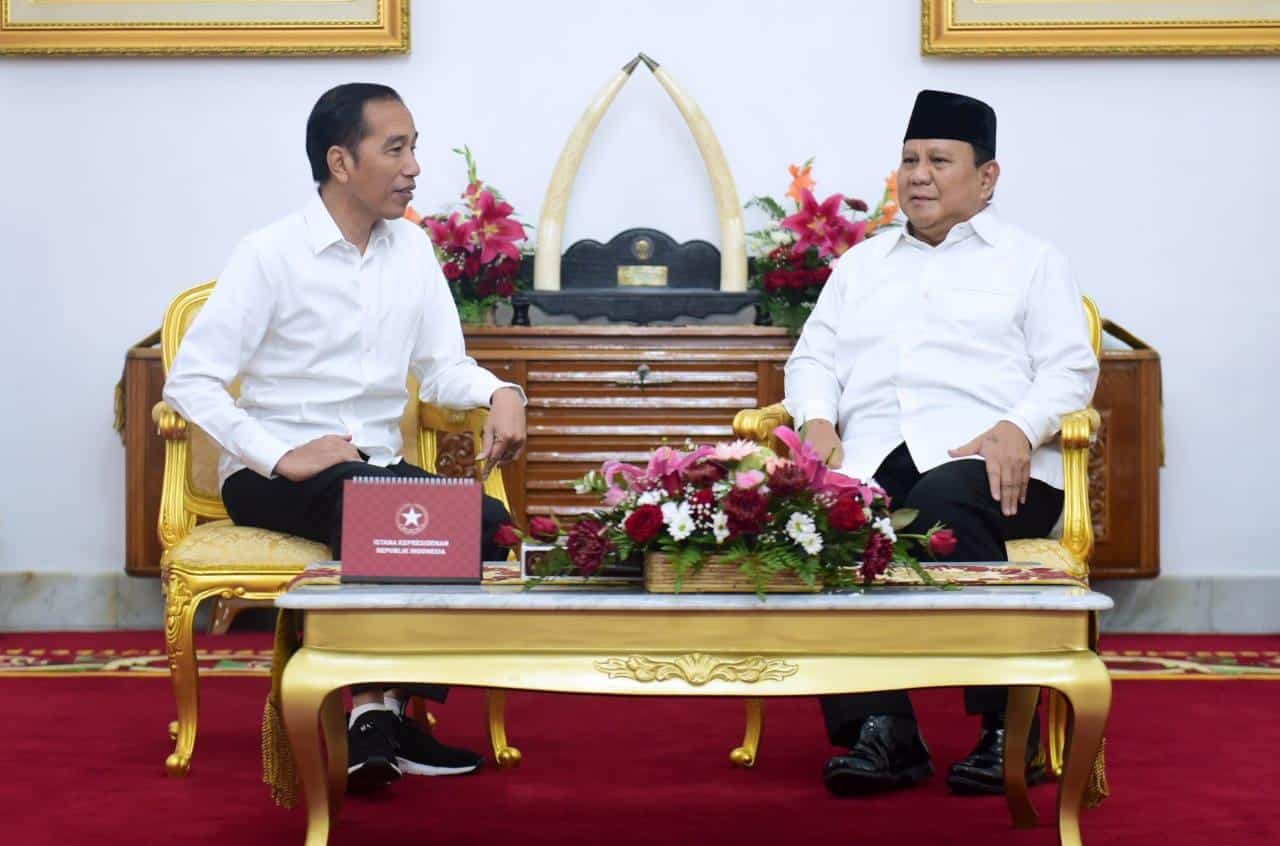
Banyak pengamat meneliti Islam di Indonesia karena tertarik perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Menarik sekali dikaji “bunga-bunga” pemikir tahun 1980an, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Jalaludin Rakhmat, maupun Kuntowijoyo berdasarkan warisan agama, budaya, dan kerohanian Nusantara. Mengapa?
Karena mereka mewakili ciri khas Islam Indonesia yang penuh warna. Penulis sendiri mulai melakukan penelitian pada tengah 1990an karena tertarik tentang pemikiran tokoh-tokoh seperti mereka.
Kata kunci memahami pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia pada saat itu seperti “Neo-modernism”, “Civil Islam”, atau “pluralism agama”, muncul dalam konteks ini. Namun, konsep-konsep seperti ini bisa menimbulkan “masalah”, sama seperti dikotomi lama, yaitu santri dan abangan diciptakan oleh Clifford Geertz berdasarkan penelitian antrpologis pada 1950an di Kediri. Pemahaman dikotomi seperti dilakukan Geertz ini bisa menyoroti penyederhanaan yang terlebihan (oversimplification) daripada keadaan sebenarnya. Meskipun di sisi lain, pada penelitian Robert W. Hefner dalam buku “Civil Islam” kita senang, karena cukup mendalam serta memperhatikan nuansa dan konteks yang renik-renik. Apalagi pada zaman ini kita menghadapi polarisasi politik mengenai agama seperti pengalaman pada pemilu 2019, khususnya pilpres antar dua duet calon. Dikotomi seperti “civil dan uncivil,” “moderat dan radikal,” “liberal dan konservatif,” maupun “pluralism dan gerakan transnasional” memperkuat narasi polarisasinya. Pemahaman akademik seperti ini gampang digantikan dengan propaganda politik dari mana pun datangnya. Itu juga bisa mengabaikan perbedaan dalam “kawan” maupun “lawan” pemikir dan gerakan sekalian.
Untuk mengatasi masalah di atas, menurut hemat penulis, ada dua pendekatan penelitian.
Pertama, kita harus mengkaji sebuah pemikiran atau gerakan lebih mendalam selepas konsep-konsep yang penulis singgung di atas.
Kedua, menganalisis peran pemikiran atau gerakan aktual dalam proses politik; misalnya proses membentuk sebuah undang-undang atau pertandingan politik seperti pemilu. Penulis mengambil jalan pertama untuk disertasi yang diselasaikan pada tahun 2002, dengan kajian pemikiran dan aktivitas generasi-generasi intelektual NU setelah Gus Dur dan mengambarkan bagaimana kelompok “Kiri Islam” muncul pada periode transisi sejak akhir Orda Baru ke awal Era Reformasi. Walaupun istilah Kiri Islam tidak lagi relevan karena distigmatisasi “hantu komunis” dimainkan sebagai alat politik, padahal yang penulis maksud dengan istilah Kiri Islam itu adalah sikap kritikal pada sejarah dan otoritas intelektual agama dan menganjurkan gerakan untuk mengakhiri ekspolitasi oleh kekuatan politik dan ekonomi (Miichi: 2001).
Baru-baru ini, penulis mengambil kedua jalan dan meneliti proses politik secara rinci. Fokus penulis termasuk isu-isu panas mengenai politik dan agama seperti pilgub DKI pada tahun 2012 (Miichi: 2013), peran majlis zikir dalam Gerakan Bela Islam atau 212 (Miichi: 2019), dan konflik Sunni-Syiah di Sampang (Miichi and Kayane: 2019). Dengan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, penulis berusaha bertemu logika mobilisasi dan bentuk jaringan (network formation). Teori-teori gerakan sosial (social movement theories) memperkuat kerangka analisis dan membuka kemungkinan studi dalam konteks lebih luas.
Pendekatan seperti ini sama untuk meneliti “islamis”. Islamism diartikan “ideologi dan gerakan yang berjuang untuk membangun kekuatan atau sistem politik Islam seperti negara agama yang menerapkan syariat dan kode moral agama di masyarakat atau komunitas Muslim” (Bayat 2013:4). Memakai istilah seperti ini bisa saja membuat dikotomi yang penulis tunjukkan di atas. Untuk menghindari penyederhanaan yang terlebihan, sekali lagi kita harus mengkaji sebuah pemikiran atau gerakan secara berhati-hati. Kita juga bisa menganalis Islamism sebagai fenomena luas tidak terbatas dari gerakan atau organisasi tertentu. Misalnya, kecenderungan Islamism tidak hanya bisa temui dalam organisasi seperti Hizbut Tahrir atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi bisa juga dalam pengikut Muhammadiyah maupun NU. Kalangan Islam tradisionalis dan komunitas tasawuf pun bisa mengaitkan dengan Islamis. Hal ini sangat jelas kalau kita observasi sikap politik gerakan seperti Front Pembela Islam (FPI) atau tokoh “tasawuf kota”, seperti almarhum Arifin Ilham. Yang penting mereka didukung oleh masyarakat yang cukup luas dengan berbagai alasan. Kita bisa mengangkat Islamism sebagai campuran budaya dan fenomena sosial-politik yang tidak bisa dibatasi dikotomi secara mudah.
Penulis sendiri pernah menganalis mulai dari Abu Bakar Baasyir, PKS sampai Aa Gym dengan kerangka Islamism dalam sebuah tulisan dan menyatakan munculnya “Islamism yang moderat” (Miichi: 2006). Walaupun PKS bisa dikategorikan partai Islamis, partai ini kadang menekankan pluralism agama dan meningkatkan peran sosial-politik perempuan. Dengan alasan ini PKS suka dipanggil “post-Islamist” baru-baru ini. Post-Islamism menekankan hak-hak asasi manusia daripada tugas agama, pluralism daripada otoritas agama tunggal, dan menikahkan Islam dengan pilihan dan kebebasan individu, menurut Asef Bayat yang promosikan istilah itu sejak awal 2000an (Bayat 2013: 8). Namun PKS biasanya ambil posisi konservatif dalam isu mengkaitkan moral seksual. Posisi ini kecendurungan ditingkatkan pada saat berkompetisi tinggi dengan partai lain.
Mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, contohnya. Pada awalnya, PKS tidak menentang RUU tersebut waktu diangkat di DPR pada tahun 2016. Baru awal 2019 ketika pemilu mendekati partai ini mulai ramai-ramai mengisukan RUU ini. Lalu pendengung media sosial (buzzer social media) memakai isu ini sebagai alat menyerang pihak incumbent dalam pilpres. Akhirnya tidak ada partai politik berani bertanggung jawab mensahkan undang-undang tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikorbankan dalam keadaan polarisasi politik pada pemilu (Miichi: 2021). Ini contoh bagaimana istilah Islamism tidak bisa diterapkan secara sedarhana. Kalau kembali ke masalah pendekatan akademik pada Islam dan politik, bagaimana sebuah aspek ideologi agama dikerahkan dalam proses pembuatan undang-undang adalah fokus utama dalam penelitian seperti ini.
Lalu penelitian seperti apa yang bisa kita kerjakan dalam keadaan dan situasi sekarang ini?
Sebetulnya, itu banyak sekali topik yang menarik untuk dikaji. Penulis sendiri tertarik perkembangan pemikiran feminis Islam. Wacana ini sudah lama berkembang sejalan dengan pemikir-pemikir pembaruan yang disebut awal tulisan ini. Lies Marcoes-Natsir, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Yuniyanti Chuzaifah, dan seterusnya sudah lama mengatasi batasan agama dan sekuler dalam feminism. Setahu penulis, narasi tasawuf kota dikembangkan oleh Jalaludin Rakhmat, Haidar Bagir, dan lain-lain juga belum dikaji secara serius. Dalam hal-hal yang mengkaitkan langsung dengan politik praktis, seperti diketahui masalah proses politik Omnibus Law, khususnya proses pembuat undang-undang sangat penting mempernahankan sistem demokrasi, tetapi masih dalam kotak hitam sampai sekarang. Proses legislasi tidak hanya DPR, tetapi termasuk pengadilan Mahkamah Konstitusi harus diselidiki secara bersungguh-sungguh.




















