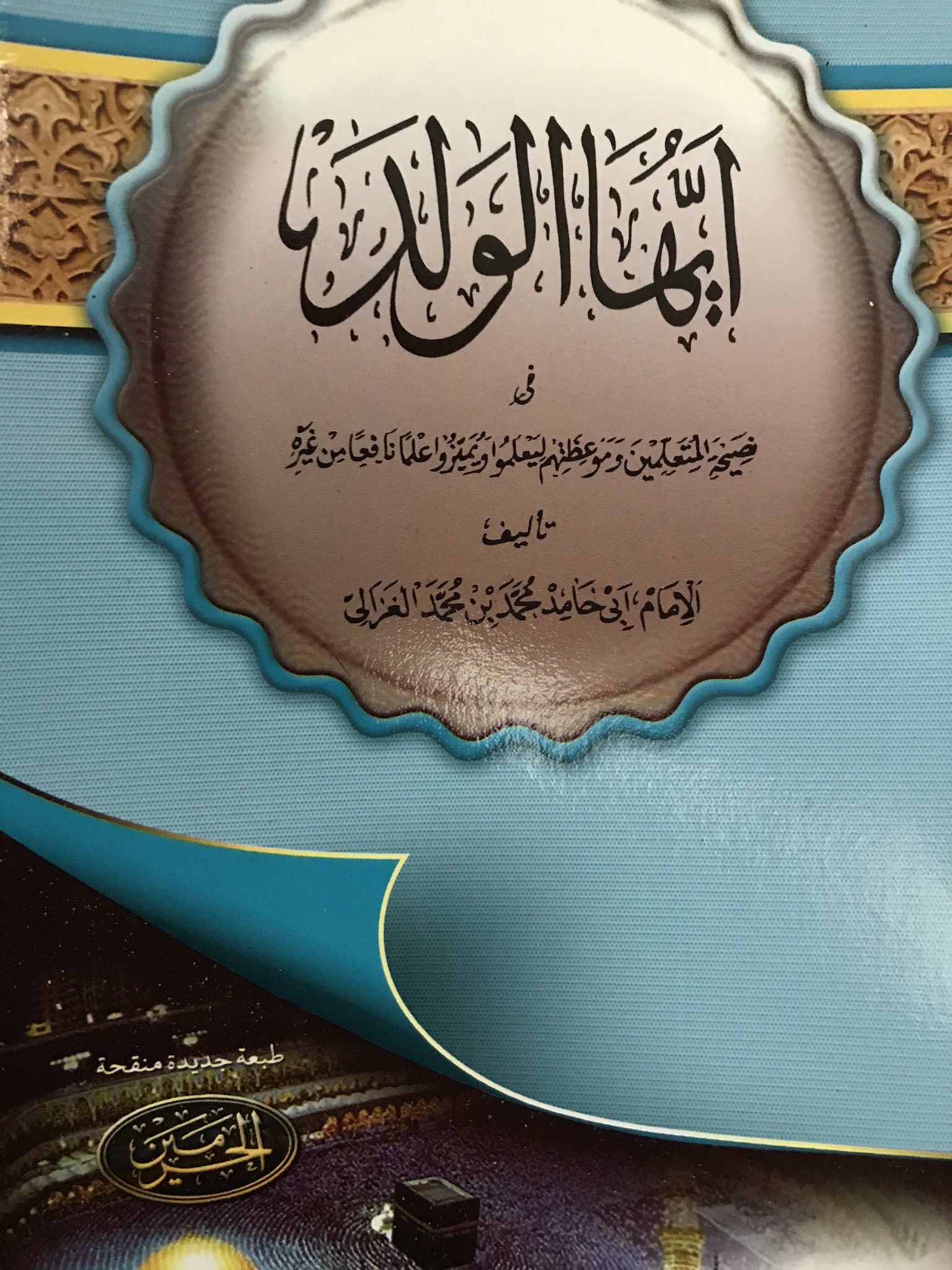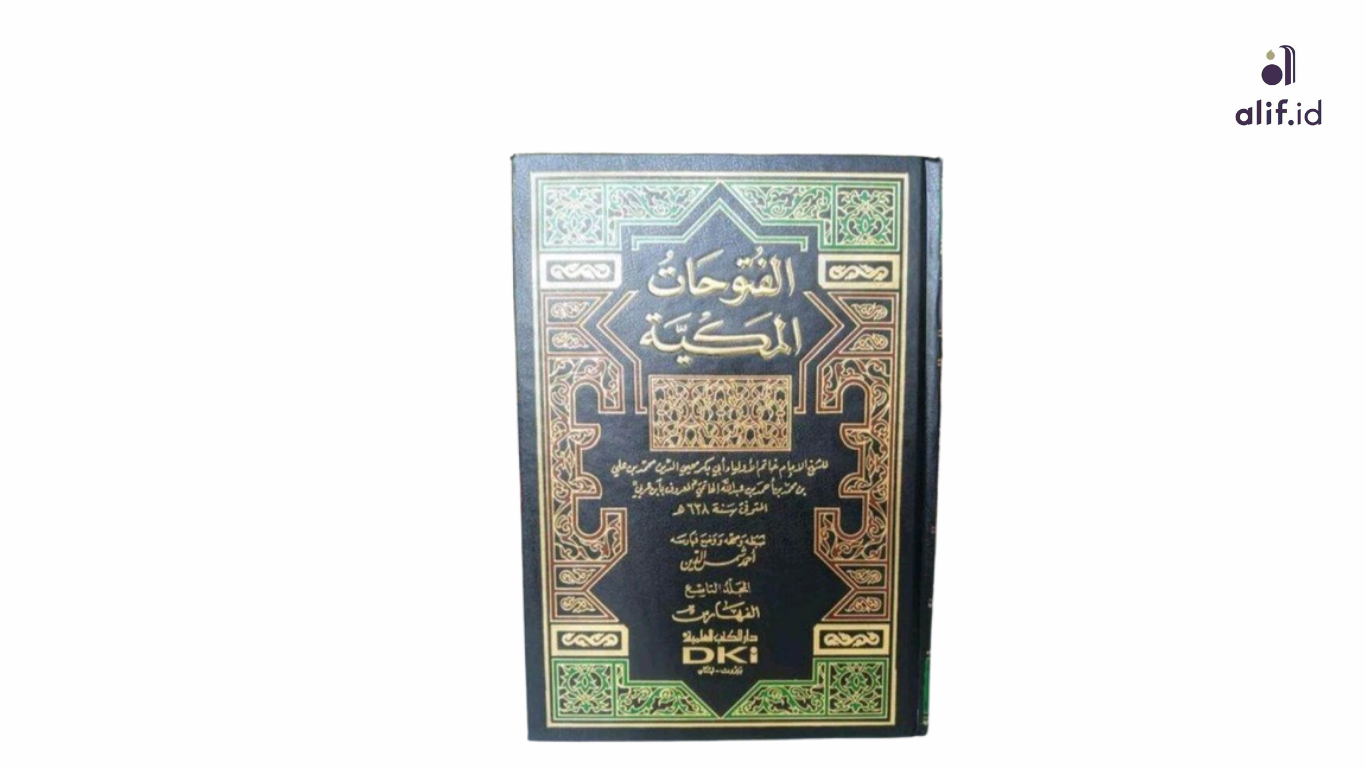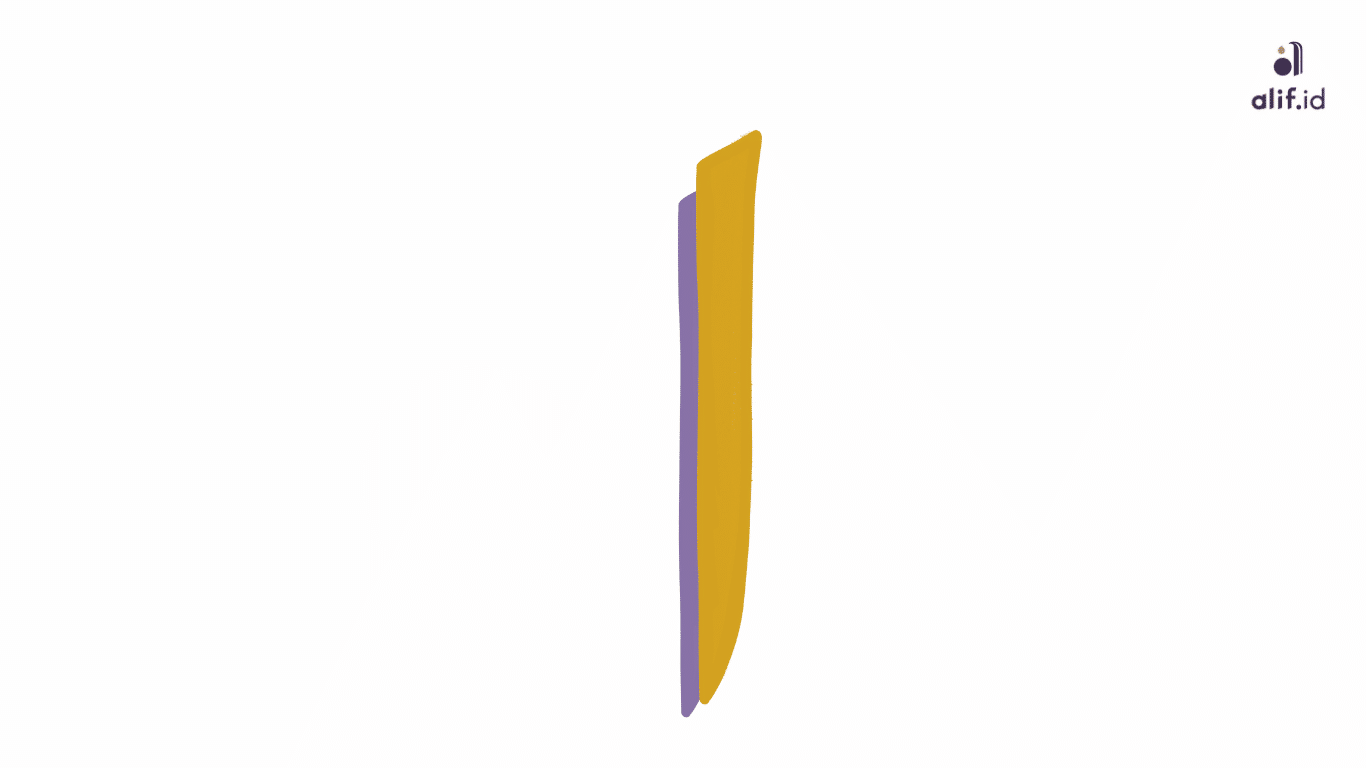“Suatu malam, aku melihat sebuah lautan besar, lautan yang terbuat dari minuman berwarna merah. Aku melihat Nabi duduk, minum di tengah-tengah kedalaman lautan ini. Ia memegang secangkir air di tangannya dan sedang meminumnya. Ketika ia melihatku, ia mengambil air dari lautan itu dengan telapak tangannya dan memberikannya kepadaku. Kemudian aku memahami bahwa Nabi berada di atas seluruh makhluk ciptaan yang meninggal karena kehausan; sementara ia tetap minum di tengah-tengah lautan kebesaran Tuhan”
Kutipan di atas merupakan salah satu penggalan terjemahan manuskrip tua tasawuf Kashful Asrar yang ditemukan di Konya, kemudian terbit di Istanbul pada tahun 1971. Ini merupakan bentuk pengalaman langsung seorang Ruzbihan Baqli (w. 606 H /1209 M)—sufi yang sezaman dengan Syaikh al-Akbar Ibnu ‘Arabi namun namanya tidak begitu masyhur di dunia Timur—dalam interaksinya terhadap dunia spiritual.
Tampak dalam narasi itu unsur-unsur sufistik yang transendental seperti pertemuan dengan Nabi atau isyarat-isyarat hakikat yang terkandung di dalamnya menunjukkan indikasi pada satu konsep yang selama ini menjadi tema utama dalam pembicaraan di kalangan para sufi yaitu kewalian.
Konsep tentang wali bagaimanapun telah memberi daya tarik yang kuat bagi para akademisi Timur maupun Barat, bahkan sekalipun telah banyak diungkap para sarjana muslim maupun non-uslim, penelusurannya sering berujung pada jalan yang rumit untuk sampai pada kesimpulan yang benar-benar komprehensif.
Tulisan ini akan mencoba melihat genealogi kewalian dalam khazanah literatur Islam klasik yang pernah menuai pro kontra sepanjang sejarah Islam untuk bercermin mengenai pentingnya posisi para wali dalam menyumbang doktrin Islam spiritual. Tentu saja bukan bermaksud menemukan solusi atas luasnya ranah mengenai kewalian, tulisan ini hanya sekian banyak dari upaya untuk memberikan titik-titik penting di mana konsep wali tetap menjadi isu utama sekalipun dunia sudah sedemikan modern.
Sepintas kita bisa melihat istilah wali banyak dirujuk pada beberapa jenis kata lain namun masih dalam satu rumpun seperti wali, walaya, wilaya, awliya.
Wali dan walaya merupakan dua kata yang maknanya terkait dengan “kedekatan (qurb) atau pertalian”. Secara umum istilah wali disepakati pengertiannya sebagai “mewakili” atau “menguasai”.
Al-Jurjani dalam kitab Ta’rifat membedakan pengertian antara walaya dan wilaya, namun keduanya masih terkait satu sama lain, yaitu keberadaan wali dan peran kosmologisnya. Lebih lanjut keberadaan yang dimaksud adalah posisi kedekatan dengan Tuhan.
Sementara definsi tentang awliya’ dalam rujukan awal bisa dilihat pada Majmu’ al-Rasail-nya Ibnu Taimiyyah yang menyebut awliya’ bermakna muraqqabun, yakni orang-orang yang dekat yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai orang-orang terpilih. Definisi Ibnu Taimiyyah ini tampaknya dekat dengan corak tasawufnya yang berorientasi pada syariat.
Gambaran sepintas tentang definisi wali di atas memang memberikan kesimpulan umum, namun dalam wacana lebih jauh, akar kewalian sesungguhnya sejalan dengan payung besar konsep kewalian yaitu sufisme, di mana realitasnya telah ada sebelum terminologinya sendiri muncul. Misalnya kehadiran para Ahlussuffah di zaman Rasulullah, atau dalam literatur Barat, Jabir ibn Hayyan yang dikenal tidak hanya sebagai seorang ahli kimia tetapi juga sufi abad ke-2 H / ke-8 M sebelum muncul terminologi sufi dan wali.
Di antara nama yang penting untuk disebutkan dalam khazanah kewalian adalah Imam al-Tirmidhi yang menurut salah seorang muridnya Abu Bakar al-Warraq merupakan murid dari Nabi Khidr yang mengunjunginya setiap hari minggu.
Imam al-Tirmidhi termasuk tokoh awal yang berbicara banyak tentang kewalian, terutama dalam karyanya Khatm al-awliya’ (Buku mengenai tanda para wali yang ditulis sekitar tahun 260 H / 873 M).
Dalam karyanya tersebut al-Tirmidhi menyebutkan bahwa kewalian terbagi dalam dua bentuk yaitu wali haqq Allah dan wali Allah Haqqan. Dua bentuk ini diibaratkan tingkatan dalam kehidupan spiritual.
Yang pertama didapatkan melalui pelaksanaan sidq, yakni pengakuan akan kebenaran dengan melaksanakan secara total tanggung jawab atas seorang hamba terhadap Tuhannya. Sementara yang kedua adalah penghambaan, dalam bahasa al-Tirmidhi “kesadaran akan kemiskinan ontologis yang radikal”.
Wali Haqq Allah termanifestasi dalam keberadaannya sebagai wali berada dalam kerangka memberi untuk menerima, sedangkan Wali Allah Haqqan adalah menghamba kepada Allah semata tanpa mengharap imbalan dan balasan.
Meski terbagi menjadi dua, bentuk kewalian ini dalam bentuk penghambaan totalnya akan menghasilkan ruang kosong di mana rahmat dan kasih sayang Allah akan segera menempatinya dan para wali akan menerima limpahan kehadiran Tuhan yang tak bisa mewujud dalam kata-kata. Mereka menjadi perwujudan Tuhan dalam diri makhluk.
Nama yang tidak begitu populer dalam memberikan kategori mengenai awliya berikutnya adalah Abu Thalib al-Makki (w. 380 H / 990).
Dalam Qut al-Qulub-nya, ia berbicara tentang “orang di tempat-tempat spiritual di anata mereka yang dekat dengan Tuhan (ahl al-maqamat min al-muqarrabin) dan membedakan tiga kategori awliya yaitu ahl al-ilm billah (orang yang mengetahui tentang Allah), ahl al-hubb (orang-orang yang Mencinta), dan ahl al-khauf (orang yang senantiasa diliputi rasa takut kepada Allah).
Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kategori tersebut, tetapi selanjutnya oleh Michel Chodkiewicz, kategori itu dianggap merujuk kepada tanda yang diberikan kepada Jesus dalam Kristen yang bisa menjelaskan masing-masing karakteristik wali tersebut.
Selanjutnya adalah Abu Nu’aym al-Isfahani (w. 430/1038) melalui karya monumentalnya Hilyat al-Awliya (Permata Para Wali). Di dalam kitab ini, ia memberikan penekanan wali akan kemisteriusan keberadaannya.
Abu Nu’aym menyatakan:
“Hamba yang dicintai Tuhan adalah yang saleh dan yang tersembunyi. Ketika mereka pergi tidak ada yang kehilangan mereka, dan ketika mereka ada, mereka tidak dipedulikan. Mereka adalah para pemberi bimbingan yang baik dan lambang dari keluasan lautan pengetahuan Tuhan”.
Abu Nu’aym tampaknya ingin memberi cetak tebal pada kenyataan bahwa seorang wali itu sesungguhnya bisa juga tidak melibatkan manifestasi spektakuler.
“Wali adalah manusia yang seringkali menghindar, berusaha untuk tidak kelihatan di dunia”.
Dari beberapa terminologi di atas, mengenai ketersembunyian para wali akan sangat panjang jika dibahas di sini, tetapi merujuk pada pembagian dalam tradisi Sunni, wali sesungguhnya terbagi menjadi dua yaitu Masyhur (terkenal) dan Mastur (tersembunyi).
Konsep wali yang sekalipun memiliki tingkatan dan kelebihan atas yang lain berdasarkan kategori-kategori, namun ia bisa kita lihat sebagai corak khas para wali dalam membentuk identitasnya yang dipilih melalui rahmat Tuhan.
Mereka bukan berada dalam bentuk hierarki atas-bawah tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Sebagaimana kita bisa melihat contoh Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Ibnu ‘Arabi dan Jalaluddin Rumi. Syekh Abdul Qadir dianugerahi gelar Sultan al-Awliya’, Ibnu ‘Arabi diberi sebutan Sultan al-Arifin, dan Rumi memperoleh julukan Sultan al-Muhibbin.