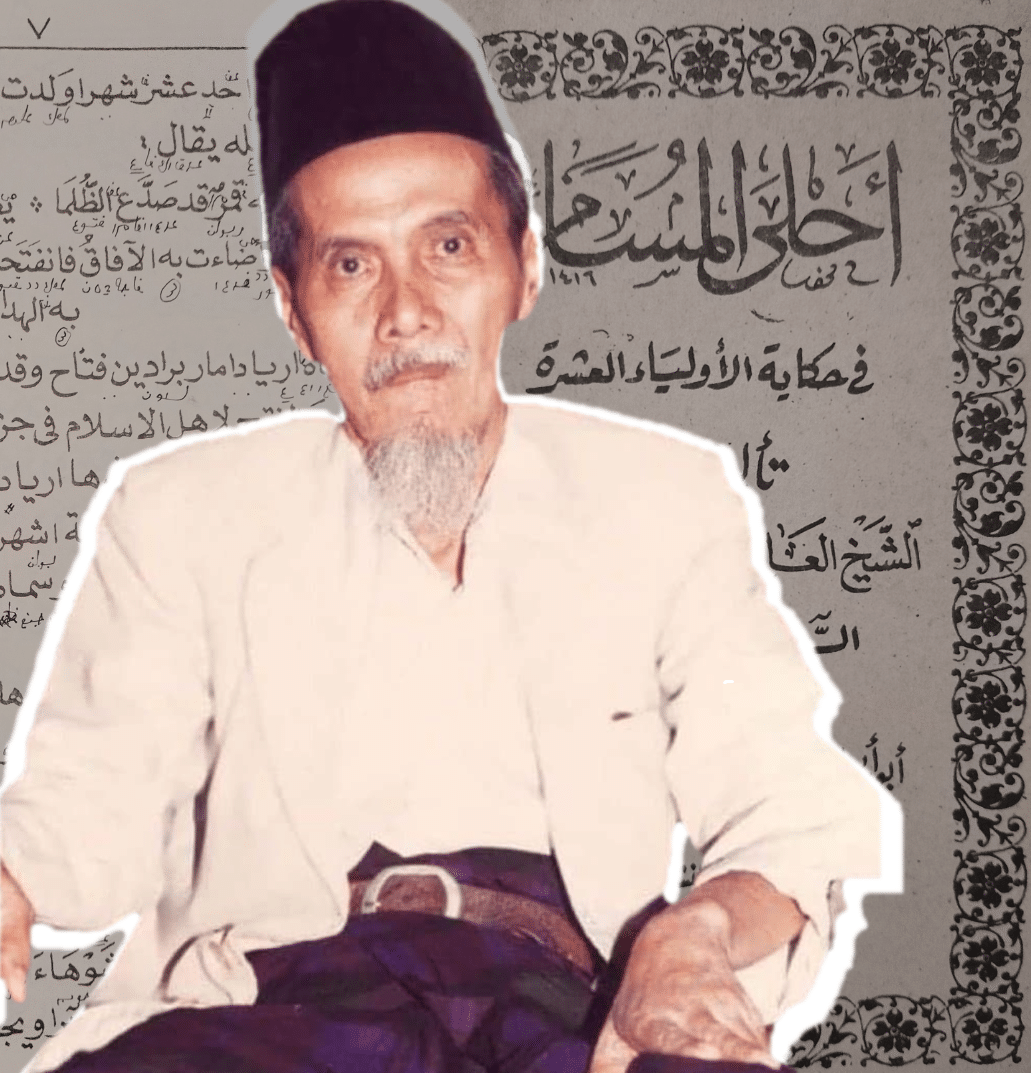Tulisan berikut adalah kelanjutan dari rangkuman ceramah KH. Abdurrahman Wahid pada diskusi dan pementasan wayang kulit dalang Ki Purbo Asmoro dengan lakon “Kunti Pinilih”.
Selain untuk mentransfer nilai-nilai masyarakat, wayang juga dapat dipakai sebagai medium untuk meninjau hubungan antara negara dan warganya. Kewajiban-kewajiban warga negara, kewajiban-kewajiban para penyelenggara pemerintahan, semuanya mendapatkan tempat dalam cerita wayang. Karena isi cerita wayang sebenarnya perihal perebutan tahta, yang berujung pada Mahabaratha atau Barathayuda.
Bahkan dalam cerita yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang, yakni cerita Ramayana, di sanapun seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka berhadapan dengan ksatria yang membela kebenaran. Meskipun kalau dipikir-pikir, sang Rama itu sebenarnya membela dirinya sendiri saja, tapi karena berhadapan dengan Rahwana yang angkara murka, maka Rama menjadi simbol perjuangan kebenaran menentang kebatilan. Jadi cerita ini sudah memakai baju Mahabaratha dan Barathayuda. Ini karena dilihat dari sudut ksatria yang berhadapan dengan penguasa yang lalim.
Kalau cerita Ramayana saja sudah memasukkan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, maka Mahabaratha jelas sekali menyangkuat kekuasaan; bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan.
Dari situlah lalu muncul kerangka kekuasaan. Siapa yang menonton lakon Parikesit (putra Abimanyu atau cucu Arjuna yang menjadi raja Astina pasca Mahabarata, red.), maka akan kenyang dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang adil.
Bagaimana menyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, membela yang lemah, dan menahan yang kuat agar jangan sewenang-wenang. Bagaimana memerintah dengan ikhlas mengabdikan diri. Tapi ternyata, untuk mewujudkan pemerintahan yang seperti itu harus didahului dengan perjuangan. Perjuangan sang Abimanyu yang menceburkan diri ke dalam lautan pertarungan batin dan akal yang intensif guna nanti melahirkan sang Parikesit.
Dengan demikian, kita dapat melihat keseluruhan wayang dari sudut hubungan antara negara dan warganya. Dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa pada akhirnya wayang dapat juga dipakai untuk melakukan koreksi jangka panjang terhadap penyelenggaraan sebuah kekuasaan. Wayang sebagai alat budaya dalam jangka panjang membentuk budaya politik. Budaya politik yang secara lambat tapi pasti membentuk pendapat umum mengenai penyelenggaraan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat.
Sementara itu di negeri kita, medium seni tidak hanya wayang; banyak medium seni yang lain. Bahkan kalau kita mendengar orang menyebut wayang sebagai kesenian nasional, itu kita masih mersa merinding. Mengapa?
Karena khawatir kalau orang luar yang bukan Jawa tersinggung; mengapa wayang dinasionalkan kok kami tidak. Padahal tari kecak itu sama nasionalnya daripada wayang. Kebetulan saja tari kecak di Bali, dan wayang di Jawa, dan karena Jawa merupakan mayoritas penduduk lalu dianggap nasional, itulah yang membuat kita merinding. Tapi kalau kita melihat UUD ‘45 yang menyebutkan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari budaya daerah, yang menjadi kita kenal karena menjadi unsur peramu dari kebudayaan nasional , maka kesenian wayang bukan hanya wayang tapi juga kesenian-kesenian yang lain juga mendapatkan perlakuan yang sama.
Tari Seudati sama dengan Tari Pendhet, sama dengan Tari Bedhaya, sama dengan Ronggeng dan lain-lain, pagelaran yang bermacam-macam itu memberikan peluang kepada wayang untuk muncul sebagai salah satu manifestasi dari kebudayaan nasional. Wayang sebagai wahana budaya membentuk budaya politik, karena memang wayang sendiri merupakan pembahasan mengenai hakikat bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk apa dan dengan cara apa.
Karena itu, wayang tidak pernah sepi dari pergulatan-pergulatan dan percaturan politik. Setia orang dapat melakukan penafsiran-penafsiran politis atas cerita wayang. Bahkan kalau menonton wayang namun tidak mengerti implikasi politisnya, akan terasa aneh.
Budaya politik yang dikembangkan oleh wayang merupakan bagian yang sangat indah. Wayang merupakah sesuatu yang setara, sama mengasyikkan dengan cerita Samkok dari peradaban China. Sebuah cerita entertainmen, cerita romantik tentang sebuah kerajaan di mana Chu-Khe-Liang sebagai perdana menteri yang sangat mahir secara politik menerapkan tipu daya politiknya untuk mengalahkan lawan dengan berbagai tipudaya, berbagai siasat dan muslihat. Wayang pun demikian.
Hanya saja kalau Samkok dibaca dan dibawakan secara perseorangan, tapi kalau wayang digelarkan dengan segala kerumitan, mulai dari gamelannya hingga simbolisasi layarnya. Sekarang pun Samkok sudah mengalami gubahan menjadi serial film kungfu, sehingga dengan sendirinya menjadi lebih rumit dari yang tadinya hanya diceritakan dari mulut ke mulut.
Kalau kita bicara tentang peranan wayang dalam pembentukan budaya politik, maka salah satu sisi penting dari wayang adalah sebagai salah satu alat untuk melakukan kritik atau pengamatan terhadap berjalannya sebuah kekuasaan. Hal itu bisa dilakukan dengan memakai pakemnya, atau bisa juga dengan carangan-nya, yaitu hal-hal lain yang ditempelkan pada wayang. Sebagai contoh, dulu pada zaman Bung Karno, ada seorang menteri penerangan Ahmadi yang tidak menikah. Suatu hari dia nonton wayang, kemudian di sana dalangnya bicara Petruk yang sedang dimarahi Ponakawan yang lain:
“Petruk Petruk, kamu ini sudah menteri gak mau kawin, kok banyak banget pacarnya, ganti-ganti tiap hari.”
Itu sebenarnya bukan Petruk yang dimaksud, tapi Ahmadi. Dan Ahmadi pun ketawa ngakak mendapat kritik seperti itu. Koreksi yang seperti itu, yang dibungkus secara kultural tidak menyakitkan bagi dia, walaupun sebenarnya cukup kritis.
Sebagai alat untuk memberikan koreksi, wayang membentuk sejumlah sudut pandang para penonton atau warga masyarakat dalam jangka panjang tentang pentingnya kesetian kepada negara, tentang pentingnya ketegaran dalam membela kebenaran, tentang pentingnya pengorbanan. Seperti Sang Bima, melebur diri dalam Dewa Ruci yang nanti berakibat pada proses penempaan dirinya sendiri.
Semua cerita itu merupakan alat pengukur bagi hal-hal yang sebenarnya harus dilaksanakan dalam pemerintahan, dan yang harus dijauhi dalam menyelenggarakan kekuasaan. Hal ini biasanya diawali dengan melakukan pengamatan terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri, atau jalannya sistem pemerintahan.
Kita lihat pada masa penjajahan, wayang menjadi alat untuk menampilkan citra mengenai para pejuang kemerdekaan yang diwayangkan sebagai ksatria, berjuang membela kebenaran, dan hampir seluruhnya dari Pandawa. Tapi kaum penjajah, karena badannya tinggi-tinggi, oleh dalang diproyeksikan sebagai buta (raksasa) yang perilakunya tidak berperikemanusiaan, yang lalim, yang serakah; semua sifat yang jelek ada pada mereka. Proyeksi ksatria menghadapi raksasa ini adalah alat untuk memelihara semangat perlawanan kepada penjajah. Ini yang merupakan tali pengikat kita dulu.
Setelah kita merdeka menjadi bangsa, apakah raksasanya hilang? Tidak. Raksasa berubah diproyeksikan menjadi pejabat pemerintahan yang lalim. Pejabat pemerintah yang memerintah tidak untuk kepentingan yang diperintah, hanya mementingkan kepentingannya sendiri; pamrihnya sendiri. Bisa saja sifat itu dilekatkan pada tokoh-tokoh seperti Dorna, Sengkuni dan segala macam.
Setelah kita melihat tipologi tokoh-tokoh wayang digunakan untuk melihat para pemimpin kita; ada yang dilihat kearifannya, keberaniannya, ketegasan sikapnya, dan seterusnya, maka kita dapat melihat melalui wayang tentang jalannya pemerintahan secara makro. Bukan lagi melihat orang per orangnya, tapi kita sedang berada di mana. Misalnya kita berasa pada situasi yang tenang, membangun tanpa gejolak; meskipun ungkapan ini sebenarnya paradoks. Karena biasanya pembangunan selalu disertai dengan pergolakan. Tapi bergolak saja juga tidak bisa membangun kalau tidak ada proses pengarahan dan pengendalian terhadap pergolakan itu. Dibutuhkan conflict management yang baik sehingga mengarah kepada sasaran yang dituju. Dalam hal inilah pengamataan wayang juga penting, karena merupakan alat untuk melihat sejauh mana keadaan kita.
Wayang merupakan stock opname untuk melihat keadaan, semisal keadaan tidak menentu yang timbul dari proses politik suksesi atau masa peralihan. Pada kisah Dewa Amral (jelmaan raksasa dari tokoh Yudhistira, red.) misalnya, kita bisa saksikan seorang ksatria akhirnya berubah menjadi dewa.
Dalam perwayangan, ksatria itu sebenarnya bukan hanya manusia, tapi prototype dari manusia luhur yang bisa saja berontak dan marah-marah kepada dewa. Bisa menggoncangkan alam yang dibuat oleh para dewa. Kekuatannya juga memiliki nilai-nilai ketuhanan. Maka perubahan fungsi ksatria menjadi dewa itu bukan suatu proses vertikal, tapi lebih banyak suatu proses horisontal sehingga memungkinkan sang ksatria berperan ganda. Peran untuk lebih memperkuat sisi rohani, atau lebih menekankan jenis perilaku tertentu yang ingin dikembangkan.
Pendewaan ksatria itu pada proses makro terjadi ketika status quo tidak bisa lagi dipertahankan. Harus ada perubahan tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan. Pada cerita Kunthi Pinilih juga terdapat suatu episode atau satu periode di mana sedang dipersiapkan lahirnya satu generasi ksatria yang baru.