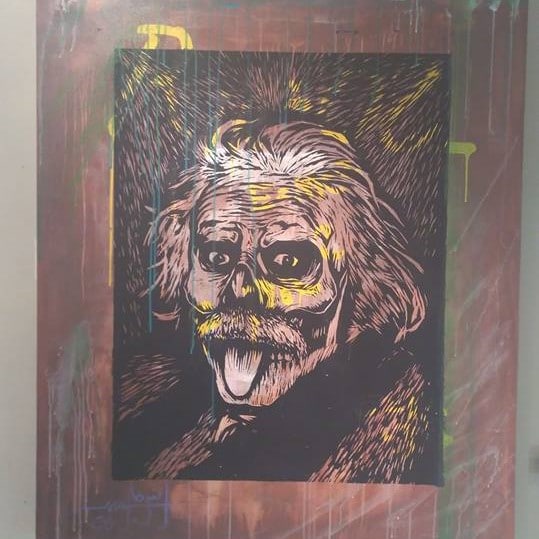
BULAN APRIL kerap mengingatkan saya pada tiga tokoh besar dunia yang namanya harum semerbak hingga hari ini. Mereka adalah Raden Ajeng Kartini, Raden Mas Panji Sosrokartono (kakaknya), dan Albert Einstein.
Demi dua orang kakak beradik itu, saya sudah pernah membuat sebuah tulisan mendalam dan lumayan panjang. Maka kali ini, saya berniat menyusun pikiran dengan kata-kata untuk Einstein, sebagai tanda bakti generasi pelanjut mereka yang telah lebih dulu pergi.
Judul tulisan ini dianggit dari potongan sesanti yang digurat Einstein sesaat setelah persamaan energi-massanya dalam E = MC², diubah Amerika jadi bom atom (fat man dan litle boy), lantas melumat Hiroshima-Nagasaki pada 6 Agustus 1945.
Bentuk aslinya berbunyi, “Agama tanpa ilmu–lumpuh, dan ilmu tanpa agama–buta.” Kendati manusia paling jenius Abad-20 ini mengaku orang tidak beragama yang sangat relijius, namun buah perenungannya dalam hidup laik dijadikan pembelajaran bagi umat manusia setelahnya.
Kini kita sungguh benar membuktikan kegelisahan Einstein tersebut. Kebiasaan menelan mentah-mentah saluran informasi yang tumpah-ruah, kerap kali menimbulkan petaka dalam laku keberagamaan kita.
Berita palsu bisa mewujud kebenaran. Sebaliknya malah tak demikian. Sudahlah kekurangan bahan bacaan, jebulnya, umat beragama cenderung malas membaca. Terutama membaca kehidupan ini.
Terkait itu, Einstein juga pernah mengingatkan. “Membaca, setelah beberapa waktu, membuntukan pikiran dari proses kreatif. Seseorang yang membaca terlalu banyak dan terlalu jarang menggunakan otaknya, akan terbiasa malas berpikir.” Bahkan mereka yang sudah gemar membaca saja masih kena hujan kritik olehnya.
Lagi, Einstein menegaskan bahwa, “perbedaan antara kebodohan dan kecerdasan adalah, bahwa kecerdasan ada batasnya. Kita mafhum hari ini betapa kebodohan bersimaharajalela di mana tempat.
Agama yang selalu dijadikan kendaraan dalam banyak sendi kehidupan, celakanya malah teramat sering memantik amarah dari mereka yang juga beragama. Seolah dengan amarah, soal yang diperselisihkan bisa tuntas dibahas. Padahal, “kemarahan hanya berdiam di dada orang-orang bodoh,” demikian Einstein menandai zaman yang sedang ia hidupi kala itu.
Sebagai Yahudi tulen, Einstein teramat sering diperlakukan secara tak manusiawi, kendati dirinya adalah saintis pilih tanding di antara rekan seangkatannya.
Fenomena bom atom yang telah memukul Einstein pada penghujung Perang Dunia II, membawanya pada sebuah perenungan mendalam, “Kehidupan menjadi begitu mengerikan karena teknologi telah melampaui kemanusiaan.”
Saat ini kita pun masih merasakan ‘bom atom’ lainnya yang meledak dalam pikiran umat beragama melalui media sosial–hampir setiap hari. Malah Perang Dunia III yang kini membara di Timur Tengah, dipantik dari sebiji cuitan di Twitter.
Kini agama hanya terhenti di ranah perdebatan, salah-menyalahkan, kafir-mengafirkan, dipolitisasi, bahkan diperdagangkan secara bebas terbuka, dan seolah menyulut peperangan. Kitab suci tinggal teronggok jadi artefak dari masa lalu yang jauh. Jadi batu. Sisa abu.
Bilamana kita ingin membuat kehidupan beragama jadi seindah pelangi, ada baiknya camkanlah pesan Einstein berikut ini:
Untuk menghadirkan pertanyaan baru, kemungkinan baru, melihat masalah lama dengan sudut pandang baru, butuh imajinasi kreatif dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Tak perlu lagi mempertentangkan agama dengan sains. Toh agama diturunkan tuhan bagi mereka yang mau menggunakan akalnya.
Bagi yang mau berpikir, merenung. Sebab sejatinya para Nabi dan Rasul adalah mereka yang dikategorikan sebagai manusia Ulul Albab. Pemikir cemerlang.
“Agama, seni dan ilmu adalah percabangan dari pohon yang sama,” demikian yang diyakini Einstein. Kita bisa menyebut pohon itu dengan “kehidupan”. Maka wajar kemudian jika ia melansir petuah lain yang berbunyi, “berusahalah, bukan untuk menjadi orang sukses, tapi jadi orang bermanfaat.”
Nuansa dari pesan itu sama belaka dengan apa yang pernah disampaikan Rasulullah Muhammad saw dalam sebuah hadis, “Khairunnas anfa’uhum linnas: sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.”
Jelang kepergiannya dari kefanaan dunia, Einstein berujar rada apatis di sisi kuburan Rudolf Ladenberg. “Hidup ini singkat, seperti bertamu sebentar di rumah yang aneh. Jalan yang harus ditempuh remang-remang di bawah kesadaran yang berkelap-kelip.”
Di pembaringannya, Einstein mulai kepayahan menanggung kegelisahan teori medan energi yang sedang ingin dirampungkannya, sebagai hadiah indah bagi umat manusia setelahnya.
Meski begitu, Einstein pun menyerah kalah dan berkata, “Tiada guna memperpanjang hidup dalam kepalsuan. Aku sudah menyelesaikan bagianku. Sekarang saatnya pergi. Aku akan melakukannya dengan elegan.”
Sebelum Einstein wafat pada 18 April 1955, Bertrand Russel, sahabat fisikanya yang kental bertutur dengan penuh hormat, “Ia tetap bijaksana di dunia yang gila ini.” Saat Einstein memungkasi usianya di angka 76 tahun–Senin dini hari, di sisi ranjangnya tergeletak sebuah konsep pidato tuk hari “kemerdekaan” Israel:
“Saya berbicara di hadapan Anda hari ini bukan sebagai warga negara Amerika dan bukan sebagai orang Yahudi, melainkan sebagai umat manusia.” Pesan puncak inilah yang perlu kita renungkan dengan baik dan benar. Apakah kita beragama demi keselamatan diri semata, ataukah menuai kemaslahatan dan kebaikan untuk umat manusia seantero dunia… []




















