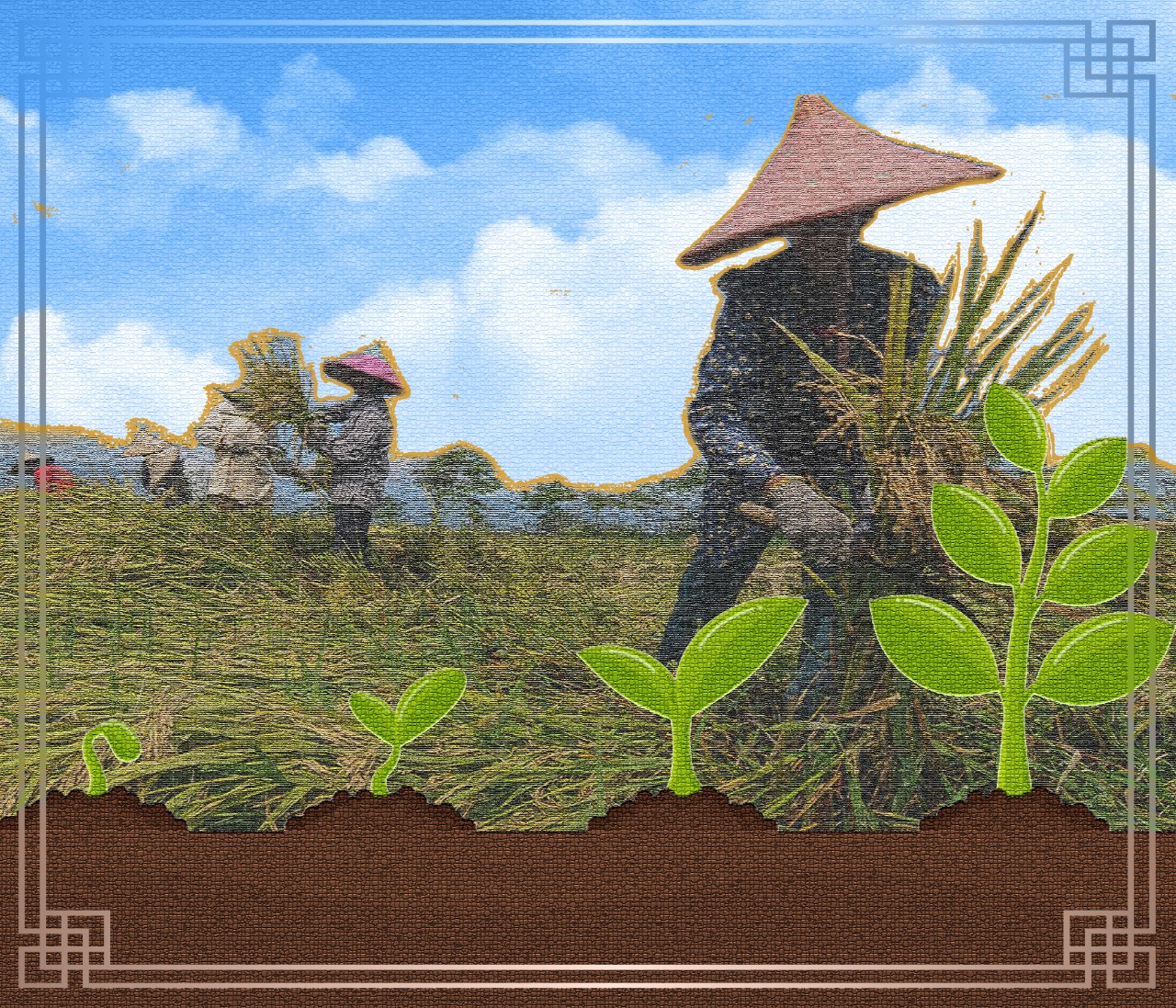Salah satu oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari Ngaji Ihya’ online semalam (Kamis, 12/3/2020) adalah ajaran Imam al-Ghazali mengenai “al-zuhdu fi al-zuhdi” yang saya terjemahkan secara gampangan saja sebagai: men-zuhud-i zuhud. Yang dimaksud dengan ajaran ini adalah kemampuan untuk tak menampakkan dan memamerkan tindakan baik kita kepada khalayak ramai.
Tindakan zuhud (yaitu mengendalikan diri agar tak dikuasai oleh dunia) adalah baik. Tetapi, jika tindakan baik ini dipamer-pamerkan, ditonjol-tonjolkan kepada orang lain, ia berubah menjadi “bencana rohani” bagi orang bersangkutan. Karena itulah tindakan zuhud ini harus di-zuhud-i pula, dengan cara tak memamerkannya kepada orang lain. Itulah pengertian al-zuhdu fi al-zuhdi.
Salah satu ciri utama yang menengarai zaman digital atau media sosial saat ini adalah kuatnya dorongan dan tekanan dari kiri-kanan untuk tampak “cool”, keren di mata orang lain. Inilah kecenderungan yang boleh disebut sebagai “gejala narsisisme” -- memamerkan apapun (tentu saja yang baik dan “pamerable”, layak dipamerkan) kepada orang lain.
Sisi lain dari kultur narsisisme ini adalah kecenderungan untuk menyimpan rapat-rapat kekurangan dalam diri kita dari publik, agar tidak mengganggu citra kita yang “kinclong” itu di mata mereka. Nyaris setiap orang, dalam ruang digital saat ini, seolah-olah bertindak sebagai “salesman”, orang yang memasarkan diri agar “laku jual” di mata orang lain. Dalam kultur semacam ini, segala kebaikan yang kita lakukan berubah menjadi semacam “komoditi” yang bisa dipertukarkan dengan “komoditi” yang lain -- yaitu pujian, tepuk-tangan, decak-kagum dan (dalam konteks dunia facebook) tanda “like”.
Kecenderungan semacam ini tentu saja merupakan hal yang alamiah dan normal dalam kehidupan sehari-hari; bahkan “sangat normal” dalam kehidupan manusia pada umumnya, baik di era digital atau pra-digital. Dorongan untuk “showing off”, memamerkan kebaikan diri jelas sesuatu yang manusiawi dan alamiah.
Tetapi, kecenderungan ini bukanlah hal yang normal dan dianjurkan dalam konteks kehidupan rohani. Seseorang yang hendak menaikkan kualitas dan maqam rohaninya, harus mampu melawan kecenderungan-kecenderungan alamiah seperti itu. Jika ia mengikuti saja, dan hanyut dalam dorongan-dorongan alamiah tersebut, ia, dalam kaca-mata ilmu tasawwuf, masuk dalam kategori “orang pada umumnya”, al-’awamm. Jika orang itu hendak meningkat dan masuk dalam golongan “orang-orang yang spesial dan dekat kepada Tuhan”, “al-khawass”, maka tak ada cara lain kecuali melawan kecenderungan-kecenderungan itu -- apa yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai “kasr al-syahawat”, menundukkan syahwat.
Kemampuan menundukkan syahwat pun terdiri dari dua level. Level pertama ialah menundukkan syahwat itu sendiri -- misalnya syahwat untuk mengkonsumsi makanan tertentu yang menjadi kesenangan orang bersangkutan. Level kedua adalah kemampuan mengendalikan syahwat untuk tampak “saleh” di mata orang lain karena ia telah mampu mengendalikan syahwat yang pertama tersebut. Inilah yang disebut oleh al-Ghazali sebagai al-zuhdu fi al-zuhdi. Dengan kata lain, zuhud pun harus di-zuhud-i.
Berbuat baik saja belum cukup, dalam konteks “latihan rohani”. Tantangan berikutnya, setelah seseorang mampu berbuat baik, adalah mengendalikan hasrat yang kuat (dan sangat alamiah) pada dirinya agar kebaikan itu diketahui oleh khalayak ramai. Saat gagal mengatasi jebakan dan hasrat ini, ia akan terjatuh pada apa yang disebut sebagai riya’, pamer. Dalam konteks ajaran rohani, pamer disebut sebagai “syirik yang samar”, al-syirk al-khafi. Ia bisa destruktif terhadap kehidupan rohani.
Seseorang yang mampu menjalani ajaran “zuhud atas zuhud” ini, oleh al-Ghazali, disebut sebagai mereka yang telah mencapai derajat “al-shiddiqun”, orang-orang yang mampu jujur pada diri sendiri. Orang-orang yang hanya tampak saleh dalam keramaian, tetapi kembali menjadi “orang biasa” yang bertindak buruk di saat tak ada orang lain, mereka telah melakukan kebohongan dua kali; bohong kwadrat.
Tasawwuf mengajarkan kepada kita cara-pandang alternatif yang melawan arus umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ketika arus umum mendorong orang-orang untuk berlomba memasarkan kebaikan-kebaikan secara terang-terangan di muka umum, dan kemudian meng-kapitalisasi atau mencari untung atas kebaikan itu, tassawwuf mengajarkan hal yang sebaliknya: kalau perlu kita malah harus tampak jelek di mata orang lain.
Oleh tasawwuf, kita diajak justru untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan itu. Malahan, kita didorong untuk “al-zuhdu fi al-zuhdi”, menjauhi hasrat ingin tampil dan dikesankan baik oleh khalayak. Kita boleh menyebut ajaran tasawwuf ini sebagai semacam “budaya tanding” (terjemahan yang pernah dipakai oleh Mochtar Pabottingi untuk istilah “counter culture”).
Dengan kata lain, salah satu “jalan rohani” yang diajarkan oleh tasawwuf adalah melawan dorongan narsisisme, dorongan pamer, dorongan tampil cantik dan keren di mata umum. Sebab, pada momen ketika kita dipandang “keren” oleh publik, di sanalah ada jebakan lain: ego kita menggelembung, kebanggaan kita mengembang, kesombongan kita pelan-pelan bersemi. Tasawwuf melatih kita untuk melawan penggelembungan ego yang bisa berdampak destruktif secara rohani. (RM)