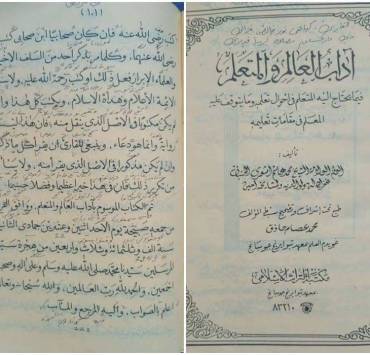Menyebut “Islam Politik” bukan semata-mata menunjukkan suatu persepsi bahwa sebagai sebuah agama, Islam tak mungkin dipisahkan dari politik, atau, politik menjadi satu-satunya alasan dari suatu bentuk “fanatisme” keagamaan.
Namun, secara teologis dan sosiologis, hanya Islam yang memiliki seperangkat aturan paling lengkap, paling tidak mengutip ungkapan H.A.R Gibb, dimana “Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization”.
“Islam, ketika mewujud dalam suatu peradaban, berarti ia tak saja bernilai teologis, namun sosial, budaya, dan juga politik yang tak penah sepi dari situasi historis yang menopangnya.”
Ketika Islam berkembang menjadi suatu peradaban dunia, yang berkelindan di dalamnya beragam tradisi, baik ilmu pengetahuan, sosio-budaya, nilai etik, dan moral, telah menjadikan Islam tak lagi bercorak “Arabistik”, namun penyebarannya yang melampaui batas wilayah dari “Nil hingga ke Oksus” terus meluas hingga wilayah Indo-Mediteranian sampai Afro-Eurasia bahkan hingga membentuk suatu peradaban khas seperti di Indonesia.
Mungkin, satu-satunya negara Islam yang luput dari peradaban Islam “Arabistik” hanya Indonesia. Sekalipun negeri yang pernah dijajah Portugis, Belanda, dan Jepang ini seringkali terabaikan dalam sejarah peradaban Islam, namun secara politik, dipandang memiliki sejarah politik yang berkaitan dengan Timur Tengah terutama pengaruh dari para haji yang kemudian mewarnai kepolitikan Nusantara.
Islam sendiri masuk ke Indonesia melalui jalur politik-perdagangan yang hampir-hampir bukan merupakan rangkaian ekspansi keagamaan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negeri sekitar jazirah Arab.
Menariknya, agama Islam di Indonesia justru berasal dari kalangan atas, lalu menyebar ke kalangan bawah, mengakar dalam suatu akulturasi dan asimilasi secara halus dengan berbagai tradisi dan budaya lokalnya.
Laporan seorang ahli obat-obatan asal Portugis, Tome Pires, yang menyusuri pantai Nusantara pada abad ke lima belas, membuktikan bahwa sepanjang jalur yang ia lalui, seluruh wilayah telah diduduki oleh penguasa-penguasa muslim (Laporan ini ia tulis dalam bukunya, “Suma Oriental”).
Secara politik, Islam telah menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, sehingga wajar jika Indonesia sampai saat ini masih disebut sebagai “negara Islam” mengingat penduduk beragama Islam mendominasi dibanding penduduk beragama lainnya.
Persepsi soal Indonesia sebagai negeri Islam juga menjadi perhatian paling penting bagi pihak kolonial, bahkan, banyak disebutkan dalam catatan sejarah, bagaimana Belanda membuat kebijakan-kebijakan yang sedemikian ekstra ketat bagi penduduk pribumi yang beragama Islam.
Awal abad ke19, seringkali disebut sebagai masa keemasan kolonialisme Eropa atas negara-negara Asia dan hampir dipastikan mereka menghadapi serangkaian pemberontakan yang diinisiasi gerakan Islam politik yang diawali dari perang Padri (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), dan perang Aceh (1873-1903).
Apa yang disebut sebagai “Islam politik” tentu saja menjadi hal yang paling menakutkan bagi kalangan kolonial. Sekalipun hal ini kemudian berubah setelah kedatangan Snouck Hurgronje ke Hindia Belanda pada tahun 1889, dimana ia melawan ketakutan Belanda terhadap Islam melalui serangkaian kebijakannya yang lebih “politis” dan populis. Dalam pandangan Snouck, Islam tidak mengenal lapisan kependetaan seperti dalam Kristen. Kiai tidak apriori fanatik. Penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi, dan bukan atasannya. Ulama independen bukanlah komplotan jahat, sebab mereka hanya menghendaki ibadah, pun pergi haji ke Mekah bukan berarti fanatik dan berjiwa pemberontak (Harry J. Benda, “The Crescent and the Rising Sun”: 1958).
Kebijakan pemerintah kolonial yang cukup populis dan berkecenderungan netral terhadap Islam, kemudian melahirkan berbagai gerakan politik di mana cikal-bakalnya dapat ditelusuri dari pendirian Sarekat Islam (SI).
SI banyak mengkritik campur tangan Belanda terhadap berbagai aspek hukum Islam, terutama soal peradilan agama, pengawasan terhadap perkawinan dan pendidikan Islam, ordonansi guru, hingga pengawasan terhadap kas masjid dan ibadah haji (untuk menelusuri kebijakan politik Belanda terhadap Islam, dapat merujuk pada buku H. Aqib Suminto, “Politik Islam Hindia Belanda”: 1985).
Tekanan politik dari pemerintah kolonial, tentu saja mendapat reaksi keras dari pihak Islam dan muncul polemik berkepanjangan, antara Belanda di satu pihak dan kelompok Islam politik di pihak lain—yang dalam hal ini seringkali diwakili SI.
Reaksi Islam atas kebijakan kolonial ini, tak hanya dilakukan oleh kalangan berpendidikan Barat, namun para santri yang notabene bermukim di wilayah pedalaman, juga menunjukkan reaksinya melalui suatu kesadaran politik, bahwa pemerintah kolonial merupakan “pemerintahan kafir” yang menjajah negara dan agama mereka.
Kelompok santri malah terkesan “radikal” dengan menganggap bahwa uang yang diterima sebagai gaji dari pemerintah kolonial adalah uang haram, bahkan celana dan dasipun dianggap haram karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda.
Reaksi tentu saja timbul akibat adanya suatu kondisi tekanan politik yang terlampau berlebihan di mana hal ini erat kaitannya dengan suatu persepsi di mana, “banyaknya permintaan justru akan menaikkan harga penawaran” sebagaimana dalam teori ekonomi.
Sekalipun bahwa reaksi umat Islam yang sedemikian hebat terhadap berbagai aturan yang mengekang kebebasan beragama mereka, namun sulit untuk tidak dikatakan, bahwa masing-masing ternyata mempunyai motif atau kepentingan politik pribadi. Polemik, ternyata tidak saja terjadi antara mereka dengan kebijakan politik Islam Belanda, namun perpecahan ulama yang cenderung ikut berpolitik juga mewarnai pasang surut Islam politik di Indonesia.
Hal ini mungkin dapat dilihat, di saat pemerintah kolonial akan memberlakukan Ordonansi Guru di Sumatra Barat yang menimbulkan reaksi keras umat Islam, berhasil diredakan oleh pidato heroik Haji Rasul pada 18 Agustus 1928 dalam suatu rapat besar di Bukit Tinggi. Sebagaimana dikutip dalam buku Deliar Noer, “Gerakan Modern Islam di Indonesia”, Ia memulai pidatonya dalam bahasa Arab, kemudian diteruskan dalam bahasa daerah.
“Sejak saya mendengar maksud pemerintah hendak menjalankan ordonansi ini di Minangkabau, berguncang persendianku, lemah lunglai seluruh tulang belulangku. Saya insyaf, sebetulnya tidak hendak menjalankan suatu ordonansi yang amat berat di negeri kita. Saya yakin, pemerintahan agung tidak hendak menyinggung perasaan kita. Tetapi peraturan ini, adalah karena kesalahan kita selama ini. Kita, ulama-ulama selalu berpecah, selalu berselisih!..(sambil beliau menitikkan air matanya).
Islam politik tentu saja memiliki persepsi yang tampak berbeda sebagaimana ditunjukkan oleh pihak pemerintah kolonial dan pribumi itu sendiri. Di satu sisi, reaksi umat Islam sangat jelas, melawan berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang mengekang kebebasan politik umat Islam.
Di sisi lain, terdapat perselisihan tajam di antara para ulama waktu itu yang mungkin saja ada yang bersikap “keras” atau “lembut”, bahkan ada yang terkesan “netral” sebagaimana keberhasilan Haji Rasul mencegah polemik lebih besar.
Bukan tidak mungkin, abad ke-19 tentu saja menguatnya suatu semangat politik keagamaan, yang dari luar dibawa oleh para haji dengan ide pan Islam dan dari dalam menguatnya semangat gerakan tarekat yang diinisiasi gerakan para santri.
Sekalipun kita tidak harus secara simplistis memandang bahwa Islam politik cenderung berasal “dari dalam” melalui gerakan tarekat dan “dari luar” melalui serangkaian perkenalan ide pan Islam yang dibawa para haji Indonesia, namun ada suatu kondisi umum dimana setiap aksi yang memunculkan “kesadaran” politik tentu saja erat kaitannya dengan “perlawanan” atas beragam persepsi atau kebijakan yang menyentuh aspek-aspek keagamaan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Keberadaan gerakan Islam politik belakangan, mungkin saja tidak terkait dengan keduanya, tetapi ada kekecewaan mendalam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak “campur tangan” terhadap apa yang dipersepsikan kalangan Islam secara politik.
Namun yang pasti, reaksi umat Islam tentu saja terkait dengan suatu kenyataan politik, dimana terdapat kekuatan-kekuatan Islam politik yang belakangan tampak diberangus melalui kebijakan-kebijakan yang seolah lebih menekankan “ketertiban” dibanding bersikap “netral” terhadap berbagai situasi politik. Isu-isu lama muncul, seperti bangkitnya kekuatan komunisme atau semangat “anti asing” (xenophobia) yang dalam beberapa hal ada dorongan menggalakan “perang suci” yang diinisiasi oleh beberapa kelompok Islam politik yang tentu saja berkepentingan terhadap kekuasaan.
Di Indonesia, semangat keagamaan ini seolah menemukan momentumnya dalam hiruk-pikuk suksesi politik nasional yang dipicu oleh banyak isu yang seolah-olah menyudutkan umat Islam.
Perpecahan para ulama tampak tak terelakkan, terutama dalam hal dukungan politik di tengah tahun politik yang lebih menggambarkan suatu rangkaian atas “persepsi”, “aksi”, dan “reaksi” yang keseluruhannya tak bisa dilepaskan dari rangkaian panjang sejarah Islam politik di Indonesia.
Uniknya, di saat ide khilafah pernah tenggelam di tahun 1920-an karena Musthafa Kemal menolaknya, sekaligus ide pan Islam yang menguat juga dianggapnya hanya sebatas ilusi dan khayalan sebagaimana pidatonya di Majelis Agung Nasional Turki pada 1921, namun gerakan “khilafah” ini justru pernah marak di Indonesia dan akhirnya dibubarkan pemerintah pada 2018 lalu.
Kita tentu saja memiliki beragam persepsi dalam memandang Islam politik di Indonesia dan hampir-hampir sulit untuk berada pada suatu pandangan yang netral atau minimal “bebas nilai” dari sudut manapun kita memandangnya. Yang terjadi justru, upaya-upaya kekanak-kanakan yang seringkali menjelma dalam suatu polemik non-verbal, sekadar klaim “benar-salah” yang jauh dari konteks diskursif yang pada akhirnya kurang merangsang rasionalitas, terlebih sebagai upaya peningkatan intelektual yang bernuansa akademis.
Kita tentu saja tidak berada dalam “abad kolonial” yang sangat mudah dipecah-belah oleh suatu kebijakan politik populis yang diberlakukan pemerintahan Belanda. Kita tentu saja berada pada kurun abad milenial yang menuntut keterbukaan, intelektualitas, rasionalitas, bukan emosi atau “semangat kosong” yang dipolitisir oleh “fanatisme” agama.