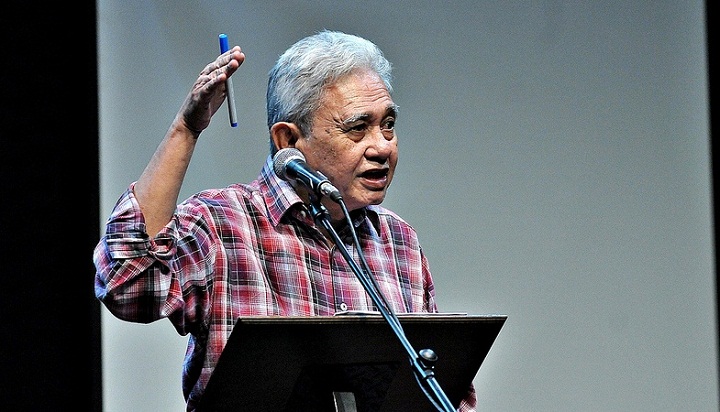SEORANG pendeta Tiongkok bernama Fa Hien, mendarat di Pelabuhan Sunda Kalapa pada Desember 412 Masehi. Ia bermukim di tanah Jawi sampai Mei 413, lantas melanjutkan perjalanan keilmuannya menuju India. Demikian catat Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Bagian II, Jaringan Asia.
Rekaman pegembaraan Fa Hien selama di Bhagasasi (Bekasi sekarang) yang di dalamnya terdapat kompleks percandian Batu Jaya itu, ia tuangkan ke dalam naskah yang berjudul Fahueki. Selain Fa Hien, bukti dari keramik-keramik Tiongkok yang ditemukan di Jawi juga menunjukkan kesamaan waktu dengan teks-teks antara abad kelima dan keduabelas Masehi.
Setelah Fa Hien, banyak pendeta Tiongkok lain yang mengikuti jejaknya. Sun Yun, Hwui Ning, dan I-Tsing merupakan tiga di antaranya. I-Tsing malah 14 tahun menetap di Sriwijaya. Pengalamannya itu ia catat ke dalam Nan Hai Chi Kuei Fa Ch’uan dan Ta T’ang Si Yu Ku Fa Kao Seng Ch’uan. Sepenggal isinya berbunyi:
“Hingga abad ketujuh hanya para pendeta Tiongkok saja yang melakukan perjalanan ke India & menyambangi Sriwijaya.”
Ketika I-Tsing mendarat di Keratuan Sriwijaya pada 671 M, Islam baru berusia seabad. Jangkauan persebaran ajarannya pun belum merambah bumi Jawi. Masih kitaran Jazirah Arabia dan sedikit masuk ke Transoksiana. Kedatangan pendeta Tiongkok tersebut demi menggali khazanah spiritual yang harum wanginya telah menyebar ke seantero dunia–dari kompleks pertapaan di Muaro Takus, Kampar.
Sejatinya, riwayat persinggungan Islam dengan masyarakat di Zamrud Khatulistiwa yang lazim disebut Nusantara, sudah terjadi sejak periode awal kenabian Muhammad saw. Manusia agung ini, telah mengirimkan para Sahabat terpilihnya, guna mengunjungi sebuah negeri nun di Timur jauh. Tanah keramat yang telah berulang kali menghiasi catatan perjalanan para kartograf, pelancong, pedagang, kalangan cerdik pandai, dan penyintas.
Ragam kisah menarik terkait itu, akan saya sajikan dalam batang tubuh tulisan ini, termasuk apa saja yang menjadikan Bumi Prativi sedemikian menarik perhatian bangsa lain di belahan barat dan utara.
Mari kita mulai dari wilayah legendaris di tepian Svarnadvīpa (Sumatra).
Barus adalah salah satu kota tertua di Indonesia dan sudah terkenal ke seantero dunia—sejak zaman kuno. Pada 2500 SM, tempat ini beken dengan hasil hutan berupa kamfer dan kemenyan. Menyimpan segudang misteri dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para ahli sejarah dan arkeolog—baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Terbukti dengan adanya makam tua di kompleks Pemakaman Mahligai. Pada salah sebuah jirat nisannya tertulis Syeikh Rukunuddin, wafat pada 672 Masehi atau 48 Hijriah, yang menguatkan adanya komunitas Muslim di daerah ini pada era itu.
Penelitian terakhir, dilakukan oleh tim arkeolog yang berasal dari Ecole Francaise D’extreme-Orient (EFEO) Perancis, bekerjasama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PPAN) di Lobu Tua–Barus pada 1995-1999, terkait Barus kota sejarah tempat masuknya Islam pertama di Nusantara.
Dari hasil penelitian tim dikemukakan, sekitar abad 9-12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan pusparagam suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, China, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Hal ini disampaikan terkait penemuan sejumlah benda-benda berkualitas tinggi yang usianya ditaksir ribuan tahun.
Sejarahwan Italia, G. E. Gerini dalam bukunya, Researches on Ptolemy’s Geography of Eastern (Further India and Indo-Malay Archipelago), mencatat bahwa sekitar 606-699 M telah banyak masyarakat Arab, yang bermukim di Nusantara. Mereka masuk melalui Barus dan Aceh di Swarnabumi Utara. Dari sana menyebar ke seluruh Nusantara hingga ke Cina Selatan.
Sekitar 625 M, sahabat Rasulullah saw, Abdullah Ibnu Mas’ud ra bersama kabilah Thoiyk, datang dan bermukim di Sumatera. Catatan bangsa Nusantara menengarai bahwa Thoiyk disebut sebagai Ta Ce atau Taceh (sekarang Aceh).
Manakala Abdullah Ibnu Mas’ud masuk ke negeri yang bertaburan permata, penduduknya sudah memiliki tradisi khusus nan luhur berkenaan dengan cara mereka mengagungkan tuhan. Sebelum istilah shalat marak terdengar dua dasawarsa belakangan, kami masih sering melafalkan kata sembahyang, untuk mewakili salah satu ritus ibadah utama dalam Islam.
Kata “sembahyang” membuktikan betapa leluhur Nusantara terdahulu tidak pernah menganut animisme atau dinamisme–sebagaimana yang dituduhkan kolonial Belanda ketika mulai lupa daratan, dan ingin merebut negeri keramat ini dari para pelanjutnya. Lantas dari mana kata itu berasal?
Kamitua Nusantara pada masa kejayaannya terdahulu terbukti sudah berketuhanan dengan penyebutan berbeda di setiap daerah. Ritual itu tertandai dengan kata “sembah Hyang” yang mereka gunakan.
Hyang adalah lema yang mengarahkan pemahaman tentang yang Maha Mutlak, Maha Esa, Hyang Widhi Mahamanunggal. Penyembah-Nya kemudian terekam bahasa Sansekerta menjadi “Para Hyang” dan kadang disebut “Para Hyang-an”. Kini bersalin rupa dan identik dengan Pariangan, yang diberi arti baru: tempat beriang-riang. Padahal akar katanya Para Hyang. Para pemuja Hyang Suci (Tuhan).
Mari kita kembali ke I-Tshing. Selama nyantri di Muara Takus, ia mencatat Svarnadvīpa adalah tempat belajar falsafah Dasar Utama atau lazim dikenal sebagai Dharma. Ajaran inilah yang kemudian dibawa tokoh² bernama Sanjaya, Sariputra, Svarnakesa, Svarnadvipi Dharmakirti, Mahavira, Dharmapala–ke India, dan Atisha yang masuk ke Tibet.
Svarnadvīpa berpusat di lokasi Matahari Tanpa Bayang/Equinox. Sesuai catatan I-Tshing, di sini tersisa rekam jejak sumber falsafah para Penyembah Hyang, sejak 1300 SM. Jauh lebih tua tinimbang Buddha & Hindu, yang para penyusun ajarannya belajar pada santri jebolan Svarnadwīpa. Nama² mereka sudah kami cantumkan pada bagian atas tulisan ini.
Tinggalan ajaran tersebut masih bisa kita telusuri melalui relief & toponimi masyarakat sekitar Muara Takus, seperti:
Can-Yaga. Posisi tubuh duduk bersila. Terbaca menjadi Can-Yago. Orang Minang mengambilnya sebagai marga (Chaniago). Dalam istilah setempat disebut Tapo. Lebih tinggi lagi disebut Bathagak, kadang dilafalkan Bethara. Jadi mudah memahami jika orang yang mumpuni disapa dengan sebutan Bathara Guru.
Piliang, yang kini mendapat arti baru yaitu pilihan. Akar katanya “pili” berarti benteng Dharma. Bodhi, pohon yang tumbuh di area suci (Boddhisatva). Kelak menjadi Budi. Semoga Anda mafhum kenapa sekarang kita mengenal frase budi darma.
Sangkayan, diberi arti baru “sangkak[r] ayam. Padahal kosa kata ini berasal dari “Sangha/Jamaah Hyang.” Para Jamaah penyembah Tuhan nan Esa.
Sungai Hyang menjadi Sungayang. Sri Suruwasa menjadi Soroaso. Jambhu Dwipa (tanah asal) berubah menjadi Jambu Lipo. Kanva beralih jadi Kampar. Panchala berubah Panchalang. Nama jenis kapal kuno dari Sumatera timur. Tempat dan nama² tersebut masih ada sampai saat ini di Jambi, Sumatera.
Shih Fa Hien atau Faxian (400 M), Sung Yun (518 M), dan Hiuen Tsiang atau Xuanzang (629 M), mencatat adanya kekuasaan yang mereka sebut “Śaka Kṣatrapas.” Berdasar identifikasi koin, diduga telah ada sekitar 225 M. Setelah berlayar selama sembilanpuluh hari lebih, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat bernama Ye-po-ti (Svarnadvīpa). Tempat hukum dan falsafah dipelajari para brahmana.
“Menyeberangi lautan ribuan li ke barat.
Meninggalkan negara Ta-lo-pi-ch’a (Drāvida), dan melakukan perjalanan ke utara, kami tiba di sebuah pulau besar yang terdapat batu-batu berharga atau Mahāratnadvīpa. Orang-orang di sini bertubuh kecil, berkulit hitam; mereka memiliki dagu persegi dan dahi tinggi, sangat kuat dan pemberani.”
“Mereka gemar belajar dan menghargai kebajikan. Sangat menghormati suatu ajaran tatanan adat yang sudah tertata dengan baik. Wilayah ini awalnya disebut Pāo-chu (Ratnadvīpa), karena ada banyak permata berharga yang ditemukan di sana.”
“Luas wilayahnya sekitar 7000 li. Di bagian pusat kotanya sekitar 40 li putaran. Tanahnya kaya dan subur. Iklimnya panas. Pohon ditanam secara teratur. Bunga dan buah diproduksi berlimpah.”
Begitu yang dilaporkan Fa Hien. Sekarang kita cermati catatan I-Tshing berikut:
“Seorang brāhmin dari Suvarṇadvīpa bernama Kin Fa (Suvarṇakeśa)–salah seorang dari enam guru besar non-Buddhis Sanjaya, datang ke Rājagṛha dan bertemu dengan Upatiṣya/Sariputra, yang berasal dari Suvarṇadvīpa (Kin Tcheou).”
Inti ajaran Dharma adalah, berbuat baik dan benar yang dilandasi kelembutan rasa welas asih. Dharma disajikan sebagai konsep terpusat yang digunakan untuk menjelaskan Kebenaran Tertinggi atau realitas puncak alam semesta
Ajaran ini menyebar hingga ke 3/4 penjuru dunia, lalu tumbuh di India menjadi Buddha dan Jaina pada Abad-5 SM. Empat abad kemudian muncul lagi menjadi Hindu. Lagi-lagi untuk menghormati “tanah kelahiran” ajaran Dharma, yang berada di barat daya Samudra Hind(ia). Sekadar pengingat, nama itu sudah ada sebelum kolonial datang ke Nusantara, dan negara bernama India masih berbentuk purwarupa. Semoga Anda masih eling dengan Kesultanan Samudra Pasai.
Ajaran Dharma kemudian dikembangkan oleh Mahaguru Agung Luhur Rhçi Shakyamuni Siddharta Gautama, dan juga Mahavira, pendiri agama Jaina. Pola pengajarannya dicitrakan dengan arca posisi orang duduk bersila topo/tapa di Çandi Vhwana Sakha Pala (Borobudur).
Situs Muara Takus di Kampar, adalah penanda dari sebuah area pusat pendidikan pengajaran pembelajaran Dharma. Dikelilingi dinding besar sebagai batas kuil, dan area luas guna menampung para brahmin yang mempelajari Dharma–sekitar 6000 santri setiap angkatan.
Area utama 4 km², area kedua 75 km², area terluar 300 km², berdasar sebaran temuan artefak di wilayah itu–termasuk sebuah stempel. Semua bersesuaian dengan catatan dari Tiongkok tentang lokasi Matahari Tanpa Bayang di Situs Muara Takus. Jejak keluhuran itu juga tergambar pada 160 panel relief di lantai dasar Borobudur yang sengaja tidak digali oleh Raffles. Silakan Anda jawab sendiri, kenapa bisa demikian.
Kendati begitu, kita masih bisa melihat bentuk ajaran Dharma dalam laku lampah masyarakat Bali (Pulang), yang memang berkecenderungan menjalani hidup untuk kem[bali] ke Rumah Asal. Senarai terkait Dharma ini adalah lanjutan dari ajaran sebelumnya yang oleh masyarakat Jawi lazim dinamai Sastrajendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.
Sebuah sistem keilmuan tingkat paripurna yang bisa dicapai manusia. Menitikberatkan pada upaya menjaga diri dengan terus menerus meruwat keangkaraan nafsu, demi mencapai hidup nan bijak bestari. Bahagia tan Alasan. Semua itu ditata sedemikian rupa dalam susunan aksara Ho-no-co-ro-ko… Warisan agung Sundayana dari masa 11.000 tahun silam, yang oleh penjajah Belanda dikerdilkan hanya sebagai sebuah suku di selatan Jawa.
Suasana kehidupan nan indah itu–yang sudah dalam balutan ketauhidan (monotheisme), kemudian beririsan dengan Islam yang dibawa oleh muhibah Abdullah Ibnu Mas’ud pada Abad-7 M. Apa yang terjadi manakala utusan Rasûlullâh Saw ini mengudar rasa dengan penduduk Nusantara? Mudah menjawabnya. Mereka saling mencocokkan pemahaman atas pedoman hidup yang sama–meski berbeda cara.
Allah itu Ahad. Bukan satu, sebab tak berbilang. Dia Manunggal ing kawulo (segala ciptaan). Mahameliputi. Tak tercandra. Tan keno kiniro. Laysa kamitslihi say’un. Tak keno kinoyo ngopo. Subhana wa Ta’ala. Gusti ingkang Moho Suci. Allah iku Wujud. Summum Bonum.
Arâfa nafsahu serupa belaka dengan sadulur papat kalimâ pancer. Islam memang tidak merincinya berdasar empat anasir pembentuk kita (angin, air api, tanah). Namun Alquran berulang kali menyatakan bahwa keempat unsur itu adalah bahan baku penciptaan manusia–bahkan alam raya seisinya.
Benarkah bila Indonesia tetap bisa berdiri tanpa Islam? Ternyata tidak. Sebab dua khazanah luhur yang telah kami uraikan tersebut, senafas dengan Islam yang dibawa oleh saudara muda kita dari Jazirah. Ajaran Bahari bersua dengan Agama Daratan.
Tiga pedoman hidup berketuhanan ini telah menubuh dalam diri Manusia Indonesia. Peristiwa budaya berkelindan dengan Islam. Ritus ke-Islaman diwarnai kebudayaan. Satu dengan lainnya saling melengkapi dan menguatkan. Zaman Kaliyuga menuntut umat manusia menerima Islam sebagai ageman pamungkas yang merahmati semesta.