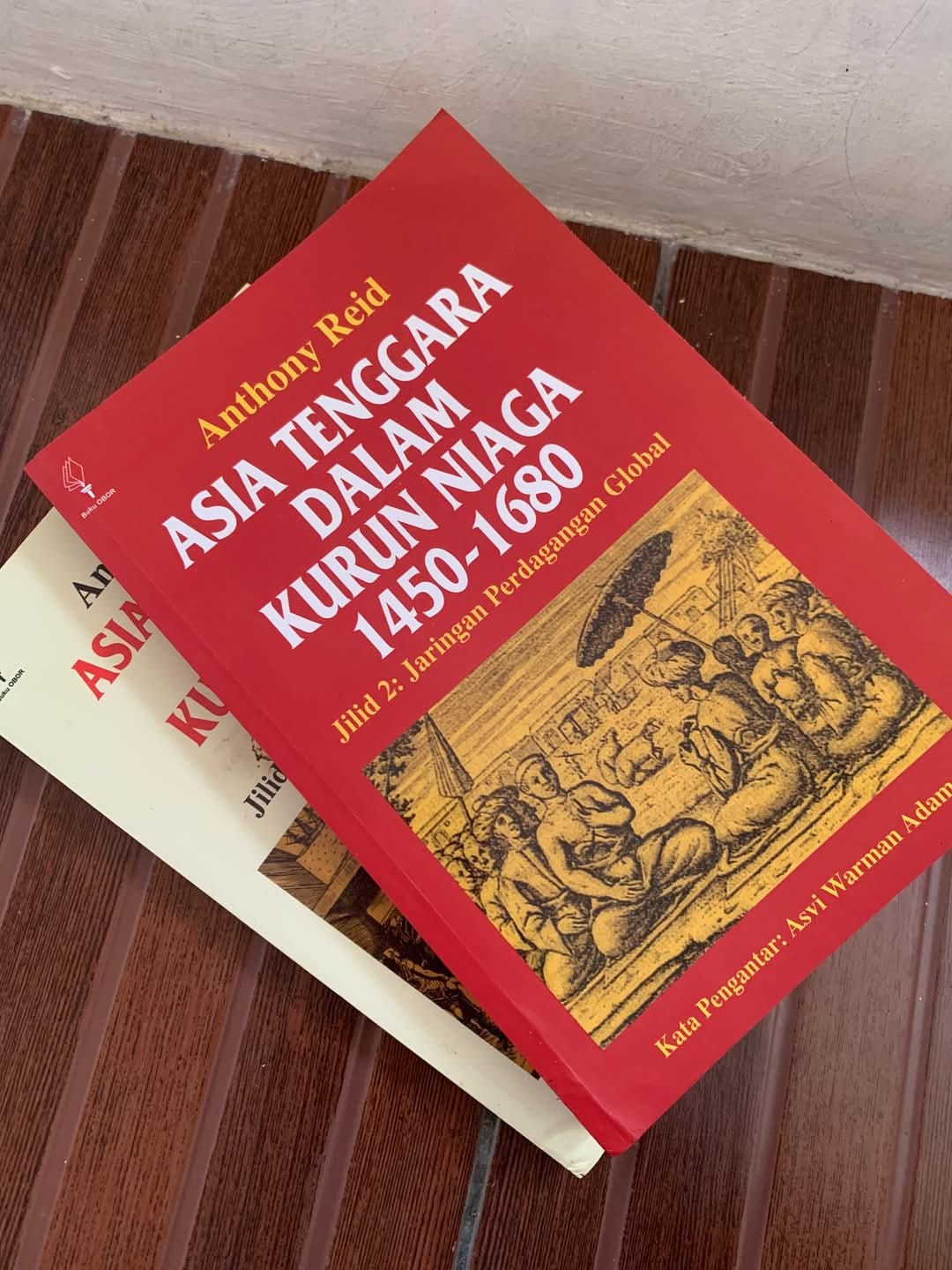28 April, tanggal yang kita kenang sebagai Hari Puisi Nasional, telah berlalu. Namun puisi—sebagai jalan sunyi, sebagai jerit batin, sebagai doa yang tak selalu selesai—terus mengalir, dituliskan, dibacakan, dan diserukan. Ia tidak tunduk pada kalender.
Sama seperti Chairil Anwar, penyair yang meninggal muda namun hidup lebih lama dari usia yang ditinggalkannya. Sajak-sajaknya, terutama puisi-puisi yang memancarkan nyali dan nestapa, tak pernah benar-benar wafat. Seperti suara yang terus memantul di lorong sejarah, sajak-sajaknya hadir sebagai jejak eksistensi yang tak lekang.
Dan dari semua gema itu, salah satu yang paling menggugah justru bukan yang berapi-api, tapi yang lirih dan letih: puisi-puisi yang menyerupai doa—doa yang tak selesai, doa yang retak, tapi tetap menyala. Serupa hembusan napas dari sebuah spiritualitas yang tak tunduk pada dogma, tapi juga tak bisa disangkal kehadirannya.
Kompleksitas
Dalam ingatan banyak orang, Chairil Anwar sering dilukiskan sebagai penyair modernis, individualis, ikon eksistensialisme Indonesia. Kita mengenalnya lewat larik “Aku ini binatang jalang”, melalui suara kerasnya yang menolak tunduk. Ia disebut anti-tradisi, liar, dan seolah tak mengenal arah pulang.
Namun tafsir semacam itu, betapa pun populernya, justru mereduksi kompleksitas sosok Chairil. Bila kita menekuri sajak-sajaknya dengan lebih jujur dan tenang, kita akan menemukan lapisan-lapisan spiritualitas yang sunyi, getir, bahkan menyentuh mistisisme dalam bentuknya yang paling manusiawi.
Ambil saja puisinya yang terkenal: Doa (1943). Tidak ada semangat heroik di sana. Tak ada pula retorika perlawanan. Yang ada hanyalah suara seorang anak manusia yang sedang kehilangan bentuk, rapuh, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan ilahi yang samar.
Puisi itu dibuka dengan larik yang menggigil:
Tuhanku / Dalam termangu / Aku masih menyebut nama-Mu.
Bukan “aku memohon”, bukan “aku percaya”, melainkan “aku masih menyebut nama-Mu”. Ada jarak, ada ragu, ada kesunyian yang menyelip. Tapi justru dari sinilah spiritualitas Chairil bersinar—dalam kegamangan. Ia tidak berdoa dalam kepastian, tapi dalam luka dan pertanyaan.
Ia bukan pendoa yang fasih. Ia seperti seseorang yang mengetuk pintu langit tanpa tahu apakah ada yang akan menjawab.
Biar susah sungguh / mengingat Kau penuh seluruh.
Larik ini seolah mengakui keterbatasan akal dan hati manusia dalam memahami Tuhan. Dalam dunia religius yang kerap menuntut kepatuhan, Chairil justru menawarkan bentuk iman yang lain: iman yang jujur, yang tidak mengklaim tahu, tapi terus meraba.
Ia menyusuri Tuhan bukan melalui kitab, tetapi lewat celah yang menganga dalam jiwanya. Inilah bentuk spiritualitas yang tak ingin dikurung dalam kerangka teologi formal—spiritualitas yang mewujud justru karena ia ringkih, tidak rampung, dan penuh kemungkinan.
Chairil tidak menulis banyak puisi dengan kata “Tuhan” di dalamnya, tapi bukan berarti ia absen dari pencarian spiritual. Dalam Yang Terampas dan Yang Putus, misalnya, kita melihat kesedihan dan keterasingan yang begitu dalam:
Kelam dan angin lalu mempesiang diriku / menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin.
Apakah ini tentang cinta manusiawi? Mungkin. Tapi Chairil selalu menulis dengan lapisan makna. Dalam suasana batin yang kosong, ragu, dan membeku, siapa tahu “dia yang kuingin” itu bukan hanya kekasih, tapi juga Tuhan yang telah lama menjauh atau tak pernah benar-benar datang?
Dalam Derai-Derai Cemara, kita menemukan semacam filsafat waktu dan kefanaan yang nyaris sufistik:
Hidup hanya menunda kekalahan / Tambah terasing dari cinta sekolah rendah.
Lagi-lagi, larik ini bukan semata-mata nihilistik. Justru dalam pengakuan tentang kekalahan hidup itu, terselip suatu jenis ketundukan yang jujur. Bahwa manusia hanya bisa menunda takdirnya, dan bahwa cinta yang murni, polos, seperti cinta masa kecil, telah semakin jauh dari jangkauan.
Kesadaran Kefanaan
Kesadaran tentang kefanaan ini—bila kita meminjam istilah Karen Armstrong—adalah bentuk paling purba dari spiritualitas manusia: kesadaran bahwa hidup terbatas, dan karena itu, harus diisi dengan pencarian makna.
Bahkan dalam puisi Aku, yang selama ini dianggap sebagai deklarasi eksistensial paling maskulin dan rebel, kita bisa menangkap semacam kerinduan terhadap keutuhan spiritual yang tercerabut:
Aku ini binatang jalang / Dari kumpulannya terbuang.
Larik ini dapat ditafsir sebagai pengakuan bahwa ia telah terlempar dari sesuatu yang lebih besar—sebuah harmoni, sebuah rumah spiritual. Bukan mustahil, inilah ratapan seorang “sufi modern” yang tidak menemukan tarekatnya, tidak memiliki mursyid, tapi tetap mendekap Tuhan dalam kehancuran.
Seperti para mistikus besar dari Timur, Chairil menyembah bukan lewat ritual, tapi lewat keterlemparannya. Ia tidak membawa tasbih, tapi membawa puing tubuh dan luka yang dirapal menjadi puisi.
Tentu Chairil bukan seorang teolog. Ia juga tidak sedang membangun sistem keyakinan. Tapi spiritualitas dalam sajak-sajaknya muncul sebagai experiential turn—peralihan dari agama sebagai sistem ke agama sebagai pengalaman batin.
Dalam perspektif cultural studies, Chairil hidup di “third space”—ruang ambang antara sakral dan profan, antara iman dan ironi. Homi Bhabha menyebut ruang ini sebagai tempat di mana identitas dinegosiasikan, bukan dikokohkan.
Chairil bukan fundamentalis, bukan pula ateis. Ia seperti penyair Jerman Rainer Maria Rilke yang menulis: “I live my life in widening circles that reach out across the world. I may not complete this last one, but I give myself to it.” Rilke sadar bahwa ia mungkin tidak akan menyelesaikan lingkaran hidupnya. Tapi ia tetap memberikan dirinya sepenuhnya—seperti Chairil, yang tahu doanya mungkin tak akan selesai, tapi ia tetap menulisnya.
Dan lihat bagaimana Doa ditutup:
Seperti kelam dan angin lalu / Aku hilang bentuk / Remuk.
Tapi ini tetap kubawa / Dalam hidup yang fana.
Ia membawa apa? Bukan ajaran. Bukan kredo. Tapi serpihan cinta dan harapannya yang telah remuk. Dan justru karena itulah puisinya terasa begitu manusiawi.
Sebab spiritualitas Chairil bukan tentang surga dan pahala, tapi tentang kejujuran mengakui keterbatasan, tentang kegigihan untuk tetap menyebut nama Tuhan bahkan dalam keadaan kehilangan bentuk.
Dalam puisi Karawang-Bekasi, Chairil juga bicara dari titik paling gelap: kematian, kehancuran, dan kehampaan. Tapi tetap ada pengakuan akan Yang Mahakuasa:
Kami cuma tulang-tulang berserakan / Tapi adalah kepunyaanmu.
Chairil tahu bahwa bahkan tulang yang berserakan pun ingin diakui nilainya oleh sesuatu yang lebih besar. Bahwa dalam kematian pun, ada harapan untuk dikenang, untuk disayangi.
Chairil tidak menyelesaikan doanya. Tapi ia memberikannya kepada kita. Maka tugas kitalah untuk membacanya, menggumamkannya kembali, dan mungkin—dalam sunyi kita masing-masing—meneruskannya.
Aku ingin hidup seribu tahun lagi.
Itu bukan seruan kesombongan. Itu seruan seorang manusia yang tahu bahwa doanya belum selesai. Dan barangkali, seperti sabda sunyi yang tak pernah rampung, puisi-puisinya adalah doa-doa yang menunggu disempurnakan oleh pembacanya—oleh kita.