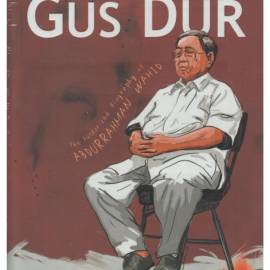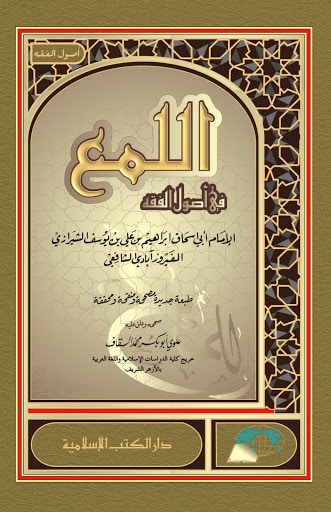Gus Dur menyebutkan: “Perlulah dikembangkan pendinamisannya, dengan cara memasukkan unsur-unsur pelengkap yang baru, seperti pemastian tempat kehendak masyarakat yang berwatak dinamis dalam proses itu, yang dapat diumpamakan dalam bentuk penyertaan opini masyarakat dalam mekanisme qaidah fiqh, seperti kaidah al-adah muhakkamah (adat kebiasaan bisa dijadikan kaidah hukum), dan sebagainya.” (Islam Kosmopolitan, hlm. 43)
Perkataan “al-`Adah Muhakkamah” merupakan salah satu kaidah fiqh yang digunakan para ahli ushul fiqh untuk merumuskan atau menggali hukum Islam, yang masuk dalam al-Qowa`id al-Kubro, di samping kaidah-kaidah: al-Umur bi-Maqosidhiha (Amal-amal tergantung pada niatnya), al-Yaqin la Yuzalu bisy Syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan); al-Masyaqqoh Tajlibut Taisir (Kesulitan mendorong Kemudahan), dan adh-Dharoru Yuzalu (Bahaya/mudharat harus dihilangkan).
Salah satu kitab yang diajarkan di pesantren yang membahas soal ini, adalah kitab kecil al-Faroidul Bahiyah, yang disusun Syaikh Abu Bakar bin Abul Qosim bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abul Qosim bin Umar al-Ahdal (984-1035 H.), atau kitab yang lebih tebal susunan al-Mufassir al-Faqih al-Hafizh, Jalaluddin as-Suyuthi berjudul al-Asybah wan Nazho’ir.
Kaidah di atas, diambil berdasarkan beberapa dalail, seperti dalam QS. An-Nisa [4]: 115, yaitu: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, wayattabi’ ghoiro sabilil mu’minin (dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin), Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”
Jalannya orang-orang mukmin, adalah jalan yang ditempuh mereka yang mendasarkan pada Alquran, sunah, dan bila tidak terdapat dalam keduanya, menggunakan jalan ijtihad melalui dan mengambil ijma dan qiyas (atau melalui prosedur lain menurut beberapa ulama). Ketika kaum muslimin dengan mendasarkan pada ini, jalan yang tidak ada dalam Alquran dan hadis secara eksplisit, lalu mereka membuat sesuatu hal, karena ada dalail implisitnya dari keduanya (Alquran dan hadis), lalu dipraktikkan dan diulang-ulang, dia bisa menjadi adat dan Urf.
Ada juga hadis yang digunakan memperkuat jalan seperi ini, dan keputusan berdasarkan adat/urf yang berkaitan dengan hukum bisa ditetapkan. Para ahli ushul fiqh menyebut riwayat hadits ini: “Ma ro’ahul muslimun hasanan fahuwa `indallohi husnun/ apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka bagi Alloh juga dianggap baik”.
Hadits tersebut dalam kitab al-Maqoshidul Hasanah yang disusun al-Hafizh as-Sakhowi terdapa dalam hadits No. 595, yang diberi keterangan dari Ibnu Mas`ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani, ath-Thoyalisi, Abu Nu’aim, dan al-Baihaqi (as-Sakhowi, Maqosidul Hasanah, hlm. 581).
Dalam pembahasan kajian ushul fiqh, kadang dibedakan antara adat dan urf, dalam pengertian: Adat, mengandaikan perbuatan yang diulang-ulang, dari kata “al-aud” dan “al-mu`awadah”, pengulangan kembali; sedangkan urf dari “al-muta`araf”, yang bermakna saling mengetahui.
Ketika adat itu dilakukan berulang kali, dan kemudian tertanam dalam hati, maka dia disebut urf. Akan tetapi hakekatnya tidak berbeda, karena urf memperkuat adat, dan dia digunakan untuk menyebut sebuah praktik di masyarakat atau seseorang, yang diulang-ulang dan terus menerus, diwariskan dari generasi ke generasi. Meski secara bahasa memiliki perbedaan, di dalam masyarakat kita, penggunakan kata adat lebih akrab daripada urf, yang dikaji dalam kitab-kitab ushul Fiqh, dan tidak dibedakan dengan istilah tertanam dalam hati apakah tidak.
Dalam beberapa contoh disebutkan, fungsi kaidah ini untuk menetapkan hukum misalnya: seberapa banyak gerak dalam salat di luar yang sudah ada dalam tuntunan, dapat membatalkan salat ukurannya tergantung adat; seberapa kadar minimal najis yang bisa di-ma’fu; tentang standar ukuran-ukuran timbangan luas di masyarakat dalam transaksi, apa menggunakan “ru” atau “bahu” atau hektar tetap syah; ukuran penerimaan barang dalam jual beli, apakah harus nyata dipegang, atau cukup dengan pemindahan hak; buah-buahan yang jatuh di pohon, apakah bisa diambil orang yang tidak memiliki pohon apakah tidak, tergantung adat di masyarakat; apakah dalam menyuguhkan tamu, makanan yang langsung disuguhkan, apakah berarti halal dimakan tanpa dipersilahkan sekalipun, atau menunggu dipersilahkan terlebih dahulu; dan masih banyak masalah yang penetuannya merujuk pada adat kebiasaan masyarakat.
Dalam kitab al-Faro’idul Bahiyah, disebutkan beberapa pembahasan adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum:
1. Adat itu harus muththorid (jelas/tetap), dan bila tidak muththorid (tidak tetap/tidak jelas) maka tidak bisa. Contohnya, adat di sebuah negara menggunakan dollar, tetapi dollar yang beredar itu ternyata bermacam-macam: ada dollar Hongkong, dollar Amerika, dan dollar yang lain. Adat yang bisa diterima kalau dollarnya yang berlaku muthorid, misalnya dollar Amerika atau dollar Hongkong. Maka kalau mengatakan dollar, harus ada qoyyidnya, Hongkong, Malaysia, dan lain-lain. Ini dalam transaksi jual beli diperlukan, tidak bisa hanya disebut dengan dollar, tetapi harus ada keterangan tambahannya.
2. Adat itu bersesuaian dengan dalil syara’ atau nilai-nilai syara’, dan bila bertentangan dengan syara’, maka yang dimenangkan syara’. Contoh, dalam adat Arab yang disebut sholat itu adalah berdoa (secara umum), tetapi syara’ memerinrtahkan sholat itu maksudnya adalah ibadah yang dimulai dari takbir sampai salam. Seorang muslim tidak boleh memenangkan adat dimana sholat hanya sebagai doa, dengan meninggalkan perintah sholat sebagai amal ibadah yang dimulai takbir sampai salam.
3. Bila terjadi pertentangan antara Urf Umum dan Urf Khusus, maka yang dimenangkan atau didahulukan adalah yang khusus (kecuali bila yang khusus sangat terbatas sekali). Contoh kata “dabbah”, itu bermakna semua hewan yang berjalan merangkak; tetapi di Baghdad, dabbah itu bermakna “kuda”.
4. Urf yang berlaku adalah yang bersamaan atau yang agak mendahlui, sedangkan yang terjadi setelah ucapan, tidaklah berlaku. Contoh, pada 10 tahun lalu seseorang mewakafkan tanah kepada A untuk dikelola menjadi pendidikan, dan setalah 10 tahun pengelolanya berganti, maka hak tanahnya ada pada A, dan B tidak memiliki hak apapun atas tanah itu.
5. Apabila adatnya bertentangan dengan pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat: ada yang menyebut dimenangkan pengertian bahasanya; ada yang berpendapat pengertian adat yang harus dimenangkan; ada yang berpendapat jika pengertian bahasa sudah umum maka pengertian bahasa yang harus dimenangkan; dan ada yang berpendapat, apabila pengertian adat tidak pernah digunakan dalam bahasa, maka pengertian bahasa yang dimenangkan.
6. Apabila tidak ada ketentuannya dalam syara dan lughat bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Contoh, dalam pencurian ada pembahasan soal tempat penyimpanan (hirzul mitsli), baik syara’ atau lughat tidak menentukannya, maka batasannya diberikan kepada adat, yang berbeda-beda, dimana tempat peyimpanan emas berbeda dengan tempat penyimpanan mobil, dan lain-lain.
7. Apabila adat yang jelas bertentangan dengan syara, ada keterangan: Pertama, jika tidak berhubungan dengan hukum, maka adat dimenangkan. Contoh, ada orang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi kemudian dia makan ikan laut, maka menurut hukum orang itu tidak melanggar sumpah, sebab menurut adat ikan laut tidak termasuk daging, meski Al-Qir’an menyebutnya termasuk lahman thoriyyan. Kedua, jika berhubungan dengan hukum, maka syara’ harus didahulukan. Contohnya, ada orang bersumpah tidak akan sholat, tetapi di kemudian waktu setelah itu dia itu berdoa kepada Alloh. Maka orang itu dianggap tidak melanggar hukum sumpah, karena dalam syara’ yang disebut sholat itu ibadah yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam.
Gus Dur menyebut kaidah di atas dalam konteks menjelaskan pentingnya penanaman Aswaja dengan menerima unsur-unsur baru, tetapi dengan tetap berpijak “dituangkan dalam ushul fiqh, qaidah fiqhiyah, dan sebagainya.” Dalam kerangka itu, Islam Aswaja menyediakan tempat bagi peranan opini masyarakat dalam peranan ushul fiqh yang tercermin dalam adat-istiadat yang dibuat mereka. Porses melakukan ini, disebut Gus Dur sebagai bagian dari internalisasi dan sosialisasi Aswaja, dimana adat juga mengambil peran penting.
Sejalan dengan itu, umat Islam yang memiliki kreativitas dan aktivitas yang membentuk adat-istiadat, adalah bagian dari mengembangkan dan mempertahankan sekaligus ajaran Aswaja. Selain melalui adat tentu saja masih banyak jalan dalam melakukan internalisasi dan sosialisasi, dan mendinamisirnya melalui pengajian, musyawarah, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Gus Dur menjelaskan bahwa mendinamisir dan menginternalisasi-mensosialisasikan Aswaja, adalah suatu yang penting, tetapi beliau mengingatkan asas-asasnya, yaitu: “Proses tersebut dituangkan dalam ushul fiqh dan kaidah fiqh”. Jadi tidak terlepas dari prosedur yang dimiliki tradisi Aswaja sendiri. Wallohu a’lam.