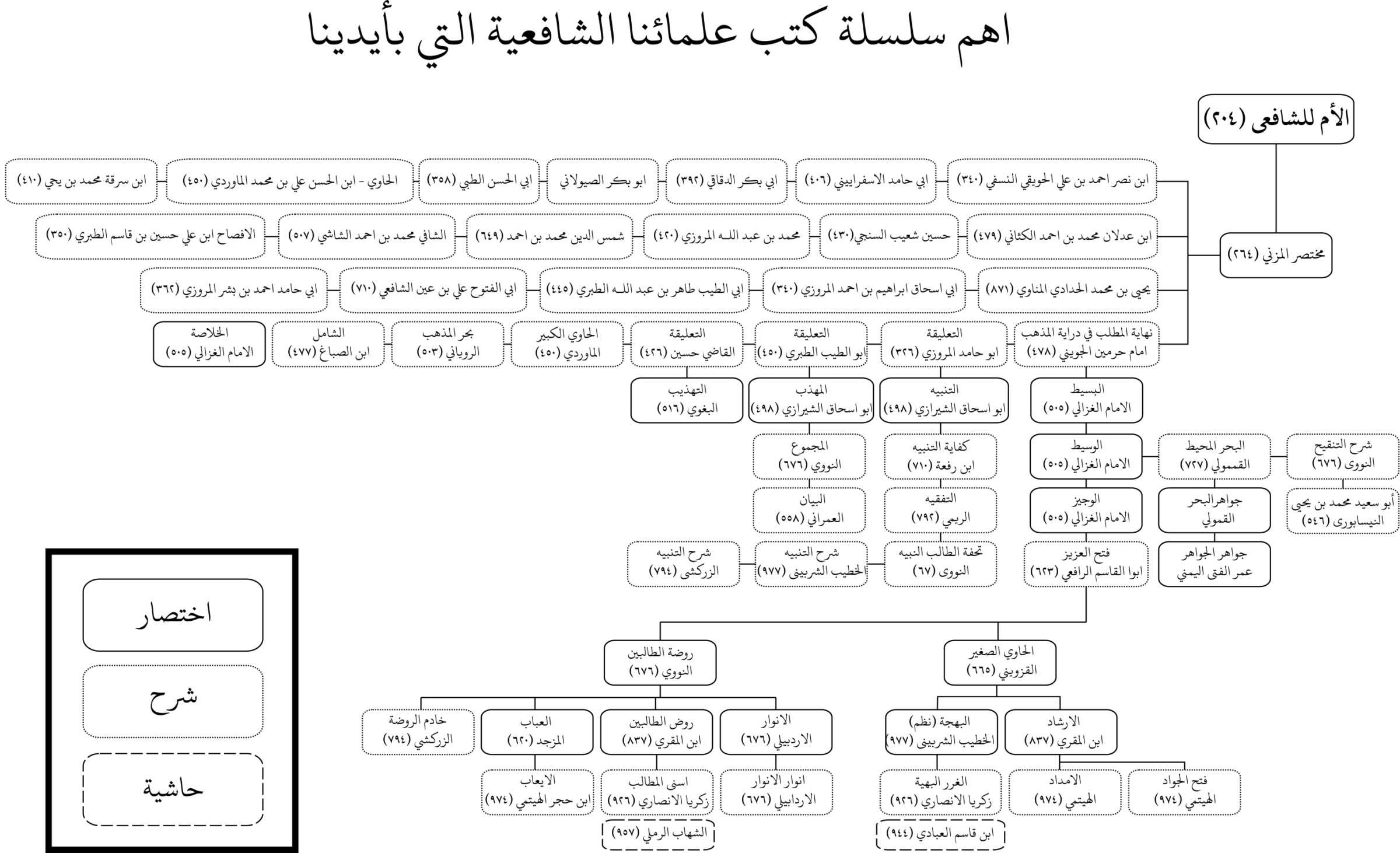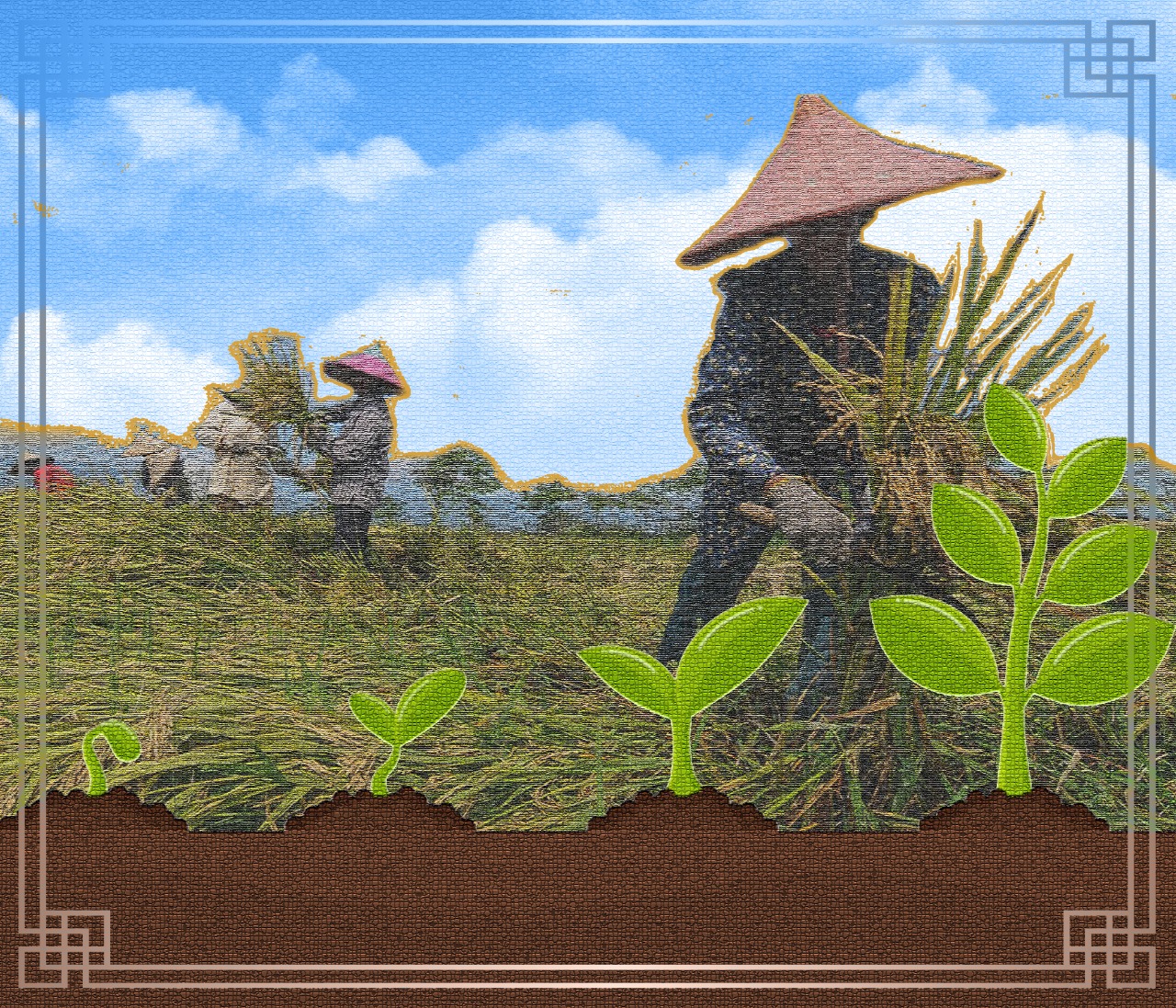
“Kita semua tuan tanah”, adalah adagium pertanahan yang dulu lekat dalam pikiran masyarakat Nusantara, namun berangsur-angsur lekang oleh jaman.
Adalah Van Vollenhoven yang berhasil memelintir adagium pertanahan Nusantara itu menjadi hak pertuanan tanah (beschikkingsrecht). Karena ada hak untuk beschikken (menguasai mutlak) atas tanah, Van Vollenhoven telah menyalahtafsirkan hak kuasa perorangan untuk memindah-tangankan kepemilikan tanah.
Pertuanan tanah sebetulnya berlangsung di tengan-tengah masyarakat sebagi bentuk pengolahan tanah untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Kenapa begitu? Nenek moyang kita dahulu tidak mengenal milik pribadi. Buktinya tidak ada kosa kata bahasa lokal di Nusantara yang punya pengertian semacam itu, melainkan hasil serapan dari bahasa asing: “Milik, duwe” misalnya adalah kosa kata yang diadopsi dari bahasa Arab.
Kedudukan perorangan sebagai tuan tanah hakekatnya adalah hak pakai sementara. Adapun yang menjadi tuan tanah sesungguhnya –meminjam ungkapan orang Batak- adalah “anggota marga yang meraja di situ” atau tiap-tiap anggota masyarakat secara kolektif.
Kesadaran mengenai adanya hubungan masyarakat dengan tanah secara kolektif dibuktikan adanya selamatan atau sedekah bumi oleh masyarakat adat. Sedangkan keyakinan adanya pertalian hidup antara kelompok masyarakat dengan tanah tampak dari upacara bersih desa sesudah musuh panen.
Pemahaman ini dapat dimaklumi karena tanah adalah jati diri bangsa yang sepenuhnya dimiliki. Bagi masyarakat Nusantara, tanah adalah symbol kehormatan yang harus dijaga dan dipertahankan. Tanah juga dipandang sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh dimiliki, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Tanah adalah adalah sumber inspirasi, menjadi asal mula manusia, tempat hidup, berpijak dan kembali setelah manusia meninggalka dunia.
Secara filosofis dan antropologis masyarakat Nusantara, tanah memiliki peran yang penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya tanah tidak layak diperdagangkan, dijadikan komoditi dan dieksploitasi.
Bagi orang Sunda, pandangan mengenai sakralitas tanah ini telihat dalam konsep “kabuyutan” (tanah yang disakralkan). Tanah kabuyutan ini harus dijaga jangan sampai direbut dan diduduki oleh orang asing. Siapa saja yang dapat menduduki tanah yang disakralkan (Galunggung), akan beroleh kesaktian, unggul perang, berjaya, bisa mewariskan kekayaan sampai turun temurun. Bila terjadi perang, pertahankanlah kabuyutan yang disucikan itu.
Masyarakat yang tidak dapat mempertahankan kabuyutan/tanah airnya maka derajadnya lebih hina dari kulit lasun (musang) yang berada di tempat sampah (Amanat Galunggung, Hal. 3)
Tanah bagi masyarakat Jawa juga memiliki nilai magis dan teologis. Dalam ajaran teologis yang dipercayai masyarakat Jawa, manusia berasal dari tanah dan harus kembali menjadi tanah. Manusia berpijak di bumi yang sama serta sama-sama diciptakan dari tanah, karena itu perjuangan untuk membantu sesama yang kekurangan merupakan “pemuncak sangkan paraning dumadi”.
Ajaran Asta Brata yang berisi delapan laku kepemimpinan dalam Ramayana antara lain menyebutkan: bahwa pemimpin harus memiliki prinsip “laku hambeging kisma”. Kisma berarti tanah, yang bersifat tak pernah membeda-bedakan siapapun yang menginjak. Pada tanahlah semua makhluk hidup menggantungkan hidup.
Jadi, pemimpin harus mampu mengayomi siapa pun dan memperjuangkan kehidupan rakyat. Bagi orang Jawa tanah juga dianggap sebagai Ibu (Ibu Petiwi) yang memberi kehidupan abagi manusia dan menjadi symbol kehormatan. Oleh karenanya tanah harus dijaga dengan segala pengorbanan sebagai tercermin dalam falsafah jawa: “sak dumuk bathuk sak nyari bumi dibelani pati”.
Di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan tanah dan segala bentuk isinya dari ancaman luar. Hal ini sejalan dengan petatah orang Melayu: ”apabila rusak alam lingkungan di situlah punca segala kemalangan musibah datang berganti-gantian celaka melanda tak berkesudahan. Apabila rusak alam lingkungan hidup sengsara binasalah badan cacat dan cela jadi langganan hidup dan mati jadi sesalan. Apabila alam porak poranda di situlah timbul silap sengketa aib datang malu menimpa anak cucu hidup merana”.
Sebagai imbalan dalam menjaga tanah, hukum adat Melayu menyebutkan masyarakat mempunyai hak bersama dalam menguasai atau memanfaatkan suatu lingkungan tanah untuk kehidupannya dan kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Dalam hal ini, orang luar tidak mendapat hak tersebut melainkan telah mendapat izin dari ninik mamak.
Ketentuan adat tentang hutan dan tanah adat juga menyebutkan: (1) hutan dan tanah adat tidak boleh diperjualbelikan dengan cara apapun sehingga pemilikan haknya menjadi berpindah tangan; (2) hutan dan tanah adat tidak boleh dibagi-bagikan menjadi milik pribadi/ perseorangan; (3) walaupun seseorang itu dapat memanfaatkan tanah secara perseorangan ia harus mengikuti ketentuan atau kewajiban-kewajiban tertentu seperti memberikan sebagian hasilnya kepada ketua suku.
Kapasitas ketua suku, ketua adat, palungguh, dan sebagainya bukanlah tuan tanah dalam arti sesungguhnya. Ia hanyalah wakil Tuhan di muka bumi yang bertanggungjawab mengelola tanah untuk kepentingan bersama dan keturunan penerusnya yang akan datang.