Tirakat Santri di Tengah Pandemi: Tradisi Nahun Pondok Tremas
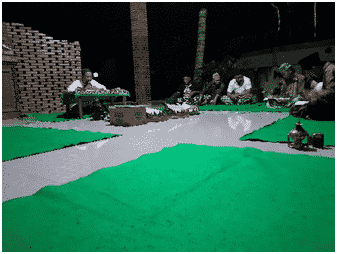
Sebagaimana yang kita ketahui, dunia sedang dihadapkan pada sebuah wabah Covid-19 yang mengubah banyak tata kehidupan global, termasuk pendidikan. Untuk menghindari merebaknya pandemi ini, lembaga pendidikan dimanapun menutup sejenak aktivitas belajar mengajar tatap muka.
Pun demikian dengan Pondok Tremas, mereka mengambil kebijakan untuk memulangkan ribuan santrinya sebagai ikhtiar hafdzu an-nafsi, mengimplementasikan dar’u al-mafasidi muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalihi. Keputusan tersebut menurut hemat penulis adalah bentuk kerendahatian para kiai, menghindari ketakabburan untuk merasa sok sakti, merasa kebal, dan merasa mampu mengatasi kemadharatan. Sebuah ketawadhuan untuk mengilhami dan mengiramakan la haula wala quwwata illa billah.
Hingga hari ini, di antara sekian banyak santri yang dipulangkan, masih tersisa hampir 300 an santri yang memilih bertahan di pesantren, menghabiskan Ramadhan dan berIdul Fitri di sana. Menikmati kesepian di tengah ketidakjelasan kapan teman-temannya akan kembali ke pondok.Ya, santri-santri tersebut tidak pulang demi menjalani sebuah tirakat nahun yang sudah mentradisi di Pondok Tremas. Nahun adalah bentuk riyadhah santri untuk tidak pulang selama tiga tahun. Tradisi yang sifatnya intangible ini sudah membudaya sejak puluhan tahun lalu, berdasarkan kepercayaan akan barokahnya kiai bagi mereka yang melakoni nahun. Banyak yang melakukan tirakat ini, dimana banyak pula dari mereka yang kemudian menjadi orang sukses ketika berkiprah di tengah realitas. Di Tremas, nahun adalah belief yang sudah menjadi habbit of mind, hingga meaning.
Penulis adalah juga santri Tremas, hal ini membuat posisi penulis berada dalam ranah insider. Untuk menghindari subyektifitas dan suguhan fakta yang penuh distorsi, maka penulis mengambil peran sebagai participant as observer, yakni berusaha untuk tidak terjebak pada bermainnya perasaan dalam mengurai sebuah fenomena. Hal ini dilakukan agar tulisan menjadi obyektif, berimbang, tidak larut dalam romantika, serta tidak terkesan ‘mempromosikan’.
Nahun; Riyadhah Kedewasaan
Jauh dari orang tua dalam kondisi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi seperti saat ini, tentu sangat tidak mudah. Kegelisahan, kejenuhan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kesepian, dan kerinduan, pasti meronta-ronta di hati mereka yang nahun. Dalam kondisi normal saja, setiap muslim Indonesia pasti menginginkan untuk kumpul dengan keluarga saat hari raya. Melewatkan tiga lebaran bersama keluarga untuk sebuah niat suci menggembleng diri demi sebuah harapan akan keberkahan hidup. Sejenak menahan pahit getirnya kesendirian, untuk mengecap manis madu kehidupan di masa yang akan datang. Menahan ‘keterasingan’ untuk kelak memiliki daya tahan pada arus kehidupan mainstream yang lebih sering menjerumuskan. Membiarkan mata menangis karena rindu, untuk nantinya memiliki ketangguhan atas problematika hidup yang tak menentu.
Untuk diketahui, santri yang nahun tidak hanya terdiri dari mereka yang berusia remaja. Banyak dari mereka yang masih berusia di bawah 17 tahun, bahkan banyak juga yang masih duduk di bangku SD. Mereka nawaitu untuk tirakat ini murni atas inisiatif sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua maupun pondok. Untuk seusia mereka, nahun adalah keputusan besar dengan konsekuensi yang besar pula. Nahun adalah uzlah untuk sejenak menyepi dan mengambil jarak dari lalu lintas keramaian, guna melatih kejernihan pikir, kepekaan batin, kedewasaan sikap,kemandirian hidup, dan kuatnya mentalitas. Untuk anak seumur mereka, berani melakukan hal tersebut,merupakan sebuah prestasi yang patut mendapat apresiasi.
Nahun bukanlah sebuah aktivitas yang tak bisa dimengerti sisi rasionalitasnya. Ia bukan keyakinan abstrak yang bersumber dari taqlid buta. Kepercayaan atas do’a tak bisa dimaknai dengan keterjebakan akan sublimasi. Santri yang nahun tak musti mereka yang hanya memiliki kecenderungan pada aspek irfani saja. Butuh waktu yang tak sebentar untuk mengobservasi tradisi ini, butuh teori antropologi yang mendalam untuk mendeteksi gejala sosial yang unik ini. Dan tulisan ini,tentu tidak bisa menggambarkannya secara detail nan memuaskan. Namun setidaknya ada beberapa point yang bisa diuraikan, sebuah analisis pribadi penulis atas persinggungannya bertahun-tahun dengan santri-santri yang nahun.
Terdapat pendidikan karakter dalam tradisi nahun. Meminjam istilah H. Keller (880-1968), karakter tidak bisa dikembangkan dengan mudah. Hanya pengalaman yang memperkuat jiwa, mengilhami ambisi dan meraih kesuksesan. Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, yang meliputi: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nahun mengajarkan asketisme dan asketisisme yang semakin jarang dimiliki manusia hari ini. Dalam nahun, dimensi afektif yang meliputi spiritual dan sosial menjadi tergarap. Tirakat ini memupuk solidaritas dan cinta kasih dalam jiwa santri. Di pesantren kita tak perlu khawatir akan radikalisme, ekstrimisme, fundamentalisme, dan terorisme.
Dari aspek koginitif, mereka yang jauh dari rumah untuk mencari ilmu, memiliki tingkat fokus yang berbeda dibanding yang dekat dengan rumah. Hiruk pikuk kehidupan seringkali mengganggu fokus belajar anak, solusi cerdas adalah mengambil jarak sejenak dari riuh rendah kehidupan sosial. Problem besar pendidikan hingga hari ini adalah demarkasi antara dunia pendidikan dan kehidupan di masyarakat, yang tak kunjung ada titik temu. Dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial seringkali berseberangan dengan yang diajarkan di sekolah. Dalam hal ini, pendidikan sering tidak bisa maksimal karena lingkungan yang tak mendukung. Sejenak keluar dari lingkar struktur, bukan berarti acuh tak acuh terhadap realitas, melainkan sebuah proses untuk mematangkan diri sebelum terjun di dunia nyata. Nahun di pesantren adalah solusi untuk tapa brata itu.
Berikutnya aspek psikomotorik, mayoritas anak pesantren memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibanding anak ‘rumahan’. Hal tersebut bisa dipahami, karena memang di pesantren anak dituntut untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Dalam konteks nahun, berpisah dengan keluarga untuk waktu yang tidak sebentar, apalagi dengan kondisi yang mencekam, menusuk, dan menggertarkan sebab pandemi ini, membuat mereka semakin kuat dhahir bathin. Mereka terbiasa untuk tangguh melawan gelombang kehidupan. Berdiri tegak dengan kaki sendiri, tanpa tergerak untuk merengek meminta belas kasihan. Wallahu A’lam





