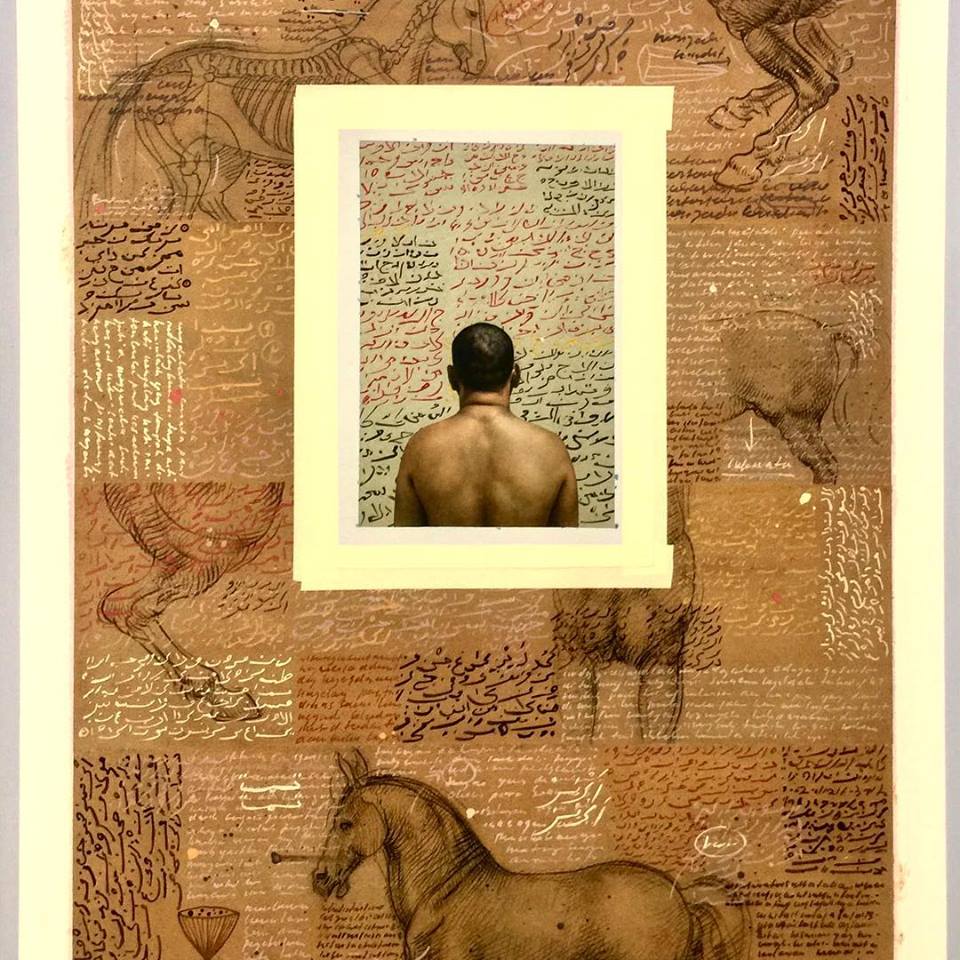Vijay Prashad, intelektual beraliran “kidal” yang sangat produktif, menulis sebuah buku tipis, In The Ruins of the Present. Prasad menggemakan kembali pikiran-pikiran tajam dan bengal dari tiga kawasan: Asia, Afrika dan Amerika Latin. Karena tidak sedang mengintrodusir Prashad (mungkin di lain kesempatan), maka hanya argumen pokoknya saja yang perlu digemakan di sini: bahwa dunia kita disusun berdasarkan pembagian kemanusian (structured around divison of humanity). Apa maksudnya ?
Kalau dipaksakan, tidak cukup ruang menjelaskanya “pembagian internasional atas kemanusiaan” ini. Pada bagian akhir dari kumpulan puisi Aime Cesaire, A Note on Return to the Native Land, terdapat sebuah bar atau podho (dalam macapatan Jawa) yang paling banyak diminati sebagai kutipan, demikian :
Sebab tidak lah benar bahwa pekerjaan manusia telah selesai
Bahwa kita tidak ada kepentingan untuk berada di muka bumi ini
Bahwa kita menjadi parasit dunia
Sedangkan pekerjaan ini baru saja dimulai
Dan manusia masih harus mengatasi segala penghalang
Terjepit dalam celah-celah kegairahannya dan tidak ada ras yang memonopoli
Keindahan,kecerdasan, kekuatan
Ada ruang bagi setiap orang pada perjumpaan penaklukan....
Tafsir simplistik atas puisi dekolinisasi Cesaire di atas,bahwa mitos keunggulan ras tertentu atas keindahan dan intelektualitas dianggap sebagai bentuk kemerosotan moral. Persoalan ini pernah saya singgung ketika menyinggung mendiang George Abraham Makadisi dalam bukunya, The Rise of Humanism dan The Rise of College, bahwa kemanusiaan itu tidak memiliki “induk” bernama Yunani, Barat, Timur, dan Arab, dan seterusnya. Apalagi humanisme yang “beribukan” agama. Humanisme itu hanya berakar,bertumbuh, dan berkembang di tanah airnya dalam hukum-hukumnya sebagai mahluk hidup: memiliki dinamika sosio-historis yang tidak memiliki imbuhan ensensialisme apapun; pasang-surut; mekar dan kolap; serta fana karena kemekarannya tidak abadi.
Lantas humanisme apa yang hendak dihadirkan Prashad dan para pendahulunya dalam rantai sanad pemikiran dekolonisasi? Humanisme yang membumi dalam artian bahwa manusia dari manapun dan di manapun bisa menumbuhkan keindahan dan pemikiran dengan kekuatan yang berlimpah dan sulit diprediksi.
Ada keharusan untuk mempercayai bahwa manusia bisa berkembang dengan maksimal sepanjang tidak ada penghalang berupa perendahan atau degradasi kemanusiaan itu sendiri. Pembagian kemanusiaan yang digemakan oleh Prashad di atas adalah penyebab utama (main cause) dari kegagalan banyak orang untuk melakukan de-esesnsialisasi terhadap dehumanisme itu sendiri.
Tidak ada yang ensensial dalam kamus kehidupan manusia. Orang yang paling kita rendahkan adalah juga manusia yang berbahan baku sama dengan kita sehingga tidak menutup kemungkinan esok atau hari yang lain menjadi seorang yang lebih menonjol dalam banyak hal daripada kita.
Mereka yang terus kita bombardir dengan kritik sebagai kolot, sumber keterbelakangan, dan sebagainya juga adalah manusia yang terus berubah sehingga tidak menutup kemungkinan di hari mendatang mereka lebih maju dan beradab dari kita. Seperti peringatan mendiang Mohammed Arkoun: setiap manusia dianugerahi kapasitas yang tidak pernah bisa diduga oleh sesamanya.
Pembagian kemanusian, pemeringkatan kemanusiaan, oleh Cesaire, Fanon, sampai Albert Memi disinyalir sebagai tunggak dari rasialisme, dan oleh Prashad ditegaskan kembali karena tidak banyak mengalami perubahan,dan cenderung menguat. Penistaan kemanusiaan dilakukan segala bangsa dan agama: semua pernah berlumur penistaan kemanusiaan. Dan hal paling buruk: di dalam benak banyak orang, pembagian kemanusiaan itu senyawa dalam gramar generatif tindakan.
Saya menulis tentang humanisme ini karena teringat dengan salah satu ceramah “paling mengesankan” Gus Dur pada tahun 2000 (masih menjabat sebagai presiden), di Pesantren Tegalrejo, Magelang,Jawa Tengah tentang pandangan kemanusian orang pesantren.
Dalam ceramah itu, Gus Dur bercerita tentang tradisi ilmu-ilmu pesantren secara luas dan pengaruhnya terhadap paham kemanusiaan orang pesantren yang khas: memuliakan manusia dalam fakta mumkinnya secara eksistensial. Manusia harus dimuliakan dalam kefanaan hidupnya. Paham ini adalah modal utama orang pesantren dalam memperkaya kosa-kata kehidupannya.
Gus Dur seringkali mengulang penjelasan soal kekayaan tersembunyi pesantren ini: tradisi pengetahuan dan kemanusiaanya karena umumnya orang tidak percaya keduanya juga tumbuh subur di pesantren.
Walaupun disebut sebagai ilmu-ilmu agama, rumpun pengetahuan yang diolah di dalam pesantren seperti ilmu alat, fikih, tauhid, etika dan tasawuf dengan segala dinamika sejarahnya menuntut suatu etika dan etos yang serba teliti, ketat, sulit dan penuh dengan tantangan. Orang pesantren yang menekuni rumpun ilmu “yang tersisa” di dalam perjalanan pesantren di Indonesia tersebut biasanya akan memiliki etos keilmuwan yang (seharusnya) selaras dengan etika sosial dunia pesantren yang melampui forma kekakuan yang displiner.
Dalam ceramah tersebut Gus Dur bercerita tentang dua gurunya, Allahuyarham Mbah Kiai Chudori dan Kiai Fattah Hasyim (Tambakberas, Jombang). Bagaimana pandangan dunia pesantren yang (seringkali) digambarkan kaku dan kolot itu sangat terikat dengan lingkungannya. Kiai Chudori tidak pernah membedakan Pesantren Tegalrejo dengan masyarakat sekitar, terutama ikhtiar Kiai Chudori (dalam konteks masa itu) untuk tidak berjarak atau tidak membuat pembedaan (distingsi maupun perbedaan) dengan kesaharian masyarakat sekitar sehingga masyarakat Tegalrejo yang teriris secara sosial oleh berbagai sebab merasa memiliki perikatan dengan pesantren Tegalrejo.
Sementara cerita tentang Kiai Fattah, ketika Gus Dur menjadi bagian kemananan pesantren Tambakberas melakukan operasi tangkap-tangan terhadap seorang santri yang melakukan pelanggaran displiner, dan kemudian dilaporkan kepada Kiai Fattah dengan catatan harus dikeluarkan dari pesantren. Apa respon Kiai Fattah?
Kiai Fattah justru mengatakan bahwa dirinya dari awal mengetahui “kenakalan” santri tersebut, dan kenakalan itu yang menjadi sebab keberadaanya di pesantren sehingga tidak perlu dikeluarkan (diusir) dari Tambakberas. "Jika pesantren tidak snggup mengubah santri itu, mau dikemanakan lagi? Orangtuanya membawanya ke sini karena sudah tidak sanggup," begitu kira-kira kata Kiai Fattah kepada Gus Dur.
Di pesantren, anak nakal tersebut pertama dan utamanya diposisikan sebagai manusia yang potensial mengubah dirinya dari kelemahan dan kekurangan.
Dalam konteks hari ini: tradisi intelektual dan kemanusiaan pesantren terus berubah. Guncangan politik praktis, media, romantisme-nostalgia pesantren bisa saja membuat pesantren hari ini tidak mampu lagi melahirkan sosok besar seperti Kiai Chudori Tegalrejo, Kiai Fattah Tambakberas, dan Gus Dur sendiri. Pertanyaanya: bagaimana menjadi santri yang teguh dengan tradisinya tapi menyongsong keragaman? Wallahu ‘alam bishawab.